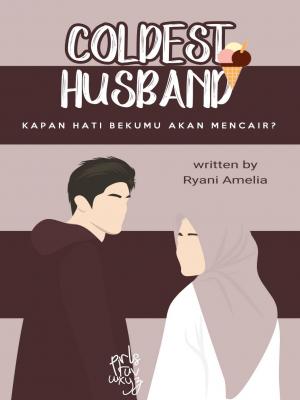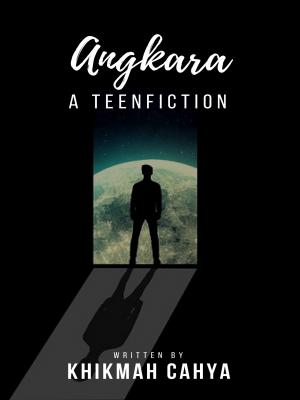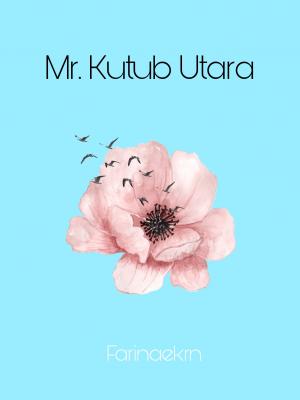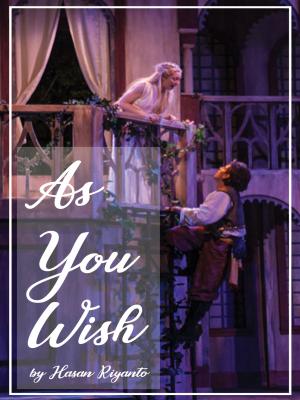Welcome home
Hari mulai menua. Senja menyapa ramah dengan senyum jingganya. Langit kian menggeser birunya dengan kemerahan sang candik. Kawanan burung terbang pulang ke sarang. Seperti juga Ali, yang sekarang berada di dalam perut burung besi. Beberapa menit lagi, ia akan menapaki tanah kelahirannya. Ali menyebutnya dengan pulang.
Dan benar saja. Perjalanan sekian jam yang Ali lakukan, sebentar lagi berakhir. Sekumpulan awan yang sempat ia lihat dari balik jendela pesawat tadi, sudah hampir tak terlihat lagi. Bahkan, warna jingga sang senja yang sekarang tampak olehnya. “Alhamdulilah, sebentar lagi landing.” Ali bergumam lirih.
Tampak seorang pramugari sedang berjalan menyusuri sela bangku penumpang. Lalu ia berhenti, berdiri tegap dan tersenyum pada seluruh penumpang. Beberapa detik kemudian, terdengar suara merdu pramugari lainnya dari sound system pesawat, memberi aba-aba untuk memperbaiki posisi duduk karena pesawat segera menyapa bumi. Penumpang yang duduk di samping Ali pun tergagap dari tidurnya.
“Alhamdulilah, sudah hampir landing, ya?” katanya pada Ali.
“Oh, iya, pak. Nyaman sekali ya, pak tidurnya.” Ali menjawab dengan senyum.
“Alhamdulilah. Bapak sudah kangen sekali dengan cucu-cucu bapak. Pengen segera memeluk mereka.”
Ali tersenyum mendengar kata-kata bapak itu. Dalam hati, Ali pun ingin juga mengatakan, betapa rindu juga melingkupi dirinya. Ingin juga memeluk orang yang dirindukannya itu. Tapi bagi Ali saat ini, dapat memandang wajahnya saja sudah mampu meruntuhkan segunung rindu yang dipikulnya. Apalagi mendapat sapa senyumnya, seolah waktu pun ikut berhenti menikmatinya. Senyum yang mampu membius Ali sejak hari itu, sekian tahun lalu.
***
“Ali! Ngapain lo disini?” Abu tetiba masuk ke ruang redaksi majalah sekolah siang itu.
“Ssstttt. Jangan keras-keras. Entar ada yang dengar.” Ali berkata lirih sambil menempelkan jari telunjuk ke bibirnya.
“Ada apa sih, bray? Ngapain lo ngumpet segala?”
“Ah, gue risih didatangi wartawan-wartawan majalah tadi itu.” Ali bangkit dari persembunyiannya dan melangkah ke arah kursi yang terletak tak jauh dari jendela.
Ruang redaksi majalah sekolah berada di lantai dua gedung sekolah. Ada jendela kaca besar menghadap ke halaman depan sekolah. Jadi, dari jendela itu, Ali dapat melihat semua orang yang ke luar, masuk halaman sekolah, termasuk para wartawan yang sejak beberapa jam tadi berusaha menemuinya.
“Oooo, sindrom artis baru?” Abu mulai mengejek Ali.
“Set dah. Mulut sambel, lo.” Ali melempar topi yang dari tadi ia pegang. Untung saja, Abu kapten basket sekolah. Jadi, sigap ia menangkap lemparan itu hingga tidak mengenai wajahnya.
“Kan keren tuh, wajah lo dipajang di sampul depan majalah.” Abu berkata dengan penuh antusias. “Apalagi barengan sama motor antik lo itu. Impian lo kan?” Abu makin terlihat antusias menyemangati Ali.
Ali terlihat berpikir sedikit serius kali ini. Ia memandangi gambar motor hasil modifikasinya di salah satu halaman majalah sekolah. Memang, di beberapa edisi, Ali adalah penulis utama di kolom “Kreativitas Remaja”. Kecintaannya mengotak-atik motor, menjadikannya idola. Bisa dibilang, Ali adalah artis baru di dunia otomotif remaja, bersama motornya tentu. Ali menamai motor itu, “Busy Sibuk”.
Dan ternyata, nama Ali tidak hanya dikenal di sekolah saja. Beberapa teman sekolah banyak yang menceritakan tentang kemahiran Ali menyulap motor menjadi cantik dan unik. Hingga Ali dikenal oleh banyak remaja lelaki. Bahkan, salah satu dealer motor besar di kotanya, ingin memajang motor Ali. Tentu saja, menginginkan wajah Ali terpampang sebagai ikon dealer.
Namun, beberapa kali tawaran itu datang, sekian kali itu juga Ali menolak. Hingga hari ini, saat beberapa wartawan datang ke sekolah hendak meliput dan mewawancara Ali, ia malah sembunyi di ruang redaksi.
“Ali! Abu! Kalian di sini rupanya. Sudah kuduga.” Zahra masuk ke ruang redaksi tiba-tiba.
“Sssstt. Aduh. Ini lagi. Tutup donk pintunya, Ra.” Ali segera sembunyi di kolong meja.
“Lo kenapa sih, Ali? Lo aneh banget deh. Saat semua orang ingin tenar, nah lo? Malah sembunyi saat dapat kesempatan.”
“Ra, gue nggak butuh tenar. Gue ini pelajar, bukan artis.” Ali mencoba berargumen.
“Lo itu artis, Ali. Lo nggak sadar apa? Butuh jiwa seni tinggi untuk ubah motor butut lo itu jadi transformer keren seperti itu.”
“Aduh, Ra. Gue hanya seneng aja. Nggak tahu kok tiba-tiba jadi gitu.” Ali duduk tepat di depan Zahra. “Jadi lo jangan sebut gue artis donk. Gue nggak suka.”
“Kenapa, bray? Bukannya keren tuh jadi artis.” Abu mengangkat kedua alisnya beberapa kali.
“Once more. Dengar ya, gue nggak mau. Titik. Artis itu buat gue konotatif banget. astaghfirullah, tuh kan, gue jadi negthink.”
“Kan nggak semua artis kayak gitu, bray.” Abu masih saja ngeyel.
“Ali, lo tahu, kan, artis itu apa? Se-ni-man. Lo nampang di majalah, di koran bahkan masuk tivi pun bukan untuk buat lo tenar, sok ngartis atau apalah. Tapi, lakukan semua karena Allah.” Zahra menatap dalam mata Ali. “Niatkan untuk menginspirasi, atau berbagi ilmu.” Mata bulat indah milik Zahra seakan memancarkan cahaya. Hingga Ali merasakan sesuatu yang menusuk masuk ke dalam matanya. Menyilaukan. Tapi entah mengapa, Ali enggan untuk berpaling dari tatapan itu. Ali pun terbius dan menikmatinya.
***
Di bandara. Ada sepasang mata di balik jendela kaca, menatap nanar ke landasan pesawat. Dua jam menunggu itu bukan waktu yang terlewat cepat. Ada kegelisahan semakin menyeruak dalam hati. Jika sesuai jadwal, seharusnya kendaraan bersayap besi itu akan mendarat dua puluh menit lagi.
Zahra menjauh dari jendela kaca besar itu. Semakin lama ia berdiri di balik jendela kaca itu, semakin gelisah membayangi waktu menunggunya. Kali ini, Zahra melangkah gontai dan duduk di salah satu jajaran bangku. Sesekali ia melirik jam di tangan kirinya. Sepuluh menit lagi. Seharusnya sudah ada pemberitahuan arrival. Dan suara yang diharapkan Zahra pun terdengar. Ada pemberitahuan tentang kedatangan pesawat dari Australia. Refleks, Zahra pun bangkit dari duduknya dan berlari kecil ke arah jendela kaca besar tadi. Mata bulatnya kembali membelalak berbinar. Hingga pandangannya menangkap sebuah titik dari langit senja yang semakin lama semakin membesar.
Pesawat yang ditumpangi Ali pun landing dengan sempurna. Orang-orang yang beberapa menit lalu masih duduk-duduk tenang, tetiba sibuk dalam keriuahan. Satu per satu, mereka bertemu dengan keluarga, sahabat, kolega atau apalah. Sedang Zahra. Ia masih berdiri terpaku di dekat jendela kaca. Pandangannya tak sedetik pun lepas dari jalur kepulangan para penumpang pesawat yang baru saja dilihatnya mendarat.
“Assalamualaikum, Zahra.” Seseorang terdengar menyapa lembut dengan suara yang sudah tidak asing lagi bagi telinga Zahra.
“Waalaikumsalam. MasyaAllah, Ali, kebiasaan deh lo.”
“Lo juga kebiasaan. Bengong di sini.”
“Lah, tadi lo lewat mana?”
“Lewat pintu kemana saja. Kenapa? Heran?” Ali mengangkat kedua alis matanya. “Tumben lo heran sama gue.”
“Whatever lah.” Zahra mengernyitkan dahinya.
“Nah gitu donk. Sekarang, lo traktir gue di tempat biasa, ya.” Ali berjalan meninggalkan Zahra yang masih berdiri kesal di tempatnya.
Dua jam menunggu Ali di bandara, berharap bisa menyambut kedatangan Ali dengan sesuatu yang berbeda. Tapi tetap saja sama. Ali tetap lelaki yang apa adanya. Candaannya tetap di mana saja. Bahkan, seakan ia tidak peduli dengan usaha Zahra demi menjemputnya di bandara kali ini. Padahal, Zahra harus ijin dari satu tindakan operasi yang sebenarnya sangat penting untuk thesisnya.
“Heeehhh. Ali masih saja begitu.” Zahra bergumam lirih.
Setelah beberapa langkah meninggalkan Zahra, Ali menengok ke arah Zahra dan berkata, “Ya Allah, Ra. Masih belum puas berdiri di situ, lo?”
Tanpa menjawab, Zahra berjalan menghampiri Ali. Hijab panjang terjuntai selaras dengan gamis yang dikenakannya, melambai seirama langkah kaki jenjangnya.
“Ke café biasa kan, Ra?” Bukan berniat bertanya, Ali hanya memastikan saja setelah ia menunjukkan tujuan mereka pada sopir taxi yang mereka tumpangi.


 FaAli
FaAli