Sepatu putih menghentakkan dirinya di lantainya, menggaungkan kecemasan yang kini didera oleh sang pemilik. Beberapa kali hal itu ia lakukan, tak mempedulikan beberapa orang melewatinya. Dhisty –pemilik sepatu- tampak berpikir keras sembali melongokkan kepalanya, untuk mencuri lihat seseorang yang kini berada tak jauh dari sana, bergabung dengan segerombolan orang.
“Sial, dia kapan pergi sih!?” geram Dhisty tertahan.
Perkuliahan sudah selesai hampir setengah jam yang lalu, dan Dhisty masih di tempat yang sama dengan pandangan yang mengarah pada laki-laki dengan kemeja biru langit tak jauh dari sana. Rencananya dia sekarang harus pergi ke tempat kerjanya untuk menandatangani kontrak, dan mendapatkan arahan –sesuai dengan sms yang diterimanya beberapa waktu lalu. Sayangnya rencanaya harus terganggu karena orang itu ada di sana. Di jalan yang harus dia lewati untuk bisa pergi dari kelas. Gala, laki-laki yang bisa menjadi sangat merepotkan ketika tidak percaya.
“Belum pergi?” Asri mengampiri, kedua tangannya sibuk menyobek bagian ataas coki-coki sebelum akhirnya memasukan coki-coki itu ke dalam celah bibirnya.
Dhisty menggeleng, putus asa. “Belum.” Punggungnya menempel dengan pintu, tangannya bersidekap. “Gue heran, kenapa juga dia harus ada di sana, biasanya juga nggak pernah tuh dia nongkrong di sana.”
Asri menghendikkan bahu, “Gue nggak tahu sih jawabnya apa,tapi kadang-kadang situasi suka gitu sih.”
“Maksudnya?” Dhisty mengernyit, sembari memperhatikan Asri yang kini kembali memasukan coki-coki ke dalam mulutnya. Sebelah tangannya tidak berhenti untuk mendorong coki-coki untuk keluar dari sobekan yang telah dibuat. “Bagi elah. Lo makan sendiri aja.”
“Beli dong, masa nggak modal.” Asri menjawabnya dengan cemberut, meski begitu tidak ada keseriusan dalam suaranya. Tak lama, dia merogoh tas, mengambil coki-coki yang lain dalam tasnya. “Nih.”
Dhisty menerima. “Bantuin gue cari cara deh gimana biar gue nggak kelihatan sama Gala. Bisa berabe–ini kenapa sulit banget dibuka, sih!” keluhnya ketika jemarinya tetap tidak bisa menarik bagian atas coki-coki untuk terbuka. Beberapa kali dia mencoba, dan ketika dia putus asa, ia membawa bungkus itu di depan bibirnya, menyobeknya dengan kesal. “Gini kek dari tadi.” Dhisty tersenyum puas, sebelum menggigit dan menarik cokelat ke dalam mulutnya.
Asri menggeleng, sedikit geli. “Maksud gue itu, kayak gimana ya jelasinnya.”Ia menggaruk rambutnya sebentar, berpikir dengan cepat. “Semesta selalu sulit ditebak, ketika lo berharap untuk tidak dipertemukan, malah dipertemukan. Berharap semuanya lancar, malah nggak. Kalau bisa dibilang– ”
“Lo dipermainin.”
“Bukan!” Asri menghela napas. “Ada halangan untuk mencapai tujuan.”
Dhisty mengerucutkan bibirnya. “Iya-iya. Coba lo bantuin gue cari cara buat ngalihin si Gala. Mana dia tadi chat gue, ngajak pulang barengan.”
“Terus lo bilang apa?”
“Gue bilang, gue lagi gosip. Urusan cewek, nggak usah diganggu.”
“Terus dia balas apa?”
“Dia awalnya nanyak banget dan akhirnya bilang kalau gue udah selesai, chat dia.” Dhisty mendorong-dorong sisa coki-coki sebelum mengigitnya dengan kencang.
“Terus—”
“Berhenti bilang terus-trus! Lo mau jadi tukang parkir?” Dhsity meremas bungkus coki-coki. “Jadi, gimana nih biar gue nggak ketahuan?”
“Sebenarnya, gue bawa bajunya Kakak gue, kalau lo mau.”
“Bilang kek dari tadi!”
“Lo nggak bilang, Saudah!”
Dhisty dengan cepat merangkap pakaiannya. Dia menyembunyikan rambutnya di dalam jaket milik Kakak Asri. Tak membutuhkan waktu lama untuk mekaianya. Tak lupa memakai topi di atas kepalanya, berjaga-jaga ketika Gala menatapnya.
“Jadi, gimana selanjutnya?”
“Lompat gih dari sana.” Asri menunjuk pinggiran tembok yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Melompati itu, bisa membuat Dhsity memasuki keadaan aman yang pertama. Dia tidak akan berhadapan dengan Gala. Masalahnya adalah Gala tetap bisa melihatnya, meski ada jarak yang memisahkan mereka.
“Tetep aja kelihatan.”
“Merangkak kan bisa.”
“Gue?”
“Ya, lo.” Asri menunjuk Dhisty. “Entar gue coba alihin deh.” Ia mengintip, menghitung dan mulai memikirkan cara agar Dhisty bisa lewat.
Dhisty menghela napas panjang, sebelum akhirnya mengangguk. Masalah ini tidak seberapa dibandingkan harus mendengarkan omelan Papanya. Harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kan?
“Okey.”
Setelah itu, semuanya berada pada posisinya masing-masing. Dhisty menoleh ke arah Gala, merasa aman dia langsung meloncati bagian tembok itu dan mulai mengambil posisi merangkak. Dia memepetkan diri di dekat tembok sembari berjalan menggunakan kedua tumit, dan dorongan kakinya.
“Kak Gala? Tumben nongkrong di sini.”
Mendengar suara Asri, Dhisty mempercepat pergerakannya. Ia menutup wajahnya ketika banyak orang yang menatapnya aneh. Merasa jauh dia langsung bangkit dan kabur dari sana.
Mision complete!
****
Bangunan dengan warna cokelat yang bercampur hitam, menjulang di depan Dhisty. Di atas bangunan itu terpampang jelas, nama toko Little Bear. Dari jendela yang terbuat dari kaca, memperlihatkan bagaimana interaksi orang-orang yang ada di sana. Ada yang saling bercengkrama, tertawa, atau pun hanya diam dengan menikmati makanan yang tersaji di mejanya.
Dhisty menarik napas panjang, dia sedikit gugup. Dilihatnya kembali jam tangan cokelat yang sudah beberapa tahun menjadi temannya. Tinggal 10 menit lagi. Bibirnya mengerucut, mengeluarkan udara, menenangkan dirinya.
“Lo bisa.” Dhisty tersenyum, kepercayaan diri terpancar jelas di wajahnya. Ia mendorong pintu, memasuki toko yang akan menjadi tempat kerjanya. Ia melogokkan kepalanya, tangannya mengeratkan peganggannya pada tali tas. Ia berjalan masuk. “Permisi saya mau bertemu dengan Pak Seva,” ujar Dhisty pada salah satu karyawan di sana.
Matanya bergerak, pada name tag yang berada pada dada sebelah kiri orang itu.
Nanda.
“Oh, Pak Seva. Ada di ruangannya.” Nanda tersenyum kecil. Terlihat jelas, laki-laki itu memperhatikan Dhisty. Kedua matanya seperti sensor yang menyinari Dhisty. “Siapanya Pak Seva?”
Nggak sopan!
Dhisty ingin sekali mencolok kedua mata Nanda, namun ia menahan diri. Dia tidak mau mencari perkara,dia ingin bekerja dengan kenyamanan.
“Gue, dipanggil buat tanda tangan kontrak kerja.” Bukan berniat sombong, dia hanya menjawab apa adanya. Dhisty menoleh ke kanan dan ke kiri. “Ruang kerjanya di mana?”
“Oh.” Nanda mengangguk paham. “Biar gue anterin lo. Eh, Ka, gue pergi ke ruang Pak Seva dulu,” katanya pada seorang laki-laki yang baru saja datang setelah mengantarkan makanan.
Dhisty hanya mengangguk. Dia malas untuk membuka mulutnya. Toh tidak ada salahnya juga dia diantarkan, lumayan bisa menghemat waktu. Selagi menunggu perbincangan dua orang itu, Dhisty memperhatikan isi kafe itu. Dari tempatnya berada, dia bisa melihat dinding-dinding yang ada di berbagai sisi mempunyai corak di bawahnya. Ada bentuk pohon yang dilukis dengan indah, dan ada daun-daun yang diukir begitu selaras dengan pohon, seolah daun-daun itu jatuh dari pohon dan bergeletak begitu saja di tanah.
“Biasa, anak baru.”
Dhisty menoleh, ia mengernyitkan dahinya.
“Ayo.”
Dhisty mengikuti Nanda, ia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi orang yang bernama Seva. Dia masih mengingat seringaian menyebalkan yang tercetak jelas di wajah laki-laki itu ketika berulang kali mereka bertemu.
Mereka tak berjalan cukup jauh, hanya perlu berbelok ketika melewati dapur, ada lorong pendek, dan ruangan Seva berada di sebelah kanan.
“Ini ruangannya.” Nanda menunjuk pintu hitam dengan jemarinya. “Gue tinggal.”
Dhisty mengangguk. Dia membiarkan Nanda berlalu begitu saja. Pintu itu, entah kenapa membawa aura tidak menyenangkan untuknya. Ia memejamkan matanya hanya beberapa detik, sebelum menatap pintu itu penuh keberanian lagi.
“Permisi, Pak.”
“Masuk.”
Dhisty membuka pintu dengan santai. Tak ada keraguan dan ketidaknyamanan yang sempat dirasakan. Dua perasaan itu sudah ia kunci dalam kotak yang ada dalam dirinya.
Tak perlu memalingkan muka atau menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok Seva. Karena, ketika dia masuk, muka Seva langsung menyapanya. Laki-laki itu tidak menggunakan kacamata, membuat Dhisty hampir tidak mengenalinya, sebelum melihat tatapan menjengkelkan dari orang itu. Tidak ada yang berbeda dari Seva hari ini dibandingkan dengan yang biasa dia ketemui.
Laki-laki itu hari ini dia menggunakan kaos biasa warna hitam, dengan kacamata yang bertengger diwajahnya. Rambut lurusnya seolah hanya disisir asal-asalan, membuat beberapa helaian rambutnya masih tidak berdampingan dengan yang lain.
“Masuk, gue nggak butuh ada patung penyambut di depan kantor gue.”
Urat-urat di sekitar kening Dhisty berkedut, emosi mulai menggeliat dan berjalan di sekitar tubuhnya. Sangat terpaksa, dia melangkahkan kakinya.
Kalau gue nggak butuh kerjaan, udah gue cakar tuh muka. Songong banget sih!
“Duduk, dan baca ini.”
Dhsity menuruti, dia menarik kursi yang bersebrangan dengan Seva. Dia meraih kontrak kerja itu, matanya bergerak membaca kontrak itu dengan seksama. Ia berhenti, lalu mendongak ke arah Seva. “Ini apaan?! Nggak boleh ngupil?!”
Kontrak macam apa ini?! Seumur-umur dia tidak pernah melihat ada perjanjian seperti ini!
“Lo ngelihatnya gimana?”
“Nggak boleh ngupil.”
“Ya udah berarti benar.” Dhisty menekan kuat-kuat rahangnya. Dia ingin menampar Seva saat ini juga. Lihat betapa angkuhnya laki-laki di depannya. “Lo mau nyerah? Bukannya lo nggak mau dibilang manja? Cuman nggak boleh ngupil aja lo udah sewotnya minta ampun.” Seva mencondongkan tubuhnya. “Kalau lo emang nggak mau kerja di sini, pergi sana. Gue nggak butuh karyawan yang nggak bisa megang janjinya.”
Tidak dihargai merasa diinjak-diinjak, diremehkan. Itulah yang kini dirasakan oleh Dhisty. Gadis yang kini mengepalkan kedua tangannya, membuat kontrak kerja yang ada ditangannya ikut diremas. Tentu, dengan harga diri tinggi, ego yang begitu terluka, membuat Dhisty menyambar pena Seva. Dia tidak mau dipandang remeh oleh siapa pun, terutama cowok sialan itu.
Ujung pena itu melekuk-lekuk sesuai dengan arahan tangan Dhisty.
“Nih!” Dhisty yang sudah emosi, membanting pena itu dengan kuat, lupa akan siapa di depannya. “Gue nggak suka ada orang yang mandang gue remeh, termasuk lo!”


 D
D
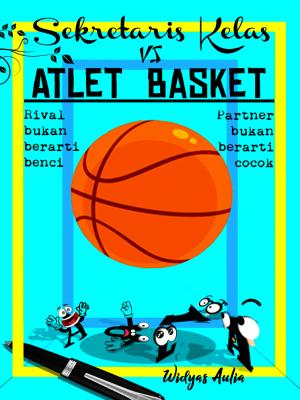




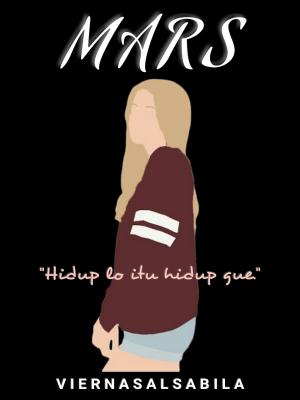



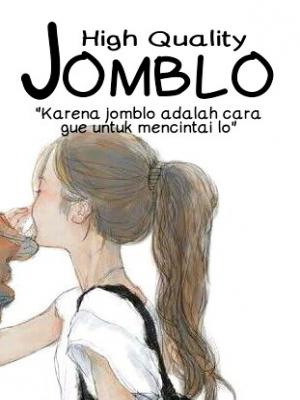
Saya anak semata wayang. Tapi saya jauh dari kata manja.
Comment on chapter Prolog