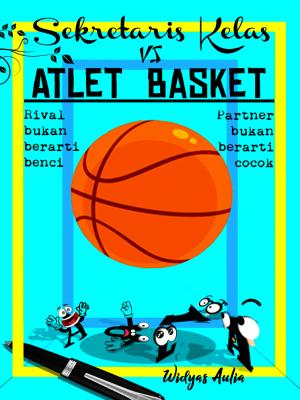Lampu pesawat telepon berkedip. Cahaya merahnya memantul di lantai yang mengilap keperakan, terlihat jelas dari pintu masuk. Tirai jendela menggelembung ketika tertiup angin, serat transparannya meloloskan sinar bulan.
Dia melepas sepatu dan kaus kakinya, menjejak lantai dengan kaki telanjang. Tagel yang dingin membuat jari-jari kakinya mengerut, tetapi setelah beberapa langkah dia menjadi terbiasa. Dia berjalan menuju dapur, menekan tombol di pesawat telepon untuk memutar pesan-pesannya sembari lewat.
Sudah tahu siapa yang meneleponnya—dan biasanya isinya tak penting—dia mendengarkan sambil lalu saja, seraya menenggak susu dingin langsung dari kotak yang dikeluarkannya dari kulkas.
Barulah pada pesan keenam sebuah suara yang sudah lama tidak dia dengar bicara,
“Jangan lupa minggu depan. Pakai baju yang pantas.”
Dia terpaku sejenak, sebelum akhirnya melempar kotak susu kosongnya ke tempat sampah dan beranjak ke lantai dua.
Minggu depan ya…
Dia mengeluarkan ponsel, lalu membuka sebuah aplikasi chat.
#
Tagel yang dingin membuat jari-jari kakinya mengerut, tapi dia harus terus melangkah. Bergerak cepat. Lari. Terus ke ujung. Harus tiba di sana secepat mungkin, sebelum—
Tirai menggelembung ketika tertiup angin, berkelepak di atas lantai yang mengilap keperakan. Lampu pesawat telepon berkedip, cahayanya membanjiri ruangan dengan warna merah menyala, sesaat, nampak seperti—
—terlambat.
…
..
.
.
.
DRRRTTTT!!!
Kay terlonjak. Detik berikutnya, yang dia tahu dia sudah jungkir balik di samping tempat tidurnya, tengkuk di lantai sementara pinggang masih tersangkut di tepi ranjang.
Dia meringis tanpa suara, berguling ke samping sehingga dia berbaring di lantai. Sementara itu telepon genggamnya terus memutar nada dering sambil berputar, getarannya teramplifikasi karena membuat meja beresonansi.
Dengan jengkel, dia meraih benda itu.
Aria Sarasvati
Ngapain orang itu menelepon jam tiga pagi?!
“Lama amat sih ngangkatnya. Aku hampir lumutan nunggu kamu ngangkat,” semprot Ra begitu Kay angkat.
Rasanya déjà vu, disemprot oleh nada tinggi melalui telepon.
“Lebay ah,” gerutu Kay dengan suara mengantuk.
“Coba aja kamu yang nelepon orang terus dicuekin sampe dering kesebelas!”
“Kamu ngitung?”
“Kamu lagi dimana?”
Kok pertanyaannya lucu…
“Di rumah.”
“Oh.”
Hening.
Kay melepas telepon dari kupingnya dan menatap layarnya, yang menampilkan nama dan foto Ra. Fotonya hanya berupa ilustrasi generik: siluet anak perempuan dengan rambut dikuncir dua.
Kadang Kay takjub deh dengan ponselnya ini. Dia suka menempelkan siluet yang benar ke kontak yang benar. Misalnya, kontak Ra ini otomatis dikasih gambar siluet anak perempuan. Lalu kontak Kak Biwa dapat siluet anak laki-laki. Kok bisa tahu ya? Benar-benar smart phone.
Tapi, balik lagi ke topik: memangnya ada suatu alasan untuk Kay tidak berada di rumah pada jam tiga pagi?
“Aku kira kamu bakal keluyuran di jalan jam segini,” kata Ra.
“Ngapain?!”
“Kenakalan remaja.”
Kay ingin membanting hapenya.
Eh, jangan, nanti dia tidak punya gantinya. Mending membanting Ra.
“Ra… saya mau tidur lagi. Teleponnya ditutup ya.” Tapi Kay sebenarnya tidak yakin akan bisa tidur lagi, karena matanya sudah melek semelek-meleknya. Paling tidak dia bisa belajar. Belum ada PR sih, tapi kan tidak ada salahnya mencoba-coba mengerjakan soal. Siapa tahu dia jadi mengantuk lagi.
“Ehhhh… tunggu bentar!”
“Ya?”
“Hari ini datang ke UKS jam tujuh ya.”
“Hah? Pagi banget? Buat apa?”
“Buat apa? Ya kerja lah! Ada banyak curhatan masuk tuh, nunggu dijawabin.”
Tapi kenapa harus jam tujuh? Sekarang kan Sabtu. Selain itu, menjawab chat kan bisa darimana saja. Sambil tiduran di kamar misalnya.
“Oke ya? Awas lho. Kalau telat, push up tiga seri per menit telat.”
Idih, kayak zaman MOS saja.
…Waktu MOS, Ra seperti apa ya? Rasanya sulit membayangkannya disuruh push up, merangkak, dan hukuman-hukuman bodoh lainnya. Jangan-jangan malah dia yang membuat panitia koprol saking dongkolnya.
“Selamat tiduuur…” akhirnya Ra menutup pembicaraan dengan salam yang berirama. “Oh iya, Key.”
“Hng?”
“Enak ya denger suara kamu?”
Kedua mata Kay langsung terbelalak.
Ap—apaaaa?
Aduh. Dadanya terasa aneh. Kepalanya jadi ringan dan kosong.
Kay tidak bisa berpikir. Kantuknya sudah hilang 100%, tapi otaknya tumpul, tidak mau bekerja.
“Okeee… yuk ya. Jangan telat!”
Tut… tut… tut…
Kay baru menyadari ketika tangannya terasa pegal, bahwa dia telah duduk dalam posisi telepon menempel di sisi wajahnya dan memandang kosong ke pintu di depannya selama dua jam.
#
Sekelompok anak Paskibra berpapasan dengannya di gerbang. Mereka sedang berlari keluar dalam seragam kaus putih dan celana lapangan serta topi dan handuk putih di kepala, berderap dalam dua banjar yang rapi sambil menyanyikan lagu-lagu mars.
Di seantero sekolah, barangkali cuma Paskibra yang jam segini sudah mulai kegiatan—selain para aktivis UKS tentu saja.
Ketika dia tiba di ruangan yang sangat dihindari mayoritas warga sekolah itu, Ra sudah ada di dalam, sedang duduk sambil bertopang dagu menekuri sesuatu di laptopnya. Hari ini dia mengenakan blus putih dan rok selutut yang sangat mirip dengan seragam sekolah. Rambutnya diikat buntut kuda secara asal, beberapa helaian, merah kekuningan ditimpa cahaya matahari pagi, tergerai di lehernya.
Penasaran, Kay berdiri di belakangnya, ikut melihat apa yang membuat kakak kelasnya itu berpikir begitu keras.
Ra tiba-tiba bersandar.
Kay spontan mencelat mundur karena kaget.
“Whoa!” Ra menjerit tertahan, sejenak kehilangan keseimbangan. Kay pikir Ra akan jatuh secara heboh, bahkan dia sudah siap-siap merasa bersalah kalau anak itu terkilir gara-gara jatuh dari tempat duduk, tapi Ra segera mencengkeram sisi kursinya kemudian—voila! Kursinya kembali tegak. Dia langsung melempari Kay pelototan pedas. “Kok kamu mundur sih?!”
“Saya kaget!” jawab Kay, tapi sejujurnya dia paling kaget melihat pertunjukan barusan.
“Jadi cowok, kagetan,” dumel Ra.
Cowok nggak boleh kaget?!
“Sini, duduk.”
Ra menarik satu kursi supaya dekat di sebelahnya. Kay menurut.
“Kita mau ngapain hari ini?” tanyanya.
“Kita punya dua agenda.”
“Bukan tradisi kayak kemarin kan?” sela Kay, teringat anak-anak Paskibra di gerbang. Ekskul lain pasti latihan juga kan? Apakah akan terjadi banyak kecelakaan juga?
“Kemarin itu pengecualian, soalnya banyak anak baru yang coba-coba. Sekarang mereka udah tau ekskul yang cocok buat mereka, jadi angka kecelakaan juga berkurang drastis.”
Kay mengangguk-angguk. Cukup masuk akal.
Rasanya aneh sekali punya pikiran begini, tapi setelah dipertimbangkan masak-masak, kegiatan paling aman di sekolah ini justru nongkrongin UKS. Satu-satunya kekurangan dari nongkrongin UKS adalah harus rela berinteraksi dengan Ra. Tapi, sebenarnya Ra tidak jelek-jelek amat. Dia hanya tidak berperasaan saja. Dan itu, kalau direnungkan secara objektif dan mendalam, bukanlah kesalahan. Apakah orang yang tidak punya tangan dianggap salah kalau tidak bisa menulis? Ra begitu—bedanya, dia tidak punya hati.
Barangkali, itulah yang membuat Kay tidak bisa berempati dengan Ra, sehingga ketika bersamanya, hati Kay justru menjadi lapang.
Jangan sampai Kak Erhu mendengar ini. Bisa-bisa dia melompat-lompat kegirangan karena berpikir plotnya berhasil.
“Lagian, ada rumor kalo ruangan ini dikutuk lho.”
“Masih ada yang percaya takhayul kayak gitu?”
“Buktinya nggak pernah ada yang dateng ke sini kalau bukan karena kepepet.”
Jangan-jangan kutukannya itu kamu?!
“Terus, belakangan ini banyak berita orang-orang dirampok di jalan. Kejadiannya menyasar pengendara motor, antara jam dua sampe jam empat pagi,” ujar Ra, tiba-tiba membuka topik baru. Mata bundarnya menatap Kay serius.
“Jadi kamu nelepon saya jam tiga pagi karena kuatir saya dirampok?”
“Ehh… kok kamu tai—eh, tau?”
Kay melempari Ra pandangan datar.
“Pertama: saya nggak punya alasan buat keluar rumah jam segitu. Kecuali mungkin kalo darurat banget. Kedua, saya nggak bisa ngendarain motor.”
“Kamu nggak bisa ngendarain motor?”
“Saya bahkan nggak punya SIM.”
“Tapi siapa sih yang repot-repot bikin SIM hari gini?”
Jangan ngomong kayak itu hal biasa!
“Aku aja dari SD udah bisa motoran lho.”
Itu sih salah asuhan!
“SMP udah bisa motoran sendiri ke sekolah.”
“Hah? Emang nggak dimarahin guru?”
“Nggak dong, kan ayahku suka ngasih uang.”
Nggak usah bangga!
“Kamu nanti aku ajarin motoran deh. Kasian banget sih anak cowok nggak bisa bawa motor.”
“Kayak yang kamu bisa aja. Motor kan berat.”
Hening sejenak, sementara Kay dan Ra bertukar pandangan.
Sejurus kemudian, Ra tertawa terpingkal-pingkal.
“Barusan kamu bercanda ya? Hahahaha…”
…
Memberikan lelucon yang ditertawakan itu menyenangkan. Tapi Kay punya perasaan bahwa Ra menertawakan dirinya, bukan leluconnya, dan itu tidak menyenangkan.
“Jadi, agenda kita?” tanya Kay sebal.
“Pertama-tama kita mau jawab beberapa chat yang masuk. Lumayan lho, sejak ada Cantabile tiba-tiba jadi banyak banget yang ngepost. Kayaknya orang-orang penasaran kamu siapa. Banyak cowok yang minta kenalan.”
“Jadi saya dikira cewek ya?”
“Emangnya cowok cuma mau kenalan sama cewek?”
“Yaa… enggak sih. Tergantung minta kenalannya buat apa.”
“Hm…” Ra menggumam sambil mengeklik satu postingan. “’Hai, Cabi… kamu imut banget sih, kok DP-nya arwana? Ini no telp aku…’”
“Hoekk…”
“Cantabile enak ya…” kata Ra.
“Enak apanya?”
“Kalo disingkat jadi ‘Cabi’. Kedengeran imut gitu. Apa kita tukeran?”
“Saya nggak terlalu peduli sih, tapi emangnya kenapa sama Dolce? Bukannya Dolce artinya ‘manis’ ya?”
“Dolce kalo dibikin panggilan sayang jadinya ‘Dodol’.”
Kay spontan menyembur tertawa.
“Kan… kan…” Kay menarik napas dalam-dalam, “kan dodol manis… cocokkkk hahahahaha…”
Kay tertawa begitu keras sampai memukul-mukul pahanya sendiri.
“Tapi… enggak deh, Cantabile lebih cocok buat kamu. Imut-imut gitu.”
Kay spontan tersedak tawanya sendiri.
“Nah… tugas pertamamu adalah ngejawab chat yang baru masuk itu. Tapi ingat: jangan kasih nomor handphone! Korespondensi dengan kita sebagai pengasuh Curhatroom cuma boleh lewat chat ini.”
Kay tidak berniat melakukannya, tapi bertanya saja untuk kejelasan, “Emang kenapa? Biar nggak ketahuan?”
“Repot kan kalau inbox kita di-spam stalker.”
“Wah, bisa ya?” Memangnya kita cukup populer untuk di-stalk? pikir Kay.
“Iya. Udah gitu isinya, ‘Mati sana!’ ‘Mampus loe!’ ‘Gua sumpain perawan tua loe!!!’”
“Serem!”
“Ya kan.”
“Itu pengalaman pribadi?”
“Iya!”
“Nggak usah kedengeran bangga…” Semakin lama berbincang dengan Ra, Kay menemukan semakin banyak fakta anehunik tentangnya. Yang membuatnya penasaran adalah mengapa Ra menyebutkan pengalaman-pengalaman itu secara ringan, seperti menceritakan pengalaman orang lain yang dianekdotkan? Apakah itu cara Ra supaya tidak merasa sedih?
Sekali lagi Kay menyayangkan ketidakmampuannya berempati dengan Ra. Tapi mungkin, memang Ra-nya tidak merasakan apa-apa. Apa mungkin seorang gadis remaja tidak merasa apa-apa disumpahi seperti itu?
“Terus apa agenda kedua kita?”
“Kita ikut rapat OSIS jam sepuluh, di kelas XI-12.”
“Rapat OSIS?” ulang Kay heran. Ra tidak kelihatan punya aura anggota OSIS. Kalau dalam pemerintahan, dia itu tipe kubu oposisi nonkooperatif. Bahasa populernya: teroris.
“Iya, aku diundang kali ini,” Ra mengangguk. Sekilas pandangannya beralih ke langit di luar, terlihat agak keruh. Kay memerhatikannya lekat-lekat.
“Kenapa?”
“Apa karena aku juru kunci UKS ya?”
“Nggak. Maksudnya, saya juga pengen tau alasan kamu diundang, tapi maksud saya tadi, kenapa kamu kayaknya ada pikiran?”
“Karena aku punya otak?”
“Maksudnya kamu kayak nggak sreg sama rapat ini,” Kay cepat-cepat mengklarifikasi dengan gemas. Ra jago banget deh membuyarkan simpati orang. “Punya bahan pikiran, gitu. Merasa ada yang salah.”
“Oh, itu.” Ra berhenti sejenak untuk menatap langit lagi. “Aku heran aja sih kenapa diundang. Soalnya aku nggak pernah punya hubungan sama OSIS.”
Kalau begitu, memang aneh. Anak-anak OSIS itu tidak bermaksud menjebak Ra kan? Apa mungkin ada yang begitu membenci Ra sampai ingin menjahatinya? Mengurungnya di dalam kelas yang sudah dibuat kedap lalu mengalirkan gas karbondioksida ke dalamnya, misalnya.
Atau barangkali Kay sudah keracunan komik detektif langganan Kak Erhu.
“Saya nanti ikut kan?”
“Tadi kan aku bilang kita.”
Kay mengangguk. Kalau begitu aman—apapun itikad buruk dari si pengundang rapat ini, Kay akan berusaha sekuat tenaga menghalanginya.
#
Di luar dugaan, menjawab chat bisa menguras tenaga juga.
Jam sepuluh kurang lima, Kay baru selesai menjawab pertanyaan seorang siswi kelas XII yang bercerita bahwa orang tuanya memaksanya berhenti aktif di ekskul dan mulai bimbel, padahal saat ini ekskulnya—Klub Handicraft, atau disingkat Handy—sedang mempersiapkan kegiatan akbar tahunan. Karena masalah tersebut, hubungannya dengan orang tuanya jadi renggang.
“Bilangin, jadi orang itu harus punya tujuan yang jelas, biar bisa bikin prioritas,” kata Ra. “Brenti ekskul atau enggak, dua-duanya nggak salah, tergantung dia maunya ngapain abis lulus dari sini.”
Yang sebetulnya adalah nasihat yang lumayan. Yang jelas, jawaban yang cuma satu kalimat itu Kay parafrasa dulu sehingga bertransformasi jadi sebuah esai. Bisa kacau kalau dia sampaikan kata-per-kata.
Namun, setelah menekan tombol Kirim, dia malah jadi tidak percaya diri kalau nasihat yang diberikannya sudah tepat.
Apakah itu jawaban yang diinginkan penanya? Apakah itu jawaban yang dibutuhkannya? Apa dia terdengar menggurui? Padahal dia sendiri masih kelas X. Dan meski pahit mengakuinya, selain ingin segera membalas kebaikan Papa dan Mama, Kay tidak punya tujuan konkret yang bisa diukur. Memangnya boleh orang yang tujuan hidupnya sendiri tidak jelas sepertinya sok menasihati orang lain, kakak kelas pula, soal cita-cita?
“Mukamu kayak kelinci belum kawin aja,” celetuk Ra.
“Metafora macam apa tuh?!”
“Jadi orang itu jangan terlalu perasa. Nanti capek sendiri.”
Dikatakan oleh orang yang tidak berperasaan membuat kata-kata itu jadi kehilangan maknanya. Kay mengerutkan kening. Ra sedang mengeset laptopnya ke mode hibernate.
“Kamu kok bisa santai gitu ngasih jawaban sama orang-orang ini? Nggak takut salah ngasih masukan?”
“Kenapa takut? Aku kan ngasih nasihat dipikir dulu, jalan keluar mana yang terbaik. Kalau semuanya sudah dipertimbangkan, nggak ada lagi alasan untuk takut melangkah.”
“Haha… dipikir ya…” kata Kay skeptis.
Mereka keluar dari UKS, ke koridor yang sunyi. Langkah kaki mereka terdengar bergaung. Perpustakaan tutup pada hari libur, pintu gandanya yang berukir lambang sekolah nampak megah dan kokoh.
“Aku juga nggak selalu nyampein setiap solusi terbaik, kok. Kadang aku kasih solusi nomor dua atau nomor tiga.”
“Ohya? Kenapa?”
“Gimana jadinya kalau solusi nomor satunya itu bunuh diri?” tandas Ra, membuat langkah Kay terhenti. Telinganya tiba-tiba berdenging. “Maksudnya… mengesampingkan masalah moral dan adat, bunuh diri itu solusi pamungkas semua masalah nggak sih? Kalau kamu mati, kamu nggak lagi sakit kan? Memang keluargamu jadi dapat masalah baru, tapi masalahmu selesai kan? Itu kalau mau egois ya… tapi kan…”
Kay terdiam mematung, tidak lagi mendengarkan. Sejenak saja, pandangannya menghitam, seperti lampu yang berkedip karena gangguan listrik. Lalu, fenomena berikutnya terjadi dalam urutan peristiwa yang cepat. Tubuhnya seolah menolak menuruti perintah otaknya; tungkai-tungkainya membeku. Pendengarannya masih tertutup bunyi yang memekakkan. Kabut kelam turun dari langit, membatasi pandangan. Kay mengerjap. Namun, semakin banyak dia mengerjap, matanya terasa makin perih dan kabutnya semakin tebal, mengisolasinya. Di kejauhan, nampak siluet-siluet samar. Tirai yang berkelepak ditiup angin… sosok yang melayang di atas tagel yang memantulkan cahaya bulan…
Sesuatu mendarat di pundaknya, membuat Kay terlonjak.
“Hei. Kamu kenapa? Kelilipan?”
Penglihatannya kembali jelas. Di depannya, Ra sedang menatapnya dengan alis terangkat. Gadis itu menggenggam wajahnya dengan kedua tangan, ibu jari menyapu pipinya dengan lembut, mengusap air mata yang Kay tidak tahu kapan keluarnya.
Kay menggeleng. Dia menjauhkan tangan Ra dan mengusap wajah dengan punggung tangannya sendiri.
Dia membuka mulut, hendak menjawab. Tapi suaranya tertahan di kerongkongan.
Tenang, tarik napas… kata-kata Kak Erhu terngiang.
Kay menarik napas dalam-dalam, sampai rasanya seluruh tubuhnya menggelembung terisi udara.
“Nggak”—Kay menarik napas lagi, kali ini lebih pelan,—“nggak kenapa-kenapa.”
Ra mengernyit. Kay membayangkan otaknya bekerja dalam kecepatan penuh. Mendadak Kay memiliki ketakutan konyol bahwa Ra tahu persis apa yang sedang berkutat di dalam kepalanya. Apakah dia begitu mudah dibaca? Mungkin ya. Kak Erhu seperti selalu tahu apa yang dipikirkannya. Selalu tahu kalau dia sedang down atau mengalami flashback. Dia membayangkan wajahnya menjadi kaku dan matanya menjadi kosong ketika hal itu terjadi, tetapi dia tak akan pernah tahu pasti. Pemikiran ini membuatnya ngeri.
“Saya nggak apa-apa, Ra. Cuma ngantuk.”
Ra mengangguk, tapi Kay tahu dia tidak percaya. Kay bersiap-siap menghadapi interogasi, tetapi betapa herannya dia karena Ra tidak mendesaknya untuk bicara. Berpura-pura memercayainya itu tanda-tanda simpati kan? Atau Ra tidak berpura-pura, dan memang percaya saja apa yang keluar dari mulutnya?
Ra berbalik, melanjutkan perjalanan. Sejurus kemudian Kay mengikutinya.
“Hati-hati lho, jangan ngelamun sambil jalan,” kata Ra. “Kamu harus tau, pernah ada anak yang kejeduk tiang listrik terus…”
Kay mengabaikannya. Dia memandang kedua tangannya yang bergetar hebat. Sudah berbulan-bulan lewat sejak terakhir dia mengalami flashback. Sudah lama sekali. Dia pikir masa itu sudah lewat. Dia pikir dia sudah melangkah maju.
Namun, sepertinya dia terlalu optimis.
Optimis ya? Hal itu membuatnya tertegun. Dalam kasusnya, mungkin yang benar bukan optimis, tapi arogan. Atau delusional.
Baru berapa tahun sejak saat itu? Rasanya seumur hidup pun tidak cukup lama. Lagipula, apa pantas dia meninggalkan peristiwa itu di belakang? Bukankah kemampuannya saat ini adalah karma—hukuman—dari Yang Mahakuasa? Sementara hukuman ini masih berlangsung, Kay tidak sepantasnya merasa bebas.
Ra semakin jauh di depan, masih berbicara, tetapi Kay tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Sesuatu tentang tiang listrik? Tiang telepon? Entahlah. Bahunya nampak berguncang. Dia sedang tertawa? Menertawakan apa?
Menertawakannya?
Kay ingin meringkuk. Perutnya tidak nyaman. Seperti baru turun dari wahana pemacu adrenalin. Seperti sepanci larutan jeli yang digoyang-goyangkan. Hanya saja, di dalam perutnya cuma ada asam. Ketika asam itu naik, mualnya tidak karu-karuan. Sementara itu, kakinya makin lama makin berat, seakan-akan sepatunya terbuat dari logam pejal.
Tarik napas dalam-dalam… Tetapi semakin dia mencoba menenangkan diri, semakin dia berdebar-debar. Kepalanya tahu apa yang harus dia lakukan untuk merasa lebih baik, tapi dia perlu sugesti yang lebih kuat.
Dia perlu bertemu seseorang. Dia perlu bicara.
Tanpa pikir panjang, Kay masuk ke sebuah ruangan, kemudian mengunci pintunya dan duduk. Cepat-cepat dikeluarkannya ponselnya lalu menghubungi nomor darurat. Setiap detik yang terlewat serasa berjam-jam.
Dia terhubung setelah dering ketiga. Tiga dering nada sambung yang panjang.
“Hai, hai… tumben kamu nelep—”
“Kak,” Kay menyela.
Terdengar gemerisik kain dan denting porselen di sisi sana. Mungkin Kak Erhu sedang menyiapkan sarapan atau mencuci piring, lalu menghentikan pekerjaannya untuk bicara dengan Kay. Mengetahui hal itu saja rasanya membuat mualnya mereda.
“Kay, ada apa?”
Bahkan dari jarak sejauh ini, dia masih bisa merasakan kehangatan Kak Erhu menjalari nadinya. Ketika tubuhnya terasa hendak shutdown, Kay selalu refleks mencari Kak Erhu. Nomor darurat di ponselnya pun terhubung ke kontak Kak Erhu, supaya dia tetap bisa menelepon dengan mudah dan cepat ketika tangannya gemetar.
“Kak, saya—“
“Kak Erhu bukan kakakmu! Kamu bukan siapa-siapa!”
Suara itu muncul entah darimana, menghentikan ucapan Kay.
Kepala Kay menjadi kosong, pikiran-pikiran meninggalkannya entah kemana.
Jika tidak bisa bicara dengan Kak Erhu, lalu dia harus bicara dengan siapa? Mungkin seharusnya dia bisa mengatasi masalahnya sendiri?
Bukankah dia tidak ingin merepotkan siapa-siapa lagi?
Kay seperti melayang dan melihat tubuhnya dari atas, duduk mematung, dengan ponsel perlahan tergelincir dari pegangan. Benda itu jatuh berkelotakan di lantai, tetapi layarnya masih menyala. Suara Kak Erhu terdengar menjerit-jerit dari sana, kalut.
“Kay? Kay?!! Kamu dimana?”
Tiba-tiba, pintu digedor, disusul teriakan rusuh.
“Key! Kamu di situ? Keeey!!”
Kay bergidik, seperti disiram seember air es. Darah kembali mengaliri otaknya dalam letupan debit. Pening, tetapi kembali berfungsi, Kay meraih ponselnya dari lantai.
Suara Kak Erhu masih terdengar, tetapi kata-katanya tenggelam oleh gedoran Ra yang makin lama makin brutal. Kay khawatir pintunya akan segera copot dari engselnya. Kalau itu terjadi, entah konsekuensi seperti apa yang harus diterimanya.
“Kak, sori, teleponnya saya tutup ya?”
“Hah? Hei, kamu nggak apa-apa? Kamu—“
Kay buru-buru memutus koneksi, memutus kata-kata Kak Erhu. Dibukanya kunci pintu.
Bukan pilihan bijak, tapi dia memang sedang tidak dalam kondisi sanggup berpikir ke depan.
Karena begitu dia melepas kunci, Ra yang masih menggedor membuat pintu menjeblak ke dalam.
JDUAKK!!
Kay langsung jatuh terjengkang.
“Key!!” seru Ra.
Gadis itu segera berjongkok di depannya dan memeriksa kepalanya. Ketika jemarinya menyibak rambut dari dahi Kay, rasanya seperti ada bagian yang kebas. Jangan-jangan benjol.
Benda kotak di tangan Kay bergetar dan mengeluarkan dering.
Pasti Kak Erhu yang menelepon balik.
Bisa gawat, pikir Kay, walau tidak jelas mengapa dia berpikir ada yang gawat. Dengan kepala yang belum sepenuhnya pulih, dia memutuskan untuk me-reject telepon Kak Erhu dan mematikan ponselnya.
“Key, bisa lihat jariku? Ada berapa?” tanya Ra, mengacungkan tangannya.
“Dua.”
“Hari ini tanggal berapa? Kita lagi dimana?”
“Sebelas Agustus. Di—“ Kay terbelalak. Baru disadarinya ruangan apa yang dimasukinya tadi. “Ra, ini kan toilet cowok!!!” serunya sambil cepat-cepat berdiri. Didorongnya Ra sampai mereka berada di luar ruangan ‘terlarang’ itu.
Ra langsung memberondongnya dengan omelan.
“Kamu sendiri! Mau ke toilet bilang-bilang dong! Nggak usah nahan kebelet sampe nangis gitu. Aku kan tadi jadi ngomong sendiri kayak orang bego!”
“Iya, iya, maaf, tadi buru-buru.” Kenapa saya jadi minta maaf… pikirnya.
“Terus… kamu suka pup sambil nelepon ya?”
Kay ternganga mendengarnya. “Saya nggak pup! Dan saya nggak suka pup sambil nelepon!”
“Terus kok aku denger suara Bu Erhu?”
Eeh… menyeramkan sekali. Dia bisa bisa mendeteksi suara yang sudah terdistorsi filter di tengah-tengah teriakannya sendiri? Jangan-jangan dia pernah semedi di gunung untuk mendapatkan kemampuan yang nyaris supranatural itu.
Tapi, itu tidak penting saat ini. Kay memandang ponselnya, layarnya hitam dan mulus, tidak lecet meskipun sudah terjatuh lumayan keras. Hanya bagian pinggirnya yang tergores. Untunglah. Kak Erhu mungkin akan meneleponnya lagi nanti, dan memarahinya karena memutus telepon seenaknya, tapi yang penting sekarang dia sudah tidak apa-apa.
…
Benarkah?
Jantungnya masih bertalu-talu, residu dari pompa neutrotransmitter yang bekerja ugal-ugalan. Bukan kejadian baru, tapi memang baru terjadi lagi setelah sekian lama sehingga sensasinya begitu kuat.
Kay mempertimbangkan untuk pulang saja, tapi membayangkan transportasinya bikin perasaannya tambah tidak enak. Sementara jalan kaki bukan pilihan bijak. Dia bisa saja sih jalan kaki sampai perasaannya baikan, lalu sambung naik bis… tapi kalau Lyra ada di rumah, itu sih namanya keluar kandang buaya, masuk kandang komodo.
Bukannya dia mau mengasosiasikan Ra dengan buaya, dan Lyra dengan komodo, ya. Hanya peribahasa yang sedikit disesuaikan dengan kondisi lapangan saja.
“Ngomong-ngomong, kamu pucat lho. Aku minta maaf deh kalau ngeganggu mood kamu. Aku tau kok gimana menderitanya nahan-nahan.”
“Saya nggak pingin pup!” bantah Kay sekali lagi, lebih keras.
“Yakin? Kalo ditahan-tahan nanti jadi penyakit loh. Namanya Pup Disorder. Disingkat pe-de.”
“Jangan nyiptain penyakit aneh-aneh!”
Ra memberi Kay tatapan no-nonsense yang menimbulkan keinginan kuat di diri Kay untuk menyumpalkan kaus kaki ke mulutnya.
“Beneran, saya nggak pingin pup! Kenapa kita malah ngedebatin ini sih?”
“Ya udah kalo gitu. Ayo, kita udah telat.”
Ra meraih tangannya lalu kembali mengayun langkah. Kay setengah terseret mengikutinya. Jika Ra merasakan tangannya lembap oleh keringat, gadis itu tidak mengomentarinya. Kay ingin melepaskan diri, tetapi entah mengapa genggaman Ra yang kuat menjadikannya lebih tenang. Bagaikan air dalam bak mandi yang sumbatnya dilepas, ketegangannya seperti menggelontor keluar dalam pusaran berkecepatan tinggi. Ironis sekali, karena penyebab Kay kumat adalah omongan gadis itu sendiri. Betapa mengerikannya ketika kata-kata yang diucapkan sambil lalu bisa membuat dunianya jungkir balik seperti barusan.
Kalau sampai Ra tahu kondisinya yang menyedihkan ini, bisa tamat riwayatnya.
Atau mungkin tidak? Ra bukan tipe yang suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Kelihatannya begitu. Tapi, bukan berarti dia akan berhati-hati supaya tidak menginjak ranjau pemicu. Jikalau demikian, Ra tahu atau tidak tahu tidak ada bedanya.
Kay menghela napas.
Benar-benar manusia yang rumit.
Tapi masih lebih parah dirinya, yang sudah sok-sokan membicarakan soal membalas budi, padahal mengurusi diri sendiri saja tidak becus.


 drei
drei