BAB 11. TERSESAT DI BELANTARA KALIMANTAN
HARI KE-39, PONTIANAK
Aku masih saja termenung menatap topi koboi warisan ayahku, mengingat-ingat masa lalu. Celah-celah dalam kalbuku terguncang dijajah kerinduan setiap kali teringat Ayah. Samar-samar aku ingat wajahnya yang tegar saat ia meninggalkanku bersama Ibu. Kala itu, aku yang belum mengerti apa-apa tak pernah menyadari bahwa saat itulah terakhir kali aku melihatnya. Jika dipikir, nasibku mirip dengan Harto dan Nasuti, hanya saja aku sedikit lebih beruntung.
Aku mendengus. Dengan muram, kumasukkan topiku ke dalam ransel, lalu meraih HP yang berbunyi sejak tadi, tapi kuabaikan. Pasalnya, tiga hari terakhir ini ada orang tak dikenal yang rutin mengirimiku sms, dua kali sehari. Sms yang dikirimkan juga aneh-aneh. Awalnya sih biasa saja, seperti bertanya kabar dan sebagainya, tapi makin lama makin mencurigakan. Dia seperti menggodaku, dengan seringnya bertanya apa makanan favoritku, kapan hari ulang tahunku, dan hal personal lainnya.
Aku tak tahu siapa orang ini. Dia tak pernah membalas jika kutanyakan identitasnya, tapi tampaknya dia mengenalku dengan baik. Dia tahu bahwa aku ikut Kempo, tahu aku anak fakultas biologi, dan tahu nama-nama teman dekatku. Aku jadi ingat kata-kata Hana tempo hari, bahwa aku punya banyak penggemar rahasia, benarkah itu? Aku ingat ada beberapa gadis yang minta tanda tangan setelah aku memenangkan turnamen, tapi aku tidak yakin jika orang misterius ini salah satu dari mereka. Aku punya perasaan kuat bahwa aku juga kenal orang ini. Nomor yang digunakan si secret admirer juga itu-itu saja. Sebenarnya, siapa sih dia? Bagaimanapun, aku tak menghargai tindakannya yang mengganggu privasiku itu.
Sms yang paling parah, sampai membuatku jengkel, seperti ini misalnya: Halo Sayang, udah makan belum? Kalau makan sedikit, nanti tambah kurusan lho. Jika aku tidak sayang HP-ku, pasti sudah kubanting. Enak saja dia mengataiku kurus. Itu kekurangan fisik yang paling menggangguku, tidak boleh disebut-sebut sembarangan jika tak ingin sifat asliku keluar. Dikatai kurus kecil dan dipanggil dengan sebutan “Dek” oleh orang yang seumuran atau lebih muda adalah hal yang paling sering membuatku sebal. Teman-temanku sudah hafal betul dengan aturan ini.
“Mereka memanggilmu Dek karena wajahmu awet muda, babyface, kayak anak SMA. Harusnya kau senang kan?” begitu Harto biasa menghiburku.
Aku jadi teringat surat singkat yang diberikan Meutia, gadis pelukis dari Aceh. Kucari-cari di ransel, lalu kubaca lagi surat singkat itu, yang kutemukan di balik lukisan pemberian Meutia tempo hari. Aku memang sempat melihatnya menulis sesuatu, tapi aku tak menyangka gadis itu menyelipkan secarik kertas kecil dalam kanvasnya. Pesannya seperti ini:
Teruntuk Kak Lutfi dan Kak Harto
Saya tak pernah menyangka bagaimana takdir mempertemukan kita, tapi saya merasa bahwa pertemuan ini sangatlah berarti. Melihat kalian, saya merasakan sesuatu yang berbeda, dan saya bisa lega berekspresi dengan lukisan hanya dengan melihat wajah cerah kalian. Energi semangat yang kalian tularkan begitu besar. Tampaknya kalian bukan orang biasa, ya? Saya merasa kalian berbeda dengan pengunjung lainnya. Saya tahu kalian punya masa lalu yang mirip dengan saya, dari sorot mata kalian.
Pertemuan kita memang sangat singkat, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik. Kalian memberi inspirasi baru untuk lukisan saya berikutnya. Terutama Kak Lutfi, yang rela menemani saya melukis. Saya tahu apa yang dilukis Kak Lutfi, meski belum selesai, dan saya senang sekali saat tahu lukisan apa itu. Maaf, saya sempat curi-curi pandang lukisan itu. Lukisan yang sangat bagus. Tampaknya bakat saya belum ada apa-apanya dibanding Kak Lutfi. Saya masih butuh belajar. Kemarin, ada seorang pengusaha yang menawar lukisan saya. Insya Allah, sebentar lagi saya bisa membeli HP, benda yang sudah lama sekali saya inginkan. Saya berharap kita bisa bertemu lagi suatu saat.
Terima kasih untuk segalanya.
Aku senang menerima surat bernada bahagia ini. Meutia memang layak mendapat kehormatan itu. Dia gadis yang ramah, berbakat, dan pantang menyerah. Sudah sepantasnya dia menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia bukan gadis tak berdaya yang butuh uluran tangan, melainkan sosok mandiri yang berani mengambil tindakan demi melepaskan diri dari jerat kemiskinan.
Tapi aku juga curiga, karena seingatku, kertas yang kupakai melukis dan kuberikan padanya ada nomor HP-ku di baliknya. Buku sketsaku itu sering kucoret-coret dengan aneka catatan di kala iseng. Jangan-jangan yang mengirimiku sms gombal itu Meutia? Ah, tapi tak mungkin, aku tahu betul dia bukan tipe gadis seperti itu. Meutia sangat sopan, sedangkan sms yang sering menggangguku itu bernada genit dan jauh dari sopan. Hari ini saja sudah sepuluh kali sms itu berdatangan, dengan nomor yang sama pula.
Sayang, udah makan belum? Sayang, bobonya jangan kemalaman ya… Sayang, jangan lupa oleh-oleh buat aku ya… Sayang, sebenernya aku pengen ikut, tapi aku sibuk, maaf ya… Sayang, inget aku kan? Aku yang waktu itu lho… Ah, memangnya dia siapa menggercokiku terus seperti itu? Kuabaikan saja.
“Hei, Lutfi, sudah siap?” Harto muncul di pintu, melambai. Sejak tadi, dia dan Nasuti kubiarkan lebih dulu berkeliling melihat pemandangan.
“Apa?” aku refleks menurunkan HP. “Oh, baiklah, ayo!”
“Kau habis melamun ya?” Harto mengernyit.
"Nggak kok,” kataku, mengusap wajah dan menarik napas, berusaha tampak senormal mungkin, lalu melangkah keluar menyusulnya. “Sudahlah, ayo!”
Aku melangkah keluar, menginjakkan kaki tepat di perbatasan garis khatulistiwa. Di hadapanku, bangunan Equator Monument yang menjadi ikon Kota Pontianak itu berdiri megah, terdiri atas empat tonggak kayu yang menyangga sebuah lingkaran dan anak panah. Sayangnya kami datang di waktu yang salah karena tak bisa melihat fenomena titik kulminasi matahari, yaitu ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Posisi seperti itu menyebabkan hilangnya semua bayangan benda, termasuk bayangan Tugu Khatulistiwa itu sendiri yang lenyap selama beberapa detik. Peristiwa itu hanya terjadi antara tanggal 21-23 Maret dan 21-23 September saja. Tapi setidaknya kami sempat berpose di depan Tugu dan mencicipi kuliner lezat seperti sotong bakar dan es lidah buaya.
“Kalian siap-siap, habis ini perjalanan akan sedikit berat,” kataku.
“Emangnya ke mana, Kapten?” Harto menenggak habis esnya.
“Ada deh, pokoknya spesial,” aku membuka peta, melihat lokasi berikutnya.
Dari Pontianak, kami menempuh perjalanan yang amat berat dan menyiksa menuju Entikong, gerbang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kami rela digonjang-ganjing dalam mobil selama belasan jam meniti jalanan rusak—Harto tak hentinya mengurut tengkuk Nasuti yang mual-mual—hingga akhirnya jalan menjadi mulus dan tibalah kami di sebuah pos yang dijaga pasukan TNI. Para penjaga perbatasan ini memeriksa kami dan menanyakan paspor, mengira kami hendak menyeberang ke Serawak. Kami menjelaskan tujuan kami, seraya minta izin untuk meliput suasana perkampungan yang bersebelahan langsung dengan negara tetangga. Kami juga sempat mewawancarai para TNI di barak dan ikut menemani patroli rutin mereka menyusuri tapal batas negara. Tugas yang tak mudah, mengingat mereka harus menyusuri hutan berhari-hari dan berbekal ransum seadanya.
Ada yang unik saat kami tiba di desa dekat perbatasan. Secara teritorial, desa ini masih dalam wilayah Negara indonesia, tapi penduduknya berbahasa Melayu dan menggunakan uang Ringgit sebagai alat tukar. Aku sampai keheranan melihatnya. Untunglah, saat kami mewawancarai seorang warga, dia sama sekali tak lupa lirik lagu Indonesia Raya. Anaknya yang masih SD bahkan bisa menyebut dengan pasti tanggal-tanggal Hari Besar Nasional dan hafal nama-nama pahlawan kemerdekaan.
“Bagus itu, patut ditiru,” kata Harto, mengurut leher Nasuti yang hampir pingsan dalam perjalanan kembali ke Pontianak. “Artinya, sedekat apapun mereka dengan negara tetangga, kesetiaan mereka tetap untuk Indonesia. Kita sebagai anak muda jangan mau kalah. Gaya boleh beken, tapi jiwa Nasionalisme harus tetap dijunjung tinggi. Setidaknya kita harus tahu judul lagu-lagu daerah, tahu nama alat musik tradisional. Jangan bisanya cuma hafal lagu Barat atau Korea doang. Tul nggak, Kapten?”
Aku mengangguk, tersenyum sambil melihat peta, menentukan tujuan berikutnya. Namun senyumku lenyap begitu melihat jendela mobil. Di kiri kanan, perkebunan sawit membentang luas mengawal perjalanan kami. Sejauh mata memandang, yang ada hanya barisan pohon sawit—tumbuhan yang terkenal boros air dan menyebabkan tanah kekeringan. Mengingat ratusan hektar hutan yang dikorbankan demi perkebunan ini, termasuk orangutan dan satwa liar lainnya yang terusir dari habitatnya, hatiku mendadak miris.
*****
HARI KE-42, PALANGKARAYA
Dari Pontianak, kami naik pesawat menuju Palangkaraya, sebuah kota nan megah di jantung Kalimantan. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhi panorama hutan tropis nan lebat di kiri-kanan, seakan kami berada di Amazon. Barisan pohon besar dan udara sejuk menyambut kami saat memasuki kawasan Cagar Alam Nyaru Menteng, pusat rehabilitasi ratusan ekor orangutan yang terluka atau ditinggal mati orangtuanya. Kami berkenalan dengan para dokter hewan, perawat dan pawang yang mengasuh serta melatih para orangutan hingga mampu bertahan hidup sendiri, untuk kemudian dikembalikan ke alam bebas. Harto senang sekali saat petugas mengantar kami berkeliling, meliput berbagai atraksi orangutan dan melihat-lihat kebun buah yang luas.
“Hebat ya, tadi ada orangutan yang diajari mencuci baju segala, nggak kalah sama manusia, nih lihat,” Harto antusias memeriksa hasil rekamannya. “Lokasi yang kaupilih keren-keren, Kapten. Nggak nyesel aku ikut kelompokmu. Coba nanti kita bandingkan video hasil liputan kita dengan kelompok Zhen, bagusan mana.”
Aku nyengir saja. “Berterimakasihlah pada ayahku, yang sudah menulis jurnal ini. Aku dapat ide lokasi yang bagus-bagus itu dari buku ini kok.”
Sebelum pergi, ada seekor anak orangutan yang merengek minta digendong Harto, menggayut tak mau lepas sementara kawannya yang lain menyandera handycam kami. Khawatir barang pinjaman itu rusak, kami terpaksa menyogok dua anak bandel ini dengan sebotol susu. Melihat wajah pias Harto, Nasuti terpingkal-pingkal.
“Mungkin kau dikira abangnya, sampai akrab banget gitu.”
Perjalanan kami berikutnya juga tak kalah seru. Meski kami menyusuri jalur darat yang makan waktu lama, tapi kami sangat terhibur dengan berbagai keunikan yang kami temui di jalan. Mobil jeep carteran yang kami naiki lincah melewati jalanan berlumpur, berasa seperti off road saat supir memacunya berkelok-kelok mendaki bukit dan menerabas sungai berbatu.
Kami sempat melewati daerah pertambangan kuno peninggalan Belanda, mencoba naik lori pengangkut batubara yang dijadikan pengganti angkutan umum di daerah ini. Rasanya seperti naik kereta mini, berdesakan dengan penduduk sekitar yang hendak ke pasar. Tampak jurang menganga di kiri kanan saat lori melintasi bukit, ditambah suara berderit yang memekakkan telinga setiap kali melewati rel tua berkarat, membuat kami berjengit. Beberapa ekor bekantan yang menggayut di sulur-sulur juga tak hentinya mengikuti dan menimpuki kami dengan biji buah.
Kami juga melewati perkampungan Suku Dayak, etnis asli Kalimantan yang bermukim di beberapa penjuru pulau ini. Berbeda daerah, berbeda pula adat istiadatnya. Adakalanya kami harus minta restu ke pemuka kampung supaya diizinkan lewat. Agak ngeri rasanya melihat beberapa pria berpakaian adat membawa mandau, senjata khas Suku Dayak. Mereka bersikap ramah terhadap pengunjung karena terbiasa berbaur dengan dunia luar, tapi ada juga suku di pedalaman yang sama sekali tak tersentuh teknologi. Bahkan, konon para kepala kampung di daerah tertentu masih ada yang mempraktikkan ilmu sihir dan tenung.
“Yang penting, kita harus selalu bersikap sopan, jangan sembarangan kalau ngomong,” aku mengingatkan kedua temanku. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormati setiap peraturan di daerah mana pun yang kita tuju. Selama tidak bertentangan dengan akidah, tak ada salahnya kita turuti adat istiadat mereka.”
Keduanya mengangguk. Meski agak jahil, syukurlah mereka tak pernah melakukan hal-hal bodoh yang menyinggung perasaan warga selama perjalanan ini. Perlahan, mobil travel yang kami tumpangi meluncur menuju Banjarmasin. Kami tak bisa berlama-lama singgah di setiap kota, mengingat pulau ini jarak tempuhnya paling panjang dibanding pulau lain. Ditambah lagi medannya yang bervariasi, mulai dari jalan aspal yang bersahabat hingga jalan berbatu yang mencekik, yang terkadang memaksa kami melek semalaman. Selain itu kami sudah tak sabar ingin bertemu Igo dan Inayah di Banjarmasin, setelah berhari-hari berpisah jalan. Kami tak sabar menggoda pasangan yang habis berbulan madu itu.
*****
HARI KE-44, BANJARMASIN
Sungai Barito yang membentang luas itu ibarat nyawa bagi warga Banjarmasin, sehingga kota ini dijuluki Kota Seribu Sungai. Aku dan dua temanku termangu di tepi Jembatan Barito, memandang arus sungai nun jauh di bawah. Aku membandingkan hidupku dengan sebatang kayu yang terbawa aliran air, terseret jauh hingga lenyap dari pandangan, entah kemudian tersangkut atau berhasil tiba di muara. Rasanya aku tak mau hidupku seperti itu. Tak punya prinsip, begitu mudah terbawa arus, ikut-ikutan tren seperti kebanyakan orang dan mati tanpa meninggalkan apa-apa. Rasanya aku harus melakukan sesuatu, berbuat banyak demi kebaikan orang lain dan menghasilkan karya yang bermanfaat, sehingga kelak ada banyak orang yang mengenang jasa-jasaku. Aku tak ingin berakhir seperti orang yang biasa-biasa saja.
Lamunanku terputus ketika terdengar orang berteriak memanggil. Di ujung jembatan tampak dua orang berlari ke arah kami. Ketika sudah dekat, kami tersenyum menyambut mereka, yang tak lain adalah Igo dan Inayah, pasangan muda yang berbahagia. Berhari-hari tak bertemu, aku sampai pangling. Penampilan Igo banyak berubah, kulitnya jadi agak gelap karena sering berjemur. Sedangkan Inayah—entah dia minum suplemen apa—warna kulitnya tetap putih meski tak memakai kosmetik. Hanya wajahnya saja yang kian berseri setelah puas berlibur di Lombok. Dia juga masih konsisten dengan busana muslimahnya.
“Hayo habis ngapain aja kalian berdua?” goda Harto. “Inayah, kamu nggak dijahatin sama Igo kan? Dia nggak nyuruh yang aneh-aneh kan?”
Wanita cantik itu tersenyum, menggeleng. Igo mengacungkan tinju.
“Kau minta disuntik ya, To? Ine, suntik dia!” serunya ketus, sementara istrinya hanya tertawa pelan, menggaruk kepala.
“Sejak kapan kau memanggilnya Ine?” Nasuti ikut meledek, yang dibalas pelototan. “Kalian nggak asik ah, setiap kali kami seru-seruan, kalian malah nggak ikut.”
“Sudah, sudah, yang penting kan kelompok kita kembali lengkap,” kataku seraya membuka peta. “Sekarang kita jajal destinasi berikutnya yuk.”
Teman-temanku bersorak sepakat. Berikutnya kami meluncur ke Pasar Terapung Kuin, salah satu daya tarik wisata Kalimantan Selatan yang cukup terkenal di mana pedagang dan pembeli bertransaksi di atas perahu. Sejak pagi buta, muara Sungai Kuin sudah sangat ramai. Tampak ratusan ibu-ibu bercaping lebar mengayuh perahu, membentuk barisan panjang di sekitar muara dan menjajakan dagangan mereka. Terkadang para penjual harus mendayung perahunya untuk mendekati pembeli yang melambai. Atau sebaliknya, si pembeli yang menghampirinya sambil melompati perahu lain.
Kami berlima menyewa perahu motor dan berkeliling pasar, mengamati kegiatan jual beli mereka yang unik karena masih menerapkan sistem barter. Meski begitu, tak sedikit juga yang memakai uang sebagai alat tukar. Barang yang dijualbelikan umumnya sayur mayur, buah-buahan, hasil bumi dan beragam kudapan. Kami meluncur kesana-kemari dan membeli aneka jajanan pasar, lalu merapat sejenak di sebuah restoran terapung demi mencicipi soto banjar dan ketupat kandangan dengan kuah ikan gabus.
“Lho, Inayah kenapa, kok kelihatan sedih?” tanya Harto.
“Jepit rambutku hilang,” Inayah tampak pucat, memeriksa tas tangannya, mengeluarkan beberapa barang, memeriksanya, lalu dimasukkan lagi. “Padahal tadi kubawa di tas.”
“Mungkin terselip, coba periksa lagi,” saran Igo, dan istrinya menurut. “Kau yakin jepitnya ditaruh di tas? Coba ingat-ingat lagi.”
“Benar kok, tadi ada di tas,” Inayah semakin panik.
“Tenanglah, nanti juga ketemu. Biasanya barang kalau tak dicari suka muncul sendiri. Tapi kalau sudah hilang, ya mau bagaimana lagi, ikhlaskan saja.”
Inayah tertunduk lesu, air matanya menitik.
“Itu... jepit kesayanganku... pemberian almarhum Kakak.”
“Sudah, sudah... aku ngerti kok,” Igo merengkuh dan membelai kepala istrinya pelan, membiarkan wajah cantik itu terisak-isak ke dadanya. Aku menggigit bibir, menatap mereka prihatin, sekaligus juga iri. Harto dan Nasuti saling pandang.
Terbersit suatu ide di kepalaku. Sepelan mungkin, kubisikkan sesuatu di telinga Igo. Pemuda itu mengernyit mendengarnya. Aku mengangguk meyakinkan seraya mengacungkan jempol. Igo bimbang sejenak, kemudian mengangguk. Perlahan, dia mengangkat dagu sang istri dan membuatnya mendongak.
“Tenanglah, Ine, di kota berikutnya, akan kubelikan kau sesuatu,” Igo memegang bahu istrinya, menatap wajahnya. “Kau pasti suka, Sayang. Aku janji.”
Dari Banjarmasin, kami meneruskan tur ke Martapura, kota yang terkenal dengan hasil tambangnya. Igo pergi ke sebuah toko, menyuruh Inayah menunggu di luar bersama kami. Sekilas, toko-toko yang berderet di pasar itu memang tak terlihat istimewa, tapi barang yang dijual tak sesederhana itu. Amat berharga malah. Tak lama kemudian Igo kembali lagi dan menyuruh istrinya menutup mata.
“Nah sekarang buka matamu.”
Inayah membuka mata, tertegun sesaat, lalu tersenyum lebar saat melihat benda yang disodorkan Igo, terharu. Kotak beludru merah itu terbuka, menampakkan sepasang cincin indah berkilauan, bertatahkan batu intan asli.
“Ini... ini pasti mahal sekali,” Inayah terkagum-kagum.
“Memang, tapi aku tak peduli soal itu. Berapapun akan kuberikan untuk membuatmu bahagia. Cincin ini kubeli dengan tabungan sendiri, sebagai lambang dan bukti cinta kita.”
Aku terbatuk mendengarnya. Harto berjingkrak-jingkrak, dan Nasuti menggigiti tiang telepon saking gemasnya. Kami kompak menyoraki pasangan itu, menimpuki Igo dengan potongan ranting, lalu buru-buru kabur saat Igo balas menyabetkan jaketnya.
Berlian Martapura memang tak diragukan kualitasnya, bahkan terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Karena penasaran, aku mengajak teman-teman melihat langsung proses pembuatannya. Metode yang digunakan masih tradisional. Dengan alat sederhana, para penambang yang kebanyakan Suku Banjar asli itu menyaring intan di sungai dengan ayakan serupa wajan, memilah mineral berharga di antara butiran pasir. Setelah terkumpul, bahan mentah akan dibawa ke pabrik untuk diolah dan diproses dengan peralatan yang juga sederhana. Seorang penambang bahkan bercerita bahwa dulu pernah ditemukan berlian seribu karat—intan terbesar di Kalimantan. Entah seberapa besarnya, aku tak sempat bertanya.
Saat kami meninggalkan Martapura, Inayah sudah tak menangis lagi. Wajahnya yang ayu kini dipenuhi gurat bahagia. Hari itu akan menjadi momen tak terlupakan baginya. Selain mendapat hadiah istimewa dari sang suami, barang kesayangannya juga sudah ketemu. Jepit rambutnya ternyata terselip di dompet.
*****
HARI KE-46, BALIKPAPAN
Setelah menempuh perjalanan darat yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di Balikpapan. Tampak kilang-kilang minyak berderet di sepanjang teluk, dengan cerobong-cerobong asap yang tinggi menjulang. Kota ini memang terkenal sebagai gudangnya minyak bumi.
Tujuan utama kami di kota ini adalah jembatan gantung di Bukit Bangkirai, wisata menarik yang cocok bagi siapa saja yang suka tantangan. Di sana banyak terdapat rumah-rumah pohon yang bertengger belasan meter dari atas tanah, pas sekali dijadikan tempat bersantai sambil minum teh. Belum lagi adanya lima pohon bangkirai berumur ratusan tahun, dengan tinggi 30 meter dan diameter tiga meter, seakan menantang kami untuk segera memanjatnya.
Aku berdecak kagum saat menatap ke atas. Beberapa menara dengan puluhan anak tangga disediakan di sekeliling pohon untuk memudahkan kami mencapai pos di ketinggian sana. Pohon-pohon ini dihubungkan sebuah jembatan sepanjang 64 meter, berupa jalinan kayu untuk pijakan dan dilengkapi jaring di kedua sisinya. Kami pun menjajal untuk menyeberangi jembatan ini dari ujung ke ujung, dari satu pohon ke pohon lainnya. Menegangkan juga rasanya saat jembatan ini bergoyang, ngeri membayangkan jika tiba-tiba saja talinya putus atau kaki kami terjeblos, hingga harus bergelantungan dengan kaki menjulur ke bawah. Harto bahkan iseng menggoyang talinya saat Inayah masih di tengah jembatan, membuatnya menjerit-jerit. Harto baru berhenti saat Igo menjitaknya. Untunglah komplek wisata ini terjamin keamanannya, sehingga tak pernah terjadi kecelakaan serius.
Kami terpukau sejenak di atas menara kayu, dihibur pemandangan hutan hijau dan kanopi dedaunan yang melebar sejauh mata memandang. Dari sini, rumah-rumah pohon di bawah tampak seperti barisan sangkar burung. Menurut seorang pemandu, jembatan ini adalah canopy bridge pertama di Indonesia sekaligus kedelapan di dunia. Tempat ini juga dijadikan area konservasi beruang madu, bekantan, kantong semar, dan spesies endemik lainnya yang dilindungi Pemerintah.
“Berikutnya ke mana, nih?” tanya Nasuti.
“Samarinda,” aku menunjuk peta.
“Kota yang terkenal sarungnya tuh,” kata Harto. Aku mengangguk, teringat beberapa koleksi sarungku di rumah yang bercorak khas Samarinda, oleh-oleh Paman Ilyasa waktu aku SMP. Coraknya yang indah amat tersohor dan disukai tokoh-tokoh terkenal sekelas presiden, dan uniknya, proses pembuatannya yang rumit itu masih memakai alat tenun tradisional.
“Kalau aku sih penasaran ingin melihat tarian Duku Dayak,” kata Nasuti. “Ceweknya cantik-cantik lho. Dari kemarin, kita beberapa kali ketemu Suku Dayak tapi bapak-bapak terus yang muncul.”
“Cewek melulu yang dipikirin,” cetus Igo, yang dibalas Nasuti dengan melempar potongan ranting. “Mending kita cari wisata alam lagi, yang kayak di sini.”
“Boleh deh, semua saran ditampung kok,” aku tersenyum. “Yang jelas, tujuan utama kita adalah Masjid Islamic Centre Samarinda, masjid terbesar kedua di Asia Tenggara yang letaknya persis di depan Sungai Mahakam. Habis itu kita ke Tarakan, lalu naik kapal cepat ke Kepulauan Derawan, salah satu surga bawah laut yang sudah lama kuincar.”
“Derawan? Wah, mantap tuh,” Harto antusias. “Aku penasaran sama danau yang di Kakaban, yang katanya ada ubur-ubur yang nggak menyengat itu lho. Ada juga ikan pari manta yang bisa diajak main, akrab sama manusia. Dan kalau beruntung, kita juga bisa lihat penyu bertelur di sekitar pantai. Pasti seru banget.”
*****
HARI KE-47, MENUJU SAMARINDA
Malam semakin pekat ketika mobil sejenis oplet yang kami tumpangi berdecit-decit aneh, bergetar hebat bagai diseruduk badak, kemudian oleng. Aku membuka mata sejenak, merasa terganggu di tengah tidurku yang nyenyak. Di sebelahku, Harto dan Nasuti menggeliat. Sopir berseru kesal dan mobil terpaksa menepi. Rupanya ban depan kempes lagi untuk kelima kalinya. Dengan malas, aku melirik jendela. Kami terjebak di tengah gulita, tak tampak satu pun lampu berkelip di antara kegelapan, hanya ada bunyi jangkrik bersahutan. Untunglah tak lama kemudian ban berhasil diganti. Sambil menggerutu, sopir kambali memacu oplet bobrok ini menerobos malam.
Apa mau dikata. Sore tadi, setelah kami menunggu berjam-jam di tepi jalan, tak ada satu pun mobil angkutan yang lewat. Igo dan Inayah tak ikut blusukan dengan kami dan lebih suka naik pesawat ke kota berikutnya. Agen travel Zhen sama sekali tak membantu. Rupanya mereka sedang banyak orderan hingga kehabisan mobil jemputan. Akhirnya hanya oplet tua ini yang lewat dan bersedia memberi tumpangan. Dengan berat hati, kami bertiga ikut naik di bangku panjang di bak belakang, berdempetan dengan kambing dan karung-karung rumput.
Supirnya juga mencurigakan. Katanya mobil ini hendak ke Samarinda, tapi ternyata kami malah dibawa berputar-putar melewati jalan kecil yang sepi, bahkan berkasak-kusuk menembus jalan setapak di hutan. Perjalanan juga terasa hambar karena Pak Supir tak mengajak kami bicara. Berkali-kali aku mendapatinya tengah mengawasi kami lewat spion. Matanya seperti menyelidik wajah-wajah kami, membuat perasaanku tak enak.
Selain kami, ada seorang penumpang lain yang tengah tertidur dalam posisi duduk di lantai, memeluk senapan berburu. Penampilannya sangat aneh, dan agaknya dia bukan penduduk sini. Wajahnya khas orang India, dengan kulit gelap dan kumisnya yang baplang. Bajunya dilapis rompi kulit yang biasa dipakai pemburu. Topinya unik, serupa hiasan kepala dengan jalinan bulu burung warna-warni, begitu juga kalungnya yang terbuat dari untaian taring binatang. Belum lagi bau-bauan aneh yang menguar dari tasnya, seperti bau tanaman obat yang membuat kepala pening, dan aku yakin sekali melihat kepala ular menyembul dari balik lengan bajunya. Sambil tetap menjaga jarak dari orang itu, kami kembali terlelap, namun aku terbangun dengan jengkel ketika Harto mengguncang bahuku.
“Ada apa sih?” tanyaku, dengan mata setengah terpejam.
“Mau ke kamar kecil, udah nggak tahan,” bisiknya.
“Di hutan begini mana ada kamar kecil,” kataku.
“Nggak apa-apa, aku mau turun di sini saja,” katanya ngotot, mukanya membiru sambil memegangi perut. “Tolonglah, antar aku sebentar.”
“Nggak bisa tahan sebentar lagi?” kata Nasuti.
“Nggak, udah nggak tahan,” keluh Harto.
Aku jengkel sekaligus iba padanya. Terpaksa kami minta turun di jalan, di pinggiran hutan yang gelap. Di situ sepi sekali, tak ada rumah satu pun apalagi toilet umum. Harto langsung berlari masuk ke hutan tanpa memedulikan panggilan kami. Nasuti mengejarnya, sementara aku mengawasi mereka dengan jengkel. Keduanya pergi lama sekali. Pak sopir mengetuk-ngetuk kemudi dengan tak sabar. Dengan tatapan dingin, dia melempar puntung rokok yang masih menyala ke dekat kakiku, mendengus, lalu segera menjalankan opletnya, meninggalkan kami.
“Pak... Pak, tunggu sebentar Pak!” aku berlari sambil berteriak, namun oplet itu sudah menjauh dan menghilang di tikungan. Yang tersisa hanya asap knalpotnya, mengepul di udara kelam dan membuatku batuk-batuk. Aku menghentikan langkah dengan kecewa. Gara-gara Harto, kami ditinggalkan di tempat seperti ini.
“Tak apa, semoga masih ada bus di belakang,” Harto berkata tenang ketika muncul tak lama kemudian. Nasuti menyusul di belakangnya, menggenggam senter dan menggerutu.
Nyatanya, tak ada mobil lagi yang lewat setelah itu. Bahkan kendaraan lain pun tidak. Tampaknya hanya kami bertiga manusia yang ada di tempat terpencil itu. Entah karena sudah terlalu malam atau mungkin jalur itu memang jarang dilewati kendaraan. Aku menyilangkan lengan di depan dada, alisku berkerut. Apa kubilang. Harto hanya menunduk malu melihat sikap jengkelku yang terang-terangan.
“Kita berkemah saja,” katanya, coba mengalihkan perhatian. “Kita tunggu sampai pagi, baru menghadang bus yang lewat. Bermalam di tengah hutan pasti mengasyikkan.”
“Tapi kita kan nggak bawa tenda,” kata Nasuti. “Igo yang bawa.”
“Nggak masalah kan? Tinggal gelar matras dan sleeping bag, berbaring beratap langit. Pasti lebih menantang,” kata Harto tanpa perasaan bersalah.
“Kalau ada binatang buas gimana?” protesku. “Lagian tidur di tempat terbuka di malam hari pasti dingin banget.”
“Gampang, tinggal bikin api unggun aja, susah-susah amat.”
Aku masih memelototinya, bahkan Nasuti tampak kecewa. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur di hutan malam itu, di tengah alam liar yang belum terjamah. Kami menyusuri sela-sela pepohonan untuk mencari tempat terbuka yang cocok untuk berkemah. Kabut suram merayap di sepanjang tanah, dan pohon-pohon besar menyeramkan berdiri menjulang bagai bayangan. Puncaknya tak terlihat ditelan kegelapan dan menggapai langit malam berbintang, tampak jauh sekali. Sesekali tampak beberapa kunang-kunang berkeliaran di depan kami.
“Eh, lihat deh, bagus banget!” Harto menunjuk ke atas.
“Subhanallah!” aku berseru, ikut melihat ke atas. Ada puluhan, bahkan ratusan cahaya yang meluncur cepat seakan menyerbu langit, membentuk garis-garis putih menakjubkan—hujan meteor. Kami terpana menatap pemandangan itu, ternganga seraya berucap zikir atas keagungan Tuhan. Fenomena itu hanya sekejap, perlahan berkurang hingga tersisa satu dua saja, dan akhirnya senyap. Meski begitu, kami takkan pernah melupakan keindahan itu.
Kami melangkahi akar-akar besar yang mencuat dari tanah, sesekali melompat saat jalan kami terhalang batang pohon tumbang. Campuran aroma kayu lapuk, lumut dan tanah basah menyengat hidungku. Suara hewan-hewan nokturnal mengepung kami bagai orkestra. Burung hantu berbunyi di suatu tempat. Kami merasa tidak sendirian di tempat sunyi ini, merasa diawasi makhluk-makhluk yang bukan manusia. Telingaku menjadi lebih peka dari biasanya. Sedikit saja ada bunyi di atas tanah, kami langsung menoleh, tak tenang, mewaspadai bahaya selama beberapa detik, namun satu-satunya benda yang bergerak hanya dedaunan atau serasah yang terkena angin. Aku menyorotkan senter dengan gugup, menemukan beberapa hewan bergelantungan di batang pohon. Seekor tupai bercericit marah, tampak terganggu ketika cahaya senter menerpa mata dan bulu-bulunya.
“Di sini saja. Tanahnya cukup datar,” kata Harto, menyorotkan senter ke tanah.
Setelah menemukan daerah kosong yang tak ditumbuhi pohon, kami mendirikan kemah dengan hanya menggelar matras, lalu berbaring beratap langit kelam. Nasuti sibuk mencari ranting untuk kayu bakar, lalu membuat api unggun. Kami meringkuk hanya berselimut sleeping bag. Harto langsung mendengkur, meninggalkan aku terjaga berdua dengan Nasuti. Saat aku berbaring, kulihat Nasuti masih duduk termenung menghadapi kobaran api yang berdenyut, tatapannya kosong dan sesekali memantulkan cahaya api. Tampaknya ia masih memikirkan ayahnya. Kami terdiam dalam keheningan, merasakan malam yang berlalu sangat panjang dan lambat. Aku hampir terlelap ketika Nasuti mengguncang bahuku.
“Da pa?” tanyaku sambil menguap.
“Kamu lihat itu?” bisiknya, menunjuk ke tengah kegelapan.
Aku langsung melonjak bangun, penasaran. Kupicingkan mata menelusuri gelapnya batang-batang pohon, mencoba melihat apa yang ditunjukkan Nasuti. Dan aku melihatnya. Di sana, di sela-sela pohon lebat, tampak sesosok benda putih setinggi manusia, melayang-layang tak terpengaruh gravitasi. Sosok itu mengingatkanku pada orang mati yang dibungkus kafan dan hendak dikuburkan. Aku merinding dan segera merapal doa. Hutan selebat ini pasti dihuni banyak makhluk halus dari bangsa jin. Biasanya mereka menjelma sebagai hantu dan menakut-nakuti orang tersesat yang lemah imannya.
“Kau juga lihat, kan?” kata Nasuti. Sosok itu masih tak beranjak, sekarang malah bergoyang-goyang di tengah udara, namun tidak mendekati kami.
Aku mengangguk. “Ingat apa yang dikatakan Igo? Jika bangsa jin menampakkan diri, itu berarti dia sedang dalam kondisi terlemahnya. Menurut hukum fisika, jika suatu benda dapat terlihat oleh mata, itu artinya benda tersebut berwujud padat sehingga cahaya tak dapat menembusnya. Berbeda dengan asap yang transparan dan tak dapat disentuh. Konon, jin yang bisa menampakkan diri berilmu tinggi sehingga dapat berpindah dimensi dan mengambil bentuk sebagai benda padat. Artinya, jin itu juga rentan terhadap serangan fisik.”
Aku mengambil sebutir kerikil di tanah, membaca Ayat Kursi, kemudian melemparnya ke arah sosok putih itu, mengirimnya kembali ke dunia lain. Perlahan, sosok itu menghilang nyaris tanpa suara. Aku tersenyum puas.
“Nah, lihat kan? Pada dasarnya, bangsa jin hanyalah makhluk yang lebih rendah derajatnya dibanding manusia, jadi tak perlu takut. Biasanya, mereka sengaja menampakkan diri dalam wujud-wujud menyeramkan untuk menakuti manusia yang lemah imannya.”
Aku kembali rileks dan merebahkan diri. Di sebelahku, Harto mendengkur semakin keras. Waktu terasa berjalan lama, dan entah kenapa aku jadi tak bisa tidur setelah peristiwa tadi. Nasuti menyodok-nyodok kayu ke api unggun, berkata, “Mau mendengar cerita horor?”
“Jangan cerita hantu ah,” kataku. “Barusan kan kita sudah lihat sendiri. Lagipula, aku khawatir hantu-hantu di sini ikut mendengarkan kalau kau cerita tentang mereka. Hiiiiy...”
“Bukan, bukan cerita hantu,” katanya. “Bahkan lebih seram.”
“Apa?” aku mulai tertarik, menegakkan badan.
“Begini,” Nasuti mendekatkan wajahnya ke api unggun, membuat matanya berapi-api dan bayangan panjang menari-nari di pohon di belakangnya. “Dulu, waktu masih semester tiga, aku pernah lembur di kampus sambil ngerjain tugas. Bersama Igo dan Harto, aku duduk di lobi tengah yang banyak sinyal wifi-nya, sampai larut malam. Awalnya kami enjoy-enjoy saja, saling gelitik, bercanda terus, dan Harto malah buka youtube, padahal deadline tugasnya besok. Sekitar pukul sebelas, suasana berubah mencekam. Selain dingin menyengat, kami juga terangguk-angguk karena ngantuk berat. Rasanya apa yang kuketik di laptopku sudah nggak karuan. Firasatku mengatakan ada yang berbeda malam itu.”
Dia menghela napas, bercerita lagi. “Tiba-tiba, terdengar suara-suara aneh, memilukan sekali. Entah dari mana asalnya. Padahal tak ada orang atau makhluk lain selain kami bertiga, setidaknya yang terlihat. Aku waspada, menatap sekitar sambil menajamkan pendengaran, Igo langsung merapal ayat. Harto jangan ditanya, dia sudah kabur duluan, terbirit-birit ke pos satpam. Suara-suara itu terus terdengar, dan makin lama makin melengking, membuat perasaan tak nyaman. Nah, tahu nggak, itu sebenarnya suara apa?”
“Suara perutmu kali,” jawabku asal.
“Bukan,” katanya serius. “Kau mau tahu? Penasaran berat? Jangan salahkan aku kalau habis ini kau mimpi buruk ya. Jangan minta diantar kalau mau ke kamar kecil. Sebenarnya aku khawatir makhluk-makhluk itu ada di sini juga.” Nasuti mendongak ke arah langit berbintang yang tampak di sela-sela kanopi pepohonan, lalu kembali menatapku tajam. “Ternyata suara itu adalah, suara... suara... kucing lagi konser! Serem kan?”
"Gubrak, garing banget! Cerita horor macam apa itu?” aku terbahak, kukira cerita apa. “Nih, aku juga punya cerita yang tak kalah menakutkan. Mau dengar?”
“Nah, begini ceritanya...” aku mengambil napas.
“Ih serem banget, atuut,” Nasuti berjengit.
“Hei, aku belum mulai!” kataku jengkel. Aku diam sejenak, menunggu tawa Nasuti reda, lalu mulai bercerita, “Tahun kemarin, saat aku masih aktif di Rohis, aku sering diajak syuro atau rapat oleh Ruqoyah, yang saat itu baru menjabat sebagai ketua umum. Aku agak jengkel karena terus-menerus dipaksanya ikut rapat, padahal kesibukanku sangat menumpuk. Apalagi saat itu aku sedang merampungkan skripsiku. Nah, suatu hari, aku berniat bolos rapat dan ngeloyor ke bioskop untuk menghindari kejaran anak Rohis. Kebetulan saat itu film yang sudah lama kutunggu sedang diputar. Sekalian saja aku nonton.
“Waktu itu banyak sms dari anak-anak Rohis yang masuk ke inbox, mengajak rapat, tapi kuabaikan saja. Tapi aku agak ragu saat melihat salah satu sms itu datang dari Ruqoyah sendiri, sang ketua umum. Pesannya begini: Kak Lutfi, ditunggu kehadiran antum di sekre ya, segera. Aku berpikir sejenak, merasa tak enak, lalu kubalas saja: Maaf, aku lagi sakit, nggak bisa keluar kamar kost. Aku minta izin ya. Kamu sendiri gimana, udah sampai di sekre? Tanpa merasa bersalah, aku enjoy-enjoy saja menonton. Masa-masa itu aku masih jahiliah, paling enggan kalau disuruh rapat. Nah, kau tahu apa jawaban Ruqoyah?”
Nasuti menggeleng. Aku mendekatkan wajah ke arahnya agar dramatis, lalu berbisik dengan nada yang kubuat berkesan mistis, “Ruqoyah menjawab: Oh, aku masih nonton di bioskop. Kebetulan aku duduk dua baris di belakang Kak Lutfi. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menoleh dan melihat gadis itu memang benar-benar ada di belakangku, mengawasi dengan lengan terlipat. Rasanya ngeri banget waktu itu. Aku ketahuan membolos, tepat di depan hidungnya. Pokoknya gawat deh. Kelanjutan ceritanya kautebak saja sendiri.”
“Idih, ngeri amat,” Nasuti tertawa, menyodok api unggun agar tetap menyala. “Nggak kebayang gimana rasanya kalau aku jadi kau. Tapi itu artinya Ruqoyah bolos rapat juga kan? Hahaha, nggak bener kalian semua. Anak Rohis kok gitu sih?”
“Itu kan dulu,” kataku. “Lagian kayak kamu udah alim aja.”
Tak seberapa lama, aku terlonjak saat terdengar lolongan mengerikan menerobos hutan, entah dari mana asalnya. Aku dan Nasuti berdiri, menatap daerah gelap yang tak jauh dari kami. Ada sesuatu di sana. Terdengar bunyi ranting yang terinjak beban berat, kemudian ada geraman. Kubangunkan Harto yang tengah meringkuk, memperingatkan akan adanya bahaya. Dia terbangun kaget dan langsung berdiri. Pasti banyak binatang buas di hutan ini. Kami merapat ke dekat api unggun, mengawasi siluet hewan besar mendekat. Apakah itu serigala? Tidak, itu lebih besar lagi. Aku menajamkan penglihatan, dan Nasuti refleks mengacungkan ranting. Sosok itu mengendus tanah, kemudian masuk ke lingkaran cahaya.
Di hadapan kami, seekor harimau besar berdiri, matanya menyala-nyala memantulkan cahaya api, dan taringnya menggigit tengkuk hewan buruan. Aku ngeri melihat rusa itu berdarah-darah, setengah hidup, namun dengan pasti menanti ajal. Nasuti menyulutkan ranting ke kobaran api, mengacungkan obor ke arah harimau itu untuk mengusirnya. Harimau itu tak terpengaruh, dengan santai berjalan mengitari kami, kemudian pergi ke balik pepohonan, lalu lenyap dalam kegelapan. Kami menahan napas, dan baru beberapa menit kemudian menjadi tenang. Hatiku mencelos.
“Bahaya sekali tadi,” Nasuti terengah. “Untung harimau itu sudah punya mangsa. Aku rasa dia akan cukup kenyang dengan rusa itu sebelum kembali mengincar kita. Dan saat itu kita pasti sudah jauh meninggalkan hutan ini.”
“Heran, kok di hutan Kalimantan ada harimau ya?” kata Harto.
“Iya, aku juga merasa aneh,” kata Nasuti. “Kalau macan tutul atau kucing hutan sih memang banyak di hutan sini. Tapi ini... harimau. Di Jawa dan Sumatera saja, habitat aslinya, populasi mereka sudah sangat langka. Lha ini, di Kalimantan, malah ada yang nyelonong di depan kita, dekat jalan besar pula. Nggak takut sama pemburu tuh?”
“Itu gara-gara ucapanmu sih,” aku menyikut Nasuti. “Tadi kau cerita soal kucing, dan yang muncul malah mbahnya. Sebenarnya dulu di Kalimantan memang ada harimau, tapi kabarnya sudah punah. Aku malah mikir begini, jangan-jangan tadi itu piaraan seseorang, atau justru harimau jadi-jadian?”
Harto dan Nasuti saling pandang, bergidik.
Aku kembali berbaring, tapi tak bisa tidur. Perasaanku tak tenang dan khawatir akan adanya ancaman lain dari tengah hutan. Setelah mengamati sekitar dan merasa sudah aman, aku beranjak dengan senter di tangan, meninggalkan Nasuti yang terangguk-angguk di depan api unggun. Aku pergi ke sungai kecil yang kutemukan tak jauh dari perkemahan, meraup airnya yang jernih, dan membasuh muka. Aku berwudhu dan memutuskan untuk bertahajjud. Aku masih mengusap rambut ketika ada yang menepuk bahuku.
“Bentar,” kataku sambil meneruskan wudhu. Nasuti pasti iseng menjahiliku. Dengan tak sabar, dia terus mencolek-colek lenganku, bahkan menarik-narik belakang bajuku. Aku mengabaikannya. Lama-kelamaan aku mulai jengkel. “Apaan sih?”
Ketika berbalik, aku kaget karena ternyata bukan Nasuti yang mencolek. Aku melihat seorang nenek tua berdiri di depanku. Kulit wajahnya yang keriput tampak kusam dan berbintik-bintik. Mata tuanya yang rabun menatapku nanar.
“Malam-malam di hutan seperti ini berbahaya,” katanya. “Ayo, mampir di gubuk saya.”
Aku masih tertegun, ragu apakah dia manusia atau makhluk lain. Rasanya tak mungkin ada seorang nenek tua yang tinggal sendirian di tempat seperti ini. Wanita tua itu tampaknya bisa membaca pikiranku.
“Tenang saja, jangan takut. Saya manusia sama seperti kalian. Coba saja pegang,” dia tertawa memperlihatkan giginya yang bolong-bolong, malah membuatku semakin ragu.
Aku bergerak menyamping, masih mengawasinya, mengira dia akan lenyap atau berubah wujud dalam sekejap jika aku berpaling. Tanpa mengalihkan perhatian, aku kembali ke api unggun dan membangunkan teman-temanku.
“Ngg, ada apa?” Nasuti bergumam sambil menguap. Harto menggeliat dan mengucek matanya, setengah sadar. Ketika melihat si nenek, keduanya terperanjat.
“Apa? Siapa?” Harto tergagap. Tanpa suara dia bergumam, M-m-Mak Lampir!
Nenek itu tersenyum, mengabaikan tatapan curiga kami. “Nama saya Jupiah, saya tinggal di dekat sini. Kalau mau, kalian boleh mampir ke gubuk saya untuk berlindung. Hutan ini berbahaya di malam hari. Banyak hewan buas berkeliaran. Ayo, jangan sungkan.”
Kami saling pandang, masih penasaran siapa sebenarnya nenek ini. Yang pasti Mbok Jupiah ini bukan hantu. Dia tersenyum dan berjalan mendahului kami. Setelah menggulung matras dan mematikan unggun, kami bergegas membuntuti Mbok Jupiah, melalui jalan setapak sempit yang ditumbuhi semak-semak liar, kemudian berhenti di depan sebuah gubuk reyot. Aku mengernyit. Gubuk itu sangat kecil, tak lebih besar dari ukuran kamarku. Bagian bawahnya disangga empat pilar dan dindingnya terbuat dari bilik bambu yang sudah lapuk. Secara keseluruhan, gubuk itu tak layak disebut rumah. Mbok Jupiah menyuruh kami masuk.
“Nenek tinggal dengan siapa di sini?” tanyaku. Harto menatap sekeliling ruangan dengan penasaran. Berbagai perabot rumah tangga seperti perlengkapan masak menggayuti dinding. Baju-baju ditumpuk begitu saja di lantai, tampak kusut dan lusuh.
“Sendirian, Nak, saya tidak punya keluarga lagi,” katanya seraya menyiapkan alas tidur untuk kami. “Kalian sedang apa malam-malam di hutan?”
“Kami ketinggalan mobil, Nek,” kata Nasuti. “Kami diturunkan di tengah perjalanan dan terpaksa berkemah di hutan sambil menunggu pagi.”
“Untung Nenek datang,” kata Harto, masih mengedarkan pandangan. “Tadi kami ketemu harimau dan hampir diterkam.”
“Ooh, kalian sudah melihat si Wage, rupanya,” Mbok Jupiah terkekeh, entah dia bercanda atau tidak kami tak tahu. “Nenek juga baru melihatnya kemarin. Mungkin dia salah satu harimau yang tersisa di hutan ini. Biasanya dia tidak menyerang manusia jika tidak terdesak. Wage dan keluarganya harus bertahan hidup di tengah hutan dan menghindari para pemburu liar. Mereka hidup tenang di bagian dalam hutan yang tak terjamah. Meski begitu, hidup mereka terancam. Kasihan, jumlah mereka semakin langka dan hanya tersisa tiga ekor. Sisanya habis diburu untuk diambil kulitnya atau diawetkan untuk dijadikan pajangan.”
“Bagaimana Nenek bisa tinggal di sini?” tanyaku, dalam hati setengah tak percaya dengan ceritanya. Katanya baru melihat harimau itu kemarin, tapi langsung bisa memprediksi jumlah populasinya, tahu kebiasaannya yang tak menyerang manusia, termasuk memberinya nama. Mungkin sebagian dikarangnya saja.
“Saya diusir penduduk desa,” katanya tenang, namun matanya berkaca-kaca. “Dulu, saya hidup tenang meski tak punya apa-apa. Saya cuma orang miskin. Saya diusir karena dituduh mencuri kayu hutan, padahal saya tak sengaja melakukannya. Saya tak tahu kalau itu dilarang, dan saya hanya bisa pasrah saat mereka melaporkan saya ke polisi. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Padahal banyak truk-truk liar di luar sana yang mengangkuti kayu, melakukan penebangan liar dan didukung perusahaan-perusahaan besar, tapi mereka hanya ditindak dengan hukuman ringan, tak sebanding dengan penderitaan yang harus saya alami.
“Saya hanya bisa menunduk malu saat dibawa ke pengadilan, malu karena tetangga-tetangga saya yang terus meneriaki saya maling. Saya tak bisa menatap Pak Hakim saat ia membacakan keputusan. Untung ia hakim yang jujur dan adil. Begitu menanyai saya, Pak hakim merasa iba pada nasib saya. Ia tampak bimbang, namun hukum harus tetap ditegakkan. Tanpa mendengarkan ocehan dari pihak pengadu, Pak Hakim membacakan keputusan bahwa saya harus menerima hukuman penjara selama dua tahun atau membayar denda dua juta rupiah. Saya menunduk lesu dan menangis, sementara pihak pengadu merasa di atas angin dan para tetangga terus mengutuki saya.
“Saat saya merasa tak ada harapan, Pak Hakim menepuk bahu saya dan memberi saya uang tunai dari dompetnya sendiri, tiga juta rupiah! Dengan begitu saya langsung dibebaskan dari hukuman. Pak Hakim terus tersenyum pada saya. Hanya sedikit sekali orang berhati malaikat seperti pria ini. Meski begitu, para tetangga tetap tak memercayai saya dan sepakat untuk mengusir saya dari desa. Saya tak diterima lagi. Dan beginilah akhirnya.”
Mbok Jupiah mengusap air matanya. Mendengar kisah itu, aku teringat pada seorang hakim di Malaysia yang melakukan hal serupa untuk membela rakyat kecil. Hakim itu bahkan memarahi setiap orang yang datang di persidangan karena membiarkan orang kecil di sekitar mereka dalam kemiskinan.
Di masa sekarang ini, yang namanya hukum bisa dibeli. Illegal logging merajalela di mana-mana dan pelakunya selalu berhasil luput dari jerat hukum dengan cara-cara kotor. Aku juga miris jika mengingat nasib hutan-hutan di Indonesia yang digunduli seenaknya tanpa ditanam kembali. Kalimantan termasuk paling parah, dan kami sudah melihatnya sendiri selama perjalanan kemarin. Banyak area hutan yang disulap jadi perkebunan sawit. Di peta yang ditunjukkan dosen konservasi di kampus dulu, tampak jelas luas hutan di pulau ini berkurang drastis dari tahun ke tahun. Aku tak tega membiarkan bumi Indonesia terluka, padahal negeri ini disebut-sebut sebagai salah satu paru-paru dunia.
Manusia rupanya sudah melupakan tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Ratapan bumi yang terluka sudah tak sampai di telinga mereka. Homo sapiens banyak yang tak bijak mengelola lingkungan, tak lagi ramah terhadap “rumah” mereka sendiri, dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan seolah tak cukup untuk memuaskan keserakahan mereka. Padahal bumi akan lebih indah jika semua sadar dengan gerakan penghijauan. Tuhan sudah menganugerahkan bumi yang indah dan kaya akan potensi alam untuk kita, serta memberi gelar kehormatan sebagai khalifah dan meletakkannya di pundak kita. Mengapa kita tidak bisa menjaganya dengan baik, atau setidaknya, mencegahnya dari kerusakan? Kalau Tuhan murka, memutuskan menjatuhkan setitik kuasanya hingga timbul bencana alam, membalas perbuatan para manusia bumi, siapa yang dapat menolong?
Kami saling pandang, bertukar pendapat tanpa kata-kata. Mbok Jupiah mengorek sesuatu di antara tumpukan barang yang kelihatan seperti kertas tak terpakai dan daun pisang.
“Ah, ini dia fotonya, Pak Hakim yang membela saya,” Mbok Jupiah mengambil salah satu koran lama yang ditumpuk di lantai, memperlihatkan sebuah artikel pada kami. “Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya karena saya tak bisa membaca, tapi sepertinya beliau orang terkenal. Saya sangat berutang budi padanya.”
Kami langsung merubungi koran itu. Nasuti diam saja membacanya, tak tertarik, tapi kemudian matanya melebar. Tangannya gemetar saat ia memegang koran itu, menunjuk.
“Ini... ini ayahku! Lihat, ini orang yang sama dengan yang di foto milikku. Ini memang Ayah!” Dia melonjak gembira, akhirnya mendapat petunjuk baru di mana sang ayah berada. Apalagi ternyata ayahnyalah hakim berhati emas yang membela Bu Jupiah di persidangan. Ia tambah senang dan bangga. Ternyata ayahnya orang baik, berjiwa besar, dan mulia. Namanya juga semakin terkenal setelah tindakannya yang berani mengadili seorang bandar besar narkotik, mengganjarnya tanpa ampun dengan hukuman berat di LP. Nusakambangan. Nasuti tertawa lebar dan tak hentinya merangkul kami.
Namun tawa Nasuti meredup. Rautnya berubah sedih saat melihat tulisan di bawahnya, yang aku sendiri sampai terkejut dan menekap mulut saat membacanya: Hakim Iqbal, salah satu korban tewas akibat kecelakaan pesawat. Dari tanggal yang tertera, pesawat itu berangkat dari Singapura ke Jakarta, hampir dua tahun lalu. Jenazah dimakamkan di sebuah pemakaman umum di Jakarta bersama beberapa kru pesawat lain yang tak memiliki keluarga dan tempat tinggal.
“Oh tidak... ini tidak mungkin terjadi... tidak!” Nasuti menutupi wajahnya, merosot ke lantai, terisak-isak. Tak sampai hati kami melihat nasibnya. Sudah sejauh ini dia mencari ayahnya, bertanya kesana kemari, dan yang ia dapat hanya berita memilukan itu.
“Kau tak apa-apa?” bisikku pelan, tak tahu bagaimana menghiburnya. Ini pasti ada hubungannya dengan dua buronan yang kubuntuti di Ende waktu itu. Aku ingat seluruh percakapan mereka, termasuk tawa Brewok saat mengenang aksinya meledakkan sebuah pesawat yang ditumpangi seorang hakim. Ternyata hakim yang dimaksud adalah ayah Nasuti.
Nasuti masih saja berjongkok di lantai, menutupi wajah. Tubuhnya berguncang. Harto mendekat, hendak menyentuh bahunya, tapi Nasuti mengangkat tangan, “Jangan, kalian tak usah menghiburku, tolong. Aku tak apa-apa, sungguh.”
Kami sungguh tak enak hati. Melihatnya merana seperti itu, membuat kami ikut merasa sakit dan terpukul. Kami tahu betul bagaimana perasaannya. Mbok Jupiah ikut membungkuk dan mengusap punggungnya, mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil berurai air mata setelah tahu ceritanya.
“Sabar ya,” Harto menatapnya iba. Kami tahu Nasuti tak sedikit pun minta dikasihani. Dia pemuda yang diberkahi ketegaran hati luar biasa, sama seperti Harto.
“Aku bangga pada Ayah,” Nasuti perlahan menegakkan diri, mengusap mata dengan lengannya, tersenyum lemah. “Ya, aku tak apa-apa. Sebetulnya aku sudah punya firasat akan hal itu. Aku... aku sudah siap jika ini harus terjadi. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan ketidakhadiran Ayah. Dan sekarang, kabar seperti ini yang harus aku hadapi. Mau tak mau aku harus merelakan kepergiannya. Aku tak akan bersedih, aku harus ikhlas.”
*****


 radenbumerang
radenbumerang



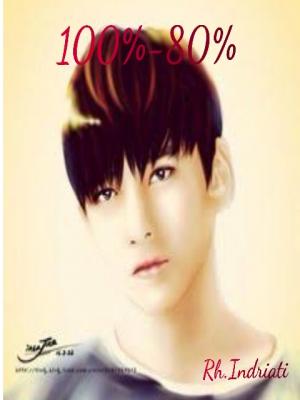





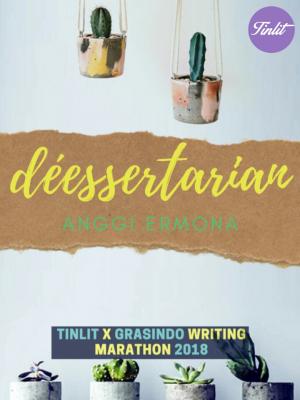
Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.