BAB 7. PESONA DAN KEJAMNYA IBUKOTA
HARI KE-16, BANTEN
Matahari merangkak tinggi di puncak cakrawala, panasnya menjilat-jilat udara. Lautan di bawahku tampak meriah dengan kemilau megah yang berdansa memantulkan mentari. Permukaannya yang biru beriak-riak keemasan saat kapal perkasa yang kutumpangi dengan gagah membelah samudera, meluncur langsung menuju Jawa Barat. Aku berdiri sendirian di geladak depan, memilih tempat paling strategis untuk memandangi laut. Kubiarkan serbuan angin laut mengiris wajahku, dalam hati mengharapkan petualangan lain yang menanti di Pulau Jawa. Harto berjalan timpang ke sebelahku, kakinya masih diperban dan ia harus memakai tongkat selama beberapa hari ke depan sebelum benar-benar pulih. Tiga jam kemudian, ekspresiku mengendur lega saat melihat daratan. Kami melemparkan pandangan ke sepanjang garis pantai ketika kapal tiba di Pelabuhan Merak.
Kami berebut keluar bersama ratusan penumpang lain saat pintu kapal dibuka. Banyak orang berlalu lalang. Di pintu masuk, tampak petugas keamanan sibuk memeriksa barang penumpang. Di sudut lain, sopir-sopir kendaraan umum berteriak-teriak nyaring menawarkan tumpangan. Harto, Igo, dan Nasuti berjalan lekat-lekat di sebelahku. Senang rasanya bisa kembali ke tanah kelahiran sendiri.
Lokasi pertama yang kami kunjungi di Pulau Jawa adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Setelah menempuh tujuh jam perjalanan, akhirnya kami tiba di suatu perkampungan yang dihuni Suku Baduy—masyarakat adat Sunda yang mengisolasi diri dari dunia luar. Agar diizinkan menginap di rumah warga, kami harus melepas alas kaki dan mengenakan pakaian adat mereka. Meski begitu, orang-orang Baduy ini sangat ramah. Malam itu sangat berkesan bagi kami bertiga, karena bisa menyaksikan kearifan lokal Suku Baduy, kedekatan mereka dengan alam, dan kesederhanaan mereka yang tak mengandalkan teknologi canggih.
Esok harinya, dengan menyewa perahu hi-speed berkapasitas delapan orang, kami meluncur menuju TNUK setelah mengurus izin masuk di kota Labuan. Aku duduk di tepi perahu. Riak-riak cerah menari-nari di antara jemariku saat aku mencelupkan tangan ke air. Agar lebih menantang, kami meminta jalur khusus yang melewati rawa-rawa. Suasana terasa menegangkan ketika kami melewati perairan yang dipenuhi pepohonan besar, tampak liar dengan sulur-sulur yang menjuntai dan aneka bryophyte (sebangsa lumut) yang menghijau. Sekilas, kami melihat kelebatan beberapa makhluk arboreal (hewan yang tinggal di pohon) bergelantungan di pohon-pohon dan berayun menggunakan sulur. Kami merasakan puluhan pasang mata mengawasi kami, makhluk asing yang menerobos teritori mereka.
Saat tiba di perairan dangkal, aku, Igo dan Nasuti menggulung celana dan terjun ke rawa. Dasar perairan yang berlumpur dan dipenuhi ganggang terasa licin di ujung kaki. Kami bertekad untuk melakukan swamping (jelajah rawa) sejenak sebelum memasuki acara utama melihat badak Jawa. Harto kami suruh tinggal di perahu karena keadaannya tak memungkinkan untuk ikut menjelajah. Sebagai gantinya, kami berjanji memotretkan beberapa foto unik untuknya.
“Boleh pinjam handycam sebentar? Kau diam di sini dan jaga perahu ya,” kata Igo. Harto hanya bisa menatap iri saat kami berjalan mengarungi perairan menuju dinding pepohonan, lalu masuk ke celah sempit yang ditutupi rumbaian sulur. Saat menoleh ke belakang, Harto dan perahunya tak tampak lagi, terhalang dedaunan lebat.
“Oi, Igo, jangan jauh-jauh, nanti kesasar,” seruku.
Igo tidak peduli, bergerak mendahului kami, mencari jalan masuk. Jika tak ada celah, dia beringas menyibak-nyibak sulur. Ini sih wisata blusukan namanya.
“Dia ngambek ya?” aku menatap Nasuti, menunjuk punggung Igo.
“Kayaknya enggak, semangat banget gitu,” jawab Nasuti.
Kami terus merangsek maju menembus belantara rawa. Adrenalin kami berpacu saat situasi mulai terasa menegangkan. Kami masuk jauh ke dalam wilayah rawa yang terkesan angker karena dipenuhi pohon-pohon lebat yang saling berdekatan, menimbulkan perasaan terkepung yang aneh. Semakin kami melangkah, suasana semakin gelap dan suram karena cahaya matahari tak sanggup menembus kanopi dedaunan. Daerah pedalaman ini tampak liar dan tak terjamah, ditambah lagi dengan kabut yang menjalar seperti hantu di udara. Di sela-sela pepohonan, tampak beberapa pasang mata bersinar menerobos kegelapan, mengikuti setiap gerakan kami.
“Aku merasa tidak sendirian di sini,” kataku, menatap sekitar.
“Memang, kita kan bertiga,” kata Nasuti. “Ini baru wisatanya cowok, ada gregetnya! Alam liar yang tak terjamah, yang banyak tantangannya. Beda banget sama cewek yang wisatanya shopping melulu. Biasanya cewek kalau jalan-jalan sukanya ke kota-kota besar, yang ada mall atau tempat belanjanya. Bandingkan dengan tempat ini, cocok banget buat cowok. Ini baru yang namanya petualangan!”
“Aduh, banyak nyamuk di sini,” kata Igo, membuka ransel dan mengeluarkan baton sword, sebilah golok tipis dengan panjang 70 cm dan terlihat seperti pedang mini. Ujungnya berkilauan tertimpa cahaya matahari yang sesekali menerobos dedaunan. Senjata unik itu dibelinya di Gor Satria saat acara Porprov Jateng dan disembunyikan dalam trekking pole—tongkat besi untuk mendaki gunung.
“Ah, benda itu lagi, apa nggak bahaya?” aku memprotes.
“Ini tumpul kok, bahkan tak bisa kugunakan menyerut pensil.”
“Ya ya, asal kaujauhkan ujungnya dari wajahku,” Nasuti agak mundur, takut tersayat. “Lagian kalau ketahuan polisi bisa disita tuh.”
Dengan semangat, Igo mengayunkan pedangnya liar saat menyeruak maju di antara sulur-sulur yang menggantung rendah. Aku memprotesnya karena menganggap tindakan itu merusak alam, tapi dia tak peduli. Dia memimpin di depan, membuka jalan. Area yang kami tapaki semakin sunyi. Benar-benar suram dan mengerikan, seperti sarang lelembut dan dedemit. Mungkin juga bangsa jin itu mendirikan kerajaan gaib di sini.
“Kalian tahu apa yang paling membuatku tertarik berpetualang? Peradaban kuno dan artefak misterius,” kata Igo, wajahnya berbinar. “Aku pernah membaca tentang beberapa artefak aneh yang menakjubkan dan menyimpan misteri yang sulit diterima nalar. Mungkin kalian pernah mendengar tentang baterai Baghdad; hieroglif yang bergambar kapal selam dan helikopter; tengkorak kristal suku Maya; prasasti Los Lunas di Meksiko; atau Dropa Stones di Tibet. Penemuan-penemuan aneh peninggalan manusia kuno yang sedikit memberi bukti adanya alien, tempat-tempat misterius yang yang keanehannya belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Kelak aku ingin melihatnya sendiri. Itulah sebabnya aku bersedia ikut dengan kalian.”
“Jadi, kau tertarik dengan benda peninggalan kuno?” tanya Nasuti. “Kalau begitu kau salah ambil jurusan, Igo. Harusnya kau kuliah di fakultas sejarah, bukan biologi.”
Aku bergidik saat lenganku bergesekan dengan kulit pohon yang kasar dilapisi lumut. Di belakang, Nasuti tiba-tiba memekik saat ada sesuatu yang menggigit betisnya. Dia mengangkat kaki, menunjukkan makhluk hitam kecil yang menempel di kulitnya.
“Ya ampun, lintah! Kok nggak kerasa ya, tiba-tiba digigit saja.”
Dipencetnya binatang hirudinae menjijikkan penghisap darah itu hingga terlepas. Aku mengaduh saat pohon di atas menghujani kami dengan lintah. Kami tersentak ngeri. Makhluk-makhluk rakus ini terus menyerbu dan tak mau lepas. Puluhan lintah juga mengepung kami dari dalam air yang keruh. Kami segera menjauhi tempat itu. Langkah-langkah kami berkecipak dan menimbulkan gangguan pada permukaan air.
“Ingat apa yang diceritakan Torik soal lintah?” aku berteriak seraya mengibaskan si penghisap berlendir dari lenganku. “Garam, cepat taburkan garam!”
Kami bergidik saat makhluk-makhluk ganas bak vampir itu berjatuhan ke air. Garam memang ampuh mengusir lintah. Tak ingin berlama-lama di sini, kami segera kembali ke arah kami datang, menuju tempat perahu ditambatkan. Saat tiba di daerah terbuka, kami terkejut karena perahu kami sudah tidak ada.
“Lho, kalau nggak salah tadi perahunya di sini,” Nasuti keheranan.
“Jangan-jangan Harto ngerjain kita?” kataku. “Atau kita yang salah jalan?”
Igo memanjat sebatang pohon untuk memantau. Dia berjongkok di batang tertinggi sambil menaungi matanya yang disipitkan. Aku juga ikut memanjat, mengedarkan pandangan. Setelah tiga kali melihat berkeliling, Igo berteriak, “Lihat, itu perahu kita!”
Perahu kami muncul di kejauhan. Dari sini kami bisa melihat Harto terbahak di atasnya, berguling-guling sambil memegangi perut. Pria tua pemilik perahu ikut tertawa, mau saja dia dihasut Harto untuk meninggalkan kami. Kami cemberut, lagi-lagi kami dikerjainya. Igo melompat turun, berteriak-teriak marah. Harto terpingkal-pingkal sambil menunjuk kami.
“Dasar, belum hilang juga jahilnya,” Igo menggerutu saat Harto mendekat.
“Siapa yang berbuat akan menuai, sekecil apapun perbuatan pasti dicatat dan dibalas dengan setimpal,” aku menceramahi Harto dengan senjata andalan yang tak bisa dibantahnya, dalil dari Al-Qur’an atau hadits. Kali ini aku mengutip kandungan surah Al-Zalzalah. “Kalau kau jahil terus, suatu saat perbuatanmu pasti akan dibalas.”
Setelah puas mengomeli Harto, kami meneruskan ke TNUK tempat si badak Jawa bermukim. Kami sudah tak sabar ingin melihat hewan yang langka ini. Dulu aku pernah ditawari dosen untuk melakukan penelitian di tempat ini. Sayangnya waktu itu aku sudah terlanjur ikut proyek penelitian moluska di Pantai Anyer, jadi tur gratis ke Ujung Kulon bersama dosen ekologi itu terpaksa kulewatkan, dengan berat hati tentu saja.
“Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten ini merupakan tempat wisata alam yang kaya dengan aneka ragam ekosistem laut, rawa dan darat,” kataku sambil membaca jurnal. “Berbagai ragam flora dan fauna langka hidup dan berkembang biak dengan bebas di taman nasional seluas 122.956 hektar ini. Lokasi ini merupakan habitat asli salah satu satwa terlangka di dunia, yaitu badak Jawa yang kini jumlahnya hanya sekitar 50-60 ekor.”
“Aku pernah dengar cerita senior yang dulu melakukan penelitian di sini,” kata Igo. “Katanya yang mereka temukan hanya jejak kaki dan kotorannya saja. Itu pun jadi bahan penelitian penting untuk mengetahui umur dan jumlah populasi mereka.”
Sebagai cagar alam dan salah satu situs warisan alam dunia yang dilindungi oleh UNESCO, di daerah ini dilarang keras melakukan perburuan ataupun perusakan lingkungan. Sayang, ketika tiba di sana, makhluk-makhluk berkulit tebal dan bercula satu itu tak kami lihat satupun. Bahkan ujung culanya pun tidak. Akhirnya, dengan perasaan kecewa kami meninggalkan Ujung Kulon dan meneruskan perjalanan ke Jakarta.
*****
HARI KE-18, JAKARTA
“Nanti kita mampir ke rumahku di Jakarta Pusat,” kata Igo, saat mobil yang kami tumpangi membawa kami ke daerah perkotaan. Di kanan-kiri mulai tampak siluet gedung-gedung pencakar langit di kejauhan, berderet rapi seperti barisan tonggak raksasa. Setelah berhari-hari menjelajah ujung barat Nusantara, akhirnya kami kembali lagi ke kota ini. “Sekalian aku mau ambil motor, supaya di perjalanan nanti tidak terlalu repot. Mungkin ayahku bisa sekalian merawat kakimu, Harto.”
Inilah Jakarta, ibukota Negara Indonesia sekaligus jantung pusat peradaban negeri yang menyimpan berjuta kesibukan. Sebagai salah satu kota terpadat di dunia, tak heran jika Jakarta selalu dihiasi dengan kepulan asap pabrik atau jalanan macet yang tak terhindarkan setiap harinya. Kami menumpang bajaj menuju Jakarta Pusat. Kami tak hentinya memandang sekitar saat kendaraan unik khas Jakarta ini membawa kami berkeliling kota.
“Beruntung, di usiaku yang kedua puluh, baru kali ini aku naik bajaj,” kata Harto, mengelus kakinya yang diperban.
Sambil berkeliling kota, kami terus menatap sekitar. Kami tertarik dengan pertunjukan ondel-ondel, boneka khas Betawi berwujud pria dan wanita yang dirias seperti sepasang pengantin. Kami melongok ke luar saat iring-iringan boneka raksasa berisi manusia itu berlenggak-lenggok meramaikan jalan raya. Kami ragu apakah orang-orang ini asli Betawi atau bukan, mengingat orang Betawi asli yang senang berpantun itu sudah semakin langka di bumi Batavia ini.
Yang paling menarik sekaligus memprihatinkan adalah tampak menjamurnya bahasa asing. Kulihat mulai dari papan penunjuk jalan, spanduk, iklan reklame, hingga pintu toilet, hampir semuanya disertai bahasa Inggris. Bahkan ada yang hanya mencantumkan Bahasa Inggrisnya saja.
“Aku tak habis pikir,” kata Igo. “Memangnya ini negara apa? Jika keadaannya seperti ini harusnya para turis bule itu tak perlu repot-repot mempelajari bahasa Indonesia, karena kita dengan sukarela menyuguhkan bahasa mereka di manapun mereka berada. Bagiku seakan negeri ini kurang menghargai bahasanya sendiri.”
“Mungkin maksudnya agar negeri ini terkesan maju dan mampu bersaing dengan taraf internasional,” kataku netral. “Yang tinggal di kota ini kan banyak orang asing juga.”
“Iya sih, tapi alangkah lebih baik jika kita tidak membuang bahasa ibu kita sendiri. Aku pernah mendengar pepatah yang berkata: Untuk membunuh sebuah bangsa, bunuhlah dulu bahasanya. Bangsa yang kehilangan bahasa adalah bangsa yang kehilangan identitasnya. Kondisi ini beda sekali dengan Jepang atau Prancis yang menjunjung tinggi bahasa mereka. Kudengar orang-orang Jepang jarang memakai bahasa asing, dan orang Prancis terkenal enggan berbahasa Inggris.”
“Kamu sok tahu ah, mereka nggak gitu juga kali,” Nasuti tertawa.
Kami tertarik pada orang-orang berdasi yang lewat di depan sebuah kantor. Dengan penuh gaya mereka berbicara keras-keras dalam bahasa asing. Harto meminta Pak Sopir memelankan laju bajajnya. Saat melewati mereka, dengan kompak Harto dan Nasuti menimpali dengan bahasa Sunda, “Maneh goreng pisan euy! (kamu jelek sekali).”
Orang-orang itu mengernyit. “Ha? Goreng pisang?” kata salah seorang dari mereka, membuat Harto makin terpingkal.
Yang paling miris adalah pemandangan yang kami lihat di sekitar sungai. Betapa kemiskinan telah menggerogoti sebagian negeri ini. Rumah-rumah sederhana berbahan seng hingga kardus berjajar berdesakan di tepian sungai. Bahkan ada juga yang tak beratap sama sekali. Para penduduknya bertubuh kurus tak berdaging, pakaian mereka lusuh dan compang-camping dihajar peradaban. Lingkungan begitu kumuh karena sampah-sampah menggunung tak terurus, lalat-lalat berpesta pora di atasnya. Tampak orang-orang mencuci dan mandi di sungai yang menghitam, tak peduli dengan aliran sampah yang mengapung di permukaannya yang keruh. Ini adalah potret kemiskinan paling parah yang pernah kulihat.
Kami minta turun di depan sebuah bioskop, berhenti sejenak sambil mengamati poster-poster film yang dipajang. Hampir semuanya film hantu, dan sekali lihat saja bisa kami tebak bahwa film itu hanya mengandalkan judul vulgar yang sama dengan gambar posternya. Sosok hantu yang ditampilkan juga tidak menyeramkan sama sekali.
“Seingatku, cuma sedikit sekali film-film dalam negeri yang sifatnya mendidik dan membangun moral,” kata Igo. “Yang paling umum ya film-film hantu ini. Kalian tahu kenapa film-film hantu tokohnya selalu urakan, berpakaian minim, dan suka hura-hura? Soalnya, kalau tokohnya sholeh, filmnya bakal tamat di awal cerita, karena jin nggak bakal berani ganggu orang yang kuat imannya. Coba kalian lihat apa yang dilakukan si tokoh pas ketemu hantu. Bukannya zikir atau baca doa, eh malah ngomong kasar dan nyumpah-nyumpahin si hantu. Gimana nggak kesal hantunya.”
“Cape deh,” kata Harto. “Kalau mau protes, sana ke produsernya langsung!”
Igo mengajak kami ke rumahnya yang tak jauh dari bioskop itu. Setiba di sana, kami terperangah kagum dan serentak menjatuhkan ransel. Rumah itu sangat besar dan megah, terdiri atas tiga lantai dan bersebelahan dengan klinik umum tempat ayah Igo bekerja. Tampak seorang gadis menyiram bunga di halaman. Ketika melihat kami, gadis itu melonjak dan menghambur ke arah kami. Segera saja dia memeluk kakaknya.
“Bang Igooo!” pekiknya. “Abang bawa temen-temen nih?”
“Iya. Kamu nggak sekolah, Karina?” Igo mengelus kepala adiknya.
“Kan lagi libur panjang, Bang, lupa ya?” sahutnya riang. “Ayo, silakan masuk Mas.” Dia tersenyum pada kami, lalu berteriak ke arah rumah. “Papaaa... Bang Igo pulang!”
Ayah Igo, Dokter Isnain muncul di pintu. Jas dinasnya bergoyang-goyang, wajahnya berbinar-binar. Dia melompat dan memeluk Igo seolah sudah berpisah bertahun-tahun. Dokter Isnain adalah pria muda berjanggut, berdagu belah, dan berwajah ceria.
“Ayo masuk, Adik-adik,” katanya ramah.
Kami masuk ke ruang tamu yang luas. Dokter Isnain mempersilakan duduk. Barisan sofa empuk menyambut kami. Di dinding dipajang beberapa lukisan termasuk sebuah foto berukuran besar yang memperlihatkan seorang wanita cantik. Mungkin itu ibunya Igo. Karina bergegas ke dapur dan membawakan beberapa cangkir teh dan camilan ringan. Kami mengobrol ringan seputar kuliah dan pengalaman selama perjalanan.
“Bagaimana perjalanannya, Adik-adik, lancar?” kata Dokter Isnain ramah. Kami hanya tersenyum sebagai jawaban. Perjalanan kami tak bisa dibilang lancar jika mengingat insiden Harto yang digigit buaya. “Dulu waktu masih muda, saya juga pernah punya keinginan untuk travelling. Maklumlah jiwa-jiwa muda, selalu bergejolak dan terus mencari tantangan. Cuma waktunya tidak pernah sempat. Masa muda saya selalu disibukkan oleh pelajaran dan seabrek tugas kuliah. Bisa kalian bayangkan kesibukan mahasiswa kedokteran seperti apa kan? Selesai kuliah, saya langsung kerja di rumah sakit, jadi niatan saya tidak pernah kesampaian hingga sekarang.”
“Ah, Papa gimana sih?” kata Igo ketus. “Kan Igo sudah bilang, kalau mau ikut kami ya ikut saja, tak usah gengsi. Meski umur beda jauh, nggak bakal diketawain kok.”
Dokter Isnain hanya tertawa menanggapinya. Karina mengulum senyum. Aku dan Harto bertukar tatapan heran melihat Igo bicara dengan ayahnya seperti kakak-adik saja.
Selepas shalat Isya, kami berkumpul di ruang tengah. Di dinding ruangan itu juga ada foto wanita yang sama dengan yang di ruang tamu. Hanya saja ukurannya lebih besar, setinggi manusia asli. Kami sampai keheranan melihat ada foto sebesar itu. Karina sibuk mondar-mandir di dapur. Igo membantunya membawakan piring-piring ke meja makan. Keramahan keluarga Igo dalam menerima tamu memang tak tanggung-tanggung. Kulihat ada ayam goreng, nasi uduk, soto betawi, kerak telor, kentang goreng, dan daun selada. Makan malam istimewa siap disantap. Semua ini disiapkan hanya untuk menjamu perut kami yang berkapasitas terbatas. Kami jadi tidak enak, tapi Igo memaksa.
“Adikku yang masak, enak lho,” katanya bangga. “Dihabisin ya.”
Kami makan dengan lahap. Semua lauk yang tampak menggiurkan kucoba satu-satu. Selama beberapa saat yang terdengar hanya bunyi denting sendok dan garpu.
“Kamu kelas berapa sekarang?” Harto menanyai Karina.
“Kelas tiga SMP Kak,” jawabnya sambil tersenyum.
“Wah hebat, masih muda sudah jago masak,” Nasuti memujinya.
“Sejak kecil, dia harus belajar mandiri,” kata Dokter Isnain. Dia kemudian menunjuk foto wanita muda di dinding. “Itu ibunya Igo, meninggal tiga tahun lalu karena penyakit paru-paru. Saya merasa bersalah karena dulu saya senang merokok. Sejak saat itu tugas ibu rumah tangga seperti mencuci dan masak kami kerjakan bersama, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti merokok.” Mendengar itu, aku, Harto dan Nasuti bergumam sedih. Karina menunduk menatap piringnya. Wajah Igo datar.
“Ah Papa, jangan diceritain dong, jadi nggak enak nih,” Igo menyikut ayahnya.
“Kok kamu nggak sopan sih sama ayahmu?” Harto mengingatkannya.
“Mereka biasa kayak gitu Mas, udah dari dulu,” Karina nyengir.
Selesai makan, Igo membisiki ayahnya sesuatu, lalu memanggil Harto. Dokter Isnain memeriksa kaki Harto, lalu mengantar Harto ke kliniknya. Perban dibuka, luka-luka gigitan di betis Harto diperiksanya.
“Lukanya sudah kering. Tapi kamu harus istirahat agar lukanya tidak terbuka lagi.”
“Dia kabur dari rumah sakit, Pa,” Igo memberitahunya. Mendengar itu, Dokter Isnain hanya tertawa.
“Saya sudah sering menghadapi pasien yang seperti itu. Dulu sewaktu saya masih kerja di rumah sakit, banyak pasien yang tak sabar minta cepat dipulangkan. Saya sendiri juga berpikir demikian. Rumah sakit memang membosankan, makanya saya lebih suka membuka klinik di rumah, hahaha.”
“Oh ya Dok, waktu di rumah sakit, saya dengar kok ada pasien yang merintih, dan kedengarannya dari ruang operasi. Harusnya kan sudah dibius. Itu kenapa ya Dok? Apa si dokter salah potong organ, obatnya tertukar atau bagaimana?” Harto bertanya.
“Biar saya tebak, mungkin dosis obat bius yang diberikan kurang,” jawab Dokter Isnain. “Itu adalah kesalahan yang umum terjadi, dan biasanya dilakukan oleh dokter yang belum berpengalaman. Dulu saya juga pernah menjadi mentor mahasiswi kedokteran yang magang di rumah sakit tempat saya bekerja. Dia gadis yang cantik, cerdas dan telaten, tapi kadang agak ceroboh dan sering melamun sehingga membuat saya kewalahan. Kalau tidak salah namanya... ah, saya lupa.”
Harto tampak lega tidak diomeli. Dokter Isnain ternyata santai dan humoris. Aku sendiri menganggapnya jenaka dan agak kekanakan. Harto diberinya beberapa obat untuk mengeringkan luka. Igo membimbing kami ke peristirahatan. Aku tidur bersama Igo di kamarnya yang luas. Harto dan Nasuti di kamar sebelah.
“Katanya beberapa hari lagi sembuh,” kata Harto. Perban baru melingkari betisnya. “Aku sudah pegal pakai tongkat terus.”
Malam itu kami tertidur lelap sekali. Rasa penat dan lelah akibat perjalanan berhari-hari telah melenakan kami. Igo sampai mendengkur keras sekali, dan aku tak kebagian tempat tidur karena dia menjarah wilayahku. Selain itu aku juga terganggu karena kakinya menindih perutku. Pagi-pagi sekali, Dokter Isnain berdiri di pintu sambil memukul-mukul wajan, berteriak, “Good morning, ohayoo (selamat pagi), ayo bangun semuanya. Kita shalat Subuh berjamaah.”
Kami bangun dengan mata masih mengantuk. Nasuti menabrak dinding saat berjalan keluar. Kami shalat berjamaah di ruang tengah. Dokter Isnain menjadi imam. Aku perhatikan bacaannya tartil dan suaranya enak didengar. Setelah sarapan nasi goreng, Igo masuk ke garasi dan muncul kembali menuntun motor Harley Davidson hitam kesayangannya. Gagah betul motor itu. Kami sempat sangsi melihat pria kurus seperti Igo menunggangi motor besar. Rencananya kami akan naik motor secara bergiliran berdua-dua, sementara dua lainnya naik bus. Pukul tujuh pagi kami pamit mohon diri.
“Terima kasih untuk jamuan dan penginapannya Dok,” kataku sambil menyalami Dokter Isnain. “Masakanmu lezat lho, Karina.”
“Terima kasih obatnya,” kata Harto. “Kaki saya sudah agak baikan sekarang.”
“Kalau kalian lewat Bandung, coba ke daerah selatan Lembang,” saran Dokter Isnain. “Ada kenalan saya di sana, namanya Pak Asep. Beliau seorang pemilik perkebunan stroberi.”
Igo mengangguk, lalu mengelus adiknya. “Jaga diri baik-baik ya Dik.”
Kami berjalan ke gerbang. Dokter Isnain dan Karina melambai melepas kami.
“Kapan-kapan main lagi ya Kak,” Karina berteriak. Kami balas melambai.
“Keluargamu heboh ya,” komentar Nasuti, saat kami mencapai jalan.
“Berisik,” Igo cemberut, menuntun motornya.
Dari depan bioskop, aku dan Harto naik bus sementara Igo naik motor bersama Nasuti yang beruntung mendapat giliran pertama. Kami tertawa-tawa geli membayangkan nasib Igo yang kerepotan dengan si mabuk kendaraan.
Selagi masih di Jakarta, aku ingin sekali mampir ke AncolDunia Fantasi yang menawarkan lebih dari 40 wahana dan atraksi termasuk roller coaster dan tornado. Namun hanya beberapa wahana yang kami coba karena waktu yang terbatas. Setelah puas bermain, kami berjalan-jalan santai di sekitar Monumen Nasional atau Monas. Menara kebanggaan kota Jakarta itu menjulang di atas kami. Puncaknya yang terbuat dari emas berkelap-kelip tertimpa cahaya matahari.
Kami shalat Zuhur di masjid Istiqlal yang tak jauh dari Monas. Kami terkagum-kagum dengan arsitekturnya yang modern, dengan ukuran yang sangat luas dan berkapasitas menampung ribuan jemaah. Memang pantas jika masjid ini dinobatkan sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Kami juga sempat tersesat di tempat wudhu yang seperti labirin dan dipenuhi deretan tiang penyangga. Papan penunjuk jalan yang tersebar di setiap dinding sama sekali tak berguna bagi kami. Akhirnya, setelah kelelahan berkeliling kesana kemari, kami berhasil tiba di ruang utama masjid. Kami kaget saat melihat veteran tua TNI yang bertugas menjaga penitipan barang, sangat mirip dengan Pak Hendro Pramono, dosen mikrobiologi di kampus dulu. Mendadak kami jadi teringat kenangan saat kuliah.
Tiba-tiba hp-ku berdering. Ada yang menelepon, ternyata Ruqoyah. Aku kaget juga, ini pertama kalinya dia menghubungiku sejak sambungan yang putus waktu itu. Aku melirik teman-temanku yang sedang rebahan di karpet, lalu memisahkan diri ke balkon.
“Halo? Assalamualaikum.”
“Waalaikumsalam,” jawabnya. “Kak Lutfi, apa aku mengganggu?”
Nggak kok,” sahutku riang. “Ada apa?”
"Begini Kak, aduh gimana bilangnya ya?” nadanya terdengar panik, dan beberapa saat tertentu yang kudengar hanya gumaman tak jelas. “Ngg, sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan. Ini soal Kak Igo. Selama ini, dia pernah dekat sama cewek nggak?”
Aku hampir saja menjatuhkan hp-ku.
“Nggak, dia tak suka dekat-dekat cewek,” kataku. “Aku tahu arah pembicaraanmu. Maaf, bukannya tak mau membantu, tapi aku tetap tak setuju kalau kau menikah dengan Igo. Menurutku, dia bukan orang yang tepat buatmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, jadi jangan anggap aku egois ya.”
"Ini bukan ideku, Kak, aku cuma ikut saran seseorang. Tolong jangan kaget ya Kak, sebenarnya aku disarankan Ayah agar cepat-cepat menikah, karena kebetulan sudah banyak yang melamar, tapi tak ada satupun yang cocok. Kemarin aku konsultasi ke Ustad Faizar, menanyakan siapa muridnya yang kira-kira cocok denganku. Beliau menyarankan Kak Igo sebagai pilihan terbaik. Katanya, beliau sudah mengamati gerak-gerik, akhlak dan perangai Kak Igo. Menurutnya Kak Igo lebih dari memenuhi syarat yang kuminta. Beliau juga siap jika diminta menjadi perantara. Ng, Kak Lutfi nggak marah kan? Maaf, aku sudah lancang karena nggak nurut saran Kak Lutfi.”
Dia mengatakan itu dengan sangat cepat sehingga kesannya seperti sudah dihafalkan. Aku melongo mendengar semua itu. Kalau sudah begini, mau bagaimana lagi.
“Ya, sudahlah... keputusannya ada padamu. Bagaimanapun, itu sudah fitrahmu sebagai wanita normal. Tapi aku tak menjamin Igo mau menerimamu atau tidak. Dan kalau nanti kamu merasa kurang bahagia, jangan menyesal ya. Aku sudah mengingatkanmu.”
“Jadi, Kak Lutfi setuju?” tanyanya lagi, terdengar girang.
“Nggak juga, hanya saja sepupuku mengincar sahabatku... rasanya agak aneh,” kataku. “Nah, jadi kapan kau… Halo? Halo? Ah, sayang, baterainya habis.”
“Siapa sih yang nelpon? Seru amat,” tanya Harto, tiba-tiba muncul di belakangku. Aku mendongak, kaget.
"Biasa, adik sepupu tersayang,” kataku. “Kau menguping ya?”
“Nggak kok,” katanya jujur.
Aku merogoh tas dan mengeluarkan charger. Saat hendak men-charge hp di lantai bawah, seorang petugas mengusirku.
“Kalau nge-charge hp jangan di sini De, di luar aja sana!”
Aku menurut saja meski agak jengkel.
“Lho, ini kan rumah Allah. Takmir kok begitu amat?” gerutu Harto.
Kami duduk-duduk di teras masjid, mengamati petugas yang sedang mengepel. Aku menatap jauh ke depan, ke arah sebuah gereja artistik yang berdiri tepat di depan masjid ini. Seorang remaja laki-laki mengamen di depan kami. Suaranya serak-serak basah. Rambutnya hitam legam dan usianya kira-kira tujuh belas tahun. Jika diperhatikan wajahnya cukup rupawan jika saja tidak kucel berlapis debu. Pakaiannya kumal dan berlubang-lubang.
“Siapa namamu, Dik?” tanyaku iseng.
“Seno, Mas,” katanya dengan logat Jawa.
“Sepertinya kamu bukan asli sini, ya? Kenapa jauh-jauh merantau ke sini?”
“Saya ke sini cari kerja, Mas,” jawabnya, mengantongi alat musiknya yang berupa kecrik dari susunan tutup botol. “Orangtua saya sudah meninggal.”
Kami tertegun sejenak. Karena tidak punya receh, anak ini kami beri makanan saja. Kami ulurkan dua bungkus roti ke tangannya. Lagipula kami khawatir jika anak ini terpaksa mengamen karena disuruh preman sekitar. Kami tak mau sedekah kami digunakan untuk tujuan maksiat. Aku sering lihat di televisi, anak-anak diculik dan dijadikan budak oleh para preman yang berkuasa. Anak-anak malang ini didoktrin agar tak ingin pulang, lalu diperbudak dan dipekerjakan sebagai pengemis atau pengamen, sementara keuntungannya diambil seenaknya, dibelanjakan untuk narkoba dan minuman keras.
“Jangan dibawa pulang De, makan disini saja,” kataku.
Seno menoleh. “Ini buat abang saya di rumah, Mas. Kasihan dia kelaparan.”
Akhirnya kami biarkan dia pergi. Kami memutuskan duduk-duduk untuk beberapa saat lagi. Tanganku mengipas-ngipaskan buku ke leher untuk mengusir gerah. Sebelum berangkat, Igo membeli es krim di dekat pintu gerbang. Saat merogoh saku, dia tampak pucat. Berkali-kali ia merogoh kantong baju dan celananya dengan kelabakan.
“Gawat,” katanya. “Dompetku hilang, padahal uangku ada di situ semua!”
Kami semua terperanjat, panik. “Sudah kauperiksa? Barangkali tadi terjatuh.”
“Mungkin juga,” Igo manggut-manggut. “Akan kucari di dalam. Kalian tolong jaga sepatuku,” Igo buru-buru masuk kembali ke masjid. Kami menunggu, hingga setengah jam kemudian dia kembali, wajahnya belum berubah. “Nggak ketemu, jangan-jangan kecopetan?”
“Dari tadi kan kami bersamamu, masa iya ada yang berani nyopet,” kata Harto.
“Cepat hubungi bank, minta blokir ATM,” saran Nasuti.
Igo buru-buru menelepon. Bisa dibayangkan jika hasil tabungannya selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap ditelan kejamnya Ibukota. Tapi yang jadi masalah bukan cuma itu. Kami khawatir jika kartu identitas seperti KTP disalahgunakan orang tak bertanggung jawab untuk tujuan kejahatan dan tindak kriminal. Kami ngeri membayangkan Igo tiba-tiba diseret polisi atas tuduhan yang tidak diperbuatnya, sementara si penjahat tertawa-tawa di luar sana. Kami kebingungan di tengah kota, tak berkutik, tak bisa ke mana-mana lagi. Kami tak mungkin meneruskan perjalanan dalam keadaan seperti ini. Masalah timbul silih berganti seolah menghadang kami. Apa yang harus kami lakukan?
Kami segera melapor ke polisi terdekat. Saat menuturkan keluhan kami, polisi itu hanya mengangguk-angguk pelan, sementara rekannya asyik menonton tv, tampak tak peduli.
“Kejadian seperti ini apa sering terjadi Pak?” tanya Nasuti.
Polisi yang duduk di sana malah membentak kami. “Tidak, jarang sekali ada pencurian di sini. Di sini aman De! Kalian saja yang kurang hati-hati!”
“Makanya, saya sarankan Adik menjaga barang baik-baik,” polisi satunya lebih lembut.
Kesannya mereka tak mau membantu sama sekali. Kami malah disuruh menyiapkan surat-surat yang tak kami punya untuk membuat laporan kehilangan. Bukannya mudah malah semakin merepotkan, seakan mereka mempersulit kami. Kesal diperlakukan begitu, kami pergi saja. Tak ada cara lain. Kami kembali ke tempat duduk tadi. Igo punya asumsi siapa pelakunya. Tak ada salahnya curiga. Betul saja, kami lihat Seno ada di situ, mengamen di depan sekelompok pelajar. Diam-diam kami buntuti anak itu. Saat dia menumpang mobil bak, Igo dan Nasuti mengejar dengan motor, sedangkan aku dan Harto naik ojek. Mobil bak itu membawa kami ke terminal bus. Kami mulai was-was.
Masih bersembunyi, kami lihat Seno berlari mendekati sekelompok orang berpenampilan mengerikan. Ada yang hidungnya ditindik, lengannya ditato, rambut dicat, dan memakai kalung berduri. Tindakan mereka tak kalah jahat dengan penampilannya. Salah seorang dari mereka menenteng gitar, kulihat mengamen di depan pria tua yang duduk sendirian sambil memaksa minta receh, mengacungkan tinju. Rekannya lebih buruk, pria berpakaian sopan dan rapi, namun nyatanya calo angkutan umum yang menjual tiket dengan harga tiga kali lipat—pemerasan cara halus yang memuakkan. Pria ketiga yang tampaknya bos preman menutupi kepala gundulnya dengan lilitan saputangan hitam. Wajahnya bercodet, tato sisik naga melingkari lengannya yang berotot. Dia mondar-mandir dan bersikap sok, penampilannya buruk tapi lagaknya selangit. Kudengar seorang anak buah memanggilnya Bang Jeki. Saat Seno mendekat, anak itu dipanggilnya untuk menghadap, dibentak-bentak. Semua uang di kantongnya dipreteli, termasuk roti pemberian kami tadi dilahapnya juga.
“Itu abangnya? Kok beda banget,” bisik Igo. Seno berbicara dengan logat Jawa, sementara “kakaknya” berlogat Betawi. Penampilan mereka sejauh langit dan bumi.
“Mana lagi, cuma segini?” bentak si preman yang bernama Jeki. “Dari pagi ngapain aja kerjaan lu?” Dia menoleh pada temannya. “Gimana menurut lu, Tomi?”
“Kasih pelajaran aja, Bang Jeki,” jawab Tomi, pengamen berambut sebahu yang berdiri di sebelahnya. “Ya nggak, Bang Uul?”
Uul, calo berpakaian rapi dan bermata tajam itu menggeleng. “Udah biarin aja Bos, nggak usah dihajar. Rotinya lumayan juga. Tumben ada yang ngasih beginian.”
“Ya udah, sana pergi! Kalau nanti sore belum dapet duit juga, kita gebukin lu!” ancam Jeki si bos.
Seno berjalan gontai, kelihatannya hampir menangis. Saat mendekat ke arah kami, langsung kami cegat dia. Anak itu kaget, berusaha melepas pegangan Harto, dan sayangnya berhasil. Dia melesat melewati kami dan berlari ke arah gang sempit. Larinya gesit sekali. Tanpa pikir panjang kami langsung mengejarnya, mengabaikan tatapan heran orang-orang, menyusuri barisan rumah susun, melewati kios-kios pedagang, dan melompati tong-tong besar atau kotak kayu berisi botol kosong yang digulingkan Seno untuk menghalangi kami.
Entah sampai kapan kejar-kejaran ini berakhir. Kakiku sudah pegal, tapi kami tetap bergegas. Seno makin terlihat jauh di depan, sesekali menyerempet orang lewat, dan melompati dinding jika bertemu jalan buntu. Kami tak kehabisan akal. Salah besar jika dia mengira kami tak bisa melewati semua ini. Kami terpaksa ikut aturan mainnya, melompat dari dinding satu ke dinding lain seperti atlet parkour. Harto dan Nasuti kusuruh mengambil jalur lain untuk mencegat anak itu. Ketika Seno tiba di ujung jalan, terhalang tembok setinggi enam meter, Harto muncul dari jalan lain dan menjegalnya, menjatuhkan anak itu ke tanah, lalu meringkusnya. Kami bawa ke tempat aman dan kami paksa dia buka mulut. Awalnya dia diam saja, menggeleng, tapi setelah didesak berkali-kali akhirnya mengaku juga kalau dirinya copet. Dia menangis keras-keras. Dari mulutnya, kami mendengar cerita memilukan.
“Ampun Mas, saya nggak salah apa-apa, jangan pukuli saya.”
“Lalu kenapa kau lari?” tanya Harto.
“Saya takut, Mas, saya terpaksa hidup begini. Dulu saya hidup enak, rumah saya di Jawa Tengah. Saat sedang main, saya diculik orang tak dikenal dan dibawa ke sini. Waktu itu umur saya sepuluh tahun. Saya dijual ke mereka—orang-orang ini. Banyak teman saya yang senasib dan diperlakukan serupa. Ada perempuan dan anak-anak juga. Saya dan beberapa teman dikurung tanpa diberi makan. Baru satu minggu kemudian dibebaskan. Itu juga kami dipaksa mengamen seharian. Kalau nggak dapat uang, kami nggak diberi makan.”
“Pantas kau kelihatan seperti orang kaya,” kata Nasuti. Seno mengusap mata dengan lengan bajunya yang kotor. Anak ini tak bersalah, dia cuma alat. Yang bersalah para preman itu. Dompet Igo yang malang pun pasti berpindah ke tangan mereka.
“Kamu tidak berani lari? Kamu punya banyak kesempatan untuk itu,” kataku.
“Nggak berani Mas, saya juga nggak punya uang buat ongkos pulang.”
“Kenapa tidak minta tolong polisi?” tanya Igo.
Seno menunduk. Hal itu mungkin tak terpikirkan olehnya. Atau mungkin dia takut.
“Begini saja, sekarang Kakak antar kamu ke kantor polisi,” kata Harto lembut. “Kalau perlu, ongkosnya Kakak yang bayari. Jangan kembali lagi ke sini, ya?”
Harto membawa Seno pergi. Itu tindakan terbaik yang bisa kami lakukan untuk bocah malang itu. Sementara itu aku, Igo dan Nasuti kembali ke dekat terminal, mengawasi para preman. Preman-preman itu membagi-bagi recehan hasil jerih payah Seno, lalu pergi sambil tertawa keras. Kami buntuti dengan hati-hati, hingga tiba di bangunan kosong yang tak terurus, mungkin semacam markas rahasia mereka. Pasti dompet Igo disembunyikan di suatu tempat di sini. Kami mengintip dari celah sempit di bawah jendela. Tampak orang-orang itu main kartu, merokok dan mabuk-mabukan bersama lusinan berandal lain. Aku jadi tak ikhlas kalau pemberian kami digunakan untuk maksiat.
“Ayo, kita hajar mereka,” Nasuti tak sabar.
“Jangan gegabah, lebih baik kita menunggu polisi,” saranku.
“Bodo amat. Penjahat jangan diberi ampun,” geram Nasuti.
“Kebanyakan nonton film action, kamu,” kataku. “Jangan cari gara-gara. Kekerasan bukan jalan keluar yang baik. Ingat ajaran kempo yang selalu kita ikrarkan. Jangan cari permusuhan, hindari perkelahian. Jika terlibat, kita harus menyerang secara pasif. Biarkan musuh menyerang terlebih dahulu. Gunakan jurus hanya untuk membela diri. Jangan melukai lawan kalau bisa.”
“Aku tak bisa menjamin itu,” kata Nasuti. “Itu mustahil. Ini bukan pertandingan. Buka matamu lebar-lebar, Lutfi. Sekarang bukan waktunya bersikap lunak. Mereka ini penjahat. Mereka sering melakukan perbuatan buruk. Banyak hal yang terjadi di dunia, yang tak pernah kita bayangkan. Selama ini kita terbiasa hidup di dalam kamar, di tempat yang damai dan tak mengenal perang. Sementara itu, di luar sana, banyak anak-anak yang tinggal dan dibesarkan di medan perang. Hari-hari mereka diwarnai ketakutan akan peluru nyasar atau ledakan bom. Mereka harus berjuang keras hanya untuk bisa makan atau sekolah. Yang kita hadapi sekarang ini hanya sebagian kecil saja dibanding pengalaman anak-anak Palestina, yang sudah menenteng senjata api di usia belia. Kita harus melawan, Lutfi! Kita harus menegakkan amar makruf nahi munkar!”
“Woi, siape lu pade? Keluar lu! Gue tau lu ngumpet di situ!” teriak seorang preman. Kami semua terdiam, menahan napas. “Keluar lu! Atau gue samperin sekalian!”
“Ah, gawat, kita terlanjur ketahuan,” kataku. “Apa boleh buat, kita harus melawan. Tapi jangan sampai ada darah yang keluar. Hanya lumpuhkan mereka kalau bisa.”
Aku malas jika harus bertarung sungguhan dan aku tak suka kekerasan. Namun Igo tampaknya lebih setuju dengan pendapat Nasuti.
“Ini demi dompetku, Lutfi,” katanya.
Aku menghela napas.
“Baiklah, kubantu kau,” aku berdiri. “Tapi kali ini saja ya?”
“Nggak ada adegan action, kurang greget,” Nasuti meninju-ninju udara, menyeringai. Tampaknya dia tak sabar lagi, menerobos masuk tanpa gentar sedikitpun. Dia melompat maju, menghadapi para preman yang entah ada berapa jumlahnya. “Satu, dua, tiga, empat… banyak juga mereka. Aku tak begitu suka berhitung. Kayaknya tiga orang yang di belakang itu bosnya. Nah, begini saja, aku akan menghadapi yang tengah, agaknya dia kuat. Lutfi, Igo, kalian lawan sisanya—hei, kenapa kalian berdua masih di situ? Bantuin sini, woi!”
Aku dan Igo meletakkan ransel yang berat di tanah, lalu melangkah masuk, mengikuti Nasuti yang tak sabar memberi pelajaran pada orang-orang kejam bak tirani ini. Para preman itu melotot mengawasi kami, yang berjalan tegak seperti tiga kawanan pembalas dendam.
“Siape lu pade, hah?” bentak Tomi si pengamen.
“Balikin dompet gue!” teriak Igo.
“Berani macem-macem lu ye!” Uul si calo menyembur. “Nggak tau siapa kita, hah? Kita yang megang di sini! Lu pengen kita tonjokin, hah?”
“Jangan bikin gara-gara lu! Margono, hajar mereka!” perintah Jeki.
Salah seorang anak buah maju dengan kapak di tangan. Aku menunggu hingga jarak kami cukup dekat. Kemudian, sebelum dia sempat melancarkan serangan, kutinju wajahnya hingga terpelanting ke tanah. Kapaknya lerlempar sia-sia. Pria bernama Margono ini terkapar tak bergerak lagi. Jika digunakan dengan benar, tinju dapat menjadi senjata yang mematikan.
Melihat rekan mereka tergeletak oleh satu serangan, beberapa preman lain berteriak garang dan menyerbu kami. Igo dan Nasuti merapat ke punggungku, bersiap menghadapi serangan. Kami sadar sedang dikeroyok kawanan preman Ibukota yang tak kenal ampun. Mereka tak akan bisa diajak bicara baik-baik. Hanya tindakan yang dapat menghentikan mereka. Seorang yang berlari paling depan mengacungkan parangnya, mencoba menusuk perutku. Aku menghindar dengan mudah, menangkap pergelangan tangannya, memuntirnya, lalu menghantam wajahnya dengan siku. Dua orang di belakangnya bergerak maju, aku menangkap kepala mereka, lalu membenturkan keduanya di udara. Dua orang lainnya tersungkur kesakitan setelah kupukul bahu mereka dengan sabitan lengan. Aku melompat ketika seorang preman menjulurkan kaki hendak menyapu kakiku, kemudian kutendang dagunya dengan tendangan tinggi.
Di belakangku, Nasuti bertarung dengan gagah berani. Ia menangkap kepala lawan dan menariknya ke bawah, lalu menghantam dahi musuhnya dengan serbuan lutut. Seorang preman menyergapnya dari belakang, Nasuti berkelit dengan cara membungkuk dan membanting musuhnya ke depan, setelah itu memberi pukulan terakhir dengan meninju wajahnya, mematahkan hidungnya. Igo lebih banyak bertarung menggunakan kakinya. Seorang lawan dibuatnya ambruk dengan serangan pisau kaki—bagian telapak kaki yang berada di sisi luar. Beberapa preman lain bergeletakan dalam sekejap setelah mencicipi tendangan mautnya. Aku merasa orang-orang ini tak ada apa-apanya, sama sekali tak menantang. Kami bertiga terengah, berdiri menatap semua lawan yang terkapar di lantai dan meringis kesakitan. Pertempuran hampir kami menangkan.
Tinggal tiga orang tersisa. Sejak tadi, mereka hanya duduk diam selama pergumulan berlangsung. Begitu melihat bawahannya habis, Jeki bangkit dan murka. Dua rekannya turut maju dan mengepung kami. Ketiga orang ini pasti semacam petinggi, levelnya di atas yang lain. Igo dan Nasuti tak gentar sedikitpun, karena mereka juga pemegang sabuk cokelat. Nasuti meremas-remas tinju, Igo menghunus trekking pole-nya. Ini akan menjadi pertarungan sengit satu lawan satu. Nasuti melawan Tomi, Igo versus Uul, dan aku sendiri menghadapi bosnya, Jeki. Babak kedua segera dimulai. Jawara beladiri provinsi melawan preman Jakarta yang terkenal ganas. Mereka tak segan membunuh, jadi aku tak akan menahan diri. Akan kukeluarkan semua jurusku karena ini bukan pertandingan biasa.
Aku mengawasi dengan tegang saat Jeki menerjang ke arahku. Gerakannya cepat, serangannya mematikan tapi tak terarah. Bisa kutebak dia tak pernah belajar beladiri sama sekali. Aku merunduk dengan cepat, menyadari tinju yang meleset di atas kepalaku. Aku menyerang Jeki dengan pukulan bertubi-tubi di perutnya, lalu meninju dagunya hingga Jeki terpaksa mendongak. Tanpa memberi kesempatan, kutendang pria itu tepat di perutnya, membuatnya terhuyung mundur.
Jeki tampak terkejut sekaligus murka melihat dirinya bisa didesak sejauh ini, oleh anak remaja sepertiku. Pria itu mencabut sesuatu dari pinggangnya—stun baton, tongkat pendek yang dialiri listrik. Pasti dia terpaksa mengeluarkan senjata pamungkasnya. Di kiri-kananku, kulihat Uul menarik belati dan Tomi mengayunkan nunchaku alias double stick. Dua orang ini juga menghunus senjata karena terdesak mundur.
“Sekarang, tak ada lagi main-main!” teriak Jeki. Aku mengelak ke samping saat penyetrum itu berkelebat di dekat pipiku. Tersentuh sedikit saja pasti membuatku gosong. Jeki makin beringas mengayunkan senjatanya hingga aku kesulitan menghindar. Jari-jarinya yang berkuku tajam berhasil mencakar wajahku. Garis-garis darah terasa muncul di pipiku. Jeki menyerang lagi sementara aku terus berkelit, mulai terdesak, dan... BUK! Jeki tertawa keras saat berhasil membenamkan tinjunya di perutku, hingga aku terbungkuk.
Jeki tertawa penuh kemenangan. Namun tawanya lenyap saat dia melihat cengiran di wajahku. Aku mendongak dan menyeringai, menunjukkan perutku yang tidak apa-apa. Jeki terkejut saat melihat tinjunya berhasil kutangkap dan dihentikan sebelum mengenai perutku. Kutendang stun baton di tangannya hingga terlontar ke udara, berputar-putar, menghantam tembok dan jatuh berkelontang di lantai. Jeki menoleh dan terkejut melihat senjatanya hancur. Memanfaatkan kesempatan itu, kutinju wajahnya keras-keras, kupukul lehernya, dan sebagai penutup, kutendang selangkangannya hingga dia jatuh berguling-guling. Sebelum dia pulih, aku segera memiting dan melipat lengannya di belakang punggung, menguncinya.
Kulihat Nasuti dan Igo juga sudah melumpuhkan lawan masing-masing. Igo berdiri sambil menatap Uul yang terengah-terengah di bawahnya, belatinya tergeletak tak berguna di lantai. Sementara itu Nasuti melepas sorbannya, melilitkan ke leher Tomi dan menariknya sampai wajah pria itu membiru. Aku khawatir dia lupa diri dan bertindak kebablasan dengan mencekik lawannya hingga mati. Semoga saja Nasuti hanya menggertak.
“Aku belum kalah, kurang ajar!”
Aku tak menyangka Tomi meronta sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Pria itu langsung berdiri, membentuk kuda-kuda. Dia meraung-raung, double stick-nya diputar-putar ke segala arah, meniru-niru gaya Bruce Lee.
“Oh, mau mulai ronde kedua?” kata Nasuti enteng. Sebelum Tomi sempat berbuat apa-apa, Nasuti menghantamkan tinjunya sekuat tenaga, tepat mengenai ulu hati lawan. Sesaat, Tomi seperti hendak meninju, tapi kemudian matanya terbeliak, menyisakan bagian yang putih, dan perlahan tubuhnya ambruk. Selesai sudah, hanya perlu satu detik.
“Bangun!” hardik Nasuti, tapi Tomi sudah pingsan.
“Ampun, ampun, kami menyerah!” rengek Jeki yang masih kupiting.
“Kalian mencuri dompetku ya? Ayo mengaku!” Igo berteriak.
“Sumpah, gue kagak tau!” Uul mengaduh. Igo menggerayangi kantongnya, mencari di bajunya, bahkan menggasak pakaian dalamnya. Hal sama dilakukannya pada preman lain yang terkapar. Setelah mengikat mereka dengan tambang yang kutemukan di gudang, kami menggeledah markas bobrok itu, tapi tak menemukan yang dicari. Igo mendongak menatap kami dengan wajah frustasi.
“Memang nggak ada,” katanya lemas. “Terus, di mana dompetku?”
Agaknya para preman ini tak tahu menahu soal dompet Igo. Kami biarkan mereka terikat di lantai sambil meringis kesakitan. Sejak dikalahkan tadi mereka hanya meringkuk, tak ada satu pun yang berani kabur.
“Awas kalian! Bos besar kami tak akan tinggal diam!” ancam Jeki.
“Siapa bosmu?” sembur Igo. “Jadi, big boss sepertimu masih punya atasan lagi? Bilang padanya, kami tidak takut!”
Lelaki itu mendongak. “Jangan bilang kalian tak kenal nama Brewok. Semua preman di sekitar sini tunduk padanya. Tak ada yang tak takut mendengar nama itu. Dia broker terkenal dari dunia gelap, orang yang memegang bisnis narkotik dan barang-barang gelap ilegal hasil selundupan dari seluruh negeri. Pria bertangan dingin yang tak kenal ampun, menyingkirkan semua yang menghalangi rencananya. Dan asal tahu saja, anak buahnya ada di mana-mana, jaringannya tersebar luas di seluruh penjuru negeri.”
Jeki tertawa lagi. “Kalian pernah mendengar nama Zefry si pimpinan geng motor, Akhsay si pemburu liar, atau Pansus si penembak jitu? Itu nama-nama penjahat terkenal yang sulit ditangkap, dan mereka semua beroperasi di bawah perintah Brewok. Seingatku ada tujuh orang mengerikan yang bekerja untuknya, di samping bawahan lain yang jumlahnya tak terhitung. Tujuh orang ini tergabung dalam grup Jerangkong, organisasi kriminal rahasia yang bahkan aku pun tak diizinkan bergabung. Jika melawanku saja membuat kalian kewalahan, kalian pasti langsung mati jika bertemu salah satu dari tujuh orang itu. Apalagi jika Brewok sendiri yang turun tangan. Kalian tak akan lolos. Kalian harus berpikir dua kali sebelum berurusan dengannya.”
“Ngawadul maneh (kau cuma membual), dasar lebay,” kata Nasuti. “Jangan dengarkan dia, paling-paling cuma membual untuk menakuti kita.”
Harto datang tak lama kemudian, bersama sepasukan polisi bersenjata lengkap. Harto memberitahu kami bahwa Seno sudah aman di kantor polisi. Salah seorang polisi berjanji akan mengantarnya ke orangtuanya, begitu juga anak-anak lain yang dipaksa mengamen. Awalnya aku takut diinterogasi, terlebih jika melihat kondisi TKP yang kacau balau, banyak penjahat bergeletakan. Terlebih, aku takut diciduk karena disangka gembong mereka. Tapi para polisi tak menanyai kami. Rupanya Harto sudah menjelaskan semuanya. Kami berdiri puas saat para preman digelandang ke mobil, tampak pasrah dengan tangan diborgol, tak ada yang berontak. Uul dan Tomi tampak loyo. Jeki kehilangan kegarangannya.
“Terima kasih atas bantuannya, Adik-adik,” kata sersan polisi. “Berkat kalian, kami berhasil menangkap oknum penculikan anak dan pengedar miras yang sudah lama kami cari. Mereka sulit dikenali karena sering berbaur dengan kernet bus dan pedagang asongan. Tapi sekarang barang buktinya sudah jelas, mereka tak bisa mengelak lagi.”
“Jangan cepat-cepat dibebaskan Pak, biar kapok mereka,” Igo mengumpat.
“Perbuatan tadi jangan ditiru ya, Adik-adik,” Harto bicara sendiri ke arah kameranya. Rupanya sejak tadi dia merekam pergumulan kami, sesaat setelah mengantar Seno dan memanggil polisi. Aku tak sadar dari mana dia mengambil gambar. Kawanku ini memang jago sekali menyusup tanpa ketahuan. “Ambil jeleknya, buang teladannya, ups kebalik ding. Yah, dilihat dari manapun, perkelahian memang nggak ada bagusnya sih.”
“Tidak juga, membela harta pribadi sama mulianya dengan jihad,” kata Igo.
Kami menang, dan kami jadi pahlawan, tapi masih ada sesuatu yang terasa kosong di antara kami. Igo duduk termenung, memikirkan nasib dompetnya yang entah ada di mana. Kami prihatin melihatnya. Kuhibur dia dengan harapan kosong yang aku sendiri tidak yakin. Aku bisa membayangkan bagaimana rasanya jika aku yang kehilangan dompet, bukan dia.
Igo baru mengangkat wajah saat HP-nya berbunyi. Dijawabnya dengan suara lesu. Terdengar suara Dokter Isnain di seberang telepon. Kami tak bisa mendengar percakapan mereka. Igo menjawab cepat dengan suara dipelankan. Seketika raut wajahnya berubah cerah.
“Ada apa?” tanya Harto. Igo menatap kami bergantian, tersenyum lebar.
“Alhamdulillah, ternyata dompetku ketinggalan di rumah,” katanya riang. Kami ikut bergembira mendengarnya, bernapas lega, lalu kompak menimpuki Igo atas keteledorannya. Kami juga merasa bersalah sudah berprasangka buruk, meski tuduhan itu ditujukan kepada preman.
“Tapi mereka memang jahat, kalian pantas menghajar mereka,” kata Harto.
Siang itu juga kami terpaksa kembali ke rumah Igo. Dia tampak malu saat menerima dompet yang diulurkan ayahnya.
“Makanya Boy, periksa barang bawaan sebelum berangkat,” pesan ayahnya. “Untung ketinggalan di rumah. Kalau di tempat lain siapa yang mau bertanggung jawab? Dan jangan buru-buru menuduh orang lain sebelum punya bukti.”
Satu lagi pelajaran penting yang kami peroleh hari ini. Jakarta memang kota yang indah dan menyenangkan, tapi para wisatawan harus hati-hati dan selalu waspada. Banyak bahaya mengancam seperti aksi kejahatan dan pencopetan. Lengah sedikit, bersiap-siaplah merugi. Penyesalan memang tak pernah datang di awal. Dengan perasaan lega, kami berangkat melintas tol Jakarta, menuju Bandung.
*****


 radenbumerang
radenbumerang

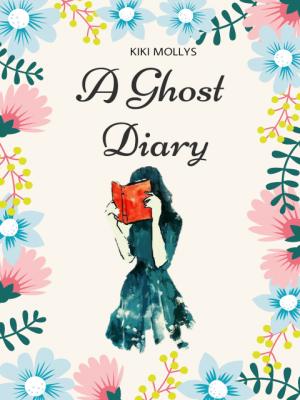





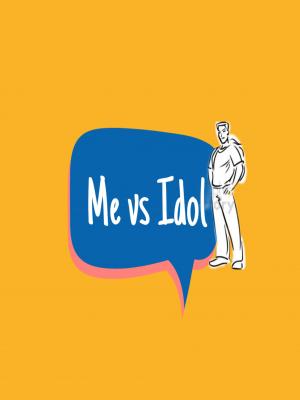


Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.