Lo membunuh sepupu gue! dasar cewek pembunuh!
Lo udah membunuh orang yang paling gue sayangi, Ra.
Dasar pembunuh
Pembunuh
Pembunuh
“Pem..bu..nuh.” Satu kata itu tercetus pelan dari mulut Mora.
Pemandangan gerombolan polisi dan dua mobil polisi yang bunyi sirini-nya seperti memecahkan gendang telinga, menimbulkan denyutan nyeri yang begitu dahsyat di kepalanya. Tiga tahun lamanya pemandangan itu menghantui pikirannya dan kini kembali tercetak di depan mata.
Datangnya polisi mengundang para tetangga mengerumuni rumahnya. Berbagai bisikan yang bila disatukan akan semakin jelas menjadi kalimat “Pak Baim membunuh bosnya.” Bisikan bernada sinis itu membawa Mora kembali ke dimensi tiga tahun yang lalu. Gemuruh sorakan menghantamnya, menusuk dalam setiap organ tubuhnya. Amarah orang-orang membanjirinya hingga udara tidak bisa memenuhi paru-parunya. Bila dulu sekolah menjadi tempat paling mengerikan karena di sanalah dirinya habis diamuk masa, maka kini rumah menjadi tempat yang akan selalu mengingatkannya pada sekolah itu.
Pembunuh
Pembunuh
Pembunuh
Kata itu seperti suara berfrekuensi tinggi yang mengorek dalam telinga dan mampu menimbulkan kucuran darah. Tangannya terkepal kuat menahan perih yang menjalari sekujur tubuh. Kerumunan orang di depannya membelah, semakin memperjelas keadaan rumah yang sesungguhnya. Dua orang polisi mengapit Papi yang berborgol diikuti Mami di belakangnya dengan wajah penuh tangis.
Hawa panas di sekitar mata Mora semakin meningkat tatkala adiknya yang berumur 5 tahun itu menangis meronta-ronta dalam gendongan seorang polisi perempuan. Mora melangkah lebar, menghadang Papi yang akan masuk ke mobil polisi. Matanya menyoroti kebencian, yang dalam sekali hentakan menghancurkan perasaan Papi. “Mora…” Ucap Papi lirih.
Mora melewati Papi, menuju Mami lalu mengambil paksa Mona dari gendongan polisi perempuan tersebut. Dibiarkannya tangisan Mona yang semakin menjadi-jadi ketika menghilang ke balik pintu.
***
Gebrakan di pintu kos kamarnya mengalihkan fokus Revi dari berita pembunuhan yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Udara seolah enggan masuk ke hidungnya saat melihat dalang yang nyaris merusak pintu kamarnya. Untung saja Bu Melati—ibu kos seksi tapi rewelnya minta ampun itu—tidak sedang patroli.
Mulut Devon terlihat hendak mencerocoskan protes namun rautnya dalam sekejap tidak menunjukkan hal itu. Revi menghela napas. Kamarnya akan aman beberapa detik ke depan, tapi entah untuk satu menit ke depan?
“Apa yang bokap gue kasih ke lo?” Tanya Devon datar setelah menghempaskan pantatnya di kasur.
Revi menelan ludah.“Nggak ngasih apa-apa.”
“Terus kenapa lo dengan gampang ngasih tahu tempat gitar-gitar gue.”
Revi mematikan televisi lalu memendekkan jaraknya dengan Devon.“Bikin sempit kamar gue!”
“Serius, Rev!” Sentak Devon menampilkan raut yang beberapa detik lagi akan berpotensi memporak-porandakan kamar itu.
Raut kekesalan, amarah, kegelapan. Apabila dirangkum akan menjadi satu kata yaitu kesedihan. Selama tiga tahun, selama itu pula raut yang setiap hari dilihat Revi. Tak ada lagi Devon yang cerewet, yang nyalinya selalu ciut, yang manjanya minta ampun, yang paling perfeksionis, yang paling ambisius.
“Karena lo nyaris mati. Lo nggak bangun-bangun dari mimpi buruk. Lo—“
“Lo udah menghancurkan Nanzo, Rev.”Potong Devon.
Revi menarik napas dalam-dalam. Dia tak mampu menahan lagi. Ditariknya Devon lalu dihempaskan dengan kasar ke dinding kamar. Kelima jarinya melingkari leher Devon lalu menekan kuat leher kurus itu. Deru napas mereka saling beradu menunjukkan betapa lelahnya mereka menghadapi kematian yang telah berlalu 3 tahun silam itu.
“Lo yang menghancurkan diri lo sendiri. Lo yang membunuh diri lo sendiri!”Semakin diperkuat tekanan di leher Devon hingga nyaris mengangkat cowok itu. “Lo udah menghancurkan gue dan Taki, yang paling parah lo udah menghancurkan hati bokap dan nyokap lo.”
“Semuanya emang udah hancur.Semuanya udah mati!”
Tonjokkan telak menghantam rahang kanan Devon lalu tanpa memberi kesempatan menghirup udara sedikitpun, tonjokkan itu beralih ke hidungnya. Revi berdesis marah sambil menyeret Devon ke sisi lain kamarnya. Emosi Revi semakin meningkat tatkala pertarungan itu hanya terjadi satu arah. Tak ada reaksi sedikit pun dari lawannya, hanya respon tatapan kosong yang semakin menyayat hatinya. Revi sedang menyadarkan sosok babak belur di depannya, tapi sosok itu sedang tidak ingin disadarkan.
“Nyatanya lo sendiri yang menghancurkan Nanzo.”
***
Mora melempar remot TV setelah menekan tombol off dengan sekuat tenaga. Semua acara berita hampir di setiap stasiun TV menyiarkan berita yang sama dengan latar belakang rumahnya. Rumah seorang karyawan swasta yang membunuh bosnya. Kata pembunuh itu rupanya tidak hanya tersemat dalam dirinya, tapi pada diri ayahnya pula.
Denting nada pesan LINE yang beruntun dilanjut dengan Free Call yang tiada henti semakin menghancurkan mood Mora. Hanya satu orang yang tidak bosan menyatroni ponselnya.Nama Cecilia tercetak di layar benda kotak itu. Merasa Cecil akan melakukan hal yang lebih ekstrim semacam mendatangi rumahnya bila panggilannya terus tak diacuhkan, akhirnya Mora memutuskan menekan tombol hijau di layar.
“Ya?” Suara serak Mora membuat Cecil di ujung telpon menghela napas lega setelah belasan kali panggilannya diabaikan.
“Mor, lo datang sekarangya ke kafe itu.”
Mora menghela napas kesal kuat-kuat, sekuat genggaman pada ponselnya yang semakin mengerat. “Lo nggak ngerti keadaan gue sekarang ya, Cil?”Tanya Mora dengan nada melengking tinggi.
“Bu..bukan gitu..bukan gitu maksud gue. Gue tahu kabar tentang bokap lo. Di sini gue, Ambar ma Ola mau ketemu lo. Kita nggak pengen lo sendiri. Kita pengen lo berbagai lagi.”
“Kenapa harus sama kalian. Gue bisa hadapi ini sendiri seperti 3 tahun yang lalu, tanpa kalian gue masih bisa hidup.”
Di ujung sana, Cecil menghela napas. “Kalau lo nggak datang, kita bakal ke--.”
“Jangan pernah kalian ke rumah gue.” Sambar Mora
Cecil mengigit bibir bawahnya. Usahanya mendatangi rumah Mora sudah dilakukan berkali-kali, dia bahkan pernah ditolak mentah-mentah. Kini yang bisa dilakukan hanyalah menunggu keajaiban mendatangi Mora dan menyadarkan cewek itu untuk membuka lagi hatinya.
“Nggak Mor. Lo nggak hidup. Lo nggak—“
Mora menekan kuat tanda bulat merah di layar, memotong omongan Cecil di ujung sana. Emosi yang telah menguasainya menghambat udara memenuhi paru-paru. Begitu sesak hingga dadanya naik turun dengan cepat.
Mora berdiri dengan menghentakan kakik lalu hendak menuju kamar ketika Mami tiba-tiba menghalangi jalannya. Jejak air mata di wajah Mami tampak jelas namun itu nyaris tertutupi oleh ketegarannya.
Mata Mami menyorotinya lembut. Helaan napas lelah Mami menyayat telinga Mora sehingga tak mampu sedikit pun dia melanjutkan langkahnya. “Mora temui teman-teman kamu.” Nasehat Mami lalu menarik Mora kembali duduk.
Mora mengekor lalu duduk di samping Mami. “Terlalu sakit, Ma. Mereka sama seperti orang-orang di luar sana yang menghina Mora, padahal mereka sendiri tahu penyebabnya tapi mereka menutup mata dan telinga.”
Mami menggeleng. “Kalau mereka seperti itu, kenapa mereka selalu menelpon Mami untuk menayakan keadaan kamu.Mereka--.”
“Itu paling Cecil, Mi.” Potong Mora ketus.
“Dua hari yang lalu Ambar dan Ola datang ke rumah, mau ketemu kamu. Mereka bahkan rela nunggu kamu sampai malam.“
Mora termangu. Dua hari yang lalu dia pulang tengah malam karena jurusannya mengadakan kunjungan studi lapangan ke salah satu pabrik pengolahan keju di Sukabumi. Dia langsung teringat mobil merah yang berpapasan dengannya yang menaikkan motor datang dari arah rumah. Sesaat dia seperti mengenali pengemudi di balik mobil itu namun malam itu otaknya terlalu lelah untuk berpikir.
Mora hanya membuang muka sambil mengangkat bahu acuh tak acuh. Keringat tiba-tiba menjalari punggung lehernya. Entah apa yang bergejolak di dadanya. Marah atau senang? Kini, segalanya terasa sulit untuk didefinisikan. Rasa kangen, marah dan benci menyerangnya berbarengan, tidak memberinya celah sedikit pun untuk menjabarkan rasa dalam hati.
“Mami lupa memberi tahu kamu kalau mereka datang.”Mami mengelus puncak kepala Mora.“Memberi maaf sama halnya dengan membersihkan diri terutama membersihkan hati. Sahabat baik bukan hanya diartikan sebagai sosok yang selalu hadir dalam suka dan duka, tetapi sahabat baik diartikan pula sebagai sosok yang selalu tahu letak kesalahan mereka dan berusaha meminta maaf bagaimana pun caranya, mereka juga akan selalu merasakan kehilangan ketika tak lagi bersama. Dan Cecil, Ambar, Ola telah memenuhi syarat itu. Sahabat baik juga selalu memberi maaf sesakit apapun hatinya. Dan kamu yang akan memenuhi syarat itu.”
Mora menyelami perkataan Mama. Luka itu sangat dalam sehingga terasa mustahil untuk bisa menutupinya hingga tak berbekas.Apakah harus semudah itu langsung memaafkan mereka?
“Apa adil buat aku, Mi?Mereka mencampakkan aku dan aku langsung memaafkan mereka begitu saja?”
“Ini bukan tentang adil dan tidak adil. Ini tentang ketulusan hati kamu.Tentang seberapa sayang kamu dengan mereka.”
Mora menggigt bibir bawahnya, menahan air mata yang siap meluncur dalam hitungan detik.Seberapa sayang? Dua kata itu yang menghentaknya.
“Memang sulit. Tapi kalau kamu memberi kesempatan bagi diri kamu sendiri melihat keseriusan mereka, Mami yakin kamu akan memaafkan mereka. Sahabat yang baik untuk sahabat yang baik juga.” Mami menghela napas, genggamannya semakin kuat mengunci tangan Mora. “Mami nggak ingin kamu menyimpan dendam. Mami kangen Mora yang dulu.”
Mora semakin terpaku di sofa hingga tidak menyadari Mami telah beranjak dan menuju kamar. Kesempatan? Batinnya.
Kesempatan itu sangat sulit untuk dihadirkan. Kecelakaan itu, penghakiman dirinya di sekolah, perlakuan cowok berambut spike itu, ribuan orang yang tiba-tiba menghujatnya di media sosial. Rentetan mimpi buruk silih berganti berdatangan hingga sekarang dan selama kejadian-kejadian itu menghantui dirinya di setiap detik menapaki bumi ini, tak satu pun dari mereka yang mengelus punggungnya, menawarkan pundak dan dada untuknya, menggenggam tangannya kuat-kuat dan menyuarakan kalimat semangat untuknya. Lalu dampaknya kesempatan itu tak terlintas di benaknya sedikit pun.
Apakah ini berarti kebencian? Bukan. Tidak. Dia tidak benci. Ada sesuatu yang mengganjalnya untuk menguarkan kebencian terhadap mereka. Sesuatu yang begitu hangat ketika tiba-tiba teringat mereka.
Setelah mengorek dalam hati dan benaknya, perlahan Mora mengetahui sesuatu yang menentramkan itu. Sesuatu yang diucapkan Cecil. Dia mengakui bahwa rasa persahabatan memang benar adanya. Rasa persahabatan itu masih ada bahkan selalu ada meskipun tidak sehebat dulu. Rasa itu menutupi kebencian.
***
Taki berdiri berkacak pinggang di depan Devon yang wajahnya nyaris tak berbentuk dan Revi yang napasnya tersengal-sengal seolah telah perang melawan ribuan musuh. Kalau Taki datang terlambat sedikit saja menghalau pertarungan satu arah itu, sudah pasti Devon akan terkapar di ranjang rumah sakit.
Pandangan Taki beralih dari Revi ke Devon.Cukup lama dia menumpahkan tatapannya ke Devon lalu duduk di samping cowok itu.“Lo mau mati ya, Dev?”
Devon hanya bergeming.
“Lo sengaja nggak melawan karena lo pengen mati kan?”
Masih dengan jawaban yang sama, Devon hanya bergeming.
“Kalau lo pengen mati, jangan bawa-bawa kita. Lo mati aja minum racun kecoa atau terjung dari gedung fakultas.”
Devon menolehkan kepala.“Kalau itu yang lo mau. Bakal gue lakukan.”
“Bukan gue yang mau.Tapi lo yang mau. Lo bahkan sengaja membuat Revi sebagai pembunuh untuk membunuh lo. Lo mau teman lo jadi pembunuh? Lo cuman memikirkan diri lo sendiri.”
“Gue emang udah mati setelah Nanzo juga mati.”
Taki mengusap wajahnya lalu meniupkan napas kencang-kencang. “Hidup lo cuman berputar di sekitar Nanzo. Bahkan lo nggak melirik sedikit pun orang-orang yang berputar di sekitar lo. Kita bukan penonton atas kesedihan lo, kita sama-sama di atas panggung, sama-sama merasakan kesedihan.Tapi saat kita telah bangkit dan mengulurkan tangan untuk lo, lo menepis keras-keras.”
Devon mengambang. Setiap kalimat itu melayang-layang di benaknya dan membawanya ke dalam batas antara realita dan khayalan. Dia berdiri tepat di garis batas itu, di tengah-tengah realita yang menggambarkan Nanzo tergeletak tak berdaya di tengah jalan dan khayalan yang menggambarkan Nanzo sedang mendekat kepadanya sambil menjulurkan tangan. Di batas itu dia harus memilih, menelusuri jalan yang terbentang ke realita atau khayalan.
Devon masih termenung dengan benaknya yang berdebat hingga getaran ponsel di saku celana jins membuyarkan lamunannya. Panggilan dari Mama.
“Tuh nyokap lo nyuruh pulang. Sana pulang.” Sahut Revi seraya berusaha menghilangkan nada jahil di suaranya. Kebiasaan Mama Devon yang rajin menelpon anaknya selalu mengundang gelak tawa, meskipun dalam keadaan menegangkan seperti ini.
Beberapa saat kemudian setelah Devon hanya menjawab panggilan itu dengan kata super singkat yaitu “Iya”, dia beranjak pergi tanpa mengacuhkan ocehan Revi yang bersarat emosi.
“Dev, ingat impian lo pas SMA dulu. Jalan-jalan ke Eropa setelah kita wisuda. Jangan mati dulu. Gue yakin mimipi lo nggak cuman itu.” Sahut Taki yang menghentikan langkah Devon di ambang pintu
Kesekian kalinya hanya gemingan yang menjawab lalu cowok itu kembali meneruskan langkahnya keluar kamar kos.
“Nanti malam jangan lupa datang ke kafe biasa. Kita bakal ketemu personil baru.”Teriak Taki yang menyembulkan kepalanya melalui bingkai pintu.
Devon mengernyitkan kening dan masih berjalan lurus, tidak tertarik menolehkan kepala ke belakang.
Personil baru?Band itu masih ada?
***


 mlounita
mlounita









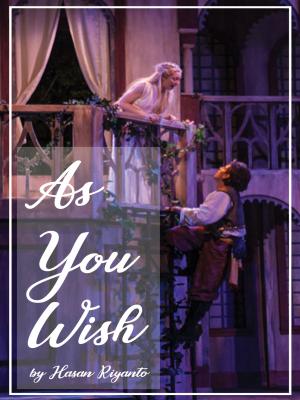
fresh banget ceritanya hehe. ditunggu kelanjutannya ya :)
Comment on chapter Chapter 1