Seminggu berlalu. Dan selama itu pula Amore Karaoke masih dalam pengawasan oleh pihak kepolisian. Devon baru saja pergi ke kantor polisi untuk diperiksa yang kedua kalinya. Sejelas mungkin dia menceritakan kejadian hari itu, termasuk perkelahian antara Bimo dan Revi. Sehari setelah insiden itu, polisi meminta Amore Karaoke ditutup sementara untuk meredakan keributan di dunia maya dan mencegah adanya kerusakan gedung yang baru direnovasi itu. Pihak Amore Karaoke meminta pula Bimo untuk diperiksa dan siang tadi Devon sempat berpapasan dengan Bimo yang baru memenuhi panggilan kepolisian. Biarlah Bimo berkata seenaknya dengan kebohongannya, biar kepolisian yang bertindak menyelidiki fakta kasus ini.
Beruntung, para haters dadakan Amore Karaoke sempat dibungkam oleh pelanggan-pelanggan terdahulu Amore Karaoke. Mereka mengaku kenal tentang tempat karaoke itu karena pada masanya terkenal di kalangan pelajar dan tidak mungkin melakukan hal tidak bermoral seperti itu apalagi pengelolanya adalah cucu dari pemilik sebelumnya. Beberapa dari mereka cukup mengenal baik Devon yang sering nongkrong di sana. Walaupun begitu para haters terus menyerang mereka dengan bukti-bukti dari live Instagram itu.
Devon menghela napas. Dia lelah. Sangat lelah. Benaknya memutar balik kilasan-kilasan kejadian sebulan ini. Pertengkaran dengan Papa. Pengusiran oleh Papa. Bahkan ketika masalah ini mencuat di berbagai media, Papa tidak menghubunginya sama sekali.
Bodoh.
Mengapa harus mengharapkan kehadiran Papa? Untuk menolongnya menggunakan kekuasaan Papa?
Satu kalimat yang diucapkan oleh mulutnya sendiri harus tertanam makin kuat di benaknya.
“Devon tidak akan pernah bergantung pada keluarga ini lagi.”
Lalu sel-sel otaknya mengarahkan ke kejadian yang mengharuskannya besinggungan dengan cewek itu. Perdebatan. Pertengkaran. Pesta Rakyat. Rumah Nenek. Foto-foto Nanzo dan Amore Karaoke.
Hidupnya sepenuhnya untuk Amore Karaoke. Dia tidak munafik bila menggantungkan juga hidupnya dari penghasilan Amore Karaoke. Namun, bukan itu alasan utamanya. Tempat itu lebih penuh dengan kenangan dibandingkan rumahnya sendiri. Tempat itu pula yang membuatnya hancur lalu membangkitkannya kembali. Dari seberang jalan, dipandanginya lekat-lekat bangunan berlantai dua yang dindingnya bertuliskan kalimat kasar itu, ulah seseorang yang tak puas menghujatnya di Instagram.
Oh..begini rasanya. Menyakitkan. Seperti yang dirasakan cewek itu, bahkan mungkin sakit ini tidak seberapa dibandingkan perihnya hati cewek itu yang berbulan-bulan bahkan sampai sekarang masih dihujani ujaran kebencian.
Tunggu. Mengapa teringat cewek itu?Jawabannya langsung terbalas saat melihat Mora berdiri tak jauh di depan Amore Karaoke. Entah sejak kapan, tapi Devon baru menyadarinya.
Tangan cewek itu terangkat seperti sedang mengusap matanya. Menangis? Devon tidak peduli, tidak merasa tersentuh, tidak lantas hatinya terketuk hanya karena dia menangisi Amore Karaoke. Mungkin cewek itu menangisi karena peninggalan kakeknya harus direnggut paksa sesaat, tapi apa yang dirasakan cewek itu tidak sebesar apa dirasakan Devon terhadap tempat ini. Yang harus ditangisi adalah dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Bukan suatu keharuzan untuk menangisi tempat ini.
Pernah, hatinya mulai membuka sedikit lebih lebar untuk menerima Mora saat Devon menguping pembicaraan Nenek dan Mora tentang Secondary Band dan bagaimana asal usul Amore Karaoke berdiri. Ketulusan persahabatan kakeknya dengan kakek Hasan sedikit mengetuk hatinya. Kata maaf mampu merekatkan kembali dua orang yang bertahun-tahun berpisah, mampu menciptakan senyuman lebar yang tidak biasanya terpatri di raut Kakek dan mampu menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuknya. Yaitu Amore Karaoke.
Namun, kini hatinya kembali tertutup rapat. Cerita Nenek tidak mampu menguatkannya.
Sebuah pernyataan menamparnya keras. Seminggu yang lalu, cewek yang dikenal Devon selalu giat menghadiri kompetisi lari Nanzo, yang berdiri paling depan setiap The Soul manggung dan yang ikut-ikutan bahkan lebih ganas menyerang Mora, datang ke Amore Karaoke.
Salsa mematung dengan mata yang menatap ngeri Devon. Raut kecewa tercipta jelas dan hanya hitungan beberap detik lagi dirinya akan meledak. Pembunuh idolanya berdiri di tempat ini dengan damai dan bekerja membangun kembali tempat ini. Sungguh gila Devon! Mengapa dia berani-beraninya memasukkan cewek itu ke tempat ini?
Salsa tidak lantas menyemprot Devon. Pandangannya beralih ke Ambar yang tampak lebih kaget. “Lo bohongin gue, Kak. Untungnya pacar teman lo itu maksa-maksa gue buat mencari keberadaan kalian berdua sebenarya di mana. Kenapa masih mau berteman dengan dia. Terutama Kak Ola, kena—”
“Sal, persabahatan kita nggak hancur semudah itu. Lagian..” Sebelum Cecil benar-benar menyelesaikan kalimatnya, ditatapnya Ola dan Devon bergantian. “Mora bukan penyebab utama kematian Nanzo. Dia jatuh terpeleset ke tengah jalan lalu tertabrak mobil, itu yang—”
“Cukup, Cecil!” Ola memekik marah. “Jangan perjelas sesuatu yang mengerikan seperti itu. Jangan terlalu sering mengungkit cerita itu karena luka yang mulai mengering akan basah lagi.” Ditatapnya Mora lekat-lekat dengan cara yang membuat Mora merasakan lagi kepedihan dibenci oleh seorang sahabat.
“Kalau memang terasa sulit dan menyiksa lebih baik tinggalkan saja.” Lalu matanya tertanam kuat pada Devon. “Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Gue yakin Kakak menahannya mati-matian dan—"
“Mendingan lo pergi dari sini.” Ambar menyela sambil melangkah lebar-lebar menghadang Salsa yang hendak mendekati Mora. “Kita dikumpulkan di sini oleh Tuhan untuk mengobati rasa sakit itu. Terutama buat Devon dan Ola, termasuk Mora juga. Kalau yang dipaksakan adalah sesuatu yang baik, gue rasa nggak ada salahnya mencoba menghadapi.”
Mora menarik pelan pundak Ambar. Mengerti apa yang akan dilakukan Mora, Ambar menggeleng cepat, dengan dagunya menyuruh Mora tetap berdiri di belakangnya.
“Gue capek dengar dia terus berkoar-koar, Bar.” Tetap dipaksakannya Ambar untuk berganti posisi dengannya. Mora mengejap-ngejapkan mata menghalau air mata yang siap berkumpul di pelupuk mata. Getaran di bibirnya langsung hilang oleh senyuman lebar yang khusus dihadiahkan untuk Salsa. “Bagaimana jika akhirnya Nano dan tempat ini berpihak pada gue? Mereka mengingingkan gue di sini untuk menghapus kebencian-kebencian yang ditularkan oleh kalian.”
Mora cepat berbalik menghadap Ola, tak mengacuhkan Salsa yang hendak membalas. “Gue masih menunggu lo menerima maaf gue, La. Gue tunggu meskipun itu harus beribu-ribu tahun karena gue sayang lo, gue sayang kalian. Begitu pula dengan lo, Devon,” Beralih Mora menatap lurus Devon. “Gue menunggu dengan sabar amarah lo terhadap gue reda, karena hanya itu yang mampu gue lakukan. Tapi gue yakin suatu saat nanti entah kapan, hati lo akan meluruh karena lo sebelumnya adalah seseorang yang baik.” Mora menghela napas sejenak sebelum kembali berhadapan dengan Salsa. “Dan untuk lo, Sal. Gue nggak peduli lo nggak akan memaafkan gue. Gue nggak akan berharap dan menunggu. Bagi gue, lo cuman orang yang ikut-ikutan membenci gue seperti orang lain.”
Jemari Salsa terlipat, terkepal kuat, tak terima bila disebut dia bersedih hanya mengikuti orang lain. Dia lebih dari itu. Baginya Nanzo bukan sekedar idola. Seseorang yang diletakkan di tempat paling spesial di hatinya. Tarikan di lengannya menyentaknya kaget. Salsa enggan pergi dari sini, tapi tarikan Devon mengalahkan kekuatannya.
“Cukup, Sal!” Devon menghempaskan pegangannya pada lengan Salsa setelah berhasil membawanya keluar gedung. “Biar ini menjadi urusan gue dan cewek itu.”
“Kenapa, Kak? Gue juga heran, kenapa lo bisa terima dia dengan mudah masuk ke kehidupan lo? Dan di tempat ini pula?”
“Gue juga nggak mau, Sal. Gue tersiksa setiap melihat dia apalagi di tempat ini. Tapi jalannya seperti ini. Kakek gue dan Kakek cewek itu bersahabat. Mereka mewariskan tempat ini pada kita berdua.”
Salsa mendengus. “Dan Kakak menerima begitu saja? Bila nggak sanggup jangan dipaksakan karena akhirnya akan lebih sakit.”
“Mora.” Bibirnya yang tanpa sadar mengucapkan nama itu memutuskan bayangan kejadian seminggu lalu. Tubuhnya tiba-tiba sudah menyeberangi jalan dan berdiri di samping Mora.
Mulanya, Mora sangat yakin suara itu tidak nyata, efek saking seriusnya menatap bangunan Amore Karaoke. Dugaannya terpatahkan saat muncul bayangan dari sosok yang menjulang tinggi berdiri di sampingnya. Mulai muncul kelegaan mendengar namanya tercetus dari bibir Devon. Seperti sebuah kebahagiaan yang sangat sulit didefinisikan. Tanpa sadar, ujung bibirnya sedikit tertarik, makin lama terpatri kian lebar.
Devon terenyak. Bagaimana bisa Mora masih sanggup tersenyum setelah badai yang tak henti menyerangnya?
“Kenapa sih lo bodoh banget?”
“Terkadang bersikap bodoh itu perlu. Kalau gue bersikap sok pintar, gue akan balas lo berkali-kali lipat. Gue bahkan akan menghancurkan tempat ini. Kita akan sama-sama keras kepala.”
Kedua alis Devon terangkat. “Maksud lo?”
“Kalau gue harus bersikap seperti lo. Permusuhan kita nggak akan selesai. Gue harus rela bersikap bodoh di depan lo, menerima semua caci maki lo. Walaupun sejujurnya gue tetap pada pendirian gue bahwa gue bukanlah penyebab kematian Nanzo. Tiga tahun dan sampai sekarang gue tetap menerima karena gue nggak mau menimbulkan peperangan berkepanjangan. Oleh karena itu, gue menunggu, menunggu kalian memaafkan gue. Meski sebenarnya—"
“Meski sebenarnya lo nggak salah. Munafik!”
Mora menghadapkan seluruh tubuhnya ke arah Devon dengan sedikit mendongakkan kepala. “Coba lo pikirkan baik-baik. Coba lo ingat baik-baik. Apa gue yang meminta Nanzo untuk berlari?” Mora menggeleng tegas. “Bukan gue. Dia menawarkan dirinya sendiri, tanda bahwa dia memang sedang bersiap menuju kematiannya. Lain cerita bila lo yang lari lalu Nanzo menyalahkan gue. Bila lo yang mati saat itu, gue pasti nggak akan mampu hidup di dunia ini.”
***


 mlounita
mlounita

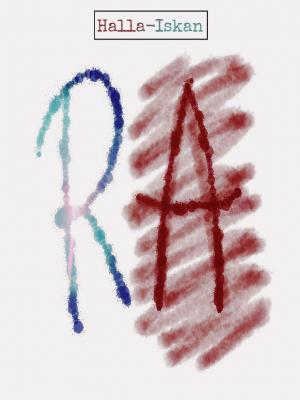








fresh banget ceritanya hehe. ditunggu kelanjutannya ya :)
Comment on chapter Chapter 1