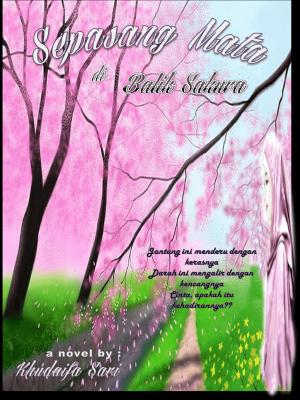Satu lompatan panjang, melambung dan terukur, menjejakkan tumit pada bak pasir. Tepuk tangan, riuh redam, ucapan selamat. Takjub dan salut. Dari arah yang berbeda, datang teriakan lantang dari tengah lapangan, nyanyian paduan suara, derap sepatu tiga pengibar bendera. Kujejakkan kaki di pinggir lapangan, mengitari pandangan, berusaha untuk lebur bersama keramaian para murid. Kubayangkan reaksi mereka yang memendam curiga pada seorang lelaki dengan pakaian kusut, berdiri di pinggir lapangan, mengamati sekelilingya dengan tatap tak pasti. Sedang menawarkan produk apa lelaki itu? Apakah dia sedang mengintai salah satu dari kita? Bisa saja mereka berpikir seperti itu. Bisa saja, dan boleh saja. Tapi tidak demikian.
Aku tidak pernah tertarik dengan perempuan yang jauh di bawah usiaku. Aku juga bukan sales, dan tidak menawarkan produk apa pun. Malah, aku memandang diriku sendiri sebagai produk. Produk sekolah ini.
Selajur keringat turun dari pelipisku. Terdedah di bawah matahari, hanya diteduhi dahan yang minim daun, aku tak bisa menjangkau sedikit pun gelegak semangat yang mereka pancarkan. Waktu telah melindas masa-masa itu menjadi sebatas kilas-kilas. Aroma keringat sehabis olahraga, degup jantung menjelang Ujian Nasional, serta perasaan gelisah akan terbawa ke mana hidup ini, semua itu kerap melingkupi sekujur tubuhku, bercampur dengan udara yang sama sekali tak bisa digenggam. Kini, setelah melalui semua itu, aku sama sekali tak sekokoh tiang bendera, juga tak sebangga bendera itu sendiri, yang berkibar-kibar merengkuh awan.
Di pinggir lapangan, aku lebih mirip kaleng minuman yang penyok teronggok di samping sepatuku, abai pada dirinya sendiri. Satu hembusan angin datang, menerbangkan debu, sampah plastik, juga rok para siswi. Waktu itu, mungkin aku akan langsung membatu, berkelahi dengan diri sendiri, memutuskan apakah ikut mata-mata yang lain, menebak-nebak warna paha yang tersingkap. Kuhela nafas, dalam dan panjang. Sekarang, dengan beban yang semakin berat tertahan di punggung dan hatiku, bahkan desahan paling erotis di dunia ini tidak mampu mengangkat ereksi di dalam celanaku. Aku berbalik, menjauh dari pinggir lapangan, melangkah ke sana; ke ruang khusus bagi mereka yang bermasalah. Ruang BK*.
Seperti asap, aku menelusur koridor, diterangi lampu redup yang hidup-mati dan menegluarkan bunyi desing yang aneh. Setiap kali aku berpapasan dengan siapa saja, tidak ada mata yang mengenaliku. Tidak ada sapaan selamat datang, atau lama tidak jumpa, atau sekarang bekerja di mana. Aku terus berjalan, menjelajah anak tangga, meresapi dingin pada pegangannya yang memantulkan bayang wajahku. Lalu, aku mendapati bahwa ruang itu masih di tempat yang sama. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya, jauh perjalananku ke sini membuahkan hasil.
Setelah kuketuk pintu, butuh waktu lima menit bagiku untuk tahu bahwa ada orang di dalam ruangan itu. Sempat aku hendak berlari, membatalkan niat awalku untuk masuk.
“Ya, bisa saya bantu?”
Suara tua. Rambut putih yang menyeluruh. Punggung yang agak membungkuk. Guru itu masih orang yang sama, namun dengan sampul yang telah berbeda. Tentu saja, pikirku. Waktu telah melindas semuanya.
Kami berjabat tangan. Kuperkenalkan diri, dan meski kulihat ia diselaput ragu, akhirnya Guru BK itu mengizinkan aku untuk masuk. Kutarik punggung kursi, kusilangkan kaki, dan jam, pada angka berapa pun yang ia tunjuk, langsung memberi peringatan, bahwa pintu menuju lorong kelam itu telah resmi ia buka. Detik-detiknya adalah sandi, yang hanya mengizinkan diriku untuk paham, bahwa akan ada penyesalan setelah ini.
“Ada hal yang ingin saya ceritakan.”
*
Kipas angin berhasil mengenyahkan gerah di balik pakaianku. Setidaknya aku akan bercerita dalam kondisi yang nyaman, sehingga tidak boleh ada alasan bagiku untuk terbata-bata dengan alasan ruang yang sempit terlalu banyak buku, juga panas. Begitu kukatakan bahwa ada hal yang ingin kuceritakan, mengenai seorang siswi yang bernama Yana, Guru BK menghadang kelanjutan kata-kataku dengan telapak tangannya. Ia beranjak dari kursi, ke luar ruangan, dan kembali lagi dengan secangkir teh hangat.
“Polyana,” kata Guru BK. Entah mengapa saat ia mengucapkan nama itu, leherku meremang. Masih ada keraguan di dalam hatiku untuk membebaskan semua cerita ini. Tapi jika bukan pada orang yang ada di depanku sekarang, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi yang dapat kupercaya sebagai wadah untuk menampung semuanya. Semua kegelisahan yang terus menerus kutahan, yang tak menghasilkan apa-apa selain rasa bersalah dan kehampaan. Hanya pada orang ini, hanya di dalam ruang ini. aku membatin, berkali-kali.
“Apa yang ingin kau ceritakan tentang Polyana?”
“Semuanya.”


 chaeru
chaeru