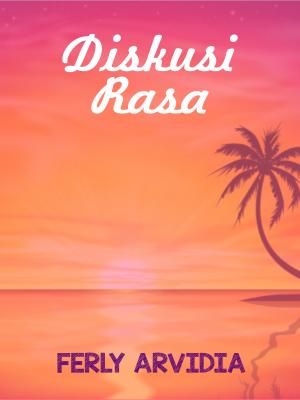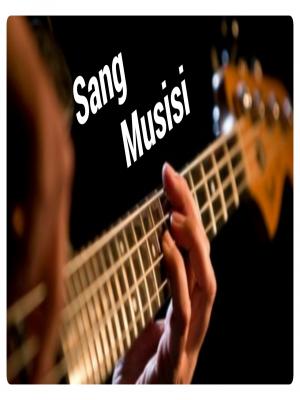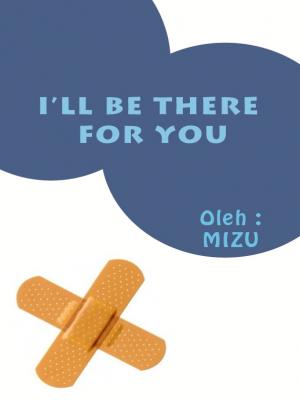Duduk sendirian di bangku panjang depan bangunan penuh kenangan. Sebuah pohon tua yang tenang menaungiku dari hangatnya mentari.
Pada halaman depan, terdapat empat anak kecil yang tengah asyik bermain. Sesekali aku dibuat tersenyum akan tingkah polos mereka.
Itu adalah ingatan akan masalaluku. Empat anak itu dulunya sangat bahagia di tempat ini. Namun, setelah mereka sudah tumbuh, berpisah, dan bertemu kembali, mereka telah kehilangan tempat masa kecil mereka dulu.
Tubuhku mulai bersandar. Memejamkan mata selagi menghirup udara dalam-dalam menikmati suasana sejuk akan terpaan angin.
"Bagaimana perasaanmu saat ini, Dy?"
Mataku terbuka, setelah angin itu membawa suara lembut dari seorang gadis yang entah bagaimana sudah duduk di sebelahku. Dia yang tengah memakai gaun putih ini, begitu tenang memandang ke arah anak-anak barusan dengan senyum.
"Kenapa ... semua jadi seperti ini, ya Kak?" ujarku tanpa sadar. "Tempat ini berubah. Begitu juga dengan mereka. Kupikir saat aku kembali, semuanya tidak ada masalah. Apa yang aku takutkan justru malah terjadi."
"Jadi ..., kau masih merasa bersalah dengan Gita?"
"Begitu juga denganmu, ’kan Kak?"
"Itu wajar saja. Karena dia satu-satunya orang yang paling aku sayangi."
Wajahku bergerak memandanginya, dan masih tak mampu berkata-kata.
"Kau masih memikirkan kepergianku?" tanyanya.
"... Iya."
Dia mulai tersenyum, bahkan lebih hangat dari biasanya. "Umur itu hanyalah persoalan hitungan waktu, yang dibatasi ruang bernama hidup. Jadi aku sama sekali tak mempermasalahkan waktuku yang singkat."
"... Apa Kakak tidak marah melihat semua ini?"
Dia beralih menghadap ke arahku. Perlahan menaruh tangannya di atas kepalaku sambil mengusap lembut.
"Marah? Tentu saja tidak, aku malah bersyukur. Aku bersyukur karena tempat ini telah mempersatukan kita. Terutama aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Terima kasih karena sudah peduli denganku."
"...!"
Aku yang hanya bisa terdiam kini mulai merasakan ada yang berat di mataku. Tubuhku mulai bergetar, dan dadaku mulai sesak.
"Aku minta maaf, Kak. Aku minta maaf karena tidak ada saat Kakak kesusahan waktu itu," ujarku terbalut tangis.
"Jangan salahkan dirimu lagi. Aku sudah percayakan semuanya padamu."
Kala matahari mulai menampakkan diri kembali, suhu udara mulai agak menaik dan embusan angin mulai sedikit kencang. Dia menggugurkan beberapa daun mati pada pohon-pohon di sekeliling.
"Tolong jaga adikku, Ferdy."
Akan tetapi, saat itulah seketika aku hanya bisa merasakan udara tipis dari usapan tersebut. Tubuhnya yang berada di sampingku beberapa saat lalu mendadak lenyap sama sekali.
Aku berdiri dari bangku dan melihat ke sekeliling area. Warna matahari perlahan meredup. Kegelapan menakutkan seolah hendak menelan tempat ini.
Aku berusaha memanggil namanya, namun tak jua ada balasan. Bahkan anehnya, anak-anak yang sedang bermain tadi juga ikut lenyap.
Sebelum aku menyadari itu semua, seluruh tempat mulai dikelilingi oleh kegelapan. Basecamp kami, pepohonan, dan juga berbagai tanaman bunga mulai runtuh seolah mereka semua terbuat dari pasir. Hanya bangku panjang dan aku sendiri yang masih tersisa di balik kegelapan ini.
Aku menutup mata, menajamkan telinga, dan mengumpulkan seluruh kekuatan untuk memanggil namanya sekali lagi.
Saat itulah mataku dengan cepat terbuka oleh suara yang keras dan menggema. Aku tak tahu apakah aku berteriak hanya di dalam mimpi atau benar benar melakukan itu di dunia nyata.
Aku mulai bangkit, lalu mengusap wajah sembari mengatur napas yang terengah-engah sampai normal kembali.
Mataku sejenak menyisir sekitar, dan berakhir pada ponsel di atas meja belajar yang sedang berbunyi karena alarm.
Pukul 04:00 WIB. Itulah waktu saat ini.
Rasa sakit mendadak kembali menyerang dada, dan aku mengalihkan pandangan ke arah jendela yang belum tertutup semalam.
"Lagi-lagi ... aku bermimpi tentang Kak Sinta."
※※※
Saat ini jam istirahat makan siang. Aku dan Ihsan membenamkan diri di salah satu meja taman sekolah dekat kantin.
Berbeda dengan anak di depanku ini, aku justru membawa bekal sendiri dari rumah. Dua potong roti sandwich, dan susu kotak yang kubeli dari kantin tadi, membuatku merasa aneh jika dibandingkan dengan anak-anak lain, terutama lelaki.
Mau bagaimana lagi, aku cuma diperbolehkan memakan makanan seperti ini oleh pengawasku. Cih!
Karena merasa tak nyaman, jadi kubiarkan saja sejenak di atas meja.
"Dy, tugas dari Pak Bambang kemarin yang sudah kau kumpulkan itu ... aku minta referensi lain soal bab 6."
Ihsan terus mengoceh, tapi aku memberi jawaban dingin yang sama setiap kali dia mengoreksi jawaban pada lembaran miliknya.
"Ya, nanti aku jelaskan."
Ihsan melirik ke arah makananku. "Kau tidak memakannya? Sayang sekali, ’lho," tanyanya seraya mengambil dan memakan roti terakhirku. Anak ini!
"Niatnya kumakan nanti, tapi sialnya aku punya teman rakus sepertimu."
"Hahaha. Maaf, maaf."
"Kau tadi sudah makan banyak, ’kan? Apa perutmu tidak meledak?"
"Ahu mahih hapar. Hadi helum semfah sahapan."
"Telan dulu makananmu, baru bicara!"
Ihsan langsung meminum es tehnya dan mengemasi lembaran-lembaran tersebut.
"Aku mau menyerahkan soal-soal ini dulu. Soalnya harus dikumpulkan sebelum bel istirahat selesai."
"Ya, nanti langsung balik ke kelas saja. Sebentar lagi mau masuk."
"Ya sudah. Aku pergi dulu."
Dengan begitu Ihsan pergi dan menyisakan aku di tempat ini.
Di penghujung istirahat makan siang, kuhisap susu dalam kemasan ini lewat sedotan, dan bisa kurasakan embusan angin sedang membuai diriku.
Mataku yang sempat melihat sekitar menangkap sosok gadis yang sekelas denganku tengah membawa lembaran sendirian. Sama seperti Ihsan, sepertinya dia juga hendak mengumpulkannya ke Pak Bambang.
Tapi, bukan itu yang menarik perhatian dan membuat mataku terus mengikuti langkahnya. Melainkan aura kesepian yang bisa kurasakan darinya.
"Mau sampai kapan kau terus melihati Gita?"
Angin yang sama ikut membawa suara yang tak asing ke telingaku. Saat aku menoleh, kulihat Putri sudah berdiri sambil mendekap beberapa lembaran setebal satu centi. Dia kali ini tampak berbeda dengan yang biasanya dia perlihatkan.
Oh, ya. Kalau aku perhatikan, Putri tidak mengenakan riasan yang berlebihan seperti saat SMP dulu. Wajahnya jadi terlihat lebih natural. Itu adalah bukti kalau dia telah berubah walaupun hanya sedikit. Serta saat Putri tersenyum, mata indah dan wajah belianya itu jadi tampak semakin menawan.
"Tumben sendirian, Dy? Ihsan mana?"
"Ke meja kerja Pak Bambang."
"Hmm. Kenapa tidak ikut?"
"...."
Kenapa juga harus ikut, sementara sebentar lagi mau masuk?! Lagian kakiku juga masih sakit gara-gara Gita kemarin. Dasar, kenapa dia tidak peka begitu, ’sih?!
"Kau sendiri mau kemana?" tanyaku balik.
"Oh ...," sesaat dia melihat lembarannya," aku mau mengumpulkan ini juga. Anak-anak di kelas banyak yang menitipkannya padaku."
"Terus, kenapa tidak bilang ke Gita untuk menitipkan padamu juga?"
"Eh?" Putri berpaling dan terlihat gusar. "Ah, itu ...."
"Ada apa? Aku perhatikan selama ini kau dan Ihsan tidak begitu dekat dengan Gita. Kalian bertengkar?"
"Bu-bukan, bukan! Kami tidak sedang bertengkar, ’kok!"
Putri buru-buru berusaha menyangkal anggapanku. Namun, entah kenapa dia termenung sejenak, kemudian dengan tenang duduk di sebelahku dan bertanya dengan nada serius.
"Soal masalah Kak Sinta ..., kau sudah tahu?"
"Sudah. Termasuk kabar mengenai Kak Sinta yang meninggal setelah dituduh menggelapkan uang dari Desa."
Sewaktu mendengarnya, wajah Putri menegang. "Kalau soal itu kau tahu dari mana?"
"Dulu Gita menelponku."
"Oh, begitu." Putri berpaling, lalu menggumamkan sesuatu. "Jadi ... Gita lebih memilih bercerita denganmu, ya?"
Suaranya begitu pelan bahkan nyaris tak kudengar. Yang kulihat hanya bibirnya komat-kamit sambil menatap ke meja. Mantra apa 'sih yang dia baca barusan?
"Ada apa, Put?"
"Eh? Tidak ada apa-apa, ’kok."
"Sungguh?"
"Sungguh! Hanya saja ... aku merasa Gita jadi berubah semenjak kakaknya meninggal. Dia seolah semakin menjauh dari semua orang yang pernah bergabung di tempat itu."
"Bahkan denganmu?"
"Iya." Suara Putri semakin memudar. "Aku jadi sangat khawatir dengannya."
Sejenak aku memikirkan sesuatu saat melihat wajah sendu Putri. Kenapa Gita menjauh dari sahabatnya sejak kecil ini? Kenapa dia menjauh dari kami? Kenapa dia seolah-olah tidak ingin ada orang lain masuk di kehidupannya?
Jika dia benar-benar ingin menjauh, tentu saja dia tidak akan bersikap ramah saat bertemu denganku di basecamp waktu itu.
Dari semua itu, aku hanya bisa menerka bahwa Gita tidak tahu harus berbuat apa. Gita mungkin secara tak langsung sedang dikucilkan oleh sekitarnya karena masalalu tentang kakaknya itu. Dan alasan dia menjauh dari kami, bisa jadi karena dia tidak ingin sahabatnya jadi ikut terkucilkan hanya karena berteman dengan adik dari orang yang dulu dituduh bermasalah.
Aku jadi mengerti kenapa dia menelponku waktu itu. Mungkin hanya aku teman dekatnya yang tidak ada di sana. Jadi, dia bisa mencurahkan kesedihannya.
"Kurasa ... Gita tidak benar-benar berubah. Dia tidak ingin menjauh dari kita," ujarku.
"Maksudmu?"
"Sebelumnya aku tanya padamu. Kalau aku mengajak kita semua membuat suatu acara atas nama organisasi kita dulu, kau mau ikut?"
"He?"
"Itu yang dia inginkan," aku buru-buru memotongnya. "Saat kami bertemu di tempat itu, Gita masih bersikap seperti dulu. Bahkan dia juga bercerita kalau dia masih merindukan kenangan kita dulu."
"Tapi ..., bagaimana caranya? Desa juga sudah memandang buruk organisasi kita. Kegiatan kita pasti juga tidak akan disetujui."
"Aku tahu. Tapi kalau kita tidak mencoba, apa gunanya?"
"...."
"Pertama-tama kita kumpulkan anggota yang dulu pernah bergabung. Tidak harus semua, ’kok. Yang mau dan niat saja. Oh ya, bilang kalau aku yang mengajak. Jangan Gita."
"Kenapa?"
"Nanti bakal banyak yang tidak mau, ’kan?"
"Hmm. Baiklah kalau begitu, nanti aku akan mengajak yang lain."
"Oke. Terus, Minggu pagi kita kumpul di basecamp, ya. Aku mau memberitahu sesuatu."
"Iya, nanti aku kasih tahu yang lain," ujar Putri dengan suara yang semakin memelan.
"Kenapa?"
"Tidak, aku hanya gugup berbicara dengan Gita nanti."
"Tenang saja. Gita belum berubah, ’kok. Kalau tidak percaya nanti aku dan Ihsan akan mengerjainya."
"Kau ini ada-ada saja."
Saat mengatakannya, Putri hanya tertawa kecil dan terdengar hampa. Lalu dengan senyum yang masih tertinggal di wajahnya itu, dia berpaling ke arah lain.
Tak lama kemudian, bel yang menandakan berakhirnya jam istirahat pun berbunyi.
"Ayo balik, Dy."
"Oke."
Putri pun beranjak menuju kelas. Sementara aku mengikuti di sampingnya dan perlahan merasa sedikit aneh.
Ketika mulai sampai di pintu kelas kami, langkahku perlahan terhenti. Putri merasa heran karena aku terus menatapnya, dan dia juga ikut berhenti.
"Ada apa, Dy?"
Tepat saat dia bertanya, aku menyadari sesuatu yang kurasa aneh tersebut. "Bukannya tadi kau mau mengumpulkan lembaran-lembaran itu?"
"Hm? ... Aaah!"
※ ※ ※ (Bab 03) ※ ※ ※


 ardianrizki
ardianrizki