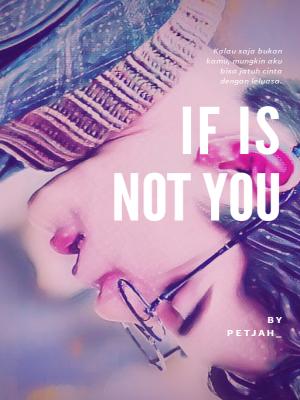"Apakah karena seseorang?" Pertanyaan Aland ketika mereka berkumpul di ruang makan masih tergiang sampai sekarang. Dalam hati, Sean tak berusaha menyangkal atau mencari jawaban selain 'Ya'. Karena memang benar seperti itu. Seorang gadis sudah mengacaukan hidupnya. Membuatnya penasaran dan berusaha mencari tahu penyebabnya.
Setelah menghabiskan makan malam, Sean buru-buru meninggalkan ruang makan. Membuat Aland dan bibi Mer saling pandang, bertanya-tanya.
"Boss kenapa, Bi?" Aland menyuarakan pertanyaan di kepalanya ketika Sean menghilang di anak tangga paling atas, masuk ke kamar.
"Entahlah, Al. Dia terlihat sedikit aneh."
"Dia bilang hidupnya kacau."
"Aku bahkan belum sempat bertanya."
Seakan tak ingin membahas masalah Sean lebih jauh, Bibi Mer bangkit dari kursinya. Membereskan piring-piring dan gelas, termasuk milik Aland, yang sudah kosong sejak tadi. Ia dibantu beberapa ART lain.
"Apa aku saja yang bertanya, Bi?"
"Tidak perlu, Al. Jika mau, dia akan bercerita. Mungkin Sean memang butuh waktu sendiri."
Memang benar, Sean butuh waktu sendiri. Di kamarnya, dengan laptop yang masih menyala, ia berselancar di dunia maya. Selama beberapa jam mengetikkan beragam kata di mesin pencari. Memadankan semua yang ia temukan dengan keanehan-keanehan yang muncul dalam dirinya.
Jantung berdegup kencang, gugup, tidak percaya diri, salah tingkah, senang, mudah tersenyum, sering merasa bahagia adalah tanda seseorang yang sedang jatuh cinta.
Sean mendengus sebal. Dari beratus link, kesimpulan yang ia dapat semuanya sama. Tapi ia sangat yakin bahwa tidak sedang jatuh cinta.
Setelah menshutdown dan menutup laptop, Sean beranjak ke balkon. Meninggalkan benda berwarna silver itu di atas kasur. Ia Membuka pintu balkon dan membiarkan angin malam berhembus masuk. Setidaknya udara sejuk bisa sedikit menyegarkan pikirannya yang seperti benang kusut.
Pandangan Sean terpaku di langit yang kosong. Hitam. Gelap. Tubuhnya terlentang di sofa panjang di samping pagar balkon. Semilir angin menembus t-shirt yang ia kenakan. Selama beberapa menit seperti itu. Hingga ketukan di pintu membuatnya tersadar dan mengerjapkan mata.
"Sean...." Bibi Mer memanggil dari depan kamar di iringi ketukan pelan.
"Masuk saja, Bi."
Tanpa diminta dua kali, Bibi Mer memasuki kamar yang di dominasi warna abu gelap. Setelah meletakkan nampan berisi air mineral di atas nakas, ia menghampiri Sean.
"Tidak baik melamun malam-malam, sendirian."
"Aku hanya sedang memikirkan sesuatu."
"Apakah bibi boleh tau apa yang sedang kau pikirkan?"
Sean mengubah posisinya dari terlentang menjadi duduk, memberi ruang bagi bibi Mer di sebelahnya. Tak segera menjawab, ia menekuk lutut dan menopang kepala diantara lututnya.
"Apa Bibi pernah jatuh cinta?"
Jeda beberapa detik. Hingga Sean berpikir bahwa bibi Mer tidak akan menjawab pertanyaannya. Tapi ia salah.
"Pernah. Dulu sekali.... bahkan kau belum lahir."
"Bibi masih ingat bagaimana rasanya?"
"Masih... perasaan yang susah digambarkan. Begitu banyak. Yang jelas didominasi oleh perasaan bahagia. Senang. Kadang gugup. Salah tingkah. Bibi juga lebih sering tertawa, seakan-akan tak pernah ada kesedihan." Sebuah senyum tersungging di bibir bibi Mer. Wajah yang telah dimakan usia itu terlihat berseri. Membuat Sean diam-diam ikut tersenyum. Perasaanya menghangat.
"Siapa seseorang itu?"
"Seorang pria yang sangat baik. Yang sudah pergi meninggalkan dunia ini dengan tenang."
Sekelumit rasa bersalah muncul di hati Sean saat melihat mata bibi Mer yang mengkristal.
"Maafkan aku..."
"Tidak apa, Bibi yang terlalu terbawa perasaan." Sambil mengulas senyum, bibi menghapus sudut mata.
"Nah, kesimpulan dari pertanyaanmu adalah, siapa gadis beruntung yang bisa mendapatkan cinta malaikat tampan sepertimu."
"A..apa? Tunggu-tunggu, ini tidak seperti yang bibi pikirkan." Gelagapan, Sean menjawab. Membuat bibi Mer tersenyum lebar.
"Aku tidak sedang jatuh cinta!" Sean menekankan setiap suku kata yang ia ucapkan. Wajahnya memerah. Bibi Mer terkikik geli melihat tampang Sean yang kekanakan seperti itu.
"Kalaupun iya juga tidak apa."
"Ayolah, Bi. Jangan menggodaku. Ini tidak lucu."
Tawa bibi Mer berhenti saat melihat ekspresi Sean yang berubah serius.
Sambil memandang langit, ia bertanya.
"Selain perasaan senang, apa bibi pernah merasa takut?"
"Takut? Kenapa?"
"Entahlah... Perasaan yang bibi ceritakan tadi, saat jatuh cinta, aku juga pernah merasakannya. Tapi itu tidak sebanding dengan perasaan lain yang muncul."
"Perasaan lain?" Kali ini bibi Mer memusatkan perhatiannya pada Sean yang mengangguk sambil menjawab.
"Kadang aku merasa takut yang tidak beralasan, resah dan tiba-tiba gelisah"
"Apakah selalu seperti itu?"
"Hampir selalu. Kadang juga aku tidak bisa mengendalikan emosi yang tiba-tiba muncul dan beberapa saat kemudian hilang."
Hening beberapa saat. Gemericik air mancur di kolam teras depan mengisi kesunyian antara mereka. Sean memejamkan mata.
"Pernahkah setidaknya sekali saja, kau merasa senang saat bersama dia?"
"Pernah. Hanya sebentar. Kemudian perasaanku menjadi campur aduk lagi. Lebih banyak kegelisahan."
Tanpa membuka mata, Sean menjawab.
Kenangan bersama Kinan berkelebat dalam memorinya. Saat ia merasa senang atas kebersamaannya dengan gadis itu. Ketika di cafe Anne, bermain piano bersama Ed. Tanpa sadar, ia kembali tersenyum. Yang tak luput dari perhatian bibi Mer.
"Seharusnya kau lebih sering tersenyum seperti itu."
Perkataan Bibi Mer membuat Sean membuka mata dan memandang heran padanya.
"Kejadiannya pasti sangat menyenangkan."
"Lumayan, Bi. Bisa membuatku tersenyum setelah sekian lama."
"Dia pasti gadis yang istimewa."
Lagi-lagi, Sean mengangguk.
"Sepertinya iya. Tapi aku belum terlalu mengenalnya."
"Kalau begitu dekati dia."
"Rasanya terlalu sulit. Dengan semua keanehan yang terjadi padaku akhir-akhir ini."
Sean menghela napas lelah. Menyadari jika masalah perasaannya terlihat sangat rumit.
"Aneh bagaimana?"
"Pernahkah Bibi melihatku gemetar ketika berhadapan dengan orang lain? Atau tiba-tiba pucat pasi dan berkeringat dingin, sampai rasanya membasahi punggungku." Sebuah gelengan menjadi jawaban bibi Mer atas pertanyaan Sean. Pria itu melanjutkan,
"Lebih seringnya lagi, aku tidak mampu memandangnya, rasanya sangat sulit. Saat melihat dia tersenyum, aku ingin kabur dari situ. Tapi disisi lain, aku ingin bertahan. Bukankah itu hal yang aneh dan tidak wajar?"
"Ya.... itu benar-benar aneh. Dan aku tidak pernah merasakan hal seperti itu."
"Bibi benar."
Untuk melarikan kegalauan, Sean memetik nada-nada ringan dari gitar yang sejak tadi bersandar di sampingnya. Gitar itu kini berada di pangkuannya.
"Kau harus menemui seseorang. Untuk menjawab semua hal tentang keanehanmu itu."
"Siapa?"
"Dr. Flyn."
"Tidak. Aku tidak mau. Aku masih baik-baik saja, Bi. Tidak sedang depresi atau setengah gila."
Dentingan nada berhenti. Sean memandang horor pada Bibi Mer.
"Kau memang baik-baik saja. Tapi ketakutanmu itu sepertinya aneh. Dan aku yakin Dr. Flyn punya jawabannya."
"Tapi..... "
"Atau kau mau, seumur hidup merasa takut dan gelisah seperti itu?"
"Tentu saja tidak." Tanpa berpikir dua kali, Sean menjawab tegas. Membuat bibi Mer tertawa.
"Oke. Sudah diputuskan. aku akan membuat janji dengan Dr. Flyn untuk bertemu denganmu."
"Ya... yaa... terserah bibi saja." Akhirnya, Sean menyerah. Petikan nada gitar kembali terdengar diantara hembusan angin malam. Bibi Mer undur diri setelah mengingatkan Sean agar tidak tidur terlalu larut.
Dalam diam, ia menyimpan sebuah pertanyaan. Siapa gadis itu?
-----------------------------------------------------------
"Halo Sean.... senang berjumpa lagi denganmu."
"Tapi aku tidak."
Dr. Flyn terbahak mendapat kata sambutan dari Sean. Mereka duduk berhadapan di sofa mewah berwarna cream. Perapian bergemeletuk, membuat ruang tamu luas itu terasa lebih hangat.
Pria paruh baya itu sangat paham, jika Sean yang sekarang bukanlah Sean yang dulu. Remaja belasan tahun yang ia tangani karena depresi akut setelah kehilangan kakeknya.
Ia sudah banyak mendengar, membaca dan menyaksikan berita tentang sosok yang terlihat dingin di hadapannya. Sempurna, tanpa cela. Tapi ia juga tahu, jika semuanya hanya bentuk dari cara mempertahankan diri. Membekukan hati. Kerena itu, sikap dingin Sean sama sekali tak berlaku untuknya.
Dengan santai, Flyn mengambil sebuah macaron yang tersaji di atas meja. Memakannya, kemudian berujar,
"Aku senang kau baik-baik saja."
"Anda lebih tahu dari pada apa yang orang lain lihat."
"Ya... kau benar. Setidaknya kau terlihat cukup baik hingga saat ini."
"Aku bisa bertahan."
Dr. Flyn mengangguk, membenarkan. Ia tahu jika Sean adalah sosok yang kuat dan keras kepala. Dulu, ia benar-benar dibuat repot. Selama hampir dua bulan, waktunya habis untuk bermonolog dengan patung hidup di hadapannya. Sama sekali tak mau berbicara sepatah kata pun.
Hingga akhirnya, ia berhasil mencongkel kebekuan Sean. Membuat pemuda itu terkapar di lantai, bergelung sangat erat dan terisak hebat. Menumpahkan semua rasa sakit dan kecewa yang membatu di hatinya.
Ingatan itulah yang membuat Sean sempat menolak usulan bibi Mer untuk kembali bertemu dengan psikiater satu itu. Tapi tak bisa dipungkiri, jika karena Flyn pula dia bisa bertahan hingga sejauh ini.
Menjadi seorang Sean yang baru. Yang selalu membentengi diri dari segala macam hal yang memungkinkan mengusik naluri. Pria yang lebih memilih menjadi egois, angkuh, dingin dan tidak peduli. Untuk menutup semua masa lalunya. Dan tentu saja, Flyn sedikit merasa bersalah. Ia juga ikut andil dalam pembentukan karakter baru dalam diri Sean. Tapi ia juga berpikir, jika Sean punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Memilih cara terbaik bagi dirinya sendiri. Kadangkala, menjadi sosok lain adalah cara terbaik menyembunyikan luka di dalam hati.
Sejak saat itu, Flyn mengira bahwa pemuda ini akan sangup bertahan. Dan kemungkinan besar sudah sembuh. Depresinya sudah hilang.
Hingga semalam, kayakinannya mulai goyah. Ada panggilan mendadak dari Merydith. Perempuan yang ia tahu telah mengasuh Sean sejak ia diboyong kakeknya dari Girona. Menjelaskan dengan detail masalah yang dihadapi Sean. Dan semuanya kembali pada perasaan. Ia yakin jika Sean tidak baik-baik saja. Tidak Seperti apa yang orang lain lihat.


 Altezza_Narain
Altezza_Narain