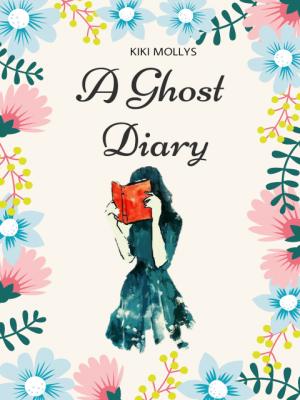Part 9. Jagakarsa
Sore ini aku sampai juga di rumah. Selepas melihat Nino pulang bersama wanita asing tadi, aku langsung menunggu bagasi dan menyetop taksi. Tidak ada satu pesan pun dari Charlie. Status kita memang tidak jelas. Aku, yang menyamarkan, putuskah kita? LDR-an kah kita? Jadi, seharusnya aku tidak terlalu memikirkannya. Ah, belum satu hari saja, aku sudah merindukannya.
Hampir menginjak 28, aku masih tinggal di rumah Ayah. Malu sih. Dulu waktu sebelum menikah, penghasilanku cuma kugunakan untuk jalan-jalan, beli baju, tas, sepatu dan make up. Sampai aku menikah, dan Nino tidak mengijinkanku bekerja. Lalu, justru dari situlah aku menemukan passion-ku, menulis. Berawal dari nggak ada kerjaan di rumah, aku menulis blog tentang review tas, sepatu, make up dan tentu saja pengalaman jalan-jalanku. Agak lebay sih kalau di bilang travelling. Aku lebih suka menyebutnya dengan, jalan-jalan.
Beberapa kali blogku masuk di artikel majalah. Baik secara online maupun on-print. Lalu aku menjadi salah satu penulis artikel di satu situs online. Mengasyikan ya bekerja sesuai minat itu. Tapi, Mimpiku adalah menjadi penulis bestseller. And here I am. Chasing on my dream! Siang ini rumah Ayah sepi seperti biasa. Cuma ada si Mbak. Pembantu yang sudah bekerja duapuluh-tahunan di rumah ini. Di awal aku sudah cerita kan ya, kalau orang tuaku bercerai, dan aku tidak tinggal dengan ibuku.
"Assalamualaikum..." Salamku memasuki rumah langsung menuju kamar. Lelah hayati, Bang.
"Wa'alaikumsalam... Eh, Mbak Luna udah pulang. Udah makan, Mbak?"
"Udah tadi di pesawat." jawabku singkat. Aku langsung ganti baju. Pakai celana pendek, dan kaos rumah. Cuci muka, lalu membenamkan diri di kasur. Bongkar koper, besok aja kali ya.
Sekelenyap, aku tahu-tahu bangun dalam keadaan kamar yang gelap gulita. Ku cek handphone, ternyata sudah sudah jam tujuh malam. Bukannya makin enak, badanku malah makin sakit-sakit. Ah elah! Lemah banget sih ini badan. Dipake naek pesawat sehari aja, kayak minta tidurnya seharian. Aku bangun dan menyalakan lampu kamar. Di luar sudah kudengar suara ayah dan adikku mengobrol. Mereka pasti sedang di ruang TV.
Agak asing dengan suasana rumah, aku mulai mempersiapkan diri. Menyisir dan menyepol rambutku ke atas, lalu keluar ke arah ruang TV.
"Hai, Yah." Sapaku duluan.
"Sampai rumah jam berapa tadi, Lun?"
"Jam empat-an." Jawabku sambil ke dapur mengambil makan malam. Kita punya meja makan, tapi bukan tipe keluarga yang biasa makan bersama-sama disuatu waktu tertentu. Semua anggota bebas mengambil makan kapan saja dan mau makan dimana saja. Asal tidak makan di kamar. Aku duduk di ruang TV sambil makan.
"Gimana nulisnya?"
"Udah beres kok. Besok rencananya Luna mau jalan ke penerbit."
Ayahku cuma manggut-manggut saja. Tidak sampai sepuluh menit, makananku sudah habis. Aku lalu beranjak mandi, dan berniat membongkar koper sehabis mandi nanti. Plan changed.
***
Pagi ini. Pagi pertamaku di Jakarta setelah tiga bulan absen dari polusi dan hiruk pikuknya. Rumahku yang terletak di daerah Jagakarsa, membuatnya berada di perbatasan antara Jakarta dan Depok. Setelah mengirim email naskahku ke beberapa penerbit semalam, hari ini aku berencana datang langsung ke dua penerbit sekaligus. Aku sudah mengeprint dua copy kertas A4 seratus-duapuluhan halaman itu. Jam sembilan pagi semuanya sudah siap. Ayah juga sudah berangkat ke kantornya jam tujuh tadi.
"Rin, gue berangkat dulu ya." Pamitku ke adikku, Karin.
"Oke." Setahuku jadwal kuliahnya itu siang.
Aku menunggu ojek onlineku di depan rumah. Tidak lama si abang ojek pun datang.
'"Ke Flix Media ya, Bang. Udah ada kan, alamatnya di peta?"
"Udah, Mbak. Oke." jawab si abang ojek.
Tidak sampai setengah jam aku akhirnya sampai di bangunan putih itu. Halaman luas dengan bangunan sebagian berbentuk gedung, sebagian tampak seperti rumah bertingkat. Aku sampai di front desk.
"Mbak, mau ketemu sama editornya. Ada?" Kataku.
"Dengan siapa, ya? Sudah buat janji?" Kata si Mbak front desk.
"Saya Aluna, saya mau kirim naskah."
"Oh, langsung aja naik terus belok kanan. Nanti Mbak Fika ada di meja ke empat dari kanan." Okeh, dapat satu info, nama editornya adalah Fika. Aku pun berjalan menruti arahan si Mbak front desk tadi.
"Permisi, Mbak Fika, ya?" Tanyaku ragu setelah sampai di meja keempat dan melihat perempuan berhijab dengan kacamata frame hitam.
"Iya. Ada apa, ya?" Jawabnya.
"Ini, saya mau kirim naskah, Mbak. Fiksi."
"Oooh... oke, saya baca dulu ya. Nanti sekitar tiga-empat bulan saya kabari." Sudah kuduga jawaban standar dari para penerbit pasti akan seperti itu.
"Oh, gitu ya... " Katakku sambil manggut-manggut, tidak puas.
"Sini, saya buatkan tanda terimanya dulu." Dia mengambil semacam nota di mejanya.
"Mmh, premisnya, tentang seorang perempuan yang jatuh cinta setengah mati sampai rela melakukan apapun demi seorang laki-laki, Mbak. Dan, di ending-nya nanti akan terjawab apakah dia bisa bertahan atau tidak dengan laki-laki tersebut." Aku berusaha menjelaskan isi cerita seratus-duapuluh halamanku menjadi satu kalimat, sembari si Mbak menuliskan tanda terima atas namaku.
Pernah dengar di salah satu workshop menulis, katanya cara seperti ini cukup ampuh. Kata si mentor waktu itu, cerita yang bagus adalah, ketika anda bisa merangkum semua isi cerita anda menjadi sebuah kalimat singkat yang biasa disebut premis, atau Logline.
"Ooh... Nih, tunggu ya. Pasti di baca, kok." Dia menyerahkan nota itu dan menebar senyum yang, sepertinya berfungsi untuk menenangkan para penulis novel baru-amatiran macam aku.
"Sip. Makasih, Mbak." Seyum palsu sok puas pun kulebarkan juga. Padahal, aku sendiri tidak yakin, selangkah aku keluar dari sini, apakah naskahku akan benar-benar dibaca, atau langsung masuk ke tong sampahnya. Atau mungkin, hanya jadi bahan kipas-kipasnya saja saat dia kegerahan. Ah, sudahlah. Aku harus belajar untuk positif thinking.
Aku lalu beranjak kembali dengan ojek online menuju penerbit yang kedua. "Ke Giant Media ya, Bang. Di peta udah jelas, kan?"
"Iya, Mbak."
Kali ini aku menuju daerah Depok. Agak jauh, tapi tidak apa-apa, ongkos ojek online tidak akan sampai semahal ongkos taksi. Lagipula, dengan naik ojek aku jadi bebas macet juga. Sekitar pukul satu siang aku sampai di depan Giant Media. Berbeda dengan namanya, bangunannya tidak "Giant." Terlihat seperti rumah bertingkat dua dengan pagar yang tinggi di depannya. Walau agak ragu, aku langsung saja masuk. Tidak ada front desk-nya. Aku bertanya kepada salah seorang yang kebetulan lewat. Dia menunjuk ke sebuah kamar yang pintunya terbuka.
TOK TOK.
"Permisi..." Ucapku. Terlihat seorang laki-laki paruh baya berkacamata. Kenapa setiap editor itu berkacamata ya. Mungkin matanya lelah, selalu menatap layar dan huruf-huruf dari karya para novelis.
"Ya?" Jawabnya, agak judes.
"Ini, Pak, saya mau kirim naskah."
"Oh. Sudah email?"
"Sudah, kemarin."
"Kalau gitu, tunggu saja. Saya biasa baca di sofcopy soalnya."
"Mmh, tapi... kebetulan, saya sudah terlanjur sampa sini nih, Pak, hehehe.... Saya taro meja Bapak aja ya hardcopy-nya..." Jawabku setengah bercanda, mencairkan suasana. Pria setengah baya itu menurunkan kacamatanya, melirik ke arahku. "He'em." Jawabnya singkat sambil mengangguk.
"Premisnya, tentang seorang perempuan yang jatuh cinta setengah mati, sampai dia rela melakukan apa saja kepada seorang pria, Pak." Sambil berjalan ke arah mejanya dan menaruh sebendel A4-ku, aku berusaha menjelaskan isi ceritaku. Lagi.
"Iya. Disitu ada email dan nomor teleponnya, kan?"
"Ada." Dia cuma kembali mengangguk. Aku pun beranjak dari ruangannya. Kembali berencana memesan ojek online dan langsung pulang.
Kulihat seketika ada warung makan, berbentuk rumah makan mini. Mirip warteg, tapi lebih luas sedikti. Perutku yang keroncongan kayaknya tidak akan kuat kalau harus menahan lapar selama perjalanan Depok-Jagakarsa. Aku memesan nasi dengan lauk ayam goreng dan telor balado kesukaanku, tidak lupa dengan segelas es teh manis tentunya. Wow, yummy... Baru dua suap, seketika aku teringat Bali.
Teringat kebiasaanku makan di warung dekat kontrakan dulu. Oh, the smell of that land. Teriknya mirip, tapi dengan lebih sedikit polusi. Teringat Bali, lalu aku, teringat Charlie. Shit!! Kenapa Bule itu lagi sih yang muncul diingatan. Nothing's wrong of being a short-relationship with a foreign man, in a foreign city, Bali. Come on, Luna! Itu Bali. Everything could be happened there, then why don't you just forget that kind of short-relationship, such as 'one-night-stand thing.' You can ever do it.
Aku menjejalkan nasi dan lauk-lauk ke mulutku. Berharap perut kenyangkku akan memberhentikan ingatanku tentang Bali. Okay, then I hate it now. I hate to remember anything about Bali. Because, it remain me with Charlie. And I hate not being with him. Makananku habis juga. Aku langsung menunggu ojek onlineku.
"Ke Jalan Kahfi, Jagakarsa ya, Bang." Si abang cuma ngangguk doang. Lalu motor matic itu melesat ke arah rumahku.
Sesampainya di rumah, kembali sepi. Adikku sedang kuliah sepertinya. dan kembali aku bertemu si Mbak. "Udah makan, Mbak Luna?"
"Udah." Duh, si Mbak nggak ada pertanyaan lain apa ya selain nanya makan.
Aku merebahkan tubuhku di kamar. Mataku kali ini tidak mengantuk. Kumainkan handphone. Ingin aku menelpon Charlie, tapi buat apa. Komunikasi kita yang ada nanti malah akan menambah rasa rindu satu sama lain. Lagian, gengsi aja gitu. Aku yang ninggalin, masa aku yang ngaku kangen duluan. Lalu aku membuka galeri foto.
Ternyata selama tiga bulan di Bali, aku hanya menyimpan tiga foto Charlie. Memandangi wajah si Bule itu. Ah, wajahnya selalu mengingatkanku dengan Mr. Fantastic di film Fantastic Four. Seketika lamunanku terganggu dengan notifikasi pesan masuk di bagian atas layar.
"Sidang terakhir, minggu depan, tanggal 5. Datang ya."
Ninooooo!!!! Can you just stop being rude! Nggak cuma orangnya, sampe pesannya aja selalu ganggu deh!
"Iya."
Tapi seganggu-ganggunya, lo pernah cinta juga sama dia kan, Lun.
***


 Eno_wid
Eno_wid