Sejak pertama mengenal Vino, Zen tak bisa mengikuti pola pikirnya. Ketika mereka masuk taman kanak-kanak yang sama, Vino lebih senang bermain di luar kelas, sedangkan Zen dengan senang hati membaca setiap buku dari gurunya. Setiap Zen membaca buku, Vino selalu memintanya bersuara keras karena saat itu Vino belum bisa membaca. Zen ingat, Vino hanya mendengarnya lima menit sebelum akhirnya berlari keluar, menatap langit yang menyakitkan mata.
Zen tidak ingat kapan pertama kali Vino suka melihat pesawat terbang. Mungkin saat umurnya tiga atau empat tahun. Mereka sudah mengenal sejak belum bisa bicara, jadi hal seperti itu sudah lenyap dari memorinya. Zen hanya mengingat alasan pertama Vino menyukai benda terbang itu.
“Dia bebas, Zen,” Vino mengatakannya saat mereka sudah agak besar. Sekitar kelas empat sekolah dasar.
“Maksudnya bebas?” Zen tak mengerti kalimat Vino. Bebas. Pesawat terbang.
Vino menunjuk langit, “Pesawat itu disana, gravitasi aja nggak bisa ngatur pesawat supaya tetap dibawah.”
Mata Zen melebar, tahu apa temannya tentang gravitasi?
“Keren…” entah apa yang dipuji Vino, ia tiba-tiba bergumam.
“Kalau emang pesawat itu bebas, kenapa kamu mau jadi astronot? Harusnya pilot, dong!” kepala Zen ikut mengadah, melihat langit yang menyilaukan mata.
“Astronot itu lebih bebas! Keluar bumi… bayangin, Zen. Jauh… Jauh… lebih jauh dari langit itu!” Vino melompat, tangannya terangkat tinggi seakan ingin menyentuh langit.
Zen berdecak, temannya sudah sedikit gila.
Kegilaan itu terjadi sampai tahun-tahun berikutnya. Sampai beberapa menit lalu Vino tiba-tiba berada di hadapannya. Sampai sekarang ia berada di depannya, berjalan lebar-lebar entah kemana.
“Vin, mau kemana?” Zen daritadi diam, tapi Vino telah membawanya ke tempat terpencil. Banyak lumut serta ilalang dibiarkan meninggi. Zen tak bisa tak bertanya saat sadar mereka di lorong diantara gedung asrama dan tembok pembatas dengan jalan raya.
“Butuh tempat aman, Zen,” Vino masih menjawab dengan bisikan padahal jika ia berteriak, Zen yakin tak akan ada yang mendengarnya.
“Maksudnya?”
Vino bukan menjawab malah menempelkan telunjuk ke bibir. Ia tersenyum tipis lalu berjalan lebih jauh lagi.
Sebenarnya apa yang dihindari oleh Vino? Zen tak punya sedikitpun petunjuk. Apa Zen sedang masuk ke permainan Vino? Bukankah Vino punya imajinasi yang tinggi? Ah, sial, Zen pernah mengalami hal serupa sebelumnya.
Zen lagi-lagi tak terlalu mengingatnya, yang jelas ia sudah cukup umur untuk tahu hal benar dan hal bohong. Saat itu, Vino mengajaknya berlari di tengah hujan, ia bilang ada pembunuh mengincarnya. Zen tak percaya hanya diam melihat temannya panik tanpa sebab.
Tapi tiba-tiba raut wajah Vino berubah, tatapan matanya tajam, ia juga melirik ke belakang beberapa kali, “Aku serius, Zen,”
Sedetik setelahnya mereka berdua berlari secepat kilat, mengetuk rumah Haya sambil berteriak.
Haya keluar dengan boneka di tangannya, “Zen, kamu bodoh banget mau dibohongin Vino.”
Hari ini sepertinya Vino melakukan hal yang sama dengan waktu itu. Membohonginya. Sekarang aku nggak… “Haya?”
Haya berdiri di ujung gang sempit lembab itu. Ia mengenakan baju tidur berbalut cardigan tipis. Haya mengetukkan kakinya ke tanah, “Lama banget kalian!”
“Tadi Zen susah dibangunin,” Vino menoleh pada Zen lalu lanjut berjalan hingga mendekati Haya.
“Ada apa ini?” Zen lalu menggertakkan gigi, seperti seseorang yang tidak tertarik bercampur dengan kesal karena waktu istirahatnya terpotong.
“Tanya lah Nocil, aku nggak tau apa-apa,” Haya mengangkat kedua tangannya.
Zen langsung melirik Vino, “Vin?”
“Tenang saudara-saudara, mari kita duduk dulu,” tanpa pikir panjang Vino duduk di salah satu bongkahan batu.
“Aku nggak mau duduk, kotor,” Haya bersandar pada tembok.
Zen tidak bergerak sedikit pun, ia menatap Vino dan Haya bergantian. Meminta jawaban atau penjelasan atau apa saja yang masuk akal. Kenapa ia harus masuk ke gang sempit hanya untuk mengobrol.
Vino berdeham, “Kita dalam bahaya! Zen kamu adalah yang paling terancam!”
Ah, itu memang, Vino-banget. Menyampaikan sesuatu dengan gaya sok benarnya. Zen menarik nafas, membiarkan berbagai bebauan masuk dan dicerna otaknya.
Bola mata Haya berputar, “Cil, jangan bercanda! Langsung ke intinya karena aku belum ngerjain tugas!”
“Pemburuan siswa terpintar itu beneran, Hay, Zen. Tadi aku sempat periksa kamar Zen, ada 3 cctv disana. Sistem sensornya berbeda dengan sistem sensor guru, bunyinya, pola terbukanya pintu, kartunya. Lagipula yang dipindahkan bukan cuma kamu, Zen, beberapa anak peringkat atas juga dipindah karena kamarnya rusak. Kalian tau Feris kan? Anak kelas sebelas yang paling pintar? Kamar mandinya tiba-tiba terus mengeluarkan air, lalu dia dipindah ke kamar dekat Zen. Sistem kamarnya beda dengan kamar kita—”
“Itu kan kamar baru, Vin, nggak usah bikin kesimpulan nggak masuk akal!” sahut Zen memotong kalimat panjang Vino.
“Ngapain di kamar itu ada cctv? Buat ngawasin kalian, orang-orang pintar!” Vino menunjuk Zen.
“Hay?”
Zen jelas meminta Haya untuk membelanya, karena memang itu yang biasanya terjadi. Kali ini Haya diam, ia menunggu kalimat lanjutan Vino.
“Zen, percaya sama—”
“Lalu, kita harus apa? Aku harus apa? Kalian tau sendiri kita nggak bisa keluar masuk dengan bebas kan?” lagi, Zen tak sabar menunggu Vino menuntaskan kalimatnya.
Vino menepuk batu yang ia duduki, “Makanya, kita disini untuk mikirin itu bareng-bareng,”
Zen terkekeh sambil menggelengkan kepala, “Aku nggak ada waktu untuk ini,” Zen mengibaskan tangan sambil berbalik. Berjalan menjauh meninggalkan Haya dan Vino.
Ia mendengar Vino memanggil namanya beberapa kali, disusul dengan Haya melakukan hal yang sama. Dari jauh, Zen mendengar Haya bicara pada Vino.
“Cil, nggak usah gila, mana mungkin Zen percaya!”
Haya bener, mana mungkin aku percaya. Zen terus berjalan, keluar dari gang sempit itu, masuk ke dalam area asrama, menyusuri setiap lorong, dan berakhir dengan lompatan ke atas ranjangnya. Zen hanya beberapa detik merebahkan tubuh, pikirannya berubah tak tenang. Zen mengambil kartunya, mendekatkannya pada sensor agar pintu terbuka.
Sensor itu berkedip tiga kali, tanpa suara.
Ini cuma sistem sensor baru, kan? Zen meyakinkan dirinya sendiri.
Ia mencobanya lagi, membuka pintu sambil memperhatikan sensornya bekerja. Saat ia akan menutup kembali pintu, Zen melihat petugas yang wajahnya asing sedang menatapnya lurus-lurus. Petugas itu mengenakan seragam seperti yang lain, tapi ia jelas terlihat berbeda. Badannya lebih tegap, tangannya lebih kekar.
Zen menelan ludah.


 MulierViridi
MulierViridi

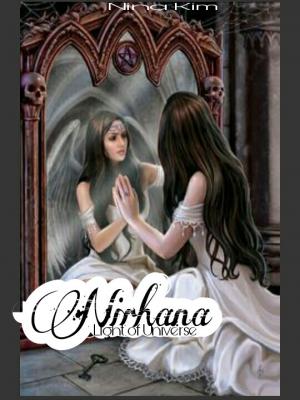



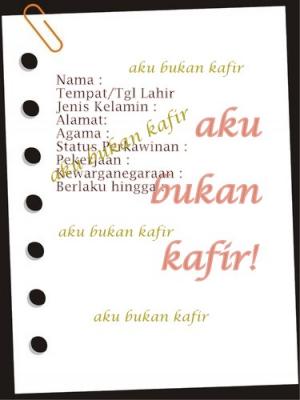




great story :)
Comment on chapter Batas ke 1