“Hai.”
Arinda tersentak ketika dia merasakan tepukan pada bahunya. Gadis itu berhenti melangkah beberapa meter dari gerbang sekolah yang sudah terbuka lebar. Arinda melirik ke belakang, menemukan seorang lelaki jangkung yang duduk di atas motor ninja berwarna merah sedang menatapnya.
“Kamu teman sekelas saya, ‘kan?” Arinda mengernyit. Belum terlalu mengenal lelaki tampan di depannya itu. Maklum, Arinda adalah murid pindahan, gadis itu baru saja menyusul saudara kembarnya yang lebih dulu bersekolah di SMA Tunas Bangsa ini beberapa hari yang lalu, jadi Arinda masih belum mengingat betul teman-teman satu kelasnya.
Arinda mengangkat bahu tak yakin.
“Hm, mungkin?” kemudian matanya melirik name tag pada seragam lelaki itu … Alvin Jonathan S.
Lelaki bernama Alvin itu tersenyum lebar.
“Saya titip tas, ya.” Kemudian Alvin dengan cepat melemparkan tas gendong berwarna hitamnya kepada Arinda, yang membuat gadis itu dengan kaget menerima tas miliknya dan mengernyit bingung.
“Kena—“ belum sempat Arinda menyelesaikan kalimatnya, Alvin sudah terlebih dahulu menjalankan motor besarnya menjauhi Arinda yang menatapnya penuh tanya.
Gadis itu menggaruk kepalanya yang tak gatal, merasa dijahili oleh orang yang mengaku teman sekelasnya itu. Arinda mendengus kesal, kenapa lelaki itu tidak membawa tasnya sendiri? Dasar orang aneh!
Arinda kembali melanjutkan perjalanannya menuju sekolah. Saat dia mencapai gerbang, bel masuk sudah berbunyi nyaring. Membuat Arinda semakin mempercepat langkahnya menuju kelas XI IPS 2 di lantai tiga.
“Kamu bawa tas siapa, Rin?” tanya Laras dengan aksen jawanya, ketika Arinda baru sampai di dalam kelas. Gadis itu sudah duduk di bangkunya, di sebelah bangku Arinda.
“Nggak tahu,” jawab Arinda sekenannya. Kemudian Arinda duduk di samping Laras.
“Gimana, toh, kok bisa ndak tahu? Wong kamu nenteng-nenteng tas segede begini?” Laras menunjuk pada tas di depan Arinda. Sementara itu Arinda hanya mengangkat bahunya bingung.
“Ini punya Alvin,” jawab Arinda tak yakin.
“Alvin? Oalah, piye, toh? Kok dia ngasih tasnya ke kamu? Alvinnya di mana? Kamu ada hubungan apa sama dia? Hati-hati, Nduk. Kamu ndak tahu Alvin itu kayak gimana orangnya, dia itu berandalan sekolah,” kata Laras tanpa spasi.
“Kalau ngomong pake tanda baca kali, Ras. Masa nyerocos gitu kayak kereta. Mana bisa gue jawab satu-satu,” dengus Arinda kesal. Laras hanya terkekeh anggun dengan menutup mulutnya menggunakan tangan kanan.
“Maaf, habis aku penasaran. Kok ya bisa tas si Alvin ada di kamu.”
“Katanya dia nitip, tadi ketemu di deket gerbang.”
“Lah, Alvinnya mana?”
“Mana gue tahu, keluyuran dulu palingan.”
Arinda mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang kelas. Mengingat-ingat di mana letak tempat duduk Alvin. Tetapi, Arinda sama sekali tak mengingatnya.
“Alvin duduk di mana, sih?” tanyanya pada Laras yang sedang membaca buku pelajaran.
Laras mengangkat wajahnya, kemudian gadis berkepribadian seperti Putri Keraton itu menunjuk bangku paling pojok.
“Di sana, Rin. Duduknya sama Robi,” kata Laras menjelaskan.
Arinda kemudian berdiri dan melangkah menuju tempat duduk Alvin. Dia mengernyit heran ketika belum mendapati tas milik Robi. Ke mana mereka berdua? Kemudian Arinda menaruh tas Alvin di atas mejanya. Setelahnya gadis itu berjalan kembali menuju bangkunya karena melihat Pak Dior yang sudah memasuki kelas.
“Alvin sama Robi ke mana?” tanya Pak Dior ketika tidak melihat dua muridnya itu. Seisi kelas hening. Tidak tahu harus menjawab apa.
“Nggak tahu, Pak. Tapi tasnya ada,” kata Adinda menunjuk tas hitam milik Alvin. Pak Dior mengernyit. “Mungkin lagi ke kantin, Pak. Bolos lagi,” Joni menyahut nyaring. Pak Dior hanya menghela napas pelan. Bingung dengan kelakuan muridnya itu yang sering membolos jam pelajaran dan tak jarang terlibat kenakalan.
***
Sementara itu …
Alvin, lelaki itu malah tengah duduk di atas motor besarnya, mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh Ilham, teman satu tongkrongannya. Lelaki bertubuh besar dan kekar itu berdiri di kelilingi oleh beberapa teman berseragam sama sepertinya.
“Jadi, kita serang aja langsung ke kandangnya. Biar mampus mereka semua,” kata Ilham menggebu-gebu. Yang lain hanya manggut-manggut mendengarkan.
“Apa nggak bahaya? Mereka di sarangnya, otomatis banyak orangnya. Kita bakalan kalah jumlah,” kata Robi menimpali.
“Bener kata Robi. Kalau kita gegabah langsung serang ke kandang, yang ada kita bakal kalah. Malu-maluin,” kali ini Erwin yang bersuara. Tidak setuju dengan pendapat Ilham. Lelaki itu sesekali menghisap rokoknya dengan santai.
“Halah, udah kita tunggu aja mereka yang nyerang. Baru kita hajar habis-habisan,” kata Robi, “lagian, siapa yang suruh mereka mulai duluan.”
Alvin tak bersuara sama sekali. Lelaki itu memilih bungkam dan menyulut rokok dan menghisapnya dramatis. Kemudian tatapannya menerawang, pada lapangan kosong yang ditumbuhi rerumputan dan dedaunan yang berasal dari beberapa pohon di pinggir lapang.
“Kalau menurut lo gimana, Vin?” Alvin melirik pada Ilham yang sedang menatapnya, meminta pendapat dari pentolan sekolahnya itu.
“Gue mah fleksibel. Serang ke kandang hayo, diam nunggu serangan juga hayo, lagian, kita ada di sini juga atas undangan mereka, ‘kan?” kata Alvin pelan.
“Harusnya kita yang nyerang duluan. Mereka udah menistakan lambang sekolah kita.” Ilham masih tidak terima pendapatnya di patahkan begitu saja oleh teman-temannya. “Tapi itu terlalu berisiko, Bodoh.” Robi meneloyor kepala Ilham keras.
“E, bangsat. Jangan pegang-pegang kepala gue,” ucap Ilham, lelaki itu menepis tangan Robi kasar.
“Mereka udah janji nyerang hari ini. Tenang, aja.”
“Palingan bentar lagi juga datang.”
Dan ketika Erwin selesai berbicara, Rio mengaduh keras. Lelaki hitam manis itu memegangi kepalanya yang barusan terkena lemparan—entah apa. Alvin menoleh dengan cepat, matanya mencari sesuatu di sekitar tubuh Rio. Dan lelaki itu mendapatkan sebuah batu tak jauh dari kaki Rio.
“Bangsat, mereka datang!” teriak Gunawan.
Keadaan yang awalnya tenang menjadi rusuh. Mereka semua bersiap-siap dengan alat-alat tempur yang sudah mereka bawa dari dalam tas. Ada yang membawa penggaris besi dan kunci inggris. Sementara sisanya membawa balok kayu yang besar. Alvin sendiri tak membawa apa-apa, dia bertangan kosong. Dan masih tenang di atas motornya, menghisap rokok yang sudah tinggal setengahnya.
Dari kejauhan terlihat anak-anak sekolah Otomotif berlari menyerang mereka. Ada lebih dari dua puluh orang siswa. Mereka berseragam biru dan hitam. Membuat para pentolan SMA Tunas Bangsa itu berjalan beberapa langkah siap menghadang lawan.
Tak berapa lama kemudian terdengar baku hantam dari kedua kubu. Mereka saling menendang dan memukul satu sama lain. Mengayunkan kayu atau senjata yang mereka bawa. Seketika, lapangan kosong itu menjadi arena perkelahian antara dua pihak yang bersitegang.
“Vin, lo nggak bawa senjata?” Robi berteriak ke arah Alvin yang berjalan menghampirinya. Alvin menggeleng sebagai jawaban. Lelaki itu menjatuhkan sisa rokoknya dan menggilasnya dengan sepatu.
“Yang bener aja? Bisa mati kena sambit lo,” kata Robi hiperbolis. Namun Alvin tak peduli, lelaki itu segera berjalan ke tengah arena dan menghantam salah satu siswa berseragam biru itu.
“Bangsat,” teriak lelaki yang sudah tersungkur di atas tanah. Menyeka darah di hidungnya dan menatap Alvin bengis. Kemudian lelaki itu kembali berdiri, bertumpu pada kedua kakinya dan menerjang Alvin dengan cepat. Menghantam perut Alvin dengan keras. Alvin tak tinggal diam, lelaki itu menendang perut lawan, kemudian meninju wajahnya sampai siswa itu kembali terjengkang. Terjembab ke atas tanah.
***
Jam pelajaran pertama hampir selesai ketika sebuah ketukan dari pintu membuyarkan konsentrasi anak-anak XI IPS 2 yang sedang mengerjakan soal dari Pak Dior, guru Matematika. Tak lama kemudian kepala Alvin muncul di balik pintu, membuat Pak Dior tercengang dan menatap bengis pada muridnya yang terkenal Bengal itu.
“Selamat pagi, Pak,” sapa Alvin ramah. Lelaki itu kini berdiri tegap di depan pintu. Tak lama kemudian muncul Robi di belakangnya. Seisi kelas menatap mereka berdua sinis.
Alvin dan Robi sangat berantakan. Baju seragam mereka keluar dari celana dan tampak sedikit kotor dan berkeringat. Wajah Robi sedikit membiru di bagian dagunya. Sementara sudut bibir Alvin sedikit mengeluarkan darah.
“Ngapain kamu di sana?” tanya Pak Dior keras. Membuat para murid tersentak. Alvin menggosok belakang lehernya gugup, kemudian dia menatap Pak Dior.
“Kami ijin masuk, Pak.”
“Kamu nggak lihat ini jam berapa?” Pak Dior berteriak nyaring.
Alvin menunduk, menatap jam yang melingkar di tangannya. “Jam Setengah sembilan, Pak,” jawabnya polos. Pak Dior menggeram marah. “Itu tandanya kalian terlambat! Sana pergi, saya tidak butuh kalian di kelas ini. Dasar tidak tahu aturan,” teriak Pak Dior kejam.
Robi sudah menarik-narik ujung seragam Alvin, kemudian lelaki itu berbisik pelan, “Udah gue bilang mending bolos aja.”
“Alvin, Robi, kenapa baju kalian berantakan? Kalian seperti habis tawuran,” kata Pak Dior baru menyadari penampilan dua muridnya itu, matanya menatap penuh selidik. Membuat Alvin dan Robi gugup.
Pak Dior adalah salah satu guru paling galak di Tunas Bangsa, maka tak heran bila mereka berdua gugup berhadapan dengan beliau.
“A-anu, Pak … tadi kami lari-larian ke sini, takut nggak keburu,” jawab Robi takut-takut.
Pak Dior menatap Robi tajam.
“Tadi kami lagi di UKS, Pak. Robi mencret-mencret, jadi saya nggak tega dan nemenin dia di sana,” kata Alvin memelas. Membuat teman-teman sekelasnya tertawa keras. Sementara Robi memukul kepala Alvin, membuat lelaki itu mengaduh.
“Sialan lo, malah ngumpanin gue,” kata Robi pelan.
Pak Dior sudah bersiap untuk memarahi mereka berdua andai saja bel pergantian pelajaran tidak berbunyi nyaring memecahkan ketegangan. Kemudian Pak Dior menghela napas lelah. “Masuk, Alvin, Robi!” perintahnya tegas.
Kemudian Alvin dan Robi segera berjalan dengan cepat menuju bangku mereka yang terletak di pojok kelas. Saat Alvin sampai di kursinya, lelaki itu tersenyum samar melihat tas miliknya. Kemudian tatapannya beralih pada seorang gadis yang juga sedang mencuri pandang ke arahnya.
***
Jam istirahat adalah surga dunia bagi anak sekolah. Dengan kecepatan cahaya mereka berhambur keluar kelas dan segera melesat ke kantin untuk mengisi dahaga dan kekosongan perut. Bahkan mereka rela berdiri berdesak-desakan saat memesan makanan. Tak jarang mereka kecewa karena tidak kebagian tempat untuk makan. Kantin memang selalu ramai.
“Arinda, ayo kita ke kantin. Aku udah ndak kuat laper banget,” rengek Laras di sampingnya. Sementara Arinda masih berkutat dengan buku tulisnya, menyalin tugas Sosiologi milik Laras.
“Aduh, Ras, lo nggak lihat apa? Gue masih nyalin PR, ini. Mending lo pergi duluan sama Adinda, nanti gue nyusul,” kata Arinda tanpa mengalihkan tatapannya dari buku. Laras mendengus pelan, kemudian gadis itu menuruti saran Arinda. Laras berjalan menuju Adinda yang sudah berdiri menunggu di pintu kelas.
Lama kemudian Arinda masih tetap mengerjakan tugasnya—menyalin lebih tepatnya—tetapi dia masih belum selesai sama sekali. Tugas sosiologi berjumlah sepuluh buah itu memang singkat, tetapi jawabannya bisa lebih dari dua lembar. Memang menyebalkan bagi anak IPS ketika menjawab soal yang membutuhkan jawaban dengan penjelasan.
Sampai-sampai Arinda tidak menyadari seseorang yang berdiri di samping mejanya dengan sebuah plastik di tangannya. Seseorang itu berdehem pelan, menarik perhatian Arinda yang masih menekuni soal. Arinda tersentak kaget ketika melihat lelaki jangkung yang tadi pagi kini berada tepat di depannya. Menjulang tinggi bagai tiang.
“Ini buat kamu.” Alvin menyerahkan sekotak nasi di tangannya itu ke hadapan Arinda. Membuat Arinda mengernyit tak mengerti.
“Anggap aja itu ucapan terima kasih karena kamu mau membawakan tas saya ke sini,” ucap Alvin ketika melihat tatapan penuh tanya dari Arinda.
“Buat s-saya?” tanya Arinda kaku, merasa canggung berbicara dengan Alvin yang menggunakan kata ganti saya dan kamu.
Alvin tersenyum tipis, kemudian mengangguk dua kali.
Arinda menggigit bibir bawahnya, merasa malu karena dibelikan makanan oleh lelaki tampan di sekolahnya itu.
“Makasih, Alvin,” katanya pelan—nyaris serupa bisikan.
“Sama-sama, Arinda.”
“Kamu tahu nama saya?” Arinda kaget.
Alvin tertawa renyah, membuat Arinda terpesona. “Kita sekelas, tentu saja saya tahu nama kamu.”
Arinda menunduk. Merasa semakin malu. Dasar bodoh, rutuknya dalam hati.
“Ya sudah, saya … pamit, ya?” buru-buru Arinda mengangkat wajahnya, kemudian mengangguk dua kali.
Lantas Alvin memutar tubuhnya dan segera berjalan meninggalkan Arinda yang masih terpaku dalam duduknya.
“A-alvin,” panggil Arinda pelan. Alvin menghentikan langkahnya yang sudah berada beberapa meter dari Arinda. Lelaki itu kembali memutar tubuhnya berhadapan langsung dengan Arinda.
“Kamu, tanganmu … berdarah,” kata Arinda pelan.
Alvin terpengarah. Mendadak dia menatap kedua tangannya dan mendapatkan sedikit luka lecet pada punggung tangan kanannya. Padahal awalnya Alvin sama sekali tidak menyadarinya. Alvin kemudian mengangkat kepalanya dan terhenyak melihat Arinda yang sudah berdiri tepat di hadapannya.
“Waktu saya terluka, biasanya saya pakai ini,” kata Arinda sambil menyodorkan plester bermotif batik berwarna biru di depan wajahnya. “Apa ini bisa menyembuhkan luka kamu juga?” tanyanya kemudian.
Alvin tertegun.
Baru kali ini ada orang yang peduli padanya. Pada luka yang terdapat di tubuhnya.
Baru kali ini …
Bersambung


 merryashida
merryashida



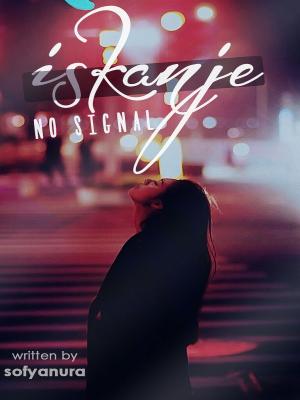

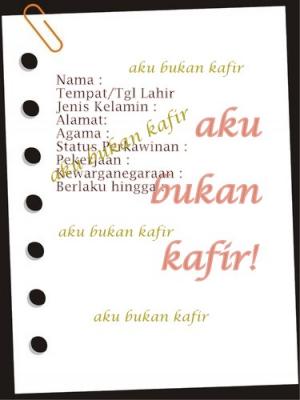




nice story, ditunggu kelanjutannya :)
Comment on chapter Kau yang Berbeda