Terik matahari membakar hampir seantero Jakarta. Tak terkecuali kampusku, berhubung banyak pohon cemara dan dan beberapa beringin disana, jadi panas yang terasa tidak terlalu menyengat. Beberapa mahasiswa memilih berteduh di bawahnya, melupakan tugas kuliah yang menuding mereka lebih tajam daripada belati jenis apapun di dunia. Beberapa juga memilih di kantin, berkelakar, sesekali dari mereka menjaili dan menggoda mahasiswi-mahasiswi cantik yang lewat. Yang di pustaka juga tidak sedikit, untuk menikmati wi-fi gratis juga membaca buku-buku menarik dan mendidik. Sedangkan aku, baru saja melepaskan penat di bangku kecil depan ruang, tidak memutuskan beranjak kemana pun karena selang 20 menit lagi mata kuliah lain akan masuk.
Handphone ku berdering. Sebuah pesan singkat dari Peter masuk.
“Biel, sorry udah seminggu nggak ngabarin, gue nggak sempat ngecek HP saking sibuknya kemarin-kemarin itu. Ampun.. deh. Mana tugas menumpuk banget. Oya, loe lagi apa? Sehat?”
Untuk pesan itu aku hanya membacanya. Tidak perlu dibalas karena memang nggak ada untungnya. Alasan itu terlalu nggak masuk akal dalam ukuran logika wanita. Sesibuk apapun dia pasti menyempatkan diri mengabarkan, bukannya menunggu hingga seminggu lebih. Aku merengut kesal.
Pasti sekarang layar di monitor Handphonenya menunjukkan centang dua biru artinya ia tau bahwa aku telah membaca pesannya. Dua menit kemudian ia menulis lagi.
“Yakin mau marah-marah? Ntar gue telepon deh. Oke?!”
Tak jauh beda dengan pesannya yang pertama. Aku juga hanya membaca pesan itu hingga akhirnya Peter tidak berkutik lagi.
Biar saja.
Agar dia tau rasa.
Lima menit kemudian mahasiswa lain masuk ke kelas yang sama dengan teratur mengikuti gerak langkah pria setengah baya di depan mereka yang berjalan tegap. Aku berjalan terakhir di belakang mereka. Mungkin sudah seperti kerangka berjalan karena gerakku yang paling lemah.
“Lemes banget, Biel. Semangat!” Kalimat itu yang sudah ku dengar beberapa kali hari ini dari hampir seperempat mereka. Ku respon dengan senyuman tipis dan anggukan kepala.
Dosen kami yang akrab disapa Pak Sam itu menyapu pandangannya pada tiap mahasiswa dari ujung ke ujung. Ia bahkan hapal nama-nama kami yang jumlahnya empat puluhan di ruangan itu. Beruntung hari itu hanya sekitar tiga orang yang tidak hadir. Kalau lebih dari 10 manusia seperti minggu kemarin, tentu sebagai hukumannya, Pak Sam langsung melempar pertanyaan seputar mata kuliahnya pada kami yang jumlahnya tak seberapa itu. Begitulah caranya melampiaskan mood buruk beliau.
“Oke, masih ke pembahasan sebelumnya, yaitu invetebrata. Silahkan buka lagi catatan kalian dan saya beri waktu setengah jam untuk mengulang. Apabila ada kata-kata asing yang saya tanyakan dan kalian tidak tau jawabannya, silahkan belajar kembali di luar” Perintah Pak Sam. Tanpa perintah selanjutnya, semua mahasiswa melakukannya. Rio yang disebelahku alisnya mengkerut, mungkin ada sesuatu yang sulit disana, juga Betty yang gaya belajarnya harus bersuara hingga beberapa kali di tegur teman-teman lain namun ia tidak kapok.
Aku membuka catatanku, mencoba memahami dengan baik kata demi kata yang artinya semakin susah itu. Harus tiga kali membaca tiap kalimat agar benar-benar paham.
Kalau begitu, kapan kelarnya?
Handphoneku berdering lama. Tertera nama Peter disana. Sesegera mungkin ku reject panggilan darinya, mengalihkan perhatianku pada penjelasan dosen di depan. Semenit kemudian handphone itu berdering lagi. Terpaksa ku angkat setelah mohon izin pada Pak Sam.
“Apaan sih?” Tanyaku jengkel.
“Gue kangen elu” Balasnya.
“Gue lagi belajar, ntar aja telepon lagi”
Peter diam. “Kali ini serius, gue bener-bener kangen loe, Biel. Kita udah seminggu...”
“Kita udah seminggu nggak berhubungan gara-gara loe saking sibuknya sama proyek –proyek itu, sampe-sampe buat ngabarin aja susah!” Bentakku. Lebih tepatnya ingin ku teriak di telinganya kalau saja tidak berada di depan ruangan sekarang.
“Kemarin itu gue bener-bener sibuk. Loe bisa tanya sama temen-temen gue gimana susahnya gue buat megang hp cuma untuk ngabarin loe. Tapi susahnya minta ampun, Biel. Gue harus minta izin dosen dulu”
Aku menarik napas panjang.“Alasan loe itu nggak masuk akal, Peter. Mana ada dosen yang tega merampas hak mahasiswa untuk megang Hanphonenya sendiri!”
“Yaudahlah. Gue males ribut. Terusin aja belajarnya, nanti kalo udah enakan, bilang ke gue, Biar gue yang menghubungi loe. Bye”
Peter mengakhiri pembicaraan itu. Tanganku geram ingin meremas-remas wajahnya betapa ia begitu menganggap masalah ini biasa saja. Dengan sebal, kumasuki ruangan itu kembali, mendengarkan Pak Sam menjelaskan yang entah sampai dimana. Aku ketinggalan banyak pembahasan gara-gara perbincangan menyebalkan tadi.
***
Jarak dari kampus ke rumahku menghabiskan waktu selama 2 jam. Paling cepat satu setengah jam bila tidak macet. Tapi nampaknya hari ini nasib baik sedang tidak berpihak padaku. Di pukul tujuh malam ini aku tiba di rumah setelah seharian berada di kampus, tak satupun mata kuliah yang dapat kuserap dengan baik karena otakku lelah memikirkan Peter, ditambah macet di perjalanan, kepalaku terasa mau pecah. Selesai memakir mobil new honda jazz merah milikku, aku beranjak masuk ke rumah dengan lunglai. Seketika langkahku terhenti tepat di tengah pintu masuk karena tiga orang memandangku kaget. Ibu, Ayah, juga seorang pria yang tak ku kenali namanya.
“Nah ini dia baru pulang. Gini lho, nak Nata, belakangan ini Biela sibuk banget, jadi pulangnya selalu malam” Ungkap Ibu tersenyum ramah. “Sini, Biel” Ajak ibu kemudian.
Aku mengikuti ajakan Ibu dan duduk di samping beliau. Lalu memasang senyum kaku pada pria berpakaian rapi yang tak kukenali ini. Ah, rasanya malas sekali. Dengan badan yang masih lengket ini, aku ingin lekas-lekas mandi.
“Biela udah besar ya, dulu mah masih sekecil kucing, hahaha” Canda pria itu. Semua ikut tertawa, termasuk aku. Tawa yang dipaksa.
Ayah ikut berbicara. “Biel, ini Pranata, dulu waktu ibumu masih jadi pengasuh di panti asuhan, Pranata tinggal disana.” Ayah menyeruput kopi yang terhidang di depannya.
“Waktu umur Pranata tujuh tahun, dia diadopsi sama Buk Ratna dan suaminya karena mereka belum punya anak”
Kini Ibu memandang ke arahku “Dua bulan setelah itu ibu menikah sama ayahmu dan dua tahun kemudian kamu lahir. Tapi Nata dulu sering ke rumah kita cuma karena ingin main sama kamu yang masih lucu. Kalian berdua semacam adik kakak. Ya, kan , Pak?”
Ayah mengangguk. Pria yang bernama Pranata itu ikut tersenyum sambil mencuri pandang ke arahku. Aku ikut tersenyum ramah walaupun sebenarnya belum terlalu mengerti.
“Lihat nih. Pranata sudah mapan sekarang. Lulusan Universitas ternama di Belanda, punya perusahaan sendiri lagi.” Tambah Ayah.
Ibu ikut menambahkan. “Makin tampan, Yah”. Kami kembali tertawa bersamaan. Pranata tersenyum kecil.
“Biela juga sangat cantik, Bi” Ucapnya.
Menurutku, itu hanya pujian palsu untuk menyenangkan hati kedua orang tuaku. Karena ketika mengucapkan hal itu ia sama sekali tidak melihatku, namun menatap lantai. Aneh.
Ayah dan Ibu mempersilakan Pranata menikmati hiadangan yang seadanya. Kopi dan biskuit kaleng yang baru dibeli Ayah tiga hari lalu yang belum disentuh. Maklum, tamu ini mungkin tidak mengabari sebelumnya bahwa ia akan berkunjung jadi mau tak mau ia harus rela dihidangkan ala kadarnya. Mereka membicarakan perkara keluarga dan pembicaraan lain yang tak ku tau arahnya kemana. Sementara aku lebih cocok sebagai pendengar yang baik dan bijak menanggapi bahan pembicaraan mereka dengan ikut tertawa dan mengangguk.
Beberapa saat setelah itu aku pamit lebih awal untuk mandi dan mereka mengiyakan. Kupijaki lantai dengan malas, duduk di atas kasur sambil memijat-mijat leherku yang kaku karena bergelut dengan waktu seharian. Selepas itu, aku mengguyur air ke seluruh tubuhku dan segalanya terasa lebih baik.
Keluar dari kamar mandi aku bernyanyi-nyanyi kecil dan seketika dikejutkan dengan kehadiran Ibu yang tiba-tiba duduk di kasur dan tersenyum.
“Gimana, Biel?” Tanya Ibu penasaran.
Aku membuka lemari. Mencari-cari piyama yang paling nyaman dibawa tidur.
“Gimana apanya, Buk?”
“Itu lho, Nata. Dia sudah mapan sekarang, punya perusahaan dan apartemen sendiri, duh, nggak kebayang deh gimana waktu kecil-kecil dulu, Nata itu paling dekil diantara temen-temennya tapi dia juga yang paling deket sama Ibu sampe kamu lahir juga dia yang bantu ibu jagain kamu kalo Ayah tugas keluar kota”
“Ooh... dia.” Aku mangut-mangut. “Ya, bagus dong, berarti Ibu beruntung bisa mendidik dia sampai sukses”.
Ibu mendekatiku kemudian menarik tanganku untuk duduk di sampingnya. “Gimana menurut kamu kalau Nata Ibu jadikan menantu?”
Spontan aku terhenyak. Ibu tetap memasang senyumannya tanpa jeda.
“Gimana, Biel? Kamu mau kan? Nata itu lho, yang sering kirimin ibu bunga tempo hari lalu. Kamu ingat kan?”
“Ibu tu seharusnya nanyak, dia udah punya pacar belom trus Biela udah punya pacar, belom?” Jawabku sambil tertawa renyah. Seketika Ibu memasang wajah murung. Rupanya inilah jawaban sebuket bunga yang menimbulkan kecurigaanku dulu pada Ibu.
“Ibu yakin, Nata itu dari dulu udah suka sama kamu, lihat deh tadi aja dia puji kamu. Kalian cocok”
Segera, ku genggam tangan ibu dan menatapnya lekat-lekat. “Bu, mau dia suka sama Biela sekalipun, keputusan nikah atau enggak juga nggak semudah itu.” Aku menarik napas. “Biela udah punya pacar, Buk.
Ibu bangkit dari duduknya. Berjalan perlahan keluar dari kamarku tanpa mengucap apa-apa lagi. Segurat kekecewaan nampak dari raut wajahnya.
***
Suara ketukan pintu menyadarkanku. Dengan langkah malas ku ayunkan kaki turun dari ranjang dan membuka pintu kamar. Ada Ibu disana, memberitahu bawa ada seorang laki-laki yang ingin sekali berjumpa denganku yang kuduga adalah Peter. Aku yakin benar cowok sombong itu ingin berlutut minta maaf. Cepat-cepat kutemui seseorang yang dikatakan Ibu namun sayangnya bukan Peter yang berdiri disana.
Tetap saja. Aku memasang senyum ramah. Tak apa. Sebenarnya, aku juga sangat merindukan laki-laki ini.
“Hey! Udah lama nggak jumpa” Sapa Nazriel. Ia menyodorkan sekeranjang buah-buahan.
“Ibumu tadi dimana, Biel?” Tanyanya lagi.
“Ibu di dapur, mungkin lagi bikinin teh. Yuk duduk dulu” Aku menarik tangannya dan mempersilakan duduk di sofa.
“Gue kangen banget sama loe” Ucapku. Nazriel tersenyum tipis.
“Gue juga minta maaf banget, karna belakangan ini agak sibuk penelitian ke kaki gunung, eh, tapi gue sering ketemu Nina beberapa hari lalu di kampus” Nazriel terlihat sumringah saat ia mengakui menjumpai Nina saat itu. Sedangkan aku dan Nina saja sudah jarang bertemu karena kami terpisah kota.
Tak lama setelah itu Ibu datang dan menyajikan teh hangat di depan Nazriel. Mata Ibu melirikku seakan memberi kode yang sulit kumengerti. Namun senyuman hangat terpancar dari wajahnya.
“Ini toh pacarnya Biela? Kok nggak pernah diceritain sih?” Sindir Ibu. Aku dan Nazriel saling menatap.
“Eh, bukan, Bu. Ini Nazriel, temennya Biela waktu SMA” Responku cepat. Kelihatannya Ibu kurang percaya dan mengalihkan pertanyaan itu pada hal lain selama beberapa menit. Kemudian beliau mohon diri ke belakang. Tinggallah aku dan Nazriel disana yang lebih banyak jaimnya mungkin karena lama tak bertemu.
Nazriel mengajakku jalan-jalan seharian karena kebetulan hari itu ia libur, begitupun denganku. Kami bercerita banyak hal, bukan hanya tentang kekesalan karena ulah dosen, sifat teman-teman baru, dan hal menarik lainnya. Nazriel menghentikan mobilnya di sebuah tempat yang sangat aku kenal. Panti Asuhan “Dunia Bintang” tempat aku, dia, dan Nina mempertaruhkan saat-saat berharga kami disana. Dua tahun lebih tak berjumpa, mereka sudah besar-besar. Bahkan tinggi mereka hampir menyamai kami.
“Cieee, Kak Biela dan kak Nazriel pasti udah pacaran!” Celutuk Amir. Anak itu masih saja suka menyebarkan berita yang aneh-aneh. Yang lain ikut tertawa menjaili.
Nazriel mengacak-acak rambut Amir sambil tertawa. “Dasar ABG labil, Baru masuk SMP udah paham begitu-begituan. Belajar dulu sana” Balas Nazriel.
“Ngaku aja, kali. Kami ikutan seneng..” Tambah Fanni. Rambutnya jadi lebih lucu karena ikal dan dikepang dua. Tampak lebih mengembang.
Aku ikut menimpali. “Hush! Jangan ngomong macem-macem. Atau Fanni dan Amir yang baru jadian sekarang?” Semua yang hadir tertawa geli. Amir dan Fanni saling meledek dan akhirnya kami berbincang-bincang sesaat tentang cita-cita mereka dan keadaan panti setelah kami jarang kesini. Andai disini ada Nina, pasti lebih seru. Tapi karena jadwal Nina yang begitu padat di pesantren, kami semakin sulit bertemu.
Sesuatu yang terjadi di panti asuhan berjalan sebagaimana mestinya. Anak-anak itu sudah hafal gaya cerita dan tema apa yang biasa kami ceritakan pada mereka tiap siang dalam tiga kali seminggu. Tiga jam lebih aku, nazriel dan anak-anak saling berbagi cerita yang intinya mereka sungguh senang karena panti asuhan itu akan direnovasi. Kebetulan banyak donatur yang benar-benar ikhlas menafkahkan harta mereka demi masa depan anak-anak ini.
Siangnya, jadwal mereka makan siang. Tinggallah aku dan Nazriel saling bercengkerama. Merindukan Nina yang hingga sekarang belum ada kabarnya. Terakhir kali gadis itu bilang, bahwa di pesantren dilarang menggunakan handphone jenis apa saja. Tidak ada pesta kelulusan, tidak ada saling kabar mengabari dengan teman di luar kecuali dalam keadaan terpaksa. Ah, Nina. Mengapa dia memilih hal itu sebagai jalan hidupnya?
Nazriel memperbaiki ikatan sepatu kets nya yang agak terlepas. “Kamu dan Peter, udah sejauh mana?” Tanyanya.
Ia menatap mataku. Saat itulah,aku kembali ingat saat dimana ia benar-benar menatapku begitu dalam, ya ketika pertemuan di Nightflower dua tahun silam.
“Gue ... gue dan Peter baik-baik aja” Sesuatu membuatku harus menjawab seperti itu walaupun agak berat.
“Aku berasa nggak yakin, Biela” Balasnya. Entah apa yang membuatnya langsung menebak bahwa hubunganku dan Peter sedang tidak baik. “Dua hari lalu, Peter yang kini nggak jauh beda sama montir itu video call sama aku. Dia lebih dulu curhat tentang kamu padahal aku nggak nanyak” Nazril melanjutkan.
Aku mencubit lengannya. “Sialan loe, masa’ cowok gue dikatain montir, sih?” Aku menggerutu kesal sambil mencubit lengannya. Nazriel tertawa.
“Ya kamu lihat aja rambutnya udah gondrong gitu, baju yang itu-itu aja, dekil lagi. Ya, walupun dia tetep ganteng di mata semua cewek, termasuk pacarnya. Katanya kamu udah posesif banget sekarang. Harus sering ngabarin walaupun cuma sehari sekali dan seminggu yang lalu dia lagi sibuk banget sama proyeknya jadi nggak sempat ngabarin.” Nazriel menarik napaspanjang.
“Anak teknik emang gitu, Biel. Maklum aja, kali”
“Kalo loe ketemu gue cuma buat mendukung Peter dan menyalahi gue, mending gausah aja” Kata-kata itu spontan keluar dari mulutku. Belakangan baru kusadari aku sudah terlalu lancang. Namun Nazriel mencoba melawan argumentasiku.
“Gue nggak tau siapa yang salah dalam hal ini. Oke, loe berdua boleh bilang gue egois, gue posesif, atau apa lah sepuas kalian. Tapi coba loe tanya ke semua cewek, kesal nggak mereka kalo orang yang mereka sayangin bahkan nggak ngasih kabar selama 24 jam lebih. Apa itu wajar? Loe bukan gue, Zriel. Loe nggak tau gimana rasanya khawatir sama dia sampe belajar aja nggak konsen hanya karena dia larut sama proyek bodohnya itu dan dengan mudahnya dia berpikir bahwa gue baik-baik aja?” Jelasku setengah berteriak. Aku berusaha tidak menangis karena terlalu lemah menangis pada laki-laki cuek seperti Peter. Malah rasanya ingin kutinju wajahnya.
Nazriel bungkam. Setengah menunduk. Ia meraih tanganku.
“Kamu nggak salah. Aku menemui kamu hanya untuk memastikan kamu baik-baik aja, Biel. Dan udah seharusnya kamu nggak menyimpan masalah sendiri lagi, menjadi pengganti Nina pun aku siap dan...”
Aku menatap Nazriel yang menunduk.
“Dan....?”
Nazriel balik menatapku. “Dan... itu aja” Nazriel terkekeh. Aku memasang wajah cemberut karena ia membuatku berpikir terlalu tinggi. Bagaimanapun keadaan ku dan Nazriel sekarang, perasaan ini masih tetap sama. Untuk kesekian kalinya, ini bukan cinta. Ini bukan perasaan ingin memiliki, dan menjadi yang paling spesial satu sama lain seperti yang pernah Peter bilang. Mungkin lebih dari sekedar bersama, namun didekat Nazriel aku merasa jauh lebih nyaman. Itu saja.


 dear.vira
dear.vira










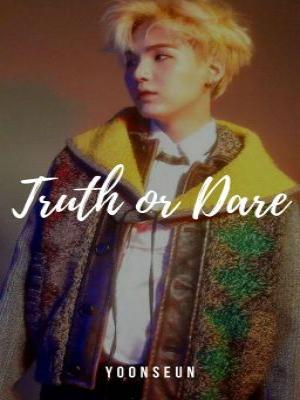




@Ardhio_Prantoko hehe, terima kasih sudah membaca :)
Comment on chapter Pemilik Tatapan Teduh