Tiga bulan berlalu setelah berhasil meyakinkan Nazriel untuk bersekolah kembali dan sejak Peter mengajakku ke tempat seram nan romantis itu. Selama tiga bulan itu, aku dan Peter kerap menghabiskan waktu tiga kali untuk jalan-jalan dan bercengkerama. Tidak, sebenarnya lima kali, karena dua kali itu ku tolak karena tidak mau terlalu larut dengan bayangan wajahnya yang membuatku insomnia sepanjang malam. Kebahagiaan lain adalah melihat Nina juga tak henti-henti mengungkapkan keceriaannya karena berkesempatan duduk dengan Nazriel lagi selepas jam istirahat. Nina menjadi lebih hiperbola, dia kerap menjadi siswa Nazriel selama tiga bulan itu. Merapat bersama-sama adik kelas di taman sambil mendengarkan lelaki idamannya itu menjelaskan sesuatu. Dari balik pohon cemara, jelas terlihat ekspresi Nina yang paling berbeda. Sepanjang Nazriel berbicara, ia begitu semangat menggigit ujung pensil hingga berlubang-lubang tanggung meskipun tatapannya tetap tertuju pada Nazriel. Sesekali ia mengajukan pertanyaan konyol yang bahkan membuat yang hadir disana terpingkal-pingkal.
“Berbeda dengan mikrometer sekrup, menentukan skala nonius pada jangka sorong adalah dengan mengalikannya dengan 0,01 mm, setelah itu kalian bisa menjumlahkan skala utama dan nonius. Finally, you got the result” Papan tulis kecil itu penuh dengan coretan-coretan rumus fisika dari Nazriel.
“Gue mau nanya” Nina mengacungkan jarinya. “ Jangka sorong, bisa nggak mengukur kedalaman perasaan di hati?”
Lantas semua yang hadir terbengong-bengong sedangkan Nazriel hanya geleng-geleng kepala. Hah, dasar perempuan aneh itu.
Tak apalah, asal Nina mau belajar. Walaupun kenyataannya seperti itu bahkan lebih baik dibandingkan keadaanku yang pasrah dan sok belajar sendiri. Namun faktanya juga aku lebih nyaman melakukan hal-hal seperti belajar dengan cara otodidak, karena itu membuatku lebih mengerti. Kenyataannya juga, UN hanya menghitung hari. Dua minggu ke depan, tak ada alasan untuk undur lagi, karena UN serentak diadakan seluruh Indonesia. Itu artinya, kami sudah layak mempersiapkan diri untuk tes masuk Perguruan Tinggi, dan yang lebih memberatkan adalah beberapa hari lagi tiga orang paling berharga itu mungkin akan berpisah dariku. Dua orang yang sangat dekat denganku belakangan ini, Peter dan Nazriel, juga seseorang yang sudah lama menjadi lebih dari sahabat, yaitu Nina.
“Biel, menurut loe, gue udah pintar belom?” Tanya Nina ketika di Kantin. Aku menanggapinya dengan senyuman kecil sambil mengaduk-aduk cappucinno cincau.
Dia menambahkan lagi. “Eh tapi beneran deh, kayaknya ilmu gue udah hampir setingkat sama Nazriel”.
“Yeah, sayangnya itu cuma harapan, “ Aku menyikut lengannya, dan Nina membalasnya dengan omelan panjang yang intinya bahwa Nazriel memang telah jatuh hati pada sosoknya yang lucu.
Tepat disampingku, Yofanna sedang duduk bersama seseorang lelaki yang bukan Peter sambil menyuapi lelaki itu sesendok batagor. Ah, berlebihan sekali. Lelaki itu bernama Beni, satu tingkat dibawah kami yang ku ketahui setelah melihat simbol di lengan baju sebelah kirinya. Selera Yofanna memang tidak jauh dari kata ‘keren’ namun agak berbeda karena kali ini ia menggandeng adik kelas. Sesaat kemudian, kami saling beradu pandang. Ia menggeser kursinya lebih dekat denganku.
“Hallo kekasih baru mantan gue”
Tatapannya membuatku jijik.
”Gue ikut seneng loe bisa dapatin orang yang udah loe impikan dari zaman Jepang” Yofanna tertawa, diikuti Beni. Nina sudah bersiap bangkit dari duduknya untuk menghajar perempuan itu namun ku tahan.
“Gue nggak jadian sama mantan loe, jadi jangan sembarangan buat gosip!” Jawabku kesal tanpa melihat wajahnya.
Yofanna bangkit dan berbisik “Nggak papa kalo belum jadian, tapi hati-hati, mantan gue itu orang yang paling berbahaya. Jangan terlalu percaya, atau loe menjadi cewek paling bodoh bahkan lebih bodoh dari cewek yang di depan loe itu” Dia jelas-jelas menunjuk Nina, karena Nina yang berada di depanku. Spontan saja Nina menarik rambut Yofanna, akan meninju wajah mulusnya.
“Hebat banget loe bilang gue bego? Mau mati, loe?” Seketika yang berada di kantin langsung berjalan merapat, tanpa mengulur waktu aku menarik lengan Nina dan menerobos kerumunan itu. Wajah Nina merah padam.
“Cewek bodoh! Pantas aja sampe sekarang nggak punya pacar!” Teriak Yofanna. Secepat mungkin kubawa Nina menjauh dari tempat itu agar situasi tidak bertambah buruk. Karena kurang berhati-hati aku menabrak Peter. Dia menatap heran pada kami, namun aku malah membenci kehadirannya untuk saat itu. Matanya mengikuti kemanapun kakiku melangkah tanpa mengejar.
***
“Biel. Nyokap aku meninggal” Lirih seseorang dalam handphoneku. Suaranya terasa lemah, anatra melanjutkan atau tidak. Panggung perayaan ulang tahun sekolah kutinggalkan begitu saja sambil menarik tangan Nina. Acara ini penting, belum lagi dalam waktu dekat ini kami benar-benar akan meninggalkan sekolah ini.
Nina melepas paksa tanganku. ”Kita mau kemana?”
“Nyokap Nazriel meninggal, Nin”. Tanganku melambai-lambai di udara memanggil taksi tanpa menghiraukan ekspresi Nina. Di sepanjang perjalanan, tak ada sepatah katapun terucap dari bibir kami. Nina menggenggam tanganku erat hingga bisa kurasakan tangannya dingin. Entahlah bagaimana kondisi Nazriel saat itu. Aku begitu mengkhawatirkannya. Lima belas menit kemudian kami tiba di tempat. Bak mimpi buruk, tenda-tenda terpasang rapi, orang-orang berkunjung semakin memadat, dan juntaian bendera merah melambangkan duka cita.
Kami turun di depan lorong. Bergegas menemui Nazriel, menyusup dalam kerumunan para tetangga yang datang melayat. Menurut kabar, jenazah belum tiba di rumah duka, keluarga sedang mengurusi administrasi rumah sakit. Aroma kapur, bunga mawar, pandan, dan segala bau mistis yang tercampur semakin tercium dari arah pintu masuk. Aku menjelajah pandangan untuk mendapati Nazriel, begitupun halnya Nina. Sayangnya, rumah Nazriel yang selebar istana menyulitkan kami menemuinya. Seisi rumah sedang sibuk menyiapkan hal-hal untuk mengurus jenazah, mungkin Nazriel masih di rumah sakit. Nina memutuskan membantu di ruang dapur, mengiris daun pandan dan sebagainya, sementara aku mengurusi kain kafan yang baru tiba di depan. Secepat mungkin aku berlari memeriksa jumlah helain kafan bersama ibu-ibu yang baru ku kenali tadi. Tujuh lapis kafan untuk jenazah wanita.
“Nak, tolong jumpai Pak Aniz, tanyakan dimana akan dikafani” Perintah seorang Ibu berjilbab merah muda. Aku mengangguk. Pak Aniz adalah Ayah Nazriel, namun aku suka memanggilnya om Aniez. Firasatku kuat mengatakan bahwa om Aniez di halaman belakang, karena beberapa saat lalu aku melihatnya, namun tidak disana. Aku mencari ke ruang dapur, juga hasilnya nihil. Tetangga semakin ramai berdatangan, semakin menyulitkanku menemukan sosok itu.
“Mungkin di ruang tengah, Dik” Jawab seseorang, ku coba mencari di ruang tengah, juga tak ada hasil. Hingga tiga orang menjawab dengan jawaban berbeda juga tak mendapati apa-apa. Aku berlari lagi ke ruang depan, berharap om Anies disana. Seketika tubuhku menabrak seseorang yang menggenggam koper dan dengan wangi parfum yang sangat menusuk. Sesosok laki-laki berpostur tinggi mengenakan jaket dan jeans hitam namun aku tidak mengenalnya.
“Eh, maaf.“ Ucapku sambil berlalu. Terakhir ku lihat laki-laki itu tersenyum berat dan matanya sembab.
Tak lama setelah itu, Om Anies tiba bersama beberapa tetangga membawa batu nisan. Secepat mungkin aku mengejarnya untuk memastikan tempat mengkafani dan Om Anies bergegas menemui tetangga yang bertugas mengurus jenazah. Mata lelaki paruh baya itu merah, terlalu lelah menangis hingga menyadari bahwa penyesalan tak ada gunanya.
Tetangga langsung memadati pekarangan rumah ketika mobil jenazah tiba. Segera air mataku menetes manakala terdengar isak tangis bersamaan shalawat nabi di dengungkan. Jenazah diturunkan perlahan dan tampaklah Nazriel yang masih berbalut seragam putih abu-abu dengan mata sembab. Tampilannya acak-acakan. Aku tak kenal pasti yang mana tetangga atau saudaranya karena beberapa dari mereka bergantian memeluk tubuh kurusnya. Beberapa lagi mengangkat jenazah ibu Nazriel ke ruangan tengah. Sesuatu itu terjadi begitu cepat, ia harus kehilangan wanita yang paling dicintainya. Tubuh kaku itu terus beralu melewatiku. Begitu pucat, wajahnya melukiskan guratan kehebatan seorang istri sekaligus ibu yang berhasil mengajarkan ketulusan dan kasih sayang.
“Loe kuat, Zriel” Ucapku saat Nazriel berhenti sejenak ketika akan masuk.
Dia tersenyum berat. “Loe salah, gue yang paling kuat” Nazriel meraih jemariku, menggenggamnya erat.
Nazriel melanjutkan berjalan memasuki rumahnya, hingga terlihat jelas Nina juga ikut mengelus pundaknya memberi semangat agar ia ikhlas. Kondisinya saat ini memang lebih baik daripada di taman tempo hari. Sesuatu yang dicintai telah dilepas, tapi ia menjadi lebih tegar. Nina berlari memelukku, bersama-sama menangis dalam pelukan. Sebuah jasad telah kembali kepada-Nya. Entah bagaimana jadinya kami nanti. Yang kutau, terlalu banyak dosa untuk dipertanggung jawabkan kelak.


 dear.vira
dear.vira














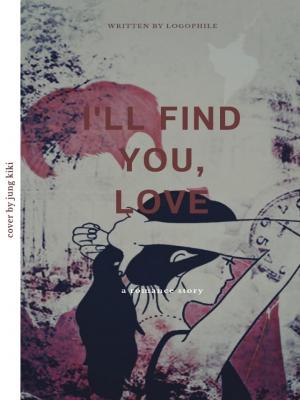
@Ardhio_Prantoko hehe, terima kasih sudah membaca :)
Comment on chapter Pemilik Tatapan Teduh