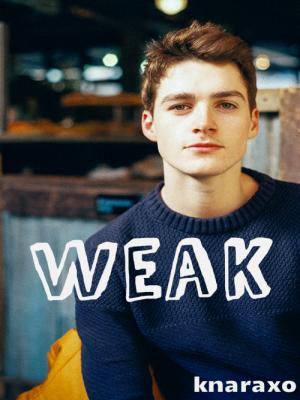Alia paling suka main ular tangga. Seringnya untuk menentukan “siapa melakukan apa”. Seperti pagi ini misalnya. Ayah terpaska bangun lebih pagi dari biasa. Mengecek isi kulkas dan berkutat di dapur untuk membuat sayur sop pesanan Alia karena semalam kalah main ular tangga.
“Pagi Ayah!” sapa Alia dari tangga ketika menuruninya. Senyumnya melengkung dengan mulut terbuka, persis seperti potongan semangka. “Wangi banget, harusnya sih enak ya, Yah!” Alia meledek, membuat Ayah mendengus di depan kompor. Kepulan halus mulai menyentuh-nyentuh hidung.
“Jangan sambil cemberut dong Yah.” Lagi-lagi Alia menggoda. Sambil memisahkan poni, Alia menguncir setengah rambutnya dan membiarkan sisanya berurai.
Ayah tidak menyahut. Sibuk memindahkan sayur dari panci ke mangkuk besar di meja makan. Sementara Alia terus mengembangkan senyum, wajah Ayah justru berkerut usai mengembalikan panci karena mendapati bau bawang putih menyengat di tangan.
“Kok piringmu kosong?”
“Ayah duluan. Jaga-jaga kalau ternyata rasanya nggak karuan.” Tawa Alia terdengar seperti wafer dibelah dua.
Di meja makan Alia dan Ayah menjadi teman. Mengobrol seolah mereka lahir ditahun yang sama. Meski jadi seperti tidak punya aturan, Alia paling menyukai momen ini. Sarapan pagi sambil mengobrol santai bersama Ayah. Satu-satunya keluarga yang ia miliki sekarang.
Pada suapan pertama Ayah terbatuk-batuk sampai Alia melayangkan air putih dari gelas miliknya. “Ini sayur apa sih?” Ayah terlihat jelek sekaligus lucu. Kepalanya mudur sedikit. Menatap heran terhadap mahakaryanya pagi ini. “Nggak ada rasa, cuma pedas, wortel keras.”
“Alhamdulillah, Alia selamat. Yaudah berangkat aja yuk Yah, beli sarapan di jalan.”
“Enak aja, Ayah udah masak dari subuh.”
“Tapi nggak enak kan?”
Ayah melirik jam tangan. Masih sempat. “Yaudah ayo. Besok-besok kalau Ayah kalah jangan suruh masak lagi,” katanya sambil berlalu keluar.
Alia mengekor. “Harus punya motivasi menang dong Yah.”
Hampir pukul setengah tujuh ketika lontong sayur di piring mereka tandas. Irisan tipis labu, telur rebus bulat, dan kuah merah yang ada sedikit rasa manisnya memanjakan lidah. Ditambah curhatan Alia soal sekolah baru membuat mereka lupa masih memiliki setengah perjalanan lagi.
“Jadi, fixed nih aku nggak boleh ikut ekskul seni peran?” Bibir Alia manyun sesudah itu. Cerita tentang Genang yang baik hati telah meminjamkan almamater walaupun sudah dibuatnya malu karena insiden mengintip tempo hari tidak cukup membuat Ayah mau memberi izin.
“Nggak. Jangan tanya kenapa, pokoknya nurut aja sama Ayah.” Ayah selalu seperti itu setiap kali menyinggung seni peran. Matanya menyorot tajam. Serius dan tegas, tidak ingin dibantah walau tidak ada alasan apapun yang dilontarkan.
Alia melirik lengan kirinya yang kosong. Setiap anak di sekolah akan memiliki badge warna-warni sesuai ekskul yang diikuti. Hijau misalnya, untuk anak-anak ekskul kelompok ilmiah remaja dan palang merah remaja. Cokelat untuk anak-anak ekskul gerakan pecinta alam, pramuka, dan paskibra. Biru untuk karate, tapak suci, dan taekwondo. Putih untuk rohani islam dan rohani kristen. Merah untuk ekskul footsal, basket, voli, dan cheerleader. Kuning untuk ekskul seni musik dan seni peran.
Alia ingat sesuatu. Membuka tas kertas di tangan dan memeriksakan sesuatu. Membaca nama Genang Bumi Wahdin di alamamater bagian dada. “Ayah!” serunya tiba-tiba. Ayah menoleh tenang. “Pasien Ayah namanya bukan Genang Bumi Wahdin kan?” lanjutnya sedikit cepat dan mendesak. Alia ingat, pemandangan samar sore itu. Sewaktu ia baru sampai di lorong rumah sakit untuk menemui Ayah. Dua orang laki-laki beralmamater sama keluar dari ruangan Ayah. Yang satu ada garis merah di lengan kirinya dan satu lagi kuning. Entah mengapa, Alia tidak lebih dulu menaruh curiga pada si garis merah.
Ayah tidak menjawab. Mengganti topik dengan membahas pelajaran tambahan di sekolah yang harus Alia ambil untuk mengejar ketinggalan. Tetapi Alia tahu, dari bola mata Ayah yang bergerak pelan dan samar, jawaban itu. Jantung Alia segera terpacu lebih cepat. Dahinya tidak bisa untuk tidak mengerut.
---------------------------------
Helaan napas Genang lumayan panjang. Ia baru saja masuk babak paling awal sebagai penderita kanker. Pagi tadi Genang bangun dengan tubuh berkeringat meski suhu ruangan normal. Kepalanya pening sampai sulit bangun dari ranjang.
Kurang dari sepuluh menit lagi bel masuk akan berbunyi. Genang memilih berada di rooftop sekolah, bagian paling tinggi dari bangunan empat lantai ini. Tempat yang selalu menjadi pilihan untuk mendapat kenyamanan. Di sini Genang bisa menjadi apa yang dimau. Bisa melakukan apa yang dimau tanpa perlu ada pertanyaan dan gangguan. Lagi pula alamamaternya belum kembali, sudah pasti ia tidak bisa masuk kelas juga.
Genang terpaksa menyumpal hidung dengan sapu tangan. Berikutnya ia akan rajin membawa air kemana-mana kalau ia mendadak mimisan seperti sekarang. Berusaha menghilangkan rasa kesal Genang beranjak ke pinggir. Merentangkan kedua tangan lebar-lebar. Mencoba menikmati sentuhan angin pagi di kulitnya. Mata kecilnya memejam, makin lama makin jauh terbang.
Tubuh yang berkeringat pergi. Pening tadi pagi pergi. Fakta kalau ia menderita kanker pergi. Setiap langkah menjadi simbol pengusiran terhadap hal-hal menyebalkan. Perlahan-lahan kepalanya kosong. Pikirannya ringan. Sampai sebuah pekikan mengudara di telinga Genang.
“Jangan bunuh diri!” Begitu bunyinya. Tepat di telinga sebelah kanan dan sangat nyaring. Seseorang memeluk Genang erat-erat, mencoba menariknya ke bagian tengah.
“Apa?” Tidak ada kata lain yang menemani. Hanya itu walau di kepala Genang berisi banyak sumpah serapah. Genang bergerak maju beberapa centi. Matanya mengintimidasi.
“Jangan bunuh diri.” Kali ini suaranya merendah dibarengi gelengan kepala. “Ini aku kembaliin almamater kamu. Masih ada satu menit lagi, masih boleh masuk kelas,” sambungnya seraya memindahkan tas tangan kepada Genang.
Genang menghela napas. Menahan diri untuk tidak menumpahkan kalimat-kalimat negatif. Ia pasrah sewaktu perempuan itu menggandengnya ke tengah.
“Maaf ya.” Gandengan dilepas. Tatapan perempuan itu masih saja khawatir. Genang kini menggaruk-garuk kepala. Bingung harus bagaimana. Terlalu lugu.
“Lo kira pikiran gue cuma lima centi ya? Mau bunuh diri gara-gara belum pakai alamamater.” Meski begitu, Genang berkata ketus.
“Kali aja.” Perempuan itu menggigit bibir bawahnya sementara Genang geleng-geleng. Dipakainya almamater dari dalam tas kertas. Aroma mawar menyeruak halus ke hidung Genang.
“Apalagi? Sana!” usir Genang setelah beberapa saat perempuan itu masih diam di tempat. Saling melempar tatapan heran untuk alasan berbeda.
“Kamu nggak mau bilang makasih aku balikin almamater kamu sebelum bel masuk?”
Sayang, usai kalimat perempuan itu, bel masuk berbunyi. Genang kembali menghela napas. Jelas-jelas ia dirugikan. Aksi relaksasinya berantakan. Berani-beraninya perempuan itu menagih terima kasih.
“Oke, bye!” perempuan itu melambai kaku. Senyumnya lebar dan datar. Mengambil satu langkah berbalik.
Genang mulai mengambil duduk. Di salah satu bagian yang terdapat pipa besar.
“Ah iya, kamu nggak ke kelas?” Rupanya perempuan itu kembali lagi.
“Nggak.”
“Oke.” Perempuan itu mengangguk-angguk. Tetapi bertanya lagi, “Kamu nggak mau bunuh diri kan?”
Mata kecil Genang sukses menjelma jadi gundu. Membulat dibarengi mulut setengah membuka. Sebelum Genang menyahut ketus, perempuan itu menunjuk hidung Genang dengan matanya yang masih khawatir. “Kamu butuh tisu sama air?”
Cepat-cepat Genang menarik sapu tangan. Menyimpannya ke dalam saku celana. Wajahnya dipasang seangkuh mungkin. Seolah tidak ada apa-apa antara ia dan sapu tangan berbercak darah dari hidungnya.
Perempuan kurus mendekat meski takut. Menyodorkan Genang satu plastik tisu dan botol minumnya. Didetik ketiga Genang mau juga menerima pemberian perempuan itu. Satu tetes lagi darah mengalir. Sangat pelan dan menyebalkan.
“Acute Myelogenous Leukemia ya? Kamu jangan terlalu capek.”
Genang berhenti pada apapun yang sedang dilakukannya. Kalimat pendek barusan mendidihkan darah Genang begitu saja. Genang bangkit dan melangkah maju dengan pasti. Semakin ia mendekati perempuan cerewet itu, semakin tajam tatapan yang Genang lemparkan.
“Dari mana lo tahu?” pertanyaan singkat yang terdengar menyeramkan. Nadanya jauh dari tenang. Alis ulat bulu Genang mengerut hampir bertautan.
“Eh? Em…” Perempuan itu jelas-jelas ciut. Tidak berani menatap Genang. Setelah hitungan ketiganya dalam hati, perempuan itu mengambil satu langkah mundur. Membuat jarak diantara mereka sedikit lebih aman. Satu tarikan napas diambil dan kemudian ia melontarkan pertanyaan, “Aku mau ikut ekskul teater, boleh?”
“Dari mana lo tahu?” Genang masih gusar. Sorot mata kecilnya masih seperti ujung pisau. Tajam dan bisa melukai.
Perempuan itu mencoba menenangkan diri melalui dehaman. “Oke, nggak bisa ya? Aku masuk kelas duluan kalau gitu. Bye!” secepat kilat perempuan itu mengambil langkah mundur lagi. Berbalik dan hendak mengambil jurus dikepung masa, jurus kaki seribu.
Namun Genang lebih cekatan. Tangannya menangkap tangan si perempuan dengan cepat. Sampai perempuan itu menoleh dan menyerah. Terlihat pangkal-pangkal rambutnya basah karena keringat yang mulai keluar. Bak daun tertiup angin, bibir perempuan itu bergetar saat mencoba untuk melengkung.
Genang tidak bicara, hanya bertanya lewat dagu yang mengangkat seraya genggaman pada pergelangan perempuan itu melonggar. Menahan seseorang dengan paksa sama sekali bukan cara sah untuk mendapat jawaban.
“Aku janji nggak akan kasih tahu siapa-siapa, sumpah!” Melihat tangan Genang yang kini hanya mengerat di almamaternya, perempuan itu memberanikan diri untuk tersenyum lebih tegas sampai gigi-giginya kelihatan lalu jari telunjuk kanannya mengacung.
Genang melepas tangannya dari sana. Ada sedikit kelegaan yang bisa ia rasakan. Meski ia tidak mengenal orang di hadapannya, dari ketakutan perempuan itu Genang mendapat keyakinan kalau perempuan itu sungguh-sungguh akan menjaga ucapan. Dan memang itu yang bisa ia harapkan begitu sadar tidak mungkin membuat perempuan itu jadi tidak tahu kalau ia penderita Acute Myelogenous Leukemia.
Kerutan di dahi Genang sedikit mereda ketika mereka akhirnnya berhadapan.
“Aku anaknnya dokter Bangga,” ucap perempuan itu sambil mulai tersenyum lebih tegas.
Genang mendengus. “Bokap lo rumpi juga ya?!” ucapnya sedikit mengejek.
“Bokap?” gantian si perempuan yang dahinya mengerut.
“Dokter Bangga.”
“Oh bukan Ayah yang bilang. Aku lihat kamu masuk ruangan Ayah.” Perempuan itu mengklarifikasi dengan cepat.
Genang tidak membalas apa-apa. Ia mulai bergegas mengambil ransel begitu yakin hidung standarnya bebas darah.
“Aku janji nggak akan bocorin ke siapa-siapa.” Perempuan itu mengulangi janji. Dan lagi-lagi jari telunjuk kanannya mengangkat.
Sebelah alis Genang mengangkat. Ia malah berpikiran negatif sekarang. “Lo mau balasan apa dari gue?” Bukannya tidak mungkin perempuan itu punya maksud sehingga berjanji dua kali begitu.
“Nggak, nggak ada.”
“Gue cuma berbaik hati selama tiga hitungan. Satu… du—”
Muncul sesuatu di dalam kepala. Perempuan itu justru ingin tertawa. Dasar kuno, pikirnya. Tidak semua orang yang bersedia tutup mulut akan meminta imbalan. Jadi perempuan itu iseng menantangnya dengan bilang, “Aku boleh ya nonton anak-anak teater latihan?” Berdasarkan track record pertemuan mereka yang tidak pernah benar-benar menyenangkan, ia yakin Genang tidak akan ingin punya urusan apapun lagi dengannya.
Genang berdiam sebentar. Otaknya menganalisa beberapa hal. Namun kemudian ketika otaknya pula yang mengingatkan bahwa ia hanya ingin rahasianya aman, Genang akhinya bilang, “Asal nggak bikin ribet,” secepat dan sesingkat mungkin.
Perempuan itu mendadak kaku di tempat. Kedua alisnya mengangkat seraya tarikan napas yang ditahannya. Aneka ragam perasaan melingkupi perempuan itu sekarang sampai-sampai ia lupa kalau tantangannya tadi tidak benar-benar ia niatkan sebagai permintaan balas budi. Dan, kata “Asik!” berseru begitu saja dari bibir tipisnya.
Beberapa detik kemudian perempuan itu bisa mengendalikan diri. Segera ia mengejar langkah Genang yang sudah lumayan jauh meninggalkannya. “Tunggu!”
Genang berhenti lalu menoleh malas. Ia tidak ingin punya urusan lagi dengan perempuan itu tapi sejak kartu as-nya diketahui perempuan itu, Genang merasa sedikit tidak yakin terlalu abai pada perempuan itu.
Perempuan itu menghampiri Genang. Lariannya membuat poni dan rambut sebahunya mengayun. “Kenalin, aku Alia.” tangan kurus yang kalau pakai jam tangan, pengaitnya akan masuk ke lubang paling pertama itu mengulur.
Genang mau melontarkan keheranannya mengapa perempuan itu malah mengajak berkenalan namun akhirnya menyahut dengan, “Lo tahu gue sakit apa, lo juga pasti tahu nama gue,” sedingin mungkin sambil kemudian berlalu.


 resawidi
resawidi