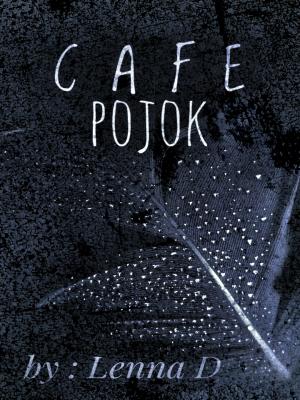“... berikut bintang tamu dari Symphoni Ochestra Festival yang diselenggarakan Institut Bishopsgate, Ana Alexa!!”
Semua penonton dan juri yang semula seru membicarakan para peserta muda kontes musik itu seketika terdiam mendengar nama ‘Ana Alexa’. Saat hak sepatu Kenan mengetuk-ngetuk panggung, beberapa orang sudah mulai berbisik-bisik. Namun, begitu Kenan sampai di tengah panggung dan matanya menusuk para hadirin di tempat itu, suasananya berubah tegang, menakutkan.
Seperti biasanya, Kenan mengangkat violinnya, memiringkan kepalanya lalu mulai menggesek violinnya.
“... itu ... Nona Alexa ? Hei, gosip itu benar tidak ya?”
“... Wolfgang Amadaus Mozart: Eine Kleine Nachtmusik? Apa-apaan lagu yang ia mainkan itu? Setiap kali kakakku memainkan lagu ini rasanya hatiku gembira! Kenapa di telingaku lagu ini seperti lagu kematian??”
“... ada apa dengan wanita itu? Sepertinya ia terkenal?? Tapi, kenapa rasanya ia menakutkan sekali? Sekalipun aku duduk di belakang, rasanya aku merinding.”
Sambil terus menggesek violinnya, Kenan menutup mata dan telinganya. Ia tak mau peduli apa yang orang bilang di hall itu. Yang ia pikirkan hanya satu, ia menuntaskan tanggung jawabnya.
Kejadiannya dua hari yang lalu saat bibi Vani berulang tahun. Beliau ingin Kenan kembali ke Inggris untuk merayakannya bersama seluruh keluarga Challysto. Yah, ternyata itu hanya akal-akalan bibi Vani–dan paman Anderson–supaya Kenan bermain violin di panggung Proms, London. Jadi, ketika Kenan sampai di London City Airport, paman Anderson sendiri yang menjemputnya. Selama perjalanan hingga ke kediaman Challysto-lah paman Anderson baru menyampaikan maksud rahasianya.
“... Kenan?” sergah bibi Vani.
Selesai memainkan lagu kesukaan Lena tersebut, Kenan menurunkan violinnya dari pundaknya. Ia memandangi para penonton yang diam saja. Sama sekali tidak ada tepuk tangan. Sama sekali tidak ada ucapan ‘bravo’. Semua diam, hening.
“... mata wanita itu menakutkan...”
“... itu kan lagu ceria tapi kenapa ekspresinya datar-datar saja?”
“... hei, kau harus tahu. Berita dari Praha, Ana Alexa sebenarnya...”
Pandangan mata Kenan hampa. Sorot matanya yang kosong secara bergantian bertemu dengan pandangan bibi Vani dan paman Anderson yang berdiri di kursi paling belakang. Seakan-akan Kenan ingin menyampaikan pada mereka: ‘aku sudah selesai di sini’.
“... kenapa dia tidak turun juga dari panggung?”
“... coba lihat matanya itu! Mata munafik! Penipu! Di belakang semua ini keluarga Challysto pasti –“
Terkejut mendengar makian yang terakhir itu, Kenan segera membungkukkan badannya. Cepat-cepat ia undur diri dari tempat itu sebelumnya muncul masalah baru. Ketukan suara sepatunya malah berhasil memicu keributan di panggung Proms.
“Kenan??” ucap bibi Vani lagi. “Sayang, anak itu kenapa?” Paman Anderson menggeleng sedih. “Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku sudah lama tidak mendapat kabarnya sejak ia berangkat ke Wina! Kenapa sekembalinya dari sana keadaan Kenan berubah jadi semakin buruk??”
Paman Anderson terpaksa menarik istrinya keluar dari aula sebelum ia semakin histeris. Ia mendudukkan bibi Vani ke kursi lalu duduk di sebelahnya. Tangan bibi Vani terlipat. Bibi Vani menutupi wajahnya dengan tangannya, menahan kesedihan terdalamnya.
“Anak itu, aku dengar... kabar kurang mengenakkan tentangnya di Praha.” Bibi Vani menurunkan tangannya lalu menoleh. “Sepertinya rahasia tentang ‘itu’ terbongkar. Dunia musik terguncang dengan isu bahwa Kenan adalah violinist yang curang. Fitnah kalau keluarga Challytso adalah dalang di balik ketenaran Kenan menyebabkan composer dan orang-orang yang berpengaruh di dunia musik klasik tidak menaruh minat lagi... padanya,” jelas paman Anderson yang berusaha jujur apa adanya di hadapan bibi Vani.
Bibi Vani sangat terpukul mendenganya. Lagi-lagi ia menangkupkan wajahnya dengan kedua tangannya lalu menangis. “Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang, Anderson?”
Paman Anderson terdiam. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia hanya ingin menyemangati Kenan. Ia berpikir, dengan mengundangnya bermain di panggung Proms, Kenan bisa sedikit melupakan masalahnya di Wina. Kenyataannya, ia malah menghancurkan Kenan dan istrinya sendiri.
“Aku, aku tidak mau kehilangan lagi. Sudah cukup aku kehilangan Ritsena. Aku tidak mau kehilangan putrinya juga!!” jerit bibi Vani. Semakin ia mengingat soal Ritsena–sahabatnya sekaligus saudara iparnya–semakin tertekan pikirannya. “Kita baru menemukannya! Aku tidak peduli apa yang Kenan katakan tentang aku, aku hanya ingin menjaganya supaya aku tidak kehilangan lagi orang yang berarti bagiku!”
“Vani,” panggil paman Anderson. Ia merangkul bibi Vani supaya ia lebih tenang. “Dengarkan aku, Vani. Kenan tidak mati. Mungkin yang terjadi padanya adalah hal buruk tapi bukan berarti segalanya sudah berakhir.” Bibi Vani sama sekali merasa terhibur dengan ucapan suaminya. “Aku akan lakukan semua yang bisa kulakukan tapi, kau tahu ini masalahnya. Kita tidak punya andil dalam hal itu. Baik Ritsena dan penyakitnya, Kenan dan masa depannya. Ia sudah dewasa, kita hanya bisa mengawasi, Vani.”
Bibi Vani menggeleng. Ia masih bersikeras menepis perkataan paman Anderson.
Jari kaki Kenan berada di ujung atap rumah sakit tempat Lena dulu dirawat. Bila ada seseorang yang usil mengagetkannya, saat itu juga Kenan akan terjun payung dari lantai 5. Sayangnya, malam itu terlampau dingin untuk orang-orang berlalu lalang di sekitar National Hospitality of Neurology, sehingga tak ada seorang pun yang rela melakukannya.
“... itu kan lagu ceria tapi kenapa ekspresinya datar-datar saja?”
“... coba lihat matanya itu! Mata munafik! Penipu! Di belakang semua ini keluarga Challysto pasti –“
Tidak bisa dipungkiri alasan Kenan hanya termenung di sana ialah untuk merenungkan kembali setiap perkataan orang-orang di panggung Proms siang tadi. Setiap makian itu... tidak menghancurkan hatinya. Ia malah bingung dimana hatinya berada. Ia hanya terus berpikir... aku... tidak punya tempat lagi di dunia ini. Ayah sudah pergi, Lena menyusulnya. Aku tinggal sebatang kara. Untuk apa aku bermain musik kalau orang-orang tidak butuh musikku lagi? Musik yang paling disukai Lena tidak diperlukan lagi di dunia ini. Aku, aku tidak punya alasan untuk bermain musik lagi, juga alasan untuk hidup... Lena.”
Nyawa Kenan tinggal 20 cm lagi. Setiap waktu Kenan siap untuk meloncat. Akan tetapi, setiap telapak kakinya bergeser maju, dada Kenan rasanya sakit.
Kenapa? Kenapa rasanya sulit sekali untuk hidup, Lena? Harapanku, nadaku, semua sudah hancur. Soundpost-ku sudah hancur!
Setitik air mata meleleh di pipinya. Ekspresinya tetap datar tapi perasaan sedih yang berkecamuk di dadanya itu tidak bisa ditahan. Kenan memang sudah lupa bagaimana cara menyuratkan ekspresi terluka di wajahnya. Ia juga sudah lupa caranya sedih dan tertawa. Walau begitu, secara naluriah matanya masih paham cara untuk melepaskan kesesakkan di dadanya adalah dengan menangis.
Kenan menengadahkan kepalanya, pasrah. Dengan menutup mata Kenan tidak perlu melihat taman yang tertutup salju yang akan menjadi tempatnya mendarat kelak. Kaki kanannya sudah terangkat, siap meloncat. Namun, saat itu juga Kenan teringat bagaimana Lena yang sudah sekarat menyuruhnya–memaksanya–untuk terus hidup. Ingatannya terus mempermainkannya, menuntutnya untuk mengingat dan mengingat lagi setiap kenangan yang ada, bersama Ryan, bersama Vincent, bersama teman-teman sekolanya dan lainnya.
Seketika itu juga keberanian lenyap dari raganya. Kaki kenan langsung lumpuh, tak lagi mampu berdiri. Kenan jatuh terduduk tepat di pinggir atap. Dirinya yang sudah seperti cangkang kosong hanya diam di tengah hujan salju bersama violinnya.
“Kenan mana, Merry? Anderson? Kenan mana!?” pekik bibi Vani.
Ia melihat ke sana kemari, berlari ke sana kemari, sambil membuka semua pintu yang ada di rumah itu. Pelayan-pelayan yang iba membantu bibi Vani untuk berkeliling rumah mencari Kenan. Bahkan, berulang kali bibi Vani menengok ke kamar Kenan, berharap kalau gadis itu tiba-tiba muncul di sana.
“Vani, tenang!” Paman Anderson menangkap lengan bibi Vani.
“Tenang!? Bagaimana aku bisa tenang!?”
“Vani,” tante Merry muncul dari pintu depan. Ia membawa berita dari pusat pencarian orang hilang. “Aku, tidak menemukan Kenan dimanapun.”
Paman Anderson mengernyit. “Lihat!? Tenang apanya!? Kenan sudah menghilang satu minggu! Kemana ia pergi selama itu tanpa membawa barang apapun!?” Bibi Vani mengeluarkan handphone dan dompet Kenan dari saku bajunya. “Dia bahkan tidak membawa ini! Bagaimana caranya kita menemukannya di Inggris ini, Anderson!?”
Kedua tangan Anderson memeluk bibi Vani. Kepalanya yang lesu jatuh ke pundak bibi Vani. “Aku tahu, Vani. Aku juga sudah mencarinya kemana saja. Hanya, kepanikan tidak membawa perubahan baik sama sekali di sini, Vani.”
Mendengar perkataan itu tante Merry menggertakkan giginya, sementara bibi Vani hanya terdiam kaku. Lelah dengan semua pencarian sia-sia itu, paman Anderson mengajak bibi Vani dan tante Merry untuk duduk di ruang tamu. Mereka hanya diam seribu bahasa. Mereka sudah kehabisan akal kemana lagi harus mencari putri mereka satu-satunya.
“Pah, Mah, Kenan benar hilang!?”
Di saat suasana sudah mulai tenang, Ryan mendadak muncul di tengah tea break. Bibi Vani tanpa sadar berdiri ketika mendengar suara putra tunggalnya. Ryan langsung berlari memeluk bibi Vani begitu melihat nanar di wajah mamanya.
“Kau yakin di sini, Ryan?” tanya ayahnya.
“Kalau tempat dimana Kenan bisa menenangkan dirinya... hanya di sini, di atap rumah sakit tempat dulu Lena di rawat.” Mendengar nama ‘Lena’, tangis tante Merry hendak meledak. Situasi seperti itu, rasanya persis seperti dirinya saat kehilangan putri kesayangannya satu-satunya.
Ryan yang baru datang memiliki banyak tenaga untuk lari ke sana kemari. Ia berkeliling hampir ke seluruh resepsionis rumah sakit itu untuk bertanya tentang Kenan. Usaha tanpa lelahnya membuahkan hasil saat seorang perawat bersama seorang penjaga dinas malam memberi informasi mengenai seorang perempuan yang sedang memeluk biola ditemukan nyaris mati membeku di atap rumah sakit beberapa hari silam.
“Ada, ayah! Mom, jangan menangis. Ayo ke tempat Kenan.”
Ryan membawa secercah harapan kepada keluarganya. Ia mengemudikan mobil ke kota seberang, King’s Cross. Ryan memarkirkan mobil ayahnya di King’s Cross Public Hospital.
“Rumah sakit?”
Sepanjang perjalanan memasuki koridor rumah sakit, Ryan menjelaskan apa yang perawat dan penjaga itu jabarkan padanya. Menjelang tengah malam, sorot senter penjaga tidak sengaja menangkap bayangan manusia di atap. Ketika ia berlari ke atap, ia menemukan seorang wanita yang sudah tidak sadarkan diri. Dari ciri-ciri yang disebutkan penjaga itu, Ryan yakin sekali bahwa itu Kenan. Namun, karena rumah sakit itu khusus menerima pasien neurologi, mereka harus memindahkannya ke rumah sakit lain. Yang bersedia dan yang terdekat saat itu adalah... King’s Cross Public Hospital.


 Furgeva
Furgeva