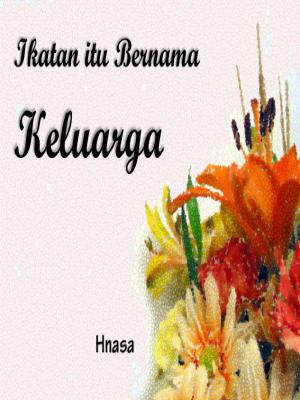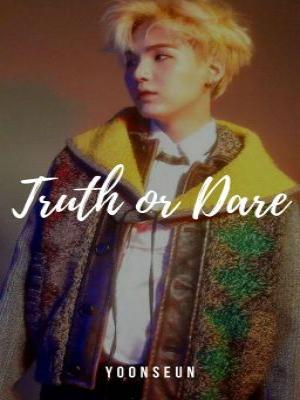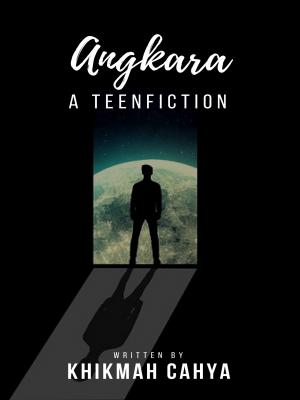Ritsuka mendapati Mai menoleh ke lapangan agak terlalu lama. Itu membuatnya memiringkan kepala agar bisa menatap ke arah yang sama.
Ada kelab bisbol di sana. Mereka membawa bola, menepuk sarung tangan, dan mengayunkan tongkat-tongkat. Beberapa muka Ritsuka kenal, sementara sebagian yang lain tidak. Tapi mau kenal atau tidak, di muka tiap-tiap mereka, Ritsuka bisa menemukan keseriusan dan fokus. Masing-masing berada dalam takaran yang sama.
“Padahal belum ada pertandingan. Tapi Keita-kun dan semua anggota kelab bisbol kelihatan semangat sekali.” Ritsuka mengatakan ini waktu mereka sudah melewati gerbang. Sekolah dan riuh aktivitas kelab eskul pelan-pelan tertinggal di belakang.
“Karena kepala mereka isinya cuma perkara bisbol,” ujar Mai. Telunjuknya mengetuk kepala dua kali. “Mungkin kalau Keita punya pacar, dia bukan beli tiket film buat kencan, tapi tiket nonton bisbol!”
Ritsuka tertawa.
Beda dengan Ritsuka yang hanya tahu samar-samar soal Keita, Mai mengenal pemuda itu dengan sangat baik. Selain menjadi teman satu SMP, Mai dan Keita berbagi ketertarikan yang sama dalam bidang olahraga. Mereka sama-masa menyukai lapangan bisbol dan sensasi berlari mengitari lapangan, dari satu base ke base lain, atau ketika tangan mereka mengayun untuk mengirim pukulan pada bola bisbol.
Yang membedakan Mai dan Keita hanya seberapa besar kecintaan mereka pada semua itu.
Mai, kendati menyukai semua hal berkaitan bisbol ataupun softbol, dia tidak terlalu banyak menaruh ekspektasi pada mereka. Bagi Mai, bisbol ataupun sofbol adalah permainan. Cara terbaik membunuh waktu dan membakar emosi dengan cara yang sehat. Dia tidak merasa perlu berinvestasi terlalu banyak.
Sementara bagi Keita, bisbol adalah cara dia bernapas. Kau bisa saja tidak mengenal dia, tapi kau bisa dengan mudah lihat bagaimana Keita mencintai bisbol. Mungkin dari cara matanya berbinar ketika turun ke lapangan, atau ketika menemukan siaran pertandingan bisbol di salah satu saluran televisi, atau saat kau tanpa sengaja membawa topik bisbol pada konversasi.
Dengan hal-hal di atas, maka wajar jika Mai selama ini mengatai Keita otak bisbol.
“Tapi, tapi,” kata Ritsuka lagi, “justru karena otak Keita-kun isinya cuma ada bisbol, makanya Mai suka, kan?”
Mai meletupkan tawa. Kalimat Ritsuka mengingatkannya pada musim gugur lalu. Itu adalah hari bersejarah bagi hidup Mai sebab, waktu itu, ia menyatakan suka pada Keita.
Itu adalah kali pertama Mai membiarkan seorang laki-laki mengetahui perasaannya. Meski di akhir, yang dia terima adalah penolakan. Bukan karena Keita tidak menyukai Mai, tapi karena dia masih mau berusaha mencari jalan ke Koshien.
Kata Keita, cita-cita dia mungkin terdengar menggelikan. Kemampuannya yang sekarang masih payah dan butuh banyak lagi latihan. Tapi jika benar Keita tidak bisa bermain di Koshien, setidaknya dia tidak menyesal karena sudah mati-matian berjuang.
Mai sendiri selalu punya alasan untuk meragukan Keita. Tapi kalau melihat Keita yang masih serius dengan bisbol sampai detik ini, entah kenapa, Mai tidak keberatan patah hati.
Tunggu. Koreksi sedikit; Mai tidak patah hati.
Keita mungkin tidak menerima perasaan Mai, tapi itu tidak mengubah apa pun. Alih-alih hancur, cinta gadis itu terus tumbuh, menjulang, dan terus mekar sampai memenuhi seluruh rongga hati.
“Yah … bagaimana, ya?” kata Mai. “Buatku, laki-laki yang gigih mengejar mimpi itu punya pesona sendiri.”
Mai menghentikan langkah, lalu berbalik tiba-tiba. Membuat Ritsuka secara refleks mundur dua langkah. Mata Ritsuka, berbentuk seperti almond, berkedip dua kali. Ada bingung yang tergambar di wajahnya. Dan Mai, dengan senang hati, menjawab dengan;
“Bukannya menyenangkan, saat melihat orang yang kau sukai tahu ke mana harus mengarahkan hidupnya? Dia tahu apa yang diinginkan dan bisa mengira-ngira apa yang membuat mereka bahagia. Kau pasti akan patah hati kalau melihat dia menghentikan langkah, hanya karena hal-hal kecil.”
“Jadi Mai tidak mau jadi alasan Keita-kun untuk bahagia?” Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulut Ritsuka. Nadanya polos, sebab pertanyaan itu benar-benar jujur dan bukan bermaksud menjatuhkan.
Mai sepertinya bisa mengerti, sebab ia tersenyum sebelum menjawab;
“Itu dua hal yang berbeda—setidaknya, buatku.”
“Beda?”
Anggukan. “Saat aku menyukai seseorang, aku merasa tidak harus selalu jadi alasan agar orang itu bahagia. Maksudku, hidupnya tidak hanya berputar padaku. Ada banyak hal yang ada di sekelilingnya.”
Ada angin yang berembus saat Mai mengakhiri kalimatnya. Ujung-ujung rambut Mai yang panjang sampai punggung terangkat sedikit. Dan dari tempatnya berdiri, Ritsuka baru sadar bahwa temannya yang satu itu cantik sekali—bukan maksudnya dulu Mai tidak cantik di mata Ritsuka. Hanya saja, setelah penjelasan panjang tadi, Ritsuka merasa Mai kelihatan jauh lebih dewasa.
Mai selama ini hanya kelihatan seperti siswi yang suka menggoda rekannya. Erika adalah korban langganan. Senang sekali Mai melihat temannya yang satu itu marah-marah. Tapi baru kali ini Ritsuka melihat bagaimana cara Mai sebenarnya melihat sesuatu.
Bagaimana Mai bisa memikirkan hal-hal yang tidak pernah lewat di kepalanya? Hal ini membuat Ritsuka berkedip dua kali.
“Keren. Mirip pujangga,” kata Ritsuka. “Kalau Erika dan Midori ada di sini, mereka pasti terkejut Mai bilang begitu!”
“Jangan meledek!”
Mai melayangkan pukulan main-main ke arah lengan atas Ritsuka—yang dengan segera ditangkis menggunakan tas.
Mereka tertawa sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Di depan adalah area pertokoan. Kombini, toko buku kecil, dan beberapa toko lain berjejeran. Intensitas pejalan kaki mulai banyak, apalagi ini dekat perempatan. Bijak jika kiranya tidak bercanda berlebihan.
“Ritsuka sendiri bagaimana?”
“Hee? Apanya?”
Ritsuka menoleh, hanya untuk mendapati Mai menatap penuh selidik. Lampu bagi pejalan kaki warnanya sedang hijau. Jadi, keduanya buru-buru menyeberang.
“Kau tahu apa maksudnya.” Mai berujar. “Aku sudah cerita soal Keita. Kau sendiri bagaimana?”
Ritsuka hanya menanggapi dengan tawa ringan. Dia paham apa maksud Mai, tapi anak itu pura-pura tidak tahu. Dan karena ini, Mai mendengus.
“Hei, hei. Rahasia, nih?”
Tidak ada jawaban dari Ritsuka. Cuma tawa dan kibasan tangan ringan. Mai mulai tidak sabar.
“Aku memperhatikan, loh!”
Alis Ritsuka naik satu. “Memperhatikan apa?”
“Ritsuka selalu jadi pasif kalau bahas hal-hal semacam urusan hati dan yang semacam itu. Seperti cari aman.”
“Ma-masa?” Ritsuka mengalihkan visi ke seberang jalan. Ada toko kue yang sedang gelar diskon untuk pembelian cheese cake. Apa besok mampir saja kesitu—
HAP!
Pipi Ritsuka ditangkap Mai.
Anak perempuan itu menatap Ritsuka intens. Curiga. Curiga. Curiga.
Ritsuka mengkeret. Muka Mai yang begitu lumayan membuatnya merasa terpojok. Perempuan berkuncir kuda itu kemudian menghela napas.
“Oke. Oke.”
Kibaran bendera putih dari Ritsuka tak pernah membuat Mai sebahagia ini. Jadi, kira-kira siapa? Mai bertanya-tanya. Apakah itu Handa si bendahara OSIS? Atau justru Hayakawa, kakak kelas pentolan kelab sepak bola yang dulu pernah mengajak ngobrol Ritsuka di kelas? Siapa? Siapa? Mai ingin tahu.
“Tapi mungkin Mai akan ketawa kalau dengar ….”
“Apa aku menertawakan Erika waktu dia bilang naksir sama adik kelas?” Mai menjawab cepat. Begini-begini, dia pantang menertawakan pujaan hati orang. Serius. Apa haknya?
Ritsuka menggaruk pipi kanan. Rasanya canggung sekali waktu dia membuka mulut dan bilang, “Uh, aku rasa … aku suka Hajime-kun ….”
Ada dua nama Hajime di sekolah mereka. Mai mengingat-ingat sejenak, lalu dengan cepat mengambil konklusi dalam satu jentikkan jari.
“Oh? Hajime Miura yang dari kelab atletik itu? Aku jarang lihat dia, sih. Tapi menurutku memang lumayan ganteng—”
“Bu-bukan! Bukan Hajime yang itu!”
“Bukan?”
Ritsuka menggeleng-geleng cepat. Mukanya begitu kikuk. Pipinya memerah tanpa alasan yang Mai tahu pasti.
Tunggu, Mai menggumam dalam hati. Nama Hajime cuma dua di sekolah. Kalau bukan Hajime Miura yang itu, berarti—
Berarti—
Mata Mai membulat seketika.
“Heeeeeee!? Hajime Shirokami!?”


 November
November