"Ujang! Kita main ke sungai yuk!"
Dani berseru keras di belakangku, dekat tukang bubur. Orang-orang yang sedang sarapan bubur merasa risih dengan suaranya. Beberapa dari mereka hanya melihat Dani dengan tatapan sinis. Bahkan ada juga yang kelihatannya memaki Dani. Dia tidak peduli. Benar, bagi kami makian dan ejekan mereka tidak berarti apa-apa. Sudah biasa.
Dia berlari menghampiriku. Napasnya tersengal.
“Yang lain mana?” Aku bertanya basa-basi, sebenarnya aku tau mereka sedang melakukan apa.
“Biasa lah, paling Ajat sama Asep lagi jual hasil mulung. Pak Wasid katanya lagi baik. Dia kasih kita uang tambahan setiap nimbang disana.”
“Beneran? Aku banyak rongsokan di gubuk.”
“Wah! Jangan ditunda-tunda tuh. Kamu tau kan Pak Wasid itu kadang baik kadang jahat.”
“Ehm!”
Aku berlari menuju gubuk kecil tempatku berteduh dari terik dan hujan yang terbuat dari karton bekas. Sendirian. Kadang Dani, Ajat dan Asep menemaniku bermalam sambil menyantap beberapa ikan bakar yang kami curi dari tambak milik warga. Atau jagung bakar yang kami curi dari pasar diam-diam. Ketika lapar tiba, kami memang harus melakukannya.
Dani mengikutiku dari belakang. Sesampainya di gubuk, dia membantuku membawa beberapa karung besar berisi rongsokan yang bisa dijual seperti gelas plastik, kaleng, karton, dan koran bekas. Semuanya ada tiga karung besar. Aku membawa karung berisi koran dan karton yang lebih berat. Yang agak ringan, karung berisi gelas plastik dan kaleng bekas dibawa Dani.
Sepanjang jalan menuju rumah Pak Wasid, ramai orang-orang yang sedang menikmati keindahan kota Bandung. Mereka sibuk mengambil gambar dengan kamera-kamera canggih yang tak pernah aku menyentuhnya. Salah satu dari mereka menatapku lamat-lamat, lalu cekrek! Dia memotretku dan Dani yang tengah menarik karung besar saking beratnya.
Kupercepat langkah kakiku. Entah kenapa aku merasa sedikit marah setelah orang itu mengambil gambarku tanpa izin. Dani malah tertawa bangga ada orang tak dikenal mengambil gambarnya. Mungkin dia merasa seperti artis yang sering dipajang fotonya di pinggir jalan untuk model iklan produk-produk makanan.
“Kunaon Jang?” (Kenapa Jang?) Dani menyusulku dari kanan.
Aku menggelang tanpa sepatah katapun. Bukannya tidak mau menjawab. Hanya saja aku tidak tau harus menjawab apa.
Dani menghela napas, memalingkan wajahnya dariku.
Rumah pak Wasid penuh dengan gelandangan lainnya. Mereka ramai menjual hasil memulungnya. Semuanya berebut mendapat tempat paling pertama. Untung saja Pak Wasid sedang baik. Kalau tidak, mungkin semuanya kena gampar. Pak Wasid kalau sudah baik, akan baik sekali. Dan kalau sedang menyebalkan, dia tidak akan segan-segan melayangkan tangannya ke pipi kita.
Aku menunggu sampai kerumunan gelandangan ini surut. Duduk selonjoran dibawah pohon mangga milik Pak Wasid. Dani tidak banyak berbicara. Dia asyik bersiul menyanyikan lagu-lagu yang sedang banyak diputar akhir-akhir ini.
“Ujang! Dani! Buru Kadieu!” (Cepat kesini!) Teriak Pak Wasid sambil melambaikan tangannya. Suara tegasnya khas, membuat kami akan bergegas menghampirinya sebelum dia marah.
Dani menyerahkan karung berisi gelas plastik dan kaleng bekas. Pak Wasid menimbangnya. Setelah ketauan beratnya, dia lalu mengeluarkan isinya dan mengembalikan karungku. Begitu juga dengan karung yang berisi koran dan karton bekas yang kubawa. Pak Wasid mengeluarkan kalkulator dari tas kecil di pinggangnya, lantas menghitung berapa rupiah yang akan dia berikan.
Jumlah uang yang kudapat hari ini cukup besar. Semuanya enam puluh ribu.
“Tabunganmu sudah banyak Jang. Yang ini mau ditabung juga atau dibawa semua?”
“Tabung saja pak.” Jawabku sekenanya.
“Nanti kalau uangnya sudah cukup buat modal usaha, mau dibelikan apa dulu?”
“Bu… buat beli gerobak pak. Ujang mau jualan gorengan.” Dani menertawakanku yang menjawab kaku. Maklum, aku segan pada pak Wasid.
“Wah! Bagus bagus. Ya sudah, pergi sana mulung lagi.”
Gelandangan di daerah ini cukup beruntung memiliki pengepul sebijaksana pak Wasid. Bisa dibilang dialah yang mengurus kami. Dia yang membantu kami mempersiapkan kehidupan esok yang lebih baik. Gelandangan seperti kami memang tidak tau apa-apa. Yang kami tau, memiliki uang banyak adalah impian terbesar.
Sejak tiga tahun terakhir pak Wasid mendirikan bank sampah. Dia menampung hasil kami memulung. Lalu uangnya ditabung agar tidak kami gunakan untuk berfoya-foya. Beberapa gelandangan yang lebih tua dariku sudah sukses memiliki usaha dengan modal memulung rongsokan dari tempat-tempat sampah dan sungai Cikapundung. Semuanya diurusi pak Wasid.
Aku mulai menabung sejak setahun yang lalu. Setiap menimbang rongsokan, aku tidak pernah mengambil sepeser pun rupiah dari hasil memulungku. Semuanya kutabung. Masalah perut, itu masalah nanti. Dua hari tanpa makan pun aku sanggup. Atau kalau tidak, kami berempat mecari makan dari sisa-sisa makanan orang lain. Atau mencuri di pasar Tegalega.
Usai menimbang hasil memulung, aku dan Dani segera menuju sungai. Ajat dan Asep sepertinya sudah berada disana. Saat masih di rumah pak Wasid kami tidak bertemu, entah aku tidak melihatnya atau mereka sudah pulang duluan sebelum kami sampai.
Ternyata benar. Ajat dan Asep sudah duluan ada di sungai. Dani melompat dari atas sambil bergaya. Kami semua tertawa gelak melihat aksi Dani. Tinggal aku yang belum basah. Ajat menciprat-cipratkan air ke arahku. Memaksaku melompat. Aku agak takut ketinggian. Jarak dari tampatku berdiri ke muka sungai sekitar tiga meter. Airnya memang tidak terlalu dalam, mungkin hanya satu setengah meter. Hanya saja bebatuan besar di tepi sungai cukup membuatku takut, kalau-kalau kepalaku malah terbentur mengenainya.
Sambil memberanikan diri, aku mencoba melompat ke muka sungai. Twing. Aku melompat salto seperti anak-anak laut. Menirukan foto mereka yang pernah kulihat di salah satu koran bekas yang kupungut dulu. Bruss! Aku basah kuyup di tengah sungai kebanggaan masyarakat kota Bandung ini.
Main di sungai adalah agenda rutin kami setiap hari. Disini ada banyak rejeki yang bisa kami dapatkan selain hanya bermain air. Terkadang kami bisa mengumpulkan sekarung rongsokan dari aliran sungai. Atau bahkan ikan gurame berukuran besar yang bisa kami santap berempat.
“Enak sekali ya menjadi mereka. Tidak stres dengan beban tugas rumah atau kerja kelompok.” Ucap salah satu anak SMP sebayaku yang lewat. Telingaku jelas mendengarnya.
Kami sudah biasa mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Rasanya ingin kubalas. Tapi Asep yang paling tua diantara kami, selalu melarang kami bermasalah dengan orang-orang seperti itu. Anak-anak manja seperti mereka bisa saja menyuruh ayahnya untuk mengirim kami kemanapun mereka mau. Apalagi gelandangan sepertiku yang hidup sebatang kara. Tidak mungkin ada orang yang akan mencariku.
Aku yang gelandangan saja ingin bisa sekolah lagi seperti mereka. Mengerjakan tugas saat malam tiba. Dan kerja kelompok sepulang sekolah. Seperti dulu. Tapi, ucapan keluh kesah mereka membuatku bingung. Apa yang salah dengan hidup berkecukupan. Apa mereka tau, apa yang kami makan untuk mengganjal perut? Apa mereka tau sulitnya mencari rupiah di jalanan tanpa ijazah? Atau, apakah mereka tau perihnya tidak makan selama dua hari?
Jika mereka tau, aku yakin mereka tidak akan mau menjadi kami.
<<<>>>


 AyPurnama
AyPurnama




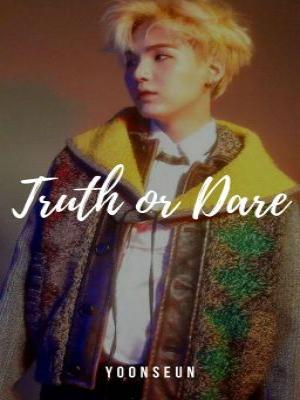
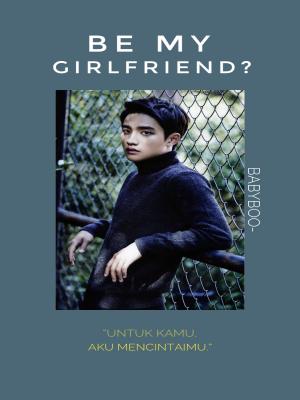




@Itikittiy aku masih muda kok kwkwk
Comment on chapter Rongsokan