Hai....
Sebelumnya aku minta maaf karena ada kesalahan Part. Jadi, part 7 (tahu diri) itu harusnya menjadi part 8, dan part 7 yang sebenarnya di upload berbarengan dengan part 9 ini. Jika teman-teman merasa ceritanya seakan loncat, silahkan baca ulang part 7 yang baru aku upload.
Sekali lagi aku mohon maaf 
Dan terimakasih juga untuk para pembaca hingga part ini. Semoga bisa memuaskan pembaca. Jangan lupa komen, like, dan share juga
Cheers,
SR
.
.
.
Semenjak ‘berbincang’ dengan Mila beberapa hari lalu, aku masih merasa kecewa pada diriku sendiri. Menandai diriku sebagai orang yang tak tahu diri, yang tanpa sadar terus berjalan menuju pintu hati Davi, dan tak bercermin sebelumnya. Aku melupakan semua itu, melupakan niat awalku bersekolah di sini.
Apa ini yang disebut cinta buta? Jika memang benar, harusnya aku tidak lengah ketika cinta, atau mungkin perasaan suka ini, menutup indra penglihatanku. Kata cinta sepertinya terlalu berat di dengar. Perasaanku belum setinggi itu.
“Kamu kenapa sih beberapa hari cemberut terus?” tanya Citra ketika kami berempat janjian membawa bekal hari ini.
“Iya. Kunaon sih?” tanya Mia yang artinya ‘kenapa sih?”
“Gak apa-apa,” dustaku. “Siapa juga yang cemberut?”
“Ti kamari kamu jamedud wae, ngalamun wae. Pasti aya masalah pan?” tanya Mia lagi dengan logat Sundanya yang khas itu. ‘Dari kemarin kamu keliatan cemberut, ngelamun aja.’
Aku sedang terbawa suasana, hingga sahabat-sahabatku pun menyadari ada perubahan dari diriku.
“Lagi PMS kayaknya,” jawabku asal.
Prisil tak menodongku dengan pertanyaan seperti Mia atau Citra. Ia hanya menepuk pelan pundakku, dan aku hanya bisa tersenyum menanggapinya.
~KALA SENJA~
Sepulang sekolah, Citra mengajak kami untuk jalan-jalan di daerah Braga. Tapi aku menolaknya, aku sedang berada dalam mood yang tidak begitu baik, dan aku ingin sendiri.
Aku berjalan-jalan di sekitar Taman Lansia, itulah judul yang terlihat di depan taman yang baru direnovasi beberapa bulan lalu itu. Meski banyak yang diperbaiki, namun rindangnya pohon-pohon masih terawat persis sebelum renovasi dilakukan.
Biasanya di sore hari banyak anak-anak yang sedang bermain-main di sini, atau para lansia yang berjalan kaki menikmati sore harinya Kota Bandung. Mungkin itu alasan kenapa taman ini disebut Taman Lansia.
Aku duduk di salah satu kursi yang menghadap ke arah kolam ikan yang cukup besar itu. Anak-anak yang sedang bermain-main tadi terlihat sedang melihat lihainya ikan-ikan yang sedang berenang itu, di selingi oleh beberapa kejahilan khas anak kecil.
“Kamu di sini juga?” suara familiar itu mengalihkan pandanganku. Sosok itu kini duduk di sampingku.
“Davi?” kataku tak percaya.
Davi duduk di sampingku, lengkap dengan pakaian seragamnya. Ia tersenyum melihatku, sementara aku merasa canggung bertemu dengannya. Bagaimana tidak. Sumber kebimbangan, kegalauan, kesedihanku beberapa hari lalu adalah ketua kelasku sendiri, yang kini muncul bagai pahlawan super yang datang tiba-tiba.
“Ngapain?” tanyanya.
“C-cuma, duduk aja,” jawabku gugup mencari-cari alasan yang tak masuk akal. Davi juga tahu jika aku sedang duduk sekarang. Duh, Tasya!
“Hahaha….” Davi kembali tertawa. “Biasanya aku juga sering nongkrong di sini,” katanya. “Karena aku gak penah ketemu sama anak-anak di sekolah kita, jadinya tempat ini cocok buat menyendiri, sambil mikirin masalah sendiri,” katanya lagi dengan cengiran khasnya.
“Ohh, kayaknya aku ngejajah tempat kamu ya?” tanyaku tidak enak.
“Gak apa-apa, tempat ini juga bukan punya aku. Lagian aku ketemunya sama Tasya, gak apa-apa kok.”
Niatku untuk pergi akhirnya kuurungkan. Meski degup jantung ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi kali ini aku tak mau beranjak pergi dari Davi, entah apa maksudnya, hanya saja aku tak ingin momen ini menjadi singkat.
Sambil menikmati semilir angin dan bisikkan dedaunan yang bergesek dengan ranting, kami menikmatinya tanpa bersuara. Mendengar suara nyaring anak-anak tadi tak membuat suasana ini menjadi rusak.
“Kamu gak apa-apa kan?” Kini Davi mulai bertanya. Meski tak menatapku, tapi aku yakin Davi sedang bertanya padaku.
“Soal apa?” tanyaku balik.
“Kamu,” jawab Davi sambil menoleh padaku. “Aku lihat Tasya gak selincah biasanya,” katanya lagi.
Aku tertawa sekilas ketika Davi mengatakan lincah.
“Nah kayak gitu,” kata Davi. “Aku biasanya sering liat Tasya yang kayak gitu. Ketawa bareng anak-anak lain.”
Aku berharap Davi memang memperhatikanku seorang, sayangnya Davi tipikal laki-laki yang supel dan sadar akan lingkungan sekitarnya. Harapanku itu terlalu tinggi.
Tapi dari pertanyaan Davi itu, aku ingin jelas-jelas menanyakan pendapat Davi mengenai ucapan Mila beberapa hari lalu, tentang pandangannya terhadap siswa terlampau biasa-biasa saja sepertiku ini.
“Boleh aku tanya sesuatu?” tanyaku.
“Anything.”
“Kalau kamu baik sama seseorang, tandanya kamu kasihan sama dia?” tanyaku. “Maksudnya semacam mengasihani orang tersebut.”
“Hmm….” Davi terlihat seperti patung karya Auguste Rodin yang tengah berpikir itu. “Kasihan sih, tapi gak maksud buat mengasihani,” jawab Davi. “Gimana ya jelasnya? Misalnya, waktu kamu di tampar sama Kak Rio, aku gak suka aja liatnya. Tiba-tiba marah, kesel, pokoknya gak enak deh kalau aku diem aja dan gak nolongin kamu. Tapi setelah aku nolong kamu, rasanya ada kelegaan, Sya. Rasanya lega karena udah bantu orang, semacam itu.”
“Bukan karena mengasihani?”
“Nggak sih. Bukan karena kasihan, karena gak suka, gitu loh, Sya. Ngerti gak sih omongan gak jelas aku ini hahaha….”
Aku mengangguk, “Iya ngerti kok ngerti.”
“Emangnya ada apa?”
“Cuma minta pendapat. Kadang aku ngerasa rendah diri, selalu ngebandingin diri sendiri sama orang lain, padahal gak boleh.”
“Jangan merasa rendah diri karena perbedaan yang kamu buat sendiri. Kita semua sama kok di mata Tuhan.”
Aku sedikit tersenyum mendengar ucapan Davi barusan. Aku sempat berpikiran sempit tentang Davi, membuat perbedaan yang kubuat sendiri. Padahal tak ada seorang pun yang mengerti bagaimana jalan pikir orang lain.


 cintikus
cintikus


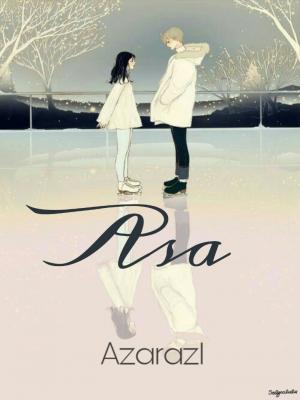

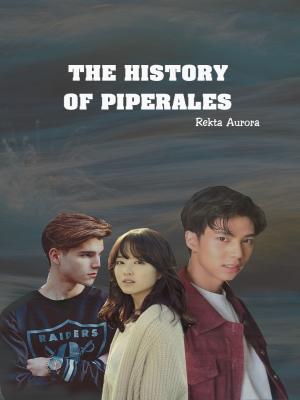




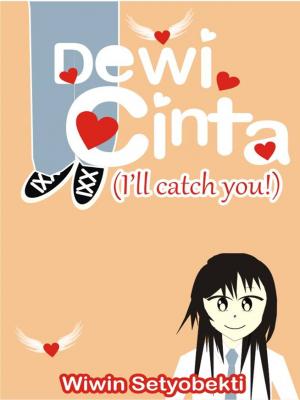
ka jangan lupa mampir untuk bantu vote ceritaku https://tinlit.com/view_story/1078/1256
Comment on chapter Satu Kelas