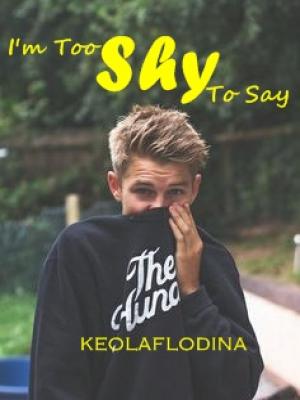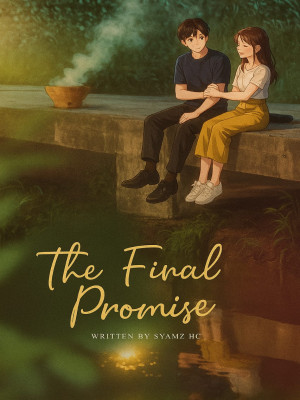Aku mengenalmu cukup lama, sudah 5 tahun lebih kurasa.
“Aku dengar rumahmu di Sektor H ya?”, ia kembali membuka percakapan kami yang sempat mengering. Tidak ada tolehan, apalagi adegan saling menatap layaknya obrolan dua orang baru kenal. Manik kami masih terlalu asik menelanjangi setiap helaian rumput hijau pinggir jalan. Mencari selimut perak bekas makanan ringan yang tak ‘disemayamkan’ dengan semestinya. “Tempat itu hanya berjarak 100m kurang dari rumahku kau tau?”, ia menyambung kalimatnya sesegera mungkin, sperti penjahit dengan benang putusnya. Bahkan aku tak sempat memberikan respon untuk pertanyaannya, retoris.
Otakku terlalu lambat, kaliamatnya terlalu cepat. Butuh waktu lebih dari 7 detik untukku membuka suara waktu itu, “Kau berada di Sektor I?”, Nihil. Hanya itu yang dapat aku keluarkan. Padahal siapapun tau pasti kedua sektor itu memiliki jarak lebih dari angka yang meluncur dari mulutnya.
Ah, mungkin sebantar lagi dia akan menjahui ku. Maksudku, hei, siapa yang ingin satu kelompok apalagi berkawan dengan bocah laki-laki pemalu dan ‘belum’ pintar sepertiku?
Tepat setelah aku bertanya, kupingku taklagi mendengar suara langkah miliknya. Sol sepatunya berhenti menggesek permukaan jalan. Bahkan kantung plastik hitam pada tangan kanannya juga sudah tak lagi berjarak dari tanah. Gaya gravitasi seolah mengambil alih sekarang, “Tidak…”,ia menjawab pelan. Dari ekor mataku aku sempat melihatnya tersenyum, tipis dan singkat. “Kita istirahat disana ya!”, setengah berteriak, suaranya mengisyaratkanku untuk menoleh, mengikuti jari telunjuknya yang terjulur.
Hamparan rumput hijau di bawah pohon asam? Sepertinya dia punya selera tinggi. Bagus juga.
Pertemuan kita tidaklah seelit drama korea kesukaannk. Bukan karena tabrakan tak sengaja atau kau yang membantuku mengejar pencopet, cerita kita tidak sesempurna itu.
Kita pertama kali bertemu dalam sebuah acara Car Free Day kota.
Apakah kau masih mengingat pertemuan klise kita?
“Kau harus lebih banyak bergaul,”,aku menoleh kearah kiri, mataku menangkap sosoknya. Ia memainkan rumput diantara kami. Tangannya yang bebas dari borgol kantung sampah plastik, kini dengan elitnya membelit serumpun daun tanpa tulang itu . Mengancam keberlangsungan hidupnya, “Jangan hanya melototin benda mirip kapsul yang biasa kau mainkan di depan rumahmu saja.”, tak. Tamatlah sudah cerita hidup si rumput tak berdosa, tercabut dari dalam tanah beserta akarnya.
Jujur, aku mulai takut dengan gadis ini! Bagaimana tidak? Dia bisa melampiaskan kekesalannya pada apa saja?! Bahkan pada rumput tak bersalah sekalipun!
Kuteguk ludahku, mencoba membasahi kerongkongan yang entah mengapa mendadak kering kala itu. “S-siapa ya-yang…Mak-maksudku.. A-aku tidak…”,
Eh?! Tunggu rasanya ada yang salah!
”Apa kau berada satu sektor denganku?”, tanyaku dengan wajah polos. Bahkan rambut acak-acakan yang kupikir keren hanya menambah kesan ketidak pekaanku. “atau jangan-jangan…” sebersit bayangan tiba-tiba melintas dalam otak kecilku.
“Jangan berpikiran macam-macam jika kau tak ingin menerima pukulan dari ku”, seolah bisa membaca pikiran ia menatapku penuh selidik. Diam. Bahkan bergerak satu milipun rasanya aku tak sanggup. Gadis ini mengerikan. Wajah imutnya seolah hanya topeng belaka. Itu pelajaran yang kudapat darinya.
“Dengar…”, ia kembali membuka suara. “Aku bukan mata-mata seperti apa yang kau pikirkan.”, ia menoleh padaku, menampik kenyataan betapa terkejutnya aku.
Darimana dia tau isi kepalaku?!
“Aku anaknya Ibu Dhira, tetangga depan rumahmu.”, kalimatnya kembali memancing pergerakan aliran listrik dalam tubuhku. Mata membulat, mulut terbuka. Aku masih mengingat air mukaku. “Catat itu, tuan tidak peka!”, kalimat terakhirnya begitu singkat, jelas, dan tepat sasaran. Cukup untuk melunturkan asumsi terakhirku.
Esoknya, ia datang ke rumahku. Dengan cengingiran khas dan rambut ikal yang dikuncir kuda, ia menemui ibuku−entah sejak kapan dekat dan bahkan dekat dengannya−meminta izin untuk mengajakku bermain. Bukannya menolaknya ibuku justru.. bahagia, “Akhirnya anakku dapat teman juga. Trimakasih Nona, anak tante bakal mau kok, yakan kak?”, Ibu berujar lega. Seolah ada beras sekarung di atas bahunya yang baru saja diangkut pergi.
Yarabb… Aku juga punya teman ibu. Memang tidak ada di sini, tapi di sekolah banyak.
Hari itu aku terpaksa mengikutinya. Lari sana lari sini, kejar sana kejar sini, ngumpet sana ngumpet sini. Asli bikin capek! Bahkan besoknya dia kembali mengajakku bermain, begitu terus, sampai rasanya aku sudah jarang sekali berdua sama PSPku. Menyebalkan sih, tapi… kenapa aku tersenyum?
Aku berharap kau masih mengingatnya. Sama seperti aku yang selalu mengingat wajah ‘lolamu’ kala itu.
Hey, Nona!
Sebenarnya, berapa liter bensin yang sudah kau habiskan untuk mengangkutku setiap sore?
10, 20, 50? Sepertinya kalkulasinya lebih dari itu.
‘Rumah kita saling bertatap muka.’. ‘Kita berada pada SMA yang sama.’, ‘kasian ibumu kalau tiap hari ngejemput kamu terus’, ‘kamu kan belum punya SIM’. Itulah 3 alasan kuat yang membuatnya bersikukuh memberikan tumpangan padaku. Segak enak apapun aku. Sekeras apapun aku menghindar. Bahkan setegas apapun aku memaparkan penolakanku. Nona akan selalu sama. Diam namun selalu menanti kepulanganku disetiap sorenya.
Kadang aku bahagia kalau-kalau Nona ada jam tambahan di sekolah−itu artinya aku bisa pulang tanpa merepotkannya, tapi pasti dalam situasi ini ia akan menghampiri gedung Sosial 1 , menemuiku, dan mengeluarkan dekrit andalannya. “Jangan pulang dulu”. Hanya 3 kata. Namun, penaatannya adalah harga mutlak bagiku.
“Astaga, Gilanggg,”,tak perlu melihat manusianyapun aku sudah tau siapa yang memanggil. Suaranya cukup untuk membuatku kembali dari kayangan. Jatuh ke bumi. Kembali ke dalam raga seorang remaja bernama Gilang yang tengah duduk menyamping di atas motor Hitam milik anak tetangga depan rumah. “Sampe kapan kamu mau terus ngikut sama Nona? Sampe kamu lulus? Ato sampe kamu kuliah”, ujar Willi seraya berjalan kearahku.
Kalimatnya seolah memilik daya tarik kuat yang tak bisa kuabaikan. Refleks kuangkat wajahku untuk membingkai figure kawan sekelas yang hendak mengambil motor, Vespa hijau yang terparkir dengan apiknya di sebelah motor Nona. “Ayo dong, kamukan cowok. Masa’ iya nebeng terus sama cewek. Malu tau, kesannya kayak kamu gak bisa apa-apa.”, ia memasukkan kunci kedalam motor kesayangannya sedangkan telingaku dalam kondisi awas−menyimak setiap katanya. Alih-alih memperingatkan dia yang nyaris menyenggol Nona saat memutar stangnya, aku justru menunggu kalimatnya lagi. “Sekedar saran sih, pake motor jelekpun tak apa, yang penting gak nebeng cewek.”. kini Wili sudah berada di atas motornya. Siap melaju dengan motor dua taknya, “Oke, aku pulang, dada, Lang~”, selanjutnya aku hanya mendengar mesin motor yang berderu. Meninggalkan aku yang kembali tenggela dalam lamunanku.
Aku selalu suka mengingatnya!
“Nona”, dari bangku penumpang aku menyebut namanya. Berusaha mendapat minimal sepertiga perhatian dari gadis manis yang berada dibelakang stir kemudi itu. Harap-harap cemas aku menunggu tanda darinya.
Kecepatan motor sedikit berkurang, “Iya? Apa, Lang?”, kini fokus Nona terbagi.
Rentetan doa aku panjatkan. Takut-takut aku kembali berniat membuka suara. Menyusun kalimat padu agar gadis ini tidak tersakiti, namun bisa menubah keputusannya. Maka setelah tarikan nafas panjang aku mengutarakannya, “Nona, Simku besok jadi.” Dari kaca sepion aku melihatnya, wajahnya begitu tenang saat berkendara. “jadi aku akan mulai membawa kendaraan sendiri. Kau tidak perlu lagi menjemput atau mengantarku. Bagaimana Nona?” Sambungku kemudian.
Sayup-sayup aku mendengarnya mendesah, “Itu kabar bagus.”, ia kembali menambah laju motornya, ”Itu sudah keputusanmu.”, jawabnya kemudian. Entah kena angin apa sampai aku tak mendapat bantahan keras−seperti biasa−darinya.
Tapi, bukan itu yang ingin kusampaikan. . .
Aku sudah tidak menumpang lagi pada Nona. Itu berita besar, bahkan satu IPS menyelamatiku−entah aku harus bahagaia atau bagaimana. Tapi, bagai koin dua sisi, keputusanku juga berimbas buruk padaku. 3 hari sudah Nona mendiamkan dan menghindar dariku.
Seolah tak memiliki celah untuk saling berbicara, kami kembali ke titik nol. Siapa sebenarnya yang menekan tombol ulang diantara kita?
Hanya ada sebuah pesan singkat yang ia kirim tadi malam,−dan parahnya aku belum membaca pesan itu.
Kau bukan lagi dirimu yang dulu aku temui. Bocah laki-lagi lamban.
Maka sekarang, saat jam istirahat aku berdiri disini. Di depan Sains 4−kelas Nona, menantinya keluar kelas untuk sekedar mengobrol sebentar. Membicarakan isi pesannya semalampun takapa. Barang 5 menit saja aku ingin mendengar dialek khas miliknya. Menteraktirnya mie ayam kantinpun tak apa, asal suara tawa dapat dengan mudah lolos dari bibirnya.
Entah sejak kapan aku candu akan bahakannya.
Kau juga bukan bocah lemah yang hanya memandang dunia dari teras rumahmu .
“Cari siapa, lang?”, teman sekelas Nona menghampiriku.
Kutegapkan badanku yang mulai membungkuk, “Cari Nona.” Jawabku singkat. Ingin segera bertemu Nona.
“Loh? Kamu gak tau ya? Berarti bener dong ya kata anak-anak... kamu putus sama Nona,”, airmukanya sedikit terkejut. Aku lebih terkejut. Siapa juga yang pacaran sama siapa? Lagipula apa-apaan kalimat ambigunya itu.
Aku menggeleng. Malas memperpajang maslah lebih tepatnya.
“Nona tadi pulang, bedannya panas .”
“Sama siapa dia pulang?”
“Sendiri.”, mendadak firasat tak karuan hadir dalam pikiranku. Mengiang-ngiang layaknya rumus Matematika wajib. “Habis, mau dianter, dia ngotot pingin sendiri. Katanya gak mau ngerepotin orang lagi. Kayaknya dia trauma, deh”
DEG! Apakah hujan hendak turun? Karena jujur saja aku seperti disabet petir barusan.
“Kapan dia balik?”
“Baru aja sih tap- Gil Gil Gilangg“ telat, aku sudah menghilang dari sana. Meluncur dengan cepatnya menuju kelasku. Mengambil kunci motorlah tujuanku. ARGH! Rasanya aku ingin membanting sesuatu. Bagaimana bila hal buruk terjadi pada Nona di jalan? Kenapa pula anak itu keras kepala sekali?
Kamu sudah banyak barubah,banyak, sangat, amat, berubah.
Bukan perubahan buruk kok!
Tapi… Seperti seekor ulat, kini kau sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Bahkan lebih kuat malah
Beberapa adik kelas yang bersimpangan denganku di jalan mengernyitkan dahi mereka. Bingung dengan kelakuan kakak tingkat 3 mereka yang tiba-tiba berlari di koridor.
Rasanya aku sudah tak peduli apa-apa. Sekarang prioritasku adalah Nona. Titik. Ah, kalau saja aku tetap ikut dengannya. Kalau saja aku tidak gengsi hanya karena masalah tebengan, kalau saja aku ada bersamanya, kalau saja waktu bisa diputar, kalau saja, kalau saja, kalau saja, terlalu banyak kalau saja hingga aku hampir lupa cara berjalan dengan benar.
Aku mulai merasakan Liquit bening merembes melalui ujung mataku. Terlalu berat. Perasaanku rasanya benar-benar campur aduk saat ini. Berkecimpung diantara marah, sedih, dan tak percaya. Mereka seolah mengelilingi ku, menamparku dengan koherensi mereka yang disebut rasa “pahit”. Aku mengenal nona sudah lama, namun kenapa aku baru sadar kalau Nona adalah salah satu sosok yang harus ku lindungi. Bila Nona terluka sedikir saja, aku takkan berani menunjukkan wajahku didepannya.
Masih berlari menuju parkiran motor yang agak jauh dari gedung utama, aku kembali mengambil benda persegi yang sepat kuabaikan tadipagi itu dari kantongku bajuku. Kutekan 12 digit nomer yang telah kuhapal mati itu.
Jadi, kalau kau mendengarkan celotehan mereka, kau salah.
Aku yang butuh kamu, bukan kamu yang butuh aku.
Ini sudah yang ke 4 kalinya. Hanya ada nada sambung yang tak kunjung mendapat sahutan. yaampunn.. semua ini salahku.
Saat aku hendak menyudahi aksi telpon-telponan ini dan menaruh hpku kedalam tas, aku baru teringat sesuatu. Nona mengirimkanku pesan. Maka di depan gerbang sekolah dengan tergesa-gesa aku membuka deretan kata dalam bungkus amplop di hpku itu.
SKAK!
Rasanya dunia barusaja berputar, kata-kata yang Nona kirimkan padaku seolah menunjukkan betapa ‘tak tahunya aku’
Saat aku sampai keparkiran. Saat aku hendak memacu kuda besiku dan mengelearkannya sesegera mungkin dari kandang luasnya, aku baru sadar satu hal. Di samping motorku, jarak dua motor. Seorang gadis dengan rambut ikalnya tengah duduk meneku lutut di rumput parkiran. Wajahnya memang tak nampak, karena ia menyembunyikannya di sela-sela lututnya. Dari postur badannya dan motor Hitam di depannya aku sudah bisa memastikan siapa gadis itu.
Cukup dengan tanda kecil itu saja aku sudah bisa bernafas lega.
Maaf selama ini kamu terus menjadi korban keegoisanku.
Maaf selama ini aku hanya membuatmu menerima anggapan miring
Maaf karena aku tak mampu. . . .
takmampu melihatmu di depan atau belakangku…
Maaf karena aku hanya mampu.. melihatmu ketika di sampingku…
“Sampai kapan Kau mau disitu. Ayo pulang”
Mengangkat kepala “Gi-Gilang? Sejak kapan…?”, wajahmu pucat pasi. Begini mau pulang sendiri?
Aku merunduk, menyetarakan tinggiku dengan posisi dudukmu, “Nanti saja. Sekarang ayo kita pulang”, kuulurkan tanganku. Nona tampak ragu sesaat sebelum akhirnya menerimanya.
“Tapi kali ini biarkan aku yang membawa kendaraannya... ah, jadi.. jangan bawa motor lagi, biar aku yang menjadi Ojekmu dari sekarng hingga seterusnya.”


 Kucing_Terbang
Kucing_Terbang