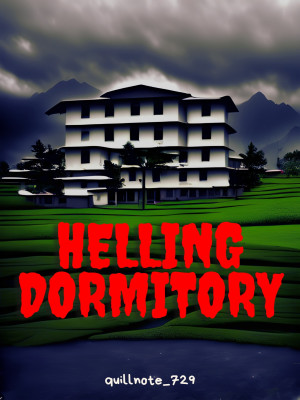Setiap manusia pasti pernah merasakannya. Seperti tumor ganas yang akan menggerogoti hatimu hingga tak mampu bertahan. Satu hal yang tak kau temui di seluruh penjuru dunia. Kecuali pada tatapnya. Suatu ketika kau mungkin akan membencinya dan membuangnya jauh-jauh. Tetapi, seberkas ingatan membawa paket rindu itu kembali padamu. Ya, rindu. Siapa yang tak pernah merindu? Mungkin ia tak memiliki rasa dan acuh pada lingkungan sekitar. Kalau dipikir-pikir, tentu takkan ada manusia seperti itu. Tetapi, aku pernah bertemu. Dia yang dingin, keras kepala, dan egois. Dan bodohnya, aku malah merindu. Tentu saja dia takkan tahu. Sebab, batu tak memiliki rasa.
Semua berawal dari hari pertama aku bergabung dengan klub rasa. Sebuah klub beranggotakan mereka yang pernah terjatuh tanpa tahu cara bangkit, yang merindu tak berujung temu, dan yang tersesat tanpa tahu jalan pulang. Mereka yang memiliki hati lebih besar dari manusia pada umumnya. Dan memiliki lebih dari dua mata, yakni satu mata yang berada pada hatinya dan disalahgunakan untuk melihat masa lalu.
Aku kira semua orang yang bergabung di klub ini memiliki rasa, keramahan, dan toleransi yang luar biasa. Tapi nyatanya, ada seorang yang sudah tak memiliki rasa dan kepercayaan, hingga dia kaku sekeras batu. Dia ditinggalkan seseorang yang amat disayanginya untuk selamanya. Sehingga dia tak percaya lagi pada rindu yang tak kunjung temu. Namun kuyakini dia hebat. Mengalahkan ego dan berusaha sekuat hati untuk tidak mengakhiri hidupnya demi rindu yang berujung temu. Teman-teman memanggilnya Nagara. Dia introvert, tapi aku suka. Cara dia bertanya, mengungkapkan pendapat, juga tatapannya.
Sore itu pertama kalinya aku mengikuti diskusi bersama klub rasa. Bertempat di sebuah café yang tak jauh dari taman kota. Seorang wanita berperawakan kecil dan pendek dengan rambut sebahunya yang dibiarkan terurai itu menyambutku dengan baik dan memperkenalkanku pada teman-teman lainnya. Meski hanya beranggotakan sepuluh orang, perkumpulan ini cukup membuat café menjadi gaduh. Sudah dua bulan setiap minggunya café ini selalu dibooking untuk diskusi rasa.
“Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja kita mulai diskusi sore ini,” ucap wanita kecil tadi sebagai moderator. “Ada yang ingin berbagi cerita atau bertanya?” lanjutnya.
“Saya,” seorang lelaki bertatap dingin mengacungkan tangan.
“Iya silakan, Nagara,” sang moderator bernama Siva mempersilakan Nagara. Dan sejak sore itulah aku mengenal Nagara.
“Saya ingin bertanya, bagaimana bisa seseorang yang dijatuhkan dari ketinggian akan terpental lalu menjadi batu?” tanyanya dengan serius.
“Ada yang ingin menjawab?” tanya Siva.
Seorang lelaki bertubuh gempal dan memakai beanie hat mengacungkan tangan, “Tentu itu takkan pernah terjadi, Nagara. justru seorang yang terjatuh dan terpental akan hancur lebur, bukan malah menjadi batu yang sama sekali tidak bisa hancur,” ucapnya menggebu-gebu.
“Kau tidak tahu, Henri. Saya sendiri yang mengalaminya,” timpal Nagara.
“Sudah, jangan ribut. Mungkin ada teman lain yang ingin menjawab atau cukup saya akhiri sampai disini?” tanya Siva memastikan.
Aku pun memiliki hasrat untuk menjawabnya. Entah mengapa ketika aku melihatnya untuk pertama kali, aku benar-benar kagum. Tatapannya yang dingin, iris matanya secokelat hazelnut, dagunya yang tegas, hidungnya yang mancung, rambutnya yang dipotong cepak, dan warna kulitnya yang cokelat asia. Juga cara dia berbicara, pertanyaannya, dan dinginnya ucapannya entah mengapa aku suka. Sejak saat itulah, aku percaya love at first sight itu nyata adanya.
Kala itu aku masih ragu untuk mengacungkan tangan, karena aku anggota baru dan belum tahu seluk beluk setiap orang di klub ini. Jantungku berdetak semakin kencang, sedang suara detik jam juga semakin berdetak. Dengan memberanikan diri, aku pun mengacungkan tangan. Seketika pandanganku resmi bertatapan dengan Nagara. Aku pun menyadari tatapannya sedingin es.
“Kau ingin menjawab, Dinda?” tanya Siva.
“Iya. Sebelumnya terima kasih telah diberi waktu. Disini saya akan menjawab pertanyaan dari Nagara. Menurut saya, seseorang yang terjatuh dan terpental menjadi batu itu ibarat magma yang keluar dari perut bumi. Ketika dia diguncang dan terpaksa untuk menerima kenyataan yang ada. Lalu dia terjatuh, entah terjatuh di tanah ataupun di sungai. Seketika itu pula, magma yang terlingkupi udara dingin akan membeku menjadi batu yang keras dan dingin,” aku berusaha mengemukakan apa yang ada di pikiranku.
“Lalu, bagaimana caranya agar batu tersebut kembali menjadi magma?” tanya Nagara kembali.
“Sebuah endapan yang telah membatu tentu takkan bisa kembali menjadi magma. Tetapi, cuaca bisa membuatnya terkikis dan sedikit demi sedikit menjadi tanah yang gembur. Batu itu akan melunak. Pada artian sebenarnya, seorang yang memiliki hati sekeras batu, masih bisa diperbaiki meski tak sesempurna sebelumnya. Akan ada pengganti yang kembali melunakkan hatinya. Pengganti yang diibaratkan sebagai cuaca. Tentu anda mengeti maksud saya,” terus terang dariku.
“Terima kasih atas penjelasannya, Dinda. Bagaimana tanggapan anda, Nagara?” Siva kembali angkat bicara. Tetapi, nampaknya Nagara tetap terdiam dan tidak mengalihkan pandangannya dari satu titik yang ditatapnya. Tak sedikit pun aku merasa geram padanya. Aku tahu, pasti dia sedang berada dalam masa-masanya yang sulit.
Satu jam berlalu, diskusi sore itu pun diakhiri, sialnya hujan turun begitu derasnya. Sudah pasti takkan ada kendaraan umum yang lewat.
“Hei,” tiba-tiba seseorang mengagetkanku, menepuk bahuku dari belakang.
“Hai,” balasku. Ternyata dia adalah Nagara. Postur tubuhnya terlihat tegap ketika berdiri. Tingginya sekitar dua puluh centimeter di atasku. Sehingga aku perlu mendongak ketika menatap matanya.
“Nunggu jemputan?” tanyanya.
“Nggak. Nunggu angkutan.”
“Mana ada angkutan maghrib-maghrib begini? Hujan deras pula,” celotehnya.
“Ehm…,” aku semakin bingung. Haruskah aku jalan kaki? Tetapi jarak rumah dari café cukup jauh.
“Udah, gak perlu mikir terlalu panjang. Sama saya saja,” aku ingin berkata tidak perlu repot-repot, tetapi dia kembali berucap, “Saya naik mobil. Gak usah takut kehujanan. Ayo, keburu malam!” ucapnya seraya melepas jaketnya, lalu dia bentangkan di atas kepalaku, dan mengajakku menuju tempat dimana mobilnya diparkirkan.
Di dalam mobil, dia membuka percakapan, “Saya suka dengan pendapatmu tadi,” ucapnya dingin. Tapi, aku membalasnya dengan senyuman. Karena aku yakin dia bisa melewati masa-masanya yang kelam.
Sungguh kejadian sore itu takkan pernah kulupakan. Setiap hal tentangnya menjadi bagian favoritku, dan akan tersimpan baik dalam memoriku selamanya.
***
Beberapa purnama telah berlalu. Entah mengapa aku ingin menjadi cuaca agar bisa memperbaiki hatinya yang membatu. Hari itu adalah hari ulang tahun Nagara. Dia pernah bilang jika dia sangat suka puding cokelat. Setiap diskusi rasa, dia selalu memesan puding cokelat kesukaannya itu. Aku pun membuat puding cokelat spesial untuk hari ulang tahunnya, dan merayakannya bersama teman-teman diskusi rasa.
“Nggak biasanya kamu semangat bikin kue kayak gini, Din,” ucap ibu ketika membantuku melipat mika yang akan digunakan sebagai tempat puding.
“Ah, biasa saja, Bu. Aku hanya ingin memberi kejutan kecil-kecilan.”
“Yang benar saja. Ibu lebih tahu apa yang terjadi padamu. Eh, itu susu cokelatnya tambah lagi. Biar lebih enak,” timpalnya.
“Iya, Bu,” aku pun menambahkan sedikit susu cokelat pada campuran puding yang masih cair. Dengan refleks aku bertanya pada ibu, “ Menurut ibu, apakah batu dapat mengikis?”
“Tentu. Dengan perlahan cuaca akan mengubah batu terkikis menjadi tanah yang gembur,” ucapnya yakin.
***
Sore itu rencanaku berjalan lancar. Teman-teman merayakan ulang tahun Nagara dengan antusias. Mereka juga memuji puding buatanku. Tapi, bukan itu yang aku tunggu.
“Terima kasih, Dinda. Seharusnya kau tak perlu repot-repot seperti ini,” ucap Nagara dengan sedikit senyuman. Pertama kali aku melihatnya tersenyum. Aku sangat senang.
“Ah, bukan apa-apa,” kataku.
“Percayalah, Nagara. Waktu akan membantumu menjalani masa-masamu yang sulit,” ucap Henri pada Nagara. Tapi lagi-lagi, Nagara tetap acuh. Entah siapa gerangan yang selama ini bercokol dalam hatinya. Tak satupun yang tahu, kecuali dirinya sendiri.
Selepas diskusi, Nagara memintaku untuk bertahan di café. Sedang yang lain sudah meninggalkan tempat itu.
“Dinda, saya ingin berterus terang,” ucap Nagara dingin. Tatapannya setajam belati. Jantungku mulai berdetak tak karuan.
“Iya?” tanyaku.
“Jujur saja, kehilangan kekasih saya kala itu merupakan pukulan terbesar dalam hidup saya. Sampai detik ini pun saya belum bisa melupakannya. Jadi, dengan permintaan maaf yang besar, saya mohon maaf belum bisa menerimamu sebagai cuaca saya. Saya tahu, pengorbananmu cukup besar untuk membantu saya melewati masa-masa ini. Bukan berarti saya menyinggung perasaanmu. Tapi, saya hanya mengingatkan, jangan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi cuaca, jika pada akhirnya usaha tak mengubah apa-apa. Saya tak ingin membuatmu kecewa nantinya,” jelas Nagara sore itu.
Penjelasannya kala itu benar-benar menghujam hatiku dengan ribuan pedang es yang dingin dan tajam. “Aku akan tetap disini, hingga batu itu melunak, Nagara.” Tak terasa pelupuk mataku blur dipenuhi air yang sudah siap untuk keluar. Pada akhirnya, cuaca memang tak mengubah apa-apa, meski ribuan kali ia berusaha. Magma yang membeku selamanya akan menjadi batu. Tak satu pun yang bisa mengubahnya menjadi tanah. Dan waktu pun menjawab segalanya. Nagara meninggalkanku sendiri dengan sisa puding yang tergeletak di meja dan harumnya cappuccino dari pelanggan di meja seberang yang semerbak di seluruh ruangan. Aku memutuskan untuk pulang dengan jalan kaki di tengah derasnya hujan. Berharap agar air mata bercampur dengan air hujan yang turun membasahi wajahku. Sehingga orang di luar sana takkan tahu jika aku menangis.
***
“Ibu, sekarang aku tahu. Bahwa cuaca tak selamanya dapat mengubah batu menjadi tanah yang gembur,” kataku berhambur dalam pelukannya sesampai di rumah.
“Jangan menyerah, Nak. Kau belum banyak berusaha. Sedang batu itu terlalu kuat untuk kau lunakkan,” ucapnya seraya mengelus rambutku yang basah.
“Lalu, apa yang harus aku lakukan jika batu itu telah hilang terbawa arus sungai?”
“Kau harus tetap menunggunya, Nak. Percayalah. Sekarang, cepat kau mandi agar tidak sakit,” nasihat ibu seraya tersenyum penuh keyakinan.
Setahun sudah tak lagi aku bertemu dengannya. Tidak juga dia hadir dalam diskusi rasa setiap Hari Minggu. Batu itu telah hilang di derasnya aliran sungai. Tanpa tahu siapa yang merindunya. Sebab, batu tak memiliki rasa.
-SELESAI-


 ferly_aa
ferly_aa