Ayam sudah sedari tadi berkokok. Bulan hampir hilang terganti sang surya yang ceria. Memberikan aba-aba pada dunia untuk segera memulai aktivitasnya.
Dipojok desa di Jawa Tengah. Sudah mulai semua kegiatan warganya. Anak-anak dengan riangnya berangkat sekolah. Bersama-sama mencari secercah ilmu untuk kesuksesan esok hari. Berjuang tak lekang untuk membuka cakrawala kehidupan yang lebih gamblang.
Mungkin itu bagi mereka yang ingin membangun negeri lebih hakiki diesok hari. Namun berbeda dengan seorang perjaka ini. Seorang laki-laki berumur 16 tahun yang memilih hidup tanpa ilmu. Menghabiskan waktu bermain kartu, bersenang-senang meminum alkohol, memaki-makin hidup kala uang tak ada dalam genggaman.
“Ah, segarnya. Sungguh minuman yang amat segar. Aku bingung, mengapa ini tak jadi minuman utama setelah air?” Rancaunya sambil meneguk sebotol minuman keras di ruang makan. Mukanya sudah kuyu, lelah dengan kehidupan yang membosankan.
Hari belum begitu siang, masih ada sisa beberapa menit untuk masuk sekolah. Tiga anak berseragam putih abu-abu mendatangi rumah perjaka tersebut. Rere, Deo, dan Yuda. Sahabat karib perjaka tersebut.
“Assamualaiakum.” Ucap Rere berusaha mencari seseorang didalamnya untuk membukakan pintu untuknya.
Tak ada jawaban dari dalam. Mereka masih menunggu walau pintu tidak dikunci. Dari dalam mereka mendengar suara gaduh. Takut terjadi apa-apa mereka segera memasuki rumah.
“Teguh, apa yang tengah terjadi? Kau tak apa?” Rere berjalan mendekat dengan wajah khawatir.
“Ah, kau rupanya, Re. Hey, kebetulan juga kau ajak Yuda dan Deo. Ayo, kawan. Kita minum sampai puas.” Teguh mengangkat tinggi-tinggi botol minuman keras itu yang tersisa setengah.
“Kau tak sekolah, Guh?”
“Apa? Sekolah? Sekolah buat apa? Lebih baik dirumah. Minum bir yang lezat ini. Ayolah kawan. Ini begitu lezat.” Ucap Teguh dengan terbatuk-batuk menawarkan sebotol minuman keras yang masih utuh ke Yuda. Deo yang melihat secercah kesegaran terpancar diwajah Teguh, hati Deo terketuk.
“Eh Deo. Jangan minum minuman itu. Bahaya.”
“Tapi, Re. Deo melihat Teguh begitu bersenang-senang.”
“Namun kemarin guru kita melarang, bukan?
“Tapi, Re..”
“Sudahlah sudah. Daripada kita terlambat dan Deo semakin ingin meminumnya. Lebih baik kita pergi sekarang. Bagaimana, Guh? Mau bergabung dengan kami?”
“Sudahlah sudah. Pergilah segera kalian. Ah, memang kalian bodoh.”
Yuda, Deo, dan Rere segera pergi meninggalkan Teguh sendiri. Teguh menatap kepergian mereka. Menatap sinis kepergian mereka.
“Mungkin mereka tak ingin aku kehausan dan kehabisan. Hahaha…”
Teguh terus dan terus meneguh botol minuman keras itu. Hingga akhirnya sebotol minuman keras itu tak setetespun mengeluarkan cairan. Teguh meneliti dengan saksama botol itu. Setelah dirasa hambis ia geletakkan sembarangan botol tersebut.
Ia berjalan tertatih-tatih. Minuman keras itu membuat kepalanya begitu pening. Ia berjalan amat sempoyongan menuju ruang tamu sambil membawa gulungan kertas.
Di dinding ruang tamu itu terdapat sebuah bingkai foto. Bingkai itu lusuh, sudah kumal dimakan waktu. Namun begitu kegagahan sosok yang terpampang di bingkai itu tak akan pernah lusuh dan kumal. Ir. Soerkarno, ya foto yang amat sangat berwibawa disamping terpasang sebuah bendera Indonesia.
Teguh menatap tak mengerti foto tersebut. Menahan rasa kebencian yang amat dalam.
“Ah foto macam apa ini? Lebih baik foto yang saya bawa ini. Wow, sungguh lebih menawan.” Teguh membuka gulungan kertas yang tadi dibawa. Membuka dengan lebar gulungan tersebut. Foto seorang laki-laki berdandan seperti anak punk.
Teguh mulai mengambil bingkai foto itu. Segera membuka bagian belakang dengan keadaan kepala yang masih pening. Belum sempat foto Ir. Soekarno terambil. Ibunya teguh, Mbok ijah keluar dari arah dapur.
“Eh, Nang. Mau kau apakan foto itu?”
“Oo.. Kau rupanya, Buk. Ah, aku mau mengganti foto usang ini.”
“Jangan, Le. Itu foto kesayangannya mbahmu.”
“Alah, tak apa, Buk. Mbah tak mungkin marah padaku.”
“Jangan, Le!!”
Mbok Ijah terus melarang Teguh mengganti foto tersebut. Mereka saling berteriak satu sama lain. Mbah Lastro, kakek Teguh yang sedari tadi beristirahat merasa terganggu dengan kebisingan mereka.
“Ada apa ini? Setia hari selalu saja kalian ribut. Eh, eh, eh.. Mau kau apakan foto itu?”
“Mau aku ganti, Mbah.”
“Ganti? Kamu ganti dengan apa?”
“Dengan foto ini, Mbah. Bagus’kan?”
“Foto macam apa itu. Jangan aneh-aneh, Le. Biarkan foto Ir. Soekarno tetap disitu.”
Teguh menatap ganas kakeknya. Begitu marah dengan perkataan kakeknya.
“Kau salah, Mbah. Ini foto yang bagus. Tak seperti itu. Jelek, kusut, kumat. Kalau punya saya ini. Gagah, perkasa!”
“Kurang ajar kau! Lebih baik aku pergi daripada tinggal serumah dengan anak sepertimu.”
“Pergi saja sana.”
Mbah Lastro dengan segera melangkah pergi menuju kamarnya. Teguh tersenyum senang. Mbok Ijah yang melihat kejadian ini begitu sungguh tak percaya. Matanya mulai nanar menatap pilu luka yang baru saja terjadi.
“Apa yang baru saja kau katakan, Teguh. Bagaimana jika kakekmu memang benar-benar pergi?”
“Biarkan saja, Buk. Itu hanya gertakannya. Kakek itu sudah tak waras. Setiap kali melihat foto jelek ini. Dia tersenyum. Menepuk keras dadanya. Terkadang hormat sambil berkata Siap grak! Tegak grak! Hormat grak! Saya siap melakukan tugas komandan! Apa itu tidak gila?”
“Itu karena dia komandannya mbahmu, Le. Komandan mbahmu-lah yang sudah membuatnya bisa berjuang melawan penjajah. Mengapa kau bisa seperti ini, Le. Sadar, Guh. Sadar!” Mbok Ijah berkata sambil terisak. Menatap sedih muka anaknya yang begitu marah.
“Sadar? Aku harus sadar seperti apalagi, Buk. Saya dendam. Amat sangat dendam dengan mereka. sudah lupakah kau, Buk? Kau menjadi janda karena mereka!”
“Sudah, Le. Sudah. Itu sudah terjadi.”
“Dulu ketika aku masih kecil. Aku diajak ayah pergi bermain. Waktu itu jalanan ramai karena ada konvoi sebuah partai yang akan menggantikan kedudukan wakil rakyat yang terdahulu.
“Jalan begitu macet. Tak sedikitpun celah yang bisa dilewati. Ayah terus saja mencari jalan. Akhirnya ditemukan. Baru saja ayah melangkah, sebuah montor salah satu orang yang mengikuti konvoi melaju kencang. Tanpa merasa bersalah ia terjang ayah hingga terjatuh. Ayah sekika meninggal disana.
“Anak mana yang tega melihat ayahnya seperti itu, Mbok? Aku menangis. Anak kecil yang amat menyayangi ayahnya menangisi ayah yang baru saja meninggal, tepat didepan matanya. Tapi lihat mereka. Tak ada satupun diantara mereka yang peduli dengan ayahku dan jeritan piluku. Tak ada! Bahkan semakin semarak meramaikan jalan. Kau tau, Buk. Ayah seperti seekor kucing yang meninggal dijalan saat itu. Tak ada yang peduli.” Teguh berkata dengan garang. Matanya berair. Perih dengan keadaan yang menimpanya. Sakit dengan perlakukan mereka.
Ibunya nanar menatap Teguh. Sama-sama merasakan sakit.
“Aku tahu, Nak. Itu amat sangat menyakitkan. Bahkan aku juga sedih menjadi janda. Namun semua memang sudah takdir. Kita harus menghadapinya. Tapi ingat satu hal. Semua biaya kehidupan kita yang menanggung itu Negara, Le. Uang hasil pensiunannya mbahmu.”
Teguh menatap ibunya tak percaya. Ia terdiam. Merasa begitu bersalah dengan kakeknya. Teguh berdiri ingin meminta maaf kepada kakeknya. Baru saja berbalik. Kakeknya sudah berdiri membawa tas.
“Mau kemana, Mbah?”
“Mau pergi. Daripada disini hidup dengan seseorang yang tak memiliki jiwa nasionalisme.”
“Jangan pergi, Mbah. Kumohon jangan. Aku minta maaf. Aku memang bersalah. Jangan pergi, Mbah.”
Teguh berlutut dihadap kakeknya. Memohon dengan sungguh maaf tulus dari kakeknya. Mbah Lastro menatap haru cucunya yang berlutut dihadapnya.
Ia melangkah mendekati bendera. Mengambilnya dengan tegas. Teguh berdiri menatap tak mengerti kakeknya.
“Lanjutkan, Le. Lanjutkan perjuangan mbahmu ini! Buat Indonesia maju!”
Dengan sigap Teguh menerima bendera itu. Dengan senyum dan semangat membara ia angkat bendera itu tinggi-tinggi dengan rasa penuh cinta bumi pertiwi.


 Sarimarvi
Sarimarvi





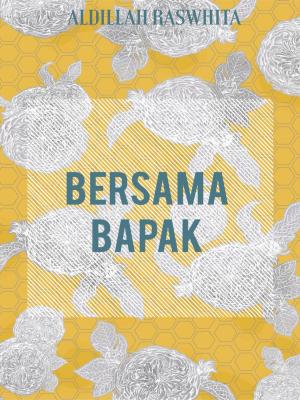

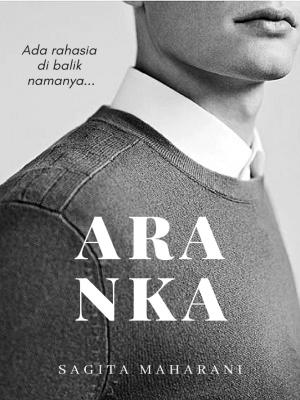




Mampir yuk ke cerita ku, makasih
https://tinlit.com/story_info/2957