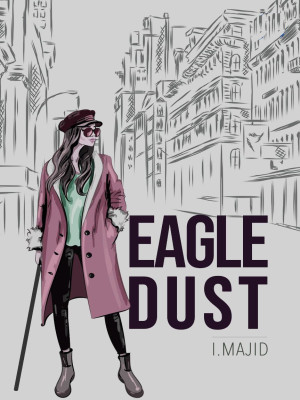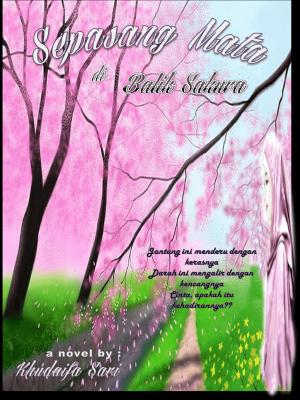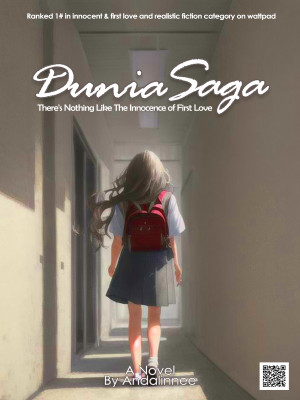Kalau ada satu hal yang tak pernah aku duga saat masuk SMA, itu adalah: seseorang seperti Reyhan bisa begitu nyaman aku ajak bicara.
Kami bukan tipe pasangan seru yang bikin heboh satu kelas, atau jadi perhatian karena duduk berdempetan ke mana-mana. Kami biasa saja. Tapi justru dari kebiasaan itu, perasaan-perasaan aneh mulai muncul.
Kami duduk tak terlalu jauh, tapi cukup untuk bisa saling melirik kalau guru sedang menulis di papan. Kadang, tatapan kami bertemu, dan salah satu dari kami cepat-cepat mengalihkan pandangan. Dan jantungku? Selalu gagal diajak tenang.
Reyhan bukan anak populer. Tapi entah kenapa, dia gampang akrab. Dia mulai sering duduk dekatku saat belajar kelompok, mulai sering menyapa dengan panggilan-panggilan konyol, dan kadang tiba-tiba datang menawarkan permen hanya karena—katanya—aku kelihatan lelah.
“Nih, manis. Biar kamu nggak asem kayak barusan,” katanya suatu hari, menyodorkan permen ke mejaku.
Aku cemberut, lalu mengambilnya juga. “Kalau aku asem, kamu asinnya.”
Dia tertawa. “Asin itu artinya awet, loh.”
Dan aku—lagi-lagi—tersenyum kecil sambil menunduk, menutupi pipi yang mulai panas.
Kadang aku benci betapa mudahnya dia membuatku gugup. Tapi di sisi lain, aku juga menunggu-nunggu momen-momen semacam itu.
Waktu istirahat jadi momen paling aku suka sekarang. Bukan karena jajanannya enak (kadang malah mahal dan nggak kenyang), tapi karena Reyhan sering duduk di meja yang sama.
Kami tidak selalu ngobrol banyak. Tapi aku selalu merasa tenang. Dia bisa cerita hal-hal lucu tentang temannya, tentang film yang dia tonton semalam, atau tentang kejadian konyol saat dia lupa bawa PR dan pura-pura sakit perut.
Dan aku… ya, aku mulai terbiasa tertawa hanya karena dia ada di situ.
Suatu hari, dia meminjam bukuku. Sebenarnya dia bisa saja minta difotokan catatannya, tapi dia bilang ingin baca langsung. Aku mengangguk dan menyerahkan buku itu tanpa berpikir. Tapi saat malamnya aku buka buku yang lain, aku melihat secarik kertas terselip di halaman terakhir.
Tulisan tangan yang kukenal:
“Kalau kamu senyum terus kayak gitu, nanti aku makin susah fokus.”
Aku menatap tulisan itu cukup lama. Tanganku gemetar sedikit. Ada rasa manis aneh yang menelusup ke dada. Aku tahu, ini bukan sekadar candaan. Tapi aku juga tak tahu harus membalasnya dengan apa.
Esoknya, aku tak berani menatap wajahnya terlalu lama. Tapi dia hanya tersenyum seperti biasa, seolah tak ada yang perlu dibahas.
Dan itulah yang paling bikin aku bingung. Kami seperti berjalan di atas tali tipis—dekat, tapi tak pernah benar-benar tahu kapan boleh melangkah lebih jauh.
Waktu terus berjalan. Ulangan demi ulangan datang. Tugas makin menumpuk. Tapi pikiranku lebih sering teralihkan oleh satu orang itu.
Reyhan.
Ada satu hari ketika dia tidak masuk. Katanya sakit. Tapi aku tak bisa menyembunyikan kekecewaan yang aneh. Hari itu jadi begitu sepi. Tidak ada celetukannya. Tidak ada lemparan permen kecil ke meja. Tidak ada Reyhan yang diam-diam menatap dan membuat aku salting seharian.
Baru saat malam, ponselku berbunyi. Satu pesan masuk.
“Hari ini aneh ya. Aku juga kangen rame-nya kelas, apalagi kursi yang paling depan itu keliatan kosong banget.”
Dia tahu aku duduk di depan. Dia tahu aku juga merasa kehilangan. Tapi, dia memilih menyampaikannya dalam kalimat yang setengah bercanda.
Aku membalas pelan.
“Cepet sembuh. Besok kursi itu nunggu kamu.”
Hubungan kami berkembang seperti bunga yang mekar perlahan. Tidak ada ledakan. Tidak ada pengakuan cinta di bawah hujan. Tapi semua terasa... nyata.
Meskipun begitu, kadang aku masih bertanya-tanya. Apakah aku satu-satunya yang dia perlakukan seperti ini? Atau aku hanya kebetulan berada paling dekat saat dia sedang butuh teman?
Pikiran-pikiran itu sesekali datang, apalagi kalau aku melihat dia terlalu lama ngobrol dengan teman perempuan lain. Aku tidak marah. Tapi aku merasa… aneh. Sesak, tapi aku tidak punya hak apa-apa.
Malam-malamku jadi sering dipenuhi pertanyaan yang tak pernah aku ucapkan. Tapi pagi harinya, saat dia datang dan menyapaku seperti biasa, semua pikiran itu seakan dibungkam hanya dengan senyumnya.
Hingga suatu sore, kami pulang bareng. Jalanan ramai, tapi kami berjalan pelan. Kadang aku berharap waktu bisa memperlambat langkah.
“Ly,” katanya tiba-tiba.
Aku menoleh. “Hmm?”
“Kamu pernah nggak, ngerasa nyaman banget sama seseorang, tapi nggak tahu itu kenapa?”
Aku berhenti sejenak, mencoba menyembunyikan detak jantung yang semakin liar.
“Pernah,” jawabku pelan.
Dia tersenyum, menatapku sesaat. Tapi kemudian kembali menatap jalan. “Kalo aku, kayaknya lagi ngerasain itu sekarang.”
Aku hanya diam. Tidak menjawab. Karena kalau aku menjawab… mungkin aku tidak akan bisa pura-pura lagi.
Dan mungkin, itu juga cukup. Untuk saat ini.
“Rasa itu tidak selalu harus diumumkan. Kadang cukup dirasakan, disimpan, dan diperjuangkan diam-diam.”


 syamzhc
syamzhc