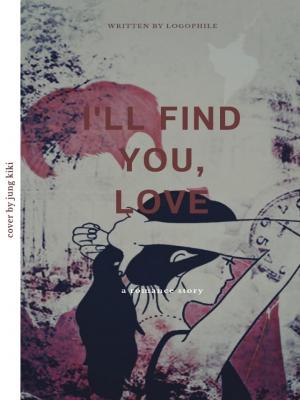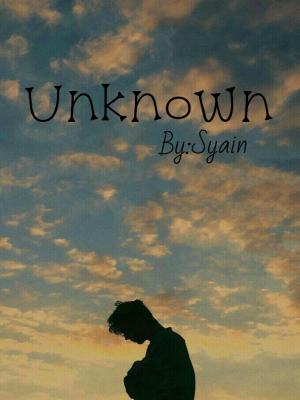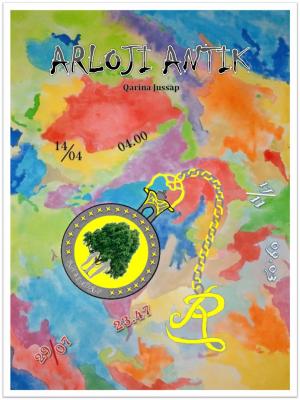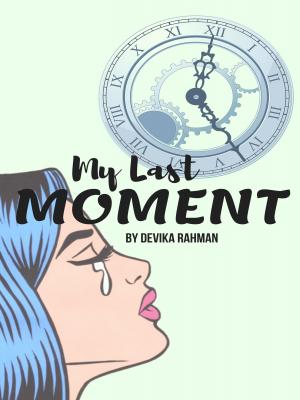“Kita tidak pernah benar-benar melupakan, hanya belajar hidup berdampingan dengan yang hilang.”
Hidup tidak selalu tentang yang kembali.
Kadang, hidup hanya tentang berdamai dengan apa yang tidak pernah pulang.
Yuana tahu, ia tidak bisa kembali ke masa lalu.
Ia juga tahu, seseorang itu tak akan pernah muncul di hadapannya, bahkan jika ia menunggu seumur hidup.
Dan entah sejak kapan,
ia berhenti menunggu.
Bukan karena tidak lagi mencintai,
tapi karena cinta pun, pada akhirnya, harus tahu kapan harus duduk tenang dan tidak meminta apa-apa.
Hari-hari berjalan seperti biasa,
dan pada suatu waktu yang tidak ia sadari kapan mulainya,
Yuana akhirnya mengizinkan hatinya untuk terbuka kembali.
Ia tidak mencari pengganti,
karena tak ada yang benar-benar bisa menggantikan.
Tapi ia belajar mencintai seseorang yang kini memilih tinggal bersamanya—
dengan sederhana, dengan sabar, tanpa banyak tanya tentang masa lalu yang tak ingin ia ceritakan.
Mereka berbagi pagi, berbagi senja,
dan kadang-kadang, berbagi diam yang tidak perlu dijelaskan.
Ruang kosong itu masih ada.
Ia tidak mencoba menutupnya.
Tidak juga berusaha mengisinya.
Ia hanya berdamai.
Menerima bahwa di dalam dirinya akan selalu ada satu nama,
satu kenangan,
satu luka yang tak bisa dijelaskan pada siapa pun.
Dan itu tidak membuatnya kurang dalam mencintai yang sekarang.
Itu justru membuat cintanya lebih utuh—karena kini ia mencinta bukan untuk melupakan,
tetapi untuk memilih hadir sepenuhnya,
meski ada bagian kecil di dalam dirinya yang tetap tinggal di masa lalu.
Yuana tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang.
Ia berjalan dalam cahaya yang ia ciptakan sendiri.
Dengan hati yang pernah luka,
tapi kini belajar menjadi rumah—untuk seseorang yang datang,
dan untuk dirinya sendiri.


 rionhana
rionhana