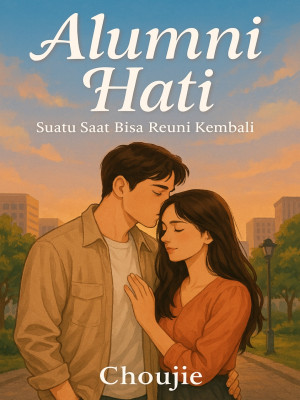Hari itu aku menemukan sebuah benda kecil di bawah tumpukan koran lama di lemari kamar belakang. Warnanya sudah pudar. Pinggir-pinggirnya terlipat. Kertasnya kekuningan, dan ada noda bekas teh atau mungkin kopi di halaman pertamanya. Sebuah buku catatan bersampul merah muda kusam, dengan tulisan spidol di sampulnya: "Rahasia Tahun 1998. Jangan dibaca kecuali kamu aku."
Tulisannya jelas tulisan anak-anak. Hurufnya tak rapi, kadang besar kadang kecil. Dan aku tahu persis siapa penulisnya.
Aku.
Tangan ini agak gemetar waktu membalik halaman pertama. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang membuncah bercampur haru. Rasanya seperti membuka pintu ke ruang yang sudah lama terkunci di kepala sendiri.
Halaman pertama hanya berisi tulisan besar: “Mulai hari ini, aku punya tempat untuk bercerita.”
Aku tersenyum. Kalimat pembuka itu sederhana, tapi jujur. Dan itu cukup jadi alasan kenapa aku ingin terus membaca sampai halaman terakhir.
3 Maret 1998
Hari ini Ibu marah karena aku nyiram tanaman pakai air cucian beras yang ada sabunnya. Tapi aku kira itu air bersih. Dira ketawa-ketawa terus dan nggak mau bantu jelasin. Jadi aku dimarahin sendiri.
Tapi malamnya Ibu kasih aku roti bakar isi cokelat. Katanya, “Tadi Ibu ngomel, tapi Ibu sayang.” Aku senang.
Betapa sederhananya rasa bersalah dan maaf saat kita masih kecil. Dunia belum penuh ego. Marah tidak pernah berlama-lama, dan cinta bisa disampaikan lewat roti bakar isi cokelat.
20 April 1998
Aku tadi nangis gara-gara nilai matematika cuma 5. Tapi Ayah bilang, “Kamu nggak perlu jadi juara, cukup terus belajar.” Terus dia ajarin aku pakai kancing baju buat ngitung. Seru juga.
Tulisanku makin jelek di bagian itu. Sepertinya ditulis sambil menangis. Tapi aku juga membaca ulang dengan senyum. Ayah memang punya cara sendiri dalam menghibur. Tidak banyak kata manis, tapi tindakannya selalu membekas.
Di halaman tengah buku itu, ada satu halaman yang dilingkari dengan spidol merah:
1 Juni 1998
Hari ini ulang tahunku yang ke-10. Aku nggak dibikinin pesta, tapi Ibu masak mie goreng spesial dan Ayah beliin kue dari toko depan gang. Dira kasih aku hadiah gambar dinosaurus dari kertas binder. Katanya, "Nih buat kamu. Karena kamu keras kepala kayak T-Rex."
Aku ketawa sampai tumpah teh di baju.
Aku bahkan masih bisa mencium aroma mie goreng Ibu di kepalaku saat membaca bagian itu. Aneh ya, ternyata kenangan bisa bertahan di ujung indera kita. Tersimpan begitu rapi, hanya perlu pemicu kecil untuk menguap ke permukaan.
Di antara tulisan-tulisan harian yang lucu dan jujur, aku juga menemukan halaman kosong. Banyak sekali. Seolah aku pernah ingin menulis banyak, tapi lupa, atau terlalu sibuk bermain petak umpet dan gundu.
Namun halaman kosong itu justru memberi ruang imajinasi. Apa yang ingin kutulis saat itu? Apa yang kupikirkan tapi tak sempat tertuang? Rasanya seperti menatap langit malam—ada begitu banyak bintang yang tak terlihat, tapi kita tahu, mereka ada.
Satu tulisan menohok muncul di bagian akhir buku:
5 November 1998
Hari ini aku lihat Ibu duduk di ruang tamu sendirian. Lampu belum dinyalakan, tapi matanya kelihatan berkaca-kaca. Aku nggak tanya kenapa. Aku cuma duduk di sampingnya, pura-pura nonton TV padahal nggak nyala.
Setelah lama diam, Ibu pegang tanganku dan bilang, “Terima kasih ya, kamu teman duduk yang baik.”
Aku menutup buku itu sebentar. Menghela napas panjang. Dan air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh juga.
Momen itu, ternyata masih hidup di kepalaku. Aku memang tidak mencatatnya di kalender, tidak menyimpannya di album foto, tapi aku pernah menyimpannya di halaman kecil buku harian ini.
Dan hari ini, aku menemukannya kembali masih utuh, masih hangat.
“Lagi baca apa?” suara Dira dari balik pintu kamar.
Aku menunjukkan buku itu. “Buku harian. Tahun 1998.”
Dia duduk di sampingku, mengambil alih buku itu dan mulai membaca perlahan. Lalu tertawa, lalu diam, lalu tertawa lagi.
“Aku memang bilang kamu kayak T-Rex, ya?” katanya geli.
“Dan kamu kasih aku gambar dinosaurus jelek,” jawabku tertawa.
Kami membolak-balik halaman itu bersama. Membaca ulang masa kecil yang ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu dipanggil kembali.
“Aku pikir dulu kita nggak punya kenangan istimewa,” ucap Dira pelan.
Aku menoleh. “Kenapa kamu pikir begitu?”
“Soalnya kita nggak punya foto-foto bagus, nggak pernah liburan mewah. Rumah ini kecil. Tapi ternyata... kita punya ini semua.” Ia mengangkat buku itu.
Aku mengangguk. Karena aku tahu: bukan bentuk kenangan yang penting, tapi rasa yang tertinggal setelahnya.
Sebelum kami menutup buku itu, aku menuliskan satu kalimat di halaman belakang:
“Untuk aku yang menulis di usia sepuluh tahun,
terima kasih sudah menyimpan cinta, tangis, dan tawa dengan jujur.
Aku, versi dewasa ini, sangat bangga padamu.”
Lalu kami menutup buku itu bersama.
Aku meletakkannya di rak kecil dekat jendela, bersama barang-barang lain yang ingin kami simpan, bukan karena mahal, tapi karena bermakna.
Refleksi:
Buku harian bukan sekadar catatan. Ia adalah saksi bisu bagaimana hati kecil kita belajar merasa. Tahun 1998 mungkin hanya angka, tapi di dalamnya terkumpul perasaan-perasaan pertama: patah hati kecil, tawa lepas, dan cinta tanpa syarat.
Dan ketika hari ini kita menemukannya kembali,
rasanya seperti bertemu dengan diri sendiri
yang selama ini hanya menunggu untuk dipeluk kembali.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_