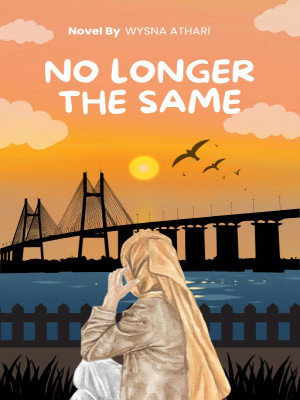Pagi di rumah lama selalu punya caranya sendiri untuk menyapa. Bukan dengan alarm ponsel atau bunyi notifikasi, tapi dengan sesuatu yang lebih lembut—lebih jujur.
Cahaya.
Cahaya pagi yang menembus dari sela-sela gorden tipis yang sudah usang. Yang warnanya dulu putih, tapi kini berubah menjadi abu-abu kekuningan karena waktu dan debu. Gorden itu tak lagi mengalir lembut ketika tertiup angin. Ia lebih sering bergelantungan kaku, seperti lelah menunggu pagi-pagi yang tak kunjung datang.
Namun entah mengapa, setiap kali aku melihatnya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah gorden itu tidak hanya menutup jendela, tapi menyaring waktu. Menyimpan sinar-sinar pagi yang dulu pernah menari di wajah-wajah kami.
Aku menarik napas panjang pagi itu, duduk di kursi dekat jendela ruang tengah. Kursi rotan yang bunyinya sudah tak lagi ramah saat diduduki. Tapi tetap jadi tempat favoritku. Di hadapanku, gorden tua itu menggantung. Sedikit robek di pinggir kanan. Dijahit seadanya oleh Ibu bertahun lalu. Benangnya warna biru, tak serasi dengan kainnya, tapi justru jadi penanda: bahwa sesuatu tak harus sempurna untuk tetap layak dipertahankan.
Cahaya pagi menerobos perlahan dari sela-sela kain. Menyapu permukaan lantai yang sudah retak di beberapa bagian. Debu beterbangan kecil, seperti butiran waktu yang enggan turun sepenuhnya.
Dan di antara semua itu, aku melihat potongan kenangan.
Dulu, setiap pagi hari Minggu, Ibu akan membuka jendela besar itu sambil menyibakkan gordennya lebar-lebar. Udara dingin pagi akan masuk, membawa bau embun dan suara ayam tetangga.
"Ayo bangun! Sayang banget pagi sebagus ini dilewatkan!" seru Ibu sambil mengibas-ngibaskan gorden agar debunya hilang.
Tentu, debunya tetap ada. Tapi kami tetap ikut Ibu keluar ke teras, duduk bareng sambil makan pisang goreng hangat atau minum teh manis dari gelas kaca buram.
Dira sering protes, “Bu, ini pagi kok kayak siang. Silau banget!”
Dan Ibu hanya tertawa. “Silau itu tandanya hidup masih semangat, Nak.”
Lucu ya. Dulu kita merasa cahaya itu gangguan. Sekarang, aku mencarinya.
Aku berdiri dan menyibakkan gorden perlahan. Jendela di baliknya berdebu, tapi masih bisa melihat keluar. Pohon jambu di depan rumah masih berdiri, walau batangnya tampak makin rapuh. Jalan kecil di depan rumah sudah beraspal ulang. Tapi ada satu hal yang tetap sama: cahaya pagi masih datang dengan cara yang sama.
Pelan. Hangat. Tidak pernah terburu-buru.
Cahaya itu tidak pernah menuntut perhatian, tapi selalu hadir. Ia tidak menabrakmu, tapi menyentuhmu. Dan gorden itu—meski sudah tua dan kumal—masih setia jadi temannya.
Aku menyentuh kainnya. Tipis. Kasar. Tapi di balik teksturnya yang usang, aku bisa merasakan kehadiran masa lalu.
Di balik gorden ini, dulu aku pernah mengintip anak tetangga yang suka main layangan. Di balik gorden ini, Dira pernah sembunyi waktu nangis karena nilai matematikanya jelek. Di balik gorden ini juga, Ibu sering berdiri diam-diam, menatap keluar sambil membawa cucian atau sambil memeluk dirinya sendiri di pagi yang dingin.
Dan sekarang, aku yang berdiri di sini. Dengan tubuh dewasa dan jiwa yang masih mencari tempat nyaman untuk bersandar.
Kadang, yang membuat kita rindu bukan tempatnya—tapi cahaya yang dulu menyinari tempat itu.
Cahaya yang jatuh tepat di ubin warna krem. Cahaya yang memantul di lemari kaca. Cahaya yang membuat kita tahu: hari baru telah dimulai, dan kita masih diberi kesempatan.
Aku duduk kembali, membiarkan cahaya itu menyinari wajahku. Mataku terpejam, dan suara pagi mulai terdengar pelan-pelan: cicit burung dari kejauhan, bunyi sapu lidi tetangga, dentingan sendok dari dapur. Semuanya menyatu seperti orkestra sederhana—tapi indah.
Dan gorden tua itu, tetap bergoyang pelan. Diam-diam bekerja menjadi peluk dari kenangan yang tak pernah pergi.
Aku jadi teringat satu pagi, bertahun lalu. Saat itu Ibu baru saja selesai membersihkan jendela. Tangannya kotor, bajunya basah sedikit. Tapi ia tersenyum lebar sambil berkata:
“Kalau kamu pengen tahu apakah rumah ini masih bahagia, lihat saja dari cara cahaya masuk. Kalau masih hangat dan tenang, berarti rumah ini masih baik-baik saja.”
Aku waktu itu hanya mengangguk. Tidak paham benar.
Tapi pagi ini, kata-kata itu seperti terpantul dari kaca jendela dan langsung menempel di hatiku.
Aku menyisir gorden itu perlahan. Di bagian bawahnya, ada bordiran kecil berbentuk bunga. Aku baru menyadari, itu buatan tangan Ibu. Benangnya tidak rapi. Ada yang keluar, ada yang kusut. Tapi justru di situlah keindahannya.
Karena rumah ini tidak dibangun dari hal-hal mewah. Rumah ini dibangun dari upaya yang tulus, dari tangan yang bekerja dalam diam, dari gorden yang tetap digantung meski tidak sempurna lagi.
Dan mungkin, itu pula cara hidup yang paling jujur:
Tidak selalu baru, tidak selalu bersih, tapi selalu ada dan tetap berfungsi.
Sebelum meninggalkan jendela, aku membuka gorden lebar-lebar. Membiarkan cahaya pagi masuk sepenuhnya. Bukan hanya untuk menerangi ruangan, tapi juga hati yang selama ini sembunyi di balik bayangan hari-hari sibuk.
Aku menulis satu catatan kecil, menempelkannya di sisi jendela:
“Untuk gorden tua dan cahaya pagi:
Terima kasih telah tetap hadir,
meski kami sering lupa menyapamu lebih dulu.”
Lalu aku tersenyum. Karena aku tahu, pagi bukan soal matahari. Tapi soal cara kita membuka hati. Dan mungkin… semua itu dimulai dari menarik gorden yang sudah lama tertutup.
Refleksi:Tidak semua pagi datang dengan semangat besar. Tapi bahkan pagi yang paling sepi pun bisa terasa hangat, kalau kita mau membuka sedikit jendela, dan membiarkan cahaya masuk. Gorden berdebu itu mungkin tak menarik, tapi ia tetap menyaring sinar dengan setia. Seperti banyak hal dalam hidup tidak harus baru untuk tetap berarti.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_