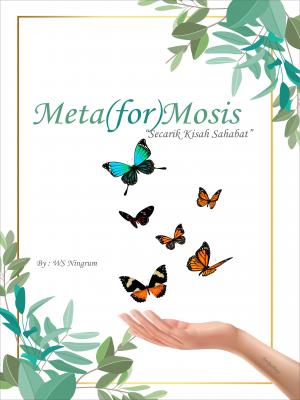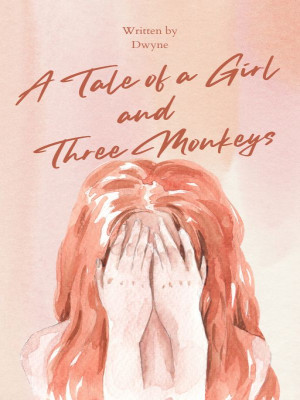Kalau rumah lama kami bisa bicara, mungkin salah satu bagian yang akan paling cerewet adalah pagarnya. Bukan karena bentuknya istimewa—hanya pagar besi biasa, bercat hijau tua yang mulai mengelupas di sana-sini—tapi karena ia pernah jadi saksi bisu kenakalan, keberanian, ketakutan, dan diam-diam: kebebasan kecil masa kanak-kanak.
Setiap ruas pagarnya mungkin mengingat suara decit sendal jepit yang tergantung, suara napas terengah-engah saat melompat turun, dan bisikan panik, “Sst! Jangan bilang Ibu!”
Ya, pagar itu pernah kami naiki. Berkali-kali. Diam-diam.
Dan dari atas sana, dunia terlihat sedikit lebih luas, dan sedikit lebih bisa dijangkau.
Dulu, pagar itu cukup tinggi untuk membuat lutut kami gemetar, tapi cukup rendah untuk tetap dicoba. Aku dan Dira sering saling tantang: siapa yang bisa naik paling cepat, siapa yang bisa duduk di palang tengah tanpa goyah, dan siapa yang bisa melompat ke luar tanpa jatuh terduduk.
“Ayo, siapa takut!” seru Dira, sudah berada di atas, kakinya menggantung dengan wajah penuh kemenangan.
“Aku takut... kalau Ibu lihat,” jawabku sambil menahan napas.
Kami tahu aturan rumah jelas: jangan panjat pagar. Tapi aturan itu terasa seperti tantangan, bukan larangan. Kami ingin tahu bagaimana rasanya berdiri di luar zona aman, walau hanya beberapa sentimeter dari tanah.
Dan anehnya, dari atas pagar itu, suara ayam tetangga terdengar lebih jelas. Jalan depan rumah terasa seperti lintasan balap. Angin lebih kencang. Dan hati kami... entah mengapa, berani sekali.
Suatu hari, aku terjatuh dari pagar. Luka kecil di lutut dan telapak tangan yang lecet jadi bukti. Dira panik, matanya membulat seperti kucing tertangkap basah.
“Kamu jangan nangis! Sini aku obatin! Jangan bilang siapa-siapa!”
Tapi air mata tetap tumpah, dan darah menetes cukup deras untuk membuat kami bingung. Akhirnya, kami menyelinap ke dapur. Dira mengambil tisu dan odol—ya, odol. Karena dia pernah dengar dari temannya bahwa luka bisa cepat kering kalau diolesi pasta gigi.
Saat Ibu menemukanku, dia tidak marah duluan. Dia menatap lututku yang berlumur odol dengan ekspresi antara prihatin dan ingin tertawa.
“Lain kali, jatuhnya jangan di tempat yang dilarang,” katanya sambil membersihkan luka dengan betadine.
Dira berdiri di sampingku, menatap lantai. Aku tahu dia merasa bersalah.
Tapi Ibu tidak memperpanjang. Karena mungkin dia tahu: anak-anak tidak belajar dari larangan, tapi dari luka kecil yang mengajarkan batas.
Pagar itu juga pernah jadi tempat kami menyaksikan dunia. Kami duduk di palangnya saat sore, menonton sepeda lalu-lalang, anak-anak tetangga bermain layangan, dan suara azan magrib yang terdengar dari masjid kecil di ujung gang.
Di momen seperti itu, pagar bukan lagi penghalang. Ia jadi tempat duduk, menara pengawas, bahkan panggung imajinasi.
“Kalau kita naik ke atap pagar ini terus, kita bisa lihat dunia luar,” kata Dira dengan mimpi besar di matanya.
Aku mengangguk setuju, walau yang bisa kulihat hanya pohon mangga dan jemuran tetangga.
Tapi dari sanalah kami belajar membayangkan. Dan dari bayangan itu, kami merangkai harapan-harapan kecil yang kemudian menjadi langkah pertama keluar dari rumah ini saat dewasa.
Waktu kami beranjak remaja, pagar itu berubah fungsi. Tak lagi dipanjat, tapi jadi tempat bersandar saat menunggu jemputan, atau tempat melongok diam-diam kalau ada suara klakson di luar.
Aku pernah menyandarkan sepeda di situ sambil pura-pura main ponsel saat menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Dira juga pernah berdiri lama di depan pagar, menatap jalan yang perlahan gelap, entah menanti siapa.
Lucunya, pagar tetap diam. Ia tidak bertanya siapa yang ditunggu, atau mengapa ada air mata jatuh saat tak ada yang datang. Ia hanya berdiri. Dan kadang, kita butuh benda seperti itu—yang tidak menuntut penjelasan, tapi tetap setia menemani.
Suatu malam, aku pulang larut setelah bertemu teman lama. Semua orang sudah tidur. Tapi pagar itu menyambutku seperti biasa: dingin, kokoh, dan tenang. Aku membuka gerbangnya pelan, takut menimbulkan suara berisik.
Saat menutupnya kembali, aku berhenti sebentar. Meletakkan telapak tangan di besi tuanya yang mulai berkarat.
“Maaf ya, dulu aku sering naik kamu diam-diam,” bisikku pelan.
Tentu, pagar tidak menjawab. Tapi angin malam berhembus lembut, seperti ucapan maaf yang diterima tanpa syarat.
Dan malam itu, aku tahu: pagar ini tidak hanya menjaga rumah, tapi juga menjaga kenangan.
Beberapa hari yang lalu, saat aku kembali ke rumah lama, aku melihat pagar itu lagi. Warnanya sudah semakin pudar. Ada lumut sedikit di bagian bawah. Tapi bentuknya tetap. Ia berdiri seolah berkata, “Kalian boleh pergi sejauh mungkin, tapi aku akan tetap di sini.”
Aku berjalan mendekat, menyentuh ujungnya. Kali ini tidak untuk memanjat, tapi untuk mengucapkan terima kasih.
“Kau bukan sekadar pagar. Kau pernah jadi tempat mimpi kecil dilambungkan, dan pelajaran besar dijatuhkan.”
“Kau diam, tapi tak pernah hampa.”
Aku menuliskan satu kalimat kecil di kertas sobekan buku, lalu menempelkannya di sisi dalam gerbang:
"Untuk pagar yang pernah jadi menara: terima kasih karena telah diam-diam mengizinkan kami naik, dan tidak pernah mengadukan kami pada dunia."
Refleksi:
Kadang, kita butuh memanjat sesuatu untuk tahu seberapa jauh dunia bisa dilihat. Dan saat kita jatuh, kita belajar bahwa batas bukan untuk ditakuti—tapi dihargai. Pagar itu pernah kami panjat diam-diam, bukan karena ingin melanggar, tapi karena kami sedang belajar melihat dunia dari sudut yang berbeda. Dan dari atas sana, untuk pertama kalinya, kami merasa... bebas.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_