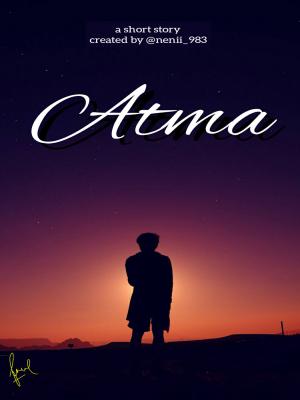Aroma wangi bawang goreng dan daun jeruk yang digeprek itu tiba-tiba menyergap hidungku begitu aku membuka pintu dapur. Waktu di rumah lama memang seakan berjalan lebih pelan, tapi aroma itu ah, ia tidak pernah lambat menyalakan ingatan.
Dapur ini sempit, dengan lantai yang sudah agak terkelupas dan keramik dinding yang beberapa retaknya menganga. Kompor tua di pojok kanan masih setia berdiri, ditemani panci yang warnanya tak lagi mengkilap. Di rak kayu atas wastafel, botol-botol kecap, saus, dan cuka berdiri seperti prajurit veteran yang tak pernah pensiun. Tapi justru di sanalah kehangatan rumah ini bermula di sudut yang sesederhana ini.
Ibu sedang berdiri membelakangi aku, mengulek sambal di cobek batu yang sudah mulai menipis karena usia.
“Wangi banget, Bu,” kataku pelan, berdiri di ambang pintu.
Ibu menoleh, tersenyum. “Kamu bangun juga akhirnya. Ini sambal terasi favorit kamu, lho.”
Aku masuk, duduk di kursi kecil yang sering dipakai Dira dulu saat bantu-bantu motong bawang lebih tepatnya, sambil terus mengeluh karena matanya perih.
“Bu, boleh aku bantu?” tawarku.
Ibu menyerahkan cobek dan ulekan padaku, lalu membuka tutup panci yang menguarkan aroma kuah santan dengan daun salam dan lengkuas yang menyeruak. Wangi masakan Ibu bukan sekadar aroma ia adalah isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Dapur ini pernah menjadi medan perang. Dira pernah membuat telur goreng gosong sampai tiga kali dan tetap bilang rasanya “unik”. Aku pernah menumpahkan satu baskom adonan kue cucur ke lantai dan hampir menangis, sampai Ibu bilang, “Nggak apa-apa, nanti bisa kita cuci dan coba lagi.”
Tapi, yang paling aku ingat adalah: tidak pernah sekalipun Ibu menuliskan resepnya.
“Kenapa sih Ibu nggak pernah catat resep? Biar aku bisa masak juga nanti,” tanyaku waktu SMP dulu.
Ibu cuma menjawab, “Karena rasa itu bukan cuma soal takaran. Tapi juga soal kenangan.”
Dulu, jawaban itu membuatku bingung. Tapi hari ini, sambil mengulek sambal dengan tangan yang pelan-pelan mulai gemetar karena usia, aku mulai mengerti.
Rasa memang bukan hanya dari seberapa banyak garam atau gula, tapi dari tangan siapa yang membuatnya, dari cerita apa yang menyertainya, dan dari suasana apa yang mengelilinginya.
Aku menatap lemari gantung tua yang warnanya mulai memudar. Di dalamnya, masih ada toples kaca berisi bawang putih goreng dan kerupuk udang yang renyahnya sudah tidak terjamin. Di bawah meja, ada ember berisi beras yang di atasnya selalu diselipkan daun pandan agar wangi.
Setiap detail di dapur ini seperti menyimpan satu kenangan kecil. Sendok kayu yang ujungnya sedikit hangus karena pernah dibiarkan di atas penggorengan. Gunting dapur dengan stiker bunga yang sudah hampir lepas. Bahkan, serbet lusuh berwarna merah muda yang sudah tidak lagi terlihat merah, tapi selalu dicuci dan dilipat rapi oleh Ibu.
“Kamu ingat waktu pertama kali masak nasi goreng sendiri?” tanya Ibu tiba-tiba.
Aku tertawa. “Yang aku pakai kecap dua kali lebih banyak dari biasanya?”
“Dan kamu maksa Ayah makan,” lanjut Ibu sambil tertawa kecil.
“Ayah bilang enak. Padahal dia sambil minum air setiap suap,” tambahku.
Kami tertawa bersama. Dapur ini, memang bukan hanya tempat memasak. Tapi juga tempat kami tumbuh, gagal, mencoba lagi, dan saling menertawakan.
Siangnya, Dira datang membawa dua potong tempe goreng dari warung sebelah.
“Kita makan di dapur aja yuk, nostalgia,” katanya sambil meletakkan tempenya di piring kecil.
Kami duduk bertiga di meja bundar mungil itu, dengan sajian sederhana: sambal terasi, sayur lodeh, tempe goreng, dan nasi putih hangat.
Tapi saat suapan pertama masuk ke mulut, tidak ada yang berbicara. Bukan karena makanannya pedas, tapi karena lidah kami seperti terlempar ke masa di mana meja ini dikelilingi suara tawa, piring-piring kecil penuh lauk, dan suara Ayah yang selalu minta nambah sambal.
“Bu,” ujar Dira pelan, “Boleh aku belajar masak dari Ibu? Aku mau bisa masak kayak Ibu.”
Ibu tersenyum, lalu menggeleng.
“Kamu nggak perlu belajar dari tulisan. Masaklah dari hati. Lihat, rasakan, dengar bunyinya. Cicipi. Kalau hatimu senang, makananmu juga akan senang.”
Dira mengangguk. Aku tahu dia menangkap makna dari kata-kata itu.
Sore itu, aku membuka laci kayu yang biasa dipakai menyimpan peralatan masak kecil. Di dalamnya, terselip secarik kertas lusuh. Tulisannya tangan Ibu—tapi bukan resep lengkap. Hanya kalimat-kalimat pendek:
1. Bawang putih, iris tipis.
2. Tumis sampai wangi, jangan gosong.
3. Tambahkan hati yang sabar.
Aku tertawa kecil. Rupanya, Ibu pernah mencoba menulis resep. Tapi tetap saja, sentuhan akhirnya selalu: tambahkan hati yang sabar.
Aku menyimpan kertas itu. Bukan karena takut lupa cara menumis bawang, tapi karena di situ ada bagian dari Ibu yang bisa aku bawa pulang kapan pun aku rindu dapur ini.
Menjelang malam, kami duduk di dapur dengan teh hangat. Lampu remang, suara jangkrik dari luar masuk pelan. Ibu menggigit kerupuk pelan-pelan sambil berkata,
“Dapur ini kecil. Tapi aku bersyukur. Di sinilah kalian belajar banyak hal. Termasuk... mencintai tanpa perlu alasan.”
Aku mengangguk.
Dan aku tahu, meskipun aku akan tinggal di tempat lain nanti, masak dengan alat modern dan buku resep digital, tapi rasa dari rumah ini tidak akan pernah tergantikan. Karena yang membuat masakan Ibu begitu enak bukan karena bahan-bahannya, tapi karena ada kenangan yang ikut dimasak bersamanya.
Refleksi Malam Itu
Kadang, kita mencari resep dari buku. Tapi rumah lama ini mengajari kita bahwa resep terbaik adalah yang hidup dari tangan yang mengasihi,dari hati yang sabar, dan dari dapur yang menyimpan tawa.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_