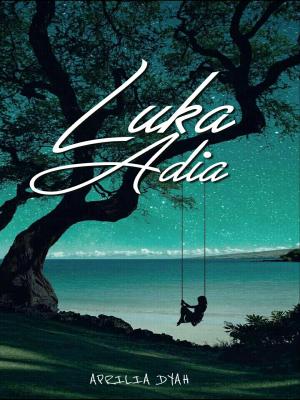Meja makan di rumah lama itu terbuat dari kayu jati. Usianya mungkin sudah lebih tua dari usia kami ketika pertama kali belajar duduk rapi di sekelilingnya. Permukaannya penuh bekas, dari goresan sendok, tetesan kuah, hingga noda tinta tugas sekolah yang tak sengaja menodai taplak bunga-bunga.
Tapi yang paling kentara bukan bekasnya. Melainkan... kekosongan yang terasa di satu sisi.
Dulu, meja itu selalu riuh. Pagi hari kami buru-buru menyendok nasi goreng buatan Ibu sambil sibuk menyambar seragam. Siang hari kadang kosong, kadang penuh, tergantung siapa yang pulang duluan. Tapi malam hari—itulah puncak kehidupannya.
Di situlah kami duduk berjejer: Ibu di sebelah kompor kecil di pojok, Ayah di ujung yang dekat ke rak buku, Dira di tengah, dan aku persis di seberangnya.
Makan malam kami sederhana. Nasi, lauk seadanya, kadang sambal kalau Ibu sempat. Tapi percakapannya? Tak pernah sederhana.
“Ayah tadi lihat berita, ada kambing bisa naik motor,” kata Ayah sambil menyendok sayur bening.
“Lho, kambingnya bawa SIM, Yah?” balas Dira, dan kami langsung meledak dalam tawa.
Ada saja yang dibahas. Bahkan topik ringan seperti suara katak pun bisa jadi bahan diskusi panjang. Dan ketika kami sedang makan mie instan bareng, Ayah bisa mendadak serius:
“Kalian harus tahu, makan bareng itu bukan cuma soal kenyang. Tapi soal hadir.”
Saat itu aku masih kecil, dan kupikir “hadir” maksudnya datang ke meja. Tapi sekarang, aku baru paham: hadir artinya benar-benar berada di sana. Menaruh perhatian. Menyimak. Merayakan keberadaan satu sama lain.
Tapi waktu berjalan seperti air—mengalir, membawa, lalu meninggalkan.
Ayah lebih dulu tak hadir. Bukan karena tak ingin, tapi karena dipanggil lebih dulu oleh Yang Maha Memanggil. Dan meja itu... mulai kehilangan suaranya.
Setelah Ayah tiada, kursi ujung itu dibiarkan kosong. Bukan karena tak bisa diisi. Tapi karena tak ada yang sanggup duduk di sana.
Lucunya, setiap kali kami duduk makan, mata kami tetap secara otomatis menoleh ke kursi itu. Seperti masih berharap suara beratnya akan muncul, entah memberi komentar soal berita, atau sekadar menyuruh kami menambah nasi.
Ibu selalu menyajikan lauk lebih banyak, walaupun hanya kami berdua yang duduk. “Kebiasaan, ya,” katanya sambil mengangkat dandang. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar kebiasaan. Itu semacam ritual. Cara diam-diam untuk bilang: kita masih ingin dia ada.
Dira paling sering mengajak teman makan di rumah setelah Ayah tiada. “Biar meja ini tetap ngobrol,” katanya. Dan benar saja, rumah jadi ramai lagi. Tapi tetap, kursi itu tak pernah ia biarkan diduduki.
Suatu hari, salah satu temannya duduk di kursi itu, dan Dira dengan lembut meminta pindah.
“Maaf ya, itu kursinya Ayah.”
Temannya bingung. “Tapi Ayah kamu udah—”
Dira hanya tersenyum. “Iya, makanya jangan diisi dulu. Dia belum pamit betul.”
Kata-kata itu melekat padaku. Belum pamit betul.
Mungkin memang begitu cara kita menjaga kenangan. Bukan dengan menangisi kehilangan terus-menerus. Tapi dengan menyisakan ruang, seolah mereka hanya sedang pergi sebentar. Seolah suara mereka masih akan kembali, bergema di tengah-tengah makan malam yang sederhana.
Beberapa waktu lalu, saat aku pulang ke rumah lama sendirian, aku duduk di meja itu. Meja yang kini agak berdebu, dengan kursi-kursi yang berderit saat ditarik.
Aku duduk di kursiku dulu, lalu memandangi kursi Ayah.
Hening.
Tapi anehnya, keheningan itu tidak menakutkan. Justru menenangkan. Seperti ada kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi sangat nyata dirasa.
Aku lalu membuka kotak kayu kecil di bawah meja, tempat kami dulu menyimpan sendok-sendok tambahan. Di sana, aku menemukan selembar kertas yang terlipat kecil. Kertas itu agak usang, tapi tulisan tangan Ayah masih terbaca jelas:
“Jika suatu hari meja ini sepi, isilah lagi dengan tawa.
Jangan biarkan meja makan hanya jadi perabot.
Ia saksi cinta kita,
dan tempat paling jujur untuk saling memaafkan.”
Aku membacanya berulang-ulang. Kata demi kata. Baris demi baris.
Dan tiba-tiba saja aku merasa... bukan hanya mengenang. Tapi dipeluk oleh kenangan.
Aku menyeduh teh, meletakkan dua cangkir. Satu untukku, satu untuk kursi kosong itu.
Lalu aku bicara. Tentang pekerjaanku. Tentang ibu yang mulai sering lupa letak kacamata. Tentang Dira yang sekarang punya anak.
Aku tahu tak ada jawaban. Tapi rasanya tidak bicara pun akan lebih menyakitkan.
Karena kursi kosong itu bukan simbol duka. Tapi pintu kecil ke masa yang penuh cahaya.
Ketika malam semakin larut, aku beranjak ke dapur, menaruh cangkir di tempat cuci. Kupandangi meja makan untuk terakhir kalinya malam itu.
Dan aku tersenyum.
Karena entah bagaimana, aku percaya... meja itu akan selalu ingat kami. Ingat suara, ingat tawa, ingat doa-doa yang dibisikkan dalam hati saat menatap lauk yang tak seberapa tapi penuh berkah.
Besok pagi, aku akan ajak Ibu sarapan di sana. Dan kali ini, tak akan kutahan air mataku. Bukan karena sedih. Tapi karena bersyukur, pernah punya meja makan yang bukan sekadar tempat makan.
Melainkan tempat pulang.
Dan mungkin itulah kekuatan rumah lama: Tak peduli berapa banyak kursi yang kosong, selalu ada ruang untuk kenangan pulang.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_