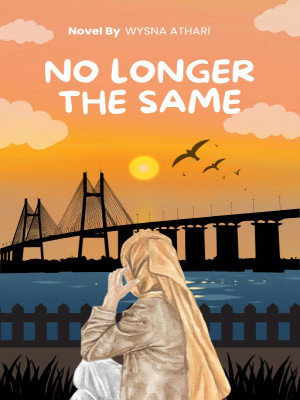Tidak ada yang benar-benar mengajarkan kita cara pulang. Terutama jika yang dituju adalah rumah yang pernah kita tinggalkan dengan hati yang patah.
Dina berdiri di depan pagar besi berkarat itu selama hampir lima menit. Tangannya ragu memegang gerbang yang sudah karatan, matanya menelusuri setiap sisi halaman. Rumput liar tumbuh bebas, sebagian mulai menjulur ke luar pagar, seolah ikut ingin menyapa orang yang baru datang setelah sekian lama.
Di bawah tatapan matahari sore yang hangat, Dina menarik napas panjang. Dadanya berdegup seperti siswa yang menanti giliran maju di depan kelas. Padahal ini cuma rumah. Rumah yang dulu jadi tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat belajar patah hati pertama kali karena nilai matematika merah, dan juga tempat terakhir ia melihat ibunya sebelum berpulang.
Tangannya meraba pot bunga tua di sisi kiri pintu pagar. Tanaman lidah mertua di dalamnya tampak masih kokoh. Ibu memang bilang tanaman itu tahan segalanya, panas, hujan, bahkan ditinggalkan anaknya bertahun-tahun.
Dina mengangkat pot itu pelan-pelan. Di bawahnya, persis seperti yang pernah ibunya ajarkan dulu, ada kunci. Kecil, berkarat sedikit, tapi masih utuh. Dina tersenyum kecil. Masih ada sesuatu yang tak berubah.
“Ibu, kamu benar. Kamu memang selalu tahu aku akan pulang,” bisiknya pelan.
Pintu pagar berderit pelan ketika didorong. Suaranya khas. Suara yang dulu membuat Dina tahu siapa yang datang sebelum mereka benar-benar sampai. Pintu depan rumah masih sama. Catnya sudah mengelupas di beberapa sisi. Tapi gagangnya, kenop bulat berwarna emas kusam itu, tetap ada. Dina memutar kunci, dan pintu terbuka.
Udara lembab langsung menyeruak keluar. Aroma rumah lama. Campuran kayu tua, debu, dan sedikit aroma lavender yang entah dari mana datangnya. Dina berdiri di ambang pintu. Ada jeda kecil di sana antara keinginan masuk dan keraguan akan semua kenangan yang akan segera menyambut.
Langkah pertamanya terasa seperti napas pertama setelah menahan diri terlalu lama.
Ruang tamu itu sunyi. Sofa lama dengan sarung bermotif bunga masih di tempatnya. Meja kayu dengan taplak bordir buatan ibu tetap berdiri di tengah ruangan. Semua seperti museum masa kecilnya, hanya lebih sepi dan sedikit lebih sendu.
Dina menjatuhkan tas ranselnya ke lantai, lalu duduk di kursi rotan pojok yang dulu selalu dipakai ibu saat menyulam. Ia membiarkan dirinya diam. Tak ada suara. Tak ada notifikasi ponsel. Tak ada percakapan. Hanya detak jam dinding yang lambat, seolah waktu di rumah ini juga berjalan dengan ritme yang berbeda.
Beberapa menit kemudian, Dina bangkit. Ia berjalan ke dapur. Ubin-ubin putih dengan bunga merah muda itu masih terjaga, walau ada yang retak di sana-sini. Lemari kayu tua tempat menyimpan piring masih berdiri tegak. Bahkan teko plastik biru yang dulu jadi kesayangan ibu masih berada di tempatnya, meski kini berdebu dan kusam.
Dina mengambil gelas dari rak, mencucinya, lalu menyalakan keran. Airnya keluar dengan suara menyedihkan, seperti mengeluh karena sudah lama tak dipakai. Ia menampung segelas air dan meminumnya perlahan.
Segelas air putih. Tapi rasanya seperti meneguk masa lalu.
Dina menelusuri setiap ruang. Melewati kamar tamu, ruang tengah, dan akhirnya berdiri di depan kamarnya sendiri. Pintu cokelat dengan tempelan stiker yang kini pudar. Dia ingat, dulu setiap kali dapat bintang dari guru kelas, dia akan menempelkan satu stiker bintang di pintu itu. Semakin lama, stiker makin banyak, tapi yang tersisa kini hanya potongan kecil dengan ujung lengket yang sudah kering.
Ia membuka pintu perlahan. Kamar itu seperti dijeda oleh waktu. Masih ada rak buku penuh novel remaja lawas, meja belajar dengan coretan-coretan kecil, dan pigura foto dirinya dengan rambut pendek tak rata. Dina tersenyum kecil, lalu duduk di kasurnya.
Kasur itu kempes di tengah. Mungkin karena dia dulu suka berguling di situ ketika galau remaja melanda.
Ia merebahkan diri. Pandangannya menatap langit-langit kamar, yang dulunya pernah ditempeli glow-in-the-dark stars. Sekarang sudah tidak menyala. Tapi dulu, bintang-bintang itu menemani tidurnya setiap malam. Dia percaya satu dari mereka adalah ibunya yang terus melihat dari jauh.
Pelan-pelan, air mata menetes. Tapi bukan tangisan keras. Hanya air mata yang diam-diam turun, seperti rindu yang tak diundang tapi datang juga. Keesokan harinya, Dina bangun dengan kepala sedikit pening. Ia tak ingat kapan tertidur. Tapi pagi di rumah lama menyambutnya dengan cahaya matahari yang lembut masuk dari celah gorden.
Di dapur, ia mencoba menyeduh kopi. Kopi bubuk tua di toples plastik ternyata masih ada. Walau rasanya sudah berubah, tapi aroma itu seperti membawa ibu kembali sejenak—mengenang pagi-pagi saat ibu menyuapinya roti bakar dan mengomel karena Dina belum mandi padahal sudah jam tujuh. Ia membawa kopi itu ke teras depan. Angin pagi menyentuh kulitnya pelan. Burung-burung bersahutan. Beberapa tetangga yang sudah tua lewat, menatapnya dengan senyum bingung.
Seorang ibu-ibu mengenalinya.
“Kamu Dina, ya?” sapanya dari balik pagar.
Dina tersenyum dan mengangguk. “Iya, Bu. Dina.”
“Udah lama banget nggak kelihatan. Waktu ibumu meninggal, kita kira kamu nggak mau pulang…”
Dina tertawa kecil, getir. “Saya juga kira begitu, Bu…”
Ibu itu tersenyum maklum, lalu melanjutkan jalannya. Sementara Dina, kembali menatap halaman. Ia memperhatikan pot bunga tempat ia menemukan kunci kemarin. Tiba-tiba matanya tertuju pada selembar kertas kecil yang terselip di sela tanah dan pot.
Ia mengambilnya. Sebuah catatan. Tulisan tangan ibu. Halus, rapi, dan penuh kasih.
"Untuk Dina. Kalau kamu baca ini, berarti kamu akhirnya pulang. Terima kasih. Rumah ini tidak lengkap tanpa kamu. Kunci memang ada di bawah pot, tapi hatiku selalu di sini menunggumu."
Tangannya gemetar. Ia menahan napas. Air matanya tak bisa dicegah kali ini.
Kenangan tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Seperti kunci di bawah pot bunga itu terselip, tapi selalu ada. Sejak hari itu, Dina mulai membenahi rumah. Ia menyapu debu, mengepel lantai, mencuci tirai, bahkan memotong rumput di halaman. Ia tidak buru-buru. Satu sudut setiap harinya. Dan setiap sudut membawa kenangan baru yang ia benahi—bukan hanya di rumah, tapi juga di dalam dirinya. Ia juga mulai berbicara pada dirinya sendiri lebih lembut. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menghindar. Ia menulis di buku harian barunya, duduk di kursi rotan ibu, dan menyulam cerita-cerita yang dulu hanya jadi suara di kepala.
Satu malam, ketika ia sedang membaca di ruang tamu, angin bertiup pelan. Pintu depan sedikit terbuka. Dina berdiri, lalu menutupnya perlahan. Sebelum menguncinya, ia menatap ke luar dan berkata pelan, seperti menyapa rumah itu kembali:
“Aku pulang.”


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_