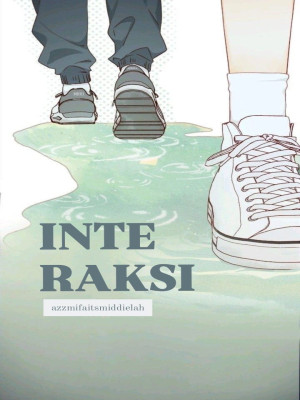Hari Jumat. Hari di mana sekolah biasanya penuh dengan suara tawa yang mulai lelah. Tapi pagi itu, Aditya berjalan lebih pelan dari biasanya. Bukan karena sakit, bukan karena malas. Tapi karena pikiran masih tertinggal di pesan DM semalam. Pesan yang diam-diam takut membuatnya—takut bahwa kata-kata yang ia ucapkan benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu.
Di ruang kelas, Bayu duduk di bangku paling belakang, seperti biasa. Ia sedang menggambar sesuatu di kertas folio bekas. Aku bisa melihat dari balik resleting: garis-garis tipis pensil membentuk sosok anak laki-laki berdiri di tengah hujan, memayungi bayangan dirinya sendiri.
“Lo gambar apa?” tanya Aditya sambil menarik kursi di sebelahnya.
Bayu tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahu. Tapi setelah beberapa detik, dia menoleh.
“Kadang, yang susah itu bukan ngelindungin orang lain… tapi ngelindungin diri sendiri dari pikiran sendiri.”
Aditya diam. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari dalam diriku: catatan kecil warna biru—sisa dari pertemuan Teman Pagi minggu lalu.
“Gue nemu ini waktunya beres-beres,” katanya. “Tulisan lo kan?”
Bayu melirik. Wajahnya merah. Tapi dia mengangguk pelan.
“Gue nulis itu waktu lagi pengin ilang.”
Aditya menghela napas. “Lo tahu kan, lo boleh cerita kapan aja?”
Bayu tersenyum tipis, lalu kembali menunduk.
Setelah istirahat, mereka mengadakan pertemuan kecil Teman Pagi di belakang perpustakaan—tempat favorit mereka sejak dulu. Hadir : Aditya, Saka, Bayu, dan Raka.
Raka datang dengan rambut agak basah karena gerimis, langsung nyeletuk, “Gue ngerasa kayak tokoh utama film indie tiap kali hujan-hujan gini.”
Saka melempar roti secara tiba-tiba. “Tokoh utama yang dibikin penonton skip.”
Tawa kecil meletup. Tapi hanya sebentar.
Aditya mengambil alih. Ia mengeluarkan selembar kertas dan bolpoin.
“Gue pengin kita bikin episode kedua podcast—tapi kali ini, bukan tentang kita. Tapi tentang Bayu.”
Bayu tersentak. "Hah? Kenapa gue?"
"Karena cerita lo penting. Dan lo nggak harus kasih solusi. Lo cuma perlu jujur."
Bayu menunduk. Tapi aku tahu dia mempertimbangkannya.
Sabtu pagi, mereka berkumpul lagi di ruang BK. Bu Ratih membukakan pintu, menyiapkan teh manis dan biskuit kecil di meja.
“Podcast kedua, ya?” tanyanya sambil tersenyum.
Aditya mengangguk. “Tema: Apa yang Gue Simpan Sendirian Selama Ini .”
Rekaman dimulai. Suara Bayu pelan. Tapi jelas.
"Gue pernah ngerasa jadi beban. Di rumah, di sekolah. Bahkan di antara temen-temen sendiri. Gue nggak pernah bilang ini ke siapa-siapa, tapi... ada masa di mana gue berharap besok nggak usah bangun lagi."
Saka dan Raka menjawab. Aditya juga. Bahkan aku, si ransel hitam, bisa merasakan hening yang menekan ruang itu.
Bayu melanjutkan.
"Tapi kemudian, ada satu hal yang bikin gue batal: waktu seseorang duduk di sebelah gue pas istirahat. Dia nggak bilang apa-apa. Tapi dia tetap duduk. Dan buat gue, itu cukup."
Aditya tahu, itu tentang dia.
Bayu diakhiri dengan kalimat:
“Kalau lo yang dengerin ini lagi ngerasa capek, istirahat dulu. Tapi jangan ilang. Karena bisa jadi, ada orang yang masih pengin duduk di samping lo.”
Minggu malam, podcast mereka tayang. Dan kali ini, bukan hanya grup angkatan saja yang membagikannya. Tapi juga akun OSIS, akun sekolah, dan bahkan organisasi kesehatan remaja kota.
Komentarnya berlimpah. Sebagian hanya emoji peluk. Sebagian panjang, bercerita balik. Tapi satu pesan menarik perhatian Aditya:
"Bayu, kalau kamu baca ini... aku juga pernah ngerasa kayak kamu. Tapi aku sekarang mulai belajar bilang ke orang lain. Makasih udah mulai duluan."
Aditya memutar kembali rekaman itu malam harinya. Di punggung, aku tergantung seperti biasa. Tapi bebanku hari ini terasa berbeda.
Bukan buku berat atau laptop. Tapi cerita. Cerita yang dulu hanya diam di kepala seseorang, kini sudah mengalir keluar.
Dan terkadang, menyuarakan luka adalah awal dari penyembuhannya.
***


 bubblejessz
bubblejessz