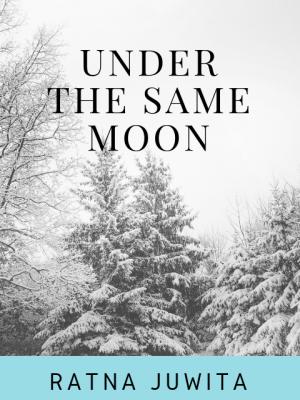Kata yang Tak Pernah Terucap
Langit sore Los Angeles tampak sendu. Di dalam apartemen yang hangat, Nafa duduk di ujung sofa dengan tangan meremas-remas jemarinya sendiri. Zac baru saja menyelesaikan pekerjaannya, dan kini mereka duduk berhadapan dalam keheningan yang berbeda dari biasanya.
> “Zac,” suara Nafa nyaris bergetar. “Aku ingin bicara… serius.”
Zac memandangnya dengan sorot mata yang waspada.
> “Aku dengarkan.”
Nafa menarik napas dalam, lalu menatap Zac dengan mata berkaca.
> “Aku... ingin bertemu Christian. Satu kali saja. Aku tidak sedang bimbang, Zac. Aku tidak akan memilih dia. Aku hanya… butuh menyelesaikan sesuatu yang tertinggal di masa lalu.”
Zac diam. Matanya berkedip lambat.
> “Apa kau masih mencintainya?”
> “Bagian dari diriku akan selalu… mencintainya,” jawab Nafa jujur. “Tapi seluruh hatiku memilihmu. Aku menikah denganmu bukan karena pelarian. Tapi karena kau rumahku. Dan Reagan… dia alasan hidupku.”
Zac memejamkan mata sejenak.
> “Lalu kenapa kau harus menemuinya?”
> “Karena aku tidak ingin hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Aku ingin mengucapkan... selamat tinggal. Dengan benar. Dengan utuh. Supaya aku bisa menutup lembaran itu dan tidak membawanya diam-diam di hatiku.”
Zac menatap Nafa. Hatinya perih, tapi ia juga tahu: cinta tidak selalu tentang kepemilikan mutlak, tapi tentang kejujuran.
> “Apa kau yakin itu tak akan membuka luka baru?”
Nafa mengangguk pelan.
> “Justru karena aku yakin. Luka itu sudah ada, Zac. Aku hanya ingin menjahitnya. Bukan mengorek.”
Zac berdiri, lalu menghampiri Nafa. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan tenang.
> “Pergilah. Katakan semua yang perlu dikatakan. Tapi saat kau pulang… aku ingin tahu kau benar-benar kembali. Sepenuhnya.”
Air mata mengalir di pipi Nafa.
> “Aku akan kembali. Bukan hanya ragaku, tapi seluruh aku. Karena meskipun aku pernah mencintai Christian dengan seluruh hidupku… aku memilih kamu untuk masa depan yang ingin kujalani.”
Zac menunduk, mencium kening istrinya.
> “Hati-hati, Nafa.”
> “And Zac…” suara Nafa bergetar. “Andai waktu bisa diputar, mungkin ceritanya akan lain. Tapi sekarang… aku hanya ingin menutup bab itu dengan cara yang benar.”
Selamat Tinggal, Tanpa Dendam
Senja menumpahkan cahaya emas ke permukaan pantai. Ombak bergulung pelan, seperti tahu bahwa ini adalah akhir dari sebuah kisah yang pernah begitu membara.
Christian duduk di atas batu besar menghadap laut, mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans lusuh. Tatapannya kosong, namun dalam. Mendengar langkah kaki mendekat dari belakang, ia tidak menoleh. Tapi entah bagaimana, ia tahu itu Nafa.
> “Hai,” suara lembut itu menyapa.
Christian berdiri perlahan dan menoleh. Nafasnya tercekat ketika melihat Nafa berdiri hanya beberapa meter darinya, mengenakan gaun putih sederhana dan syal cokelat yang dulu pernah ia hadiahkan.
> “Kau datang,” gumamnya.
> “Aku harus,” jawab Nafa lirih. “Ada hal yang belum selesai.”
Keduanya berdiri dalam diam cukup lama, hanya ditemani suara laut.
> “Aku mencarimu selama lima tahun,” ucap Christian akhirnya. “Setiap hari… aku berharap bisa lihatmu lagi. Mendengar suaramu. Sekadar memastikan kamu baik-baik saja.”
Nafa tersenyum sendu.
> “Aku baik. Aku… bahagia, Chris.”
Christian menunduk.
> “Dengan dia?”
> “Dengan hidupku sekarang,” jawab Nafa pelan. “Dengan anakku. Dengan Zac. Tapi… kamu adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa aku hapus. Aku tidak ingin menghapusmu.”
> “Lalu kenapa terasa seperti aku dilupakan?”
> “Karena dunia memaksaku melupakan,” mata Nafa mulai berkaca. “Aku koma. Aku dibawa ke Amerika. Semua orang mengira kamu… meninggal.”
Christian menarik napas panjang.
> “Aku tahu. Aku seharusnya mencarimu lebih cepat. Tapi waktu itu aku… hancur.”
Nafa melangkah mendekat.
> “Kita tidak salah, Chris. Kita hanya… salah waktu. Salah takdir. Tapi cintamu, bukan sesuatu yang ingin aku lupakan. Aku hanya ingin menyimpannya. Di tempat yang tidak mengganggu langkahku ke depan.”
Christian menatap mata Nafa, yang dulu selalu membuatnya merasa pulang.
> “Kau bahagia?”
> “Ya,” Nafa mengangguk. “Dan aku ingin kau juga bahagia. Tanpa aku.”
Air mata jatuh di pipi Christian, cepat ia seka dengan punggung tangan.
> “Aku pikir… aku akan marah. Tapi nyatanya, aku hanya ingin kau baik-baik saja.”
> “Aku minta maaf karena tidak bisa memilihmu,” ucap Nafa nyaris berbisik. “Tapi aku berterima kasih karena pernah mencintaiku begitu dalam.”
Christian tersenyum, tipis tapi tulus.
> “Dan aku akan selalu mencintaimu… cukup dari jauh.”
Keduanya saling memandang untuk terakhir kali, dalam diam yang mengandung berjuta kata.
Langit senja membias jingga ke permukaan laut. Ombak berkejaran pelan, seolah tak ingin mengganggu dua jiwa yang saling diam di bawah langit yang nyaris menangis.
Christian menatap wajah Nafa dalam hening. Di matanya, ada ribuan kata yang tak sempat tertulis, dan ratusan tanya yang tak lagi butuh jawaban.
> “Nafa…” suaranya serak. “Bolehkah aku… memelukmu? Untuk yang terakhir kalinya.”
Nafa menatap matanya. Ada keraguan, ada luka, tapi juga ada pengertian yang dalam.
Ia mengangguk pelan.
Christian melangkah maju, ragu sejenak, lalu memeluk Nafa dalam diam. Pelukan itu bukan milik sepasang kekasih yang akan bersama, tapi dua jiwa yang pernah saling menggenggam begitu erat, dan kini harus merelakan.
Nafa memejamkan mata di dadanya. Detak jantung Christian masih sama — tenang dan hangat. Aroma kulitnya masih membangkitkan rindu yang pernah membakar dunia mereka.
> “Terima kasih pernah mencintaiku sebegitu tulusnya,” bisik Nafa.
> “Dan terima kasih karena pernah jadi segalanya,” jawab Christian lirih.
Beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup… sebelum akhirnya pelukan itu dilepaskan.
Nafa menatapnya sekali lagi, lalu mundur perlahan.
> “Selamat tinggal, Chris.”
Christian mengangguk.
> “Sampai kita bertemu lagi. Di tempat yang tak lagi melukai.”
Nafa berbalik dan berjalan menjauh.
Christian menatap punggungnya yang menjauh, dan saat itu… air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan. Tapi karena ia tahu, cinta yang sesungguhnya… adalah melepaskan, bukan menggenggam.
Dan pelukan terakhir itu… akan ia simpan sebagai pengingat bahwa pernah, ia dicintai dengan sungguh-sungguh.
Janji yang Ditepati
Dari balik pepohonan, Zac berdiri diam.
Angin laut menerpa wajahnya, membawa serta suara samar dari dua orang yang tak lagi menjadi sepasang kekasih… tapi masih saling memiliki ruang di dalam hati.
Zac melihat bagaimana Christian memeluk Nafa, pelan dan penuh perasaan. Ia melihat bagaimana istrinya memejamkan mata di dada pria itu — bukan dengan pengkhianatan, tapi dengan rasa pamit yang menyakitkan.
Dan meski hatinya terasa ditarik ke ribuan arah, Zac tidak melangkah maju.
Ia menepati janjinya sendiri.
> "Aku tidak akan pernah memaksa kamu untuk melupakan masa lalu. Aku hanya ingin jadi bagian dari masa depanmu."
Kalimat itu pernah ia ucapkan, suatu malam, saat Nafa masih mencoba berdamai dengan luka-luka lamanya. Dan kini, saat menyaksikan perpisahan itu, Zac tahu… ini bukan tentang siapa yang lebih dulu datang. Tapi siapa yang bersedia tinggal bahkan saat hati yang dicintainya retak oleh kenangan.
Saat Nafa berbalik dan berjalan menjauh dari Christian, Zac menoleh pergi, lebih dulu meninggalkan tempat itu.
Bukan karena kalah.
Tapi karena ia tahu, cinta bukan soal memenangkan hati yang dulu pernah hilang, melainkan soal keberanian untuk bertahan — bahkan ketika harus berbagi ruang dengan masa lalu.
Dan ketika Nafa kembali ke rumah nanti… ia akan menyambutnya. Bukan dengan pertanyaan. Tapi dengan pelukan.
Sebab Zac telah memilih: mencintai Nafa, sepenuhnya — dengan masa lalunya, dan dengan semua luka yang dibawanya.


 choujie
choujie