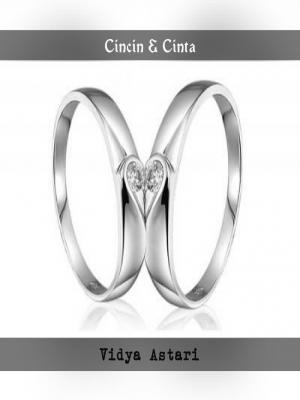Yang Mereka Tidak Pernah Tahu
Sebuah kafe kecil di sudut kota. Musik akustik pelan, aroma kopi pekat mengisi udara.
Titto duduk di pojokan, gelisah. Tangannya berkeringat meski AC menyala dingin. Ia melirik jam, lalu memandang ke arah pintu.
Tak lama kemudian, dua sosok perempuan muncul. Iriantie dengan blazer hitam dan kacamata bulat, rambut disanggul rapi. Emilia menyusul di belakang, mengenakan kaus putih dan jaket jeans, lebih santai.
Mereka duduk, Emilia langsung menyambar minuman di meja.
"Lo manggil kita mendadak banget, Tit. Ada apa sih?" tanya Iriantie, nada curiga.
Titto menatap mereka bergantian, lalu berkata pelan. “Gue nemu orang.”
Emilia mengangkat alis. “Nemu orang? Maksud lo?”
Titto menarik napas dalam. “Christian.”
Sunyi.
Hening beberapa detik. Seolah waktu menahan napasnya.
“…Lo bilang apa tadi?” Iriantie bertanya pelan, hampir seperti takut mendengar jawabannya.
“Gue ketemu Christian. Dia hidup, Rha”
Emilia menatapnya dalam-dalam. “Titto… jangan bercanda soal ini. Kita semua—”
“Gue gak becanda!” Titto memotong cepat, nadanya nyaris gemetar. “Dia berdiri di depan gue. Kita pelukan. Dia cerita. Dia... dia hidup selama ini.”
Iriantie terdiam. Matanya perlahan memerah. “Tapi... kita lihat makamnya, Tit... kita datang ke pemakaman itu…”
“Yang dikubur di sana bukan dia,” ucap Titto lirih. “Dia bilang, dia dipukul dari belakang. Pingsan. Dan yang bawa Nafa malam itu... bukan dia. Itu Marco.”
Emilia mematung. “Lo yakin itu Christian?”
“Kalau lo lihat matanya... lo gak akan ragu. Itu dia. Luka di alisnya masih sama. Bahkan dia masih ingat hal-hal kecil soal kita. Termasuk kejadian terakhir sebelum semuanya berantakan.”
Iriantie menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar.
“Gue gak tahu harus senang atau marah,” gumamnya. “Kenapa dia gak kasih tahu dari dulu?”
“Karena dia koma lama. Gak sadarkan diri berbulan-bulan. Dipindah-pindah rumah sakit, tanpa identitas lengkap. Sekarang dia balik... dan pengen ketemu Nafa.”
Emilia menatap Titto tajam. “Nafa gak tahu?”
Titto menggeleng. “Belum. Tapi... seharusnya dia tahu.”
"Kemungkinan Nafa gak tahu, di gak disini sekarang"
Mereka bertiga terdiam. Di antara gelas kopi dan lampu kuning redup, ada rasa yang selama ini tertimbun bertahun-tahun—mengambang kembali ke permukaan.
Iriantie mengusap pipinya yang basah. “Lo bisa atur ketemu dia lagi, Tit?”
Titto mengangguk. “Bisa.”
Emilia menarik napas panjang. “Kalau gitu… ayo kita ketemu dia.”
Café kecil di ujung gang itu masih sama seperti dulu — aroma kopi kuat, lampu kuning temaram, dan musik jazz pelan yang mengisi ruang hening di sela percakapan. Titto sudah mengabari Emilia dan Iriantie, dan keduanya datang.
Emilia masuk lebih dulu. Langkahnya terhenti di ambang pintu.
Iriantie nyaris menabraknya dari belakang. “Kenapa lo—”
Matanya juga membelalak saat melihat sosok di meja pojok. Pria itu berdiri perlahan, mengenakan hoodie hitam dan topi.
“Christian…?” bisik Emilia tak percaya.
“beneran Christian??,” tanya Iriantie, air matanya jatuh begitu saja.
Christian berdiri canggung, tak tahu harus memeluk atau menyapa. Tapi kemudian Emilia melangkah maju dan memeluknya erat.
“Kami kira lo... udah mati,” suaranya bergetar. “Kami ke pemakaman lo, Chris... kami lihat mayat itu...”
“Aku tahu.” Christian duduk, dan mereka semua ikut duduk. “Dan kalian harus dengar semuanya sekarang.”
Ia menatap mereka, lalu mulai bercerita perlahan.
“Malam itu aku kalah balapan dari Marco.
Aku terluka parah
Dia ambil Nafa, bawa motorku, lengkap dengan jaket dan helm. Kita berdua memiliki tato segitiga yang sama... karena dulu, aku dan Marco adalah sahabat”
Ia menghela napas, menatap tangannya sendiri yang masih membekas luka.
“Malam itu dia membuat kesepakatan sendiri dia ingin memiliki Nafa jika memenangkan balap. Dan hal itu terjadi dia menang dan aku tidak terima. Kita berkelahi aku kalah dan dia bawa Nafa pergi "
Iriantie mengatupkan mulutnya, menahan isak. Emilia masih menunduk dengan tatapan hampa.
“Kevin nemuin aku luka parah di jalan kecil tak jauh dari lokasi kecelakaan. Dia bawa aku ke rumahnya, sembunyiin aku. Aku bahkan gak sadar berhari-hari. Dan waktu aku bangun, aku... pengecut. Aku minta dia tutup mulut. Aku pikir kalau aku muncul, malah nyakitin Nafa lebih dalam.”
“Dan sekarang?” tanya Emilia lirih. “Kenapa muncul sekarang?”
Christian menatap mereka dengan mata penuh luka. “Karena aku gak bisa terus sembunyi. Karena setiap malam aku masih mimpiin dia. Karena aku gak tahu dia... baik-baik saja atau tidak.”
Iriantie menyeka air matanya.
Suasana hening.
Christian hanya diam.
Emilia melanjutkan pelan, “Dia di bawa ke Amerika. Sampai kini kita gak pernah dengar kabar dia lagi"
Christian menunduk. Jemarinya mengepal, tapi ia mengangguk perlahan.
“Aku cuma... ingin lihat dia sekali. Pastikan dia bahagia. Itu aja.”
---
Flashback
Malam Itu, Sebelum Segalanya Berubah
Langit malam masih menyisakan jingga tipis. Mereka duduk berdampingan di atas motor Christian yang terparkir di pinggir tebing, menghadap laut. Angin laut meniup pelan, membawa aroma asin dan sunyi yang tenang.
Nafa memeluk lututnya. Rambutnya beterbangan tertiup angin. Matanya menatap garis horizon.
“Aku suka tempat ini,” gumamnya pelan.
Christian mengangguk. “Gue sering ke sini kalau lagi bingung. Kayak... semua ribut di kepala bisa diem sebentar.”
Mereka terdiam. Tapi bukan canggung—lebih seperti nyaman.
Christian menoleh. Matanya jatuh ke wajah Nafa yang diterangi remang senja. Hatinya berdetak lebih keras. Ia meneguk ludah.
“Naf…”
“Hm?”
“Boleh aku…” Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan, suaranya pelan. “…cium kamu?”
Nafa menoleh. Matanya lebar, seperti tak percaya dia benar-benar mendengar itu.
Christian cepat-cepat menambahkan, “Kalau lo gak nyaman, gue enggak—”
“Boleh,” potong Nafa cepat, suaranya nyaris berbisik.
Christian terpaku.
Matanya mencari mata Nafa.
Lalu ia mendekat perlahan. Perlahan sekali.
Hingga jarak di antara mereka hanya tinggal hembusan napas.
Ciuman itu lembut. Gugup. Tidak sempurna. Tapi jujur.
Seolah dunia berputar lebih lambat hanya untuk memberi ruang pada dua anak muda yang mencoba percaya bahwa cinta bisa dimulai dari tempat yang tak terduga.
Saat mereka saling melepaskan, Nafa menunduk dan tersenyum malu.
Christian menyentuh ujung hidungnya ke dahi Nafa, berbisik, “Makasih…”
Tepian Tebing yang Sama, Tapi Tak Lagi Sama
Christian berdiri di tempat yang sama. Di tepi tebing yang pernah menjadi saksi ciuman pertama mereka. Laut di depannya masih membentang luas, tapi warnanya kelam. Angin yang dulu menenangkan kini terasa menggigit.
Ia memejamkan mata.
Masih bisa ia bayangkan Nafa duduk di sampingnya, kaki menggantung, rambut tergerai, wajah malu-malu saat bilang “boleh”.
Christian tersenyum pahit.
Rasa di dadanya berdesakan. Rindu, sesal, marah pada waktu.
"Kalau gue nggak bawa dia ke dunia gue...
Kalau gue berhenti lebih cepat…
Mungkin… dia masih jadi milik gue sekarang."
Matanya terbuka. Tajam menatap laut, tapi tak benar-benar melihat. Yang muncul adalah bayangan-bayangan: tawa Nafa, mata Nafa, suara Nafa yang selalu bilang “Aku percaya kamu”.
Ia duduk di tanah berpasir, tangannya meremas segenggam rumput liar.
“Apa lo masih ingat tempat ini, Naf?” gumamnya. “Atau… lo udah ngelupain semuanya, kayak semua ini nggak pernah kejadian?”
Laut tak menjawab.
Tapi hatinya—yang sudah lama beku—berdesir perlahan.
Christian menunduk.
Ia mengusap wajah dengan kasar.
Lalu menatap cincin kecil yang dulu sempat ia simpan untuk diberikan… sebelum semua berantakan.
“Gue udah janji mau pulang, Naf. Dan gue pulang.
Tapi sekarang... lo udah tinggal di tempat yang gak bisa gue jamah lagi.”
Matanya berkaca. Tapi air mata itu tak jatuh.
Ia hanya duduk diam.
Di tempat mereka pernah saling percaya.
Di tempat segalanya dimulai.
Dan mungkin... juga berakhir.


 choujie
choujie