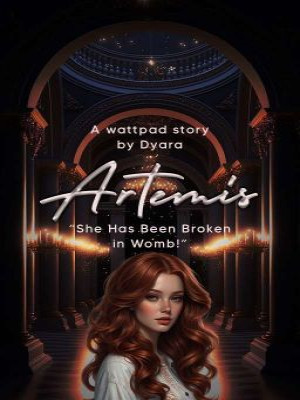“Ayo cepet, nanti kehabisan sayur asem!”
Suara Ibu menggema dari dalam rumah. Masih pukul tujuh pagi, dan aku baru saja selesai menyikat gigi. Damar, dengan kaus lusuh dan rambut awut-awutan, sudah duduk di depan rumah sambil membawa kantong belanja anyaman plastik warna-warni.
“Kita ke Pasar Minggu, nih?” tanyaku sambil merapikan rambut.
“Kalau bukan Pasar Minggu, mana ada yang jual tempe yang rasanya kayak dulu?” jawab Ibu, sambil menggulung lengan bajunya. Wajahnya berseri-seri seperti mau pergi piknik, bukan ke pasar tradisional. Damar mengangguk setuju. “Selain itu, hanya di Pasar Minggu kamu bisa dapat bonus: kenangan masa kecil, gratis.”
Aku tertawa. Ya, memang. Pasar Minggu bukan cuma tempat belanja bagi kami—tapi semacam mesin waktu. Tempat semua hal terasa akrab, bau-bau khas yang mengaduk perut dan hati sekaligus, serta wajah-wajah ramah yang selalu seperti belum berubah dari sepuluh tahun lalu. Kami berangkat naik becak motor. Suara mesin yang berisik itu tak bisa mengalahkan suara hati yang mendadak ceria. Jalanan pagi masih sepi, embun masih menempel di dedaunan, dan langit sedikit mendung, tapi tidak menakutkan.
Begitu sampai di gerbang pasar, semuanya terasa langsung menyambut: aroma daun pisang basah, keringat penjual ayam, suara ibu-ibu menawar, dan denting sendok dari warung bubur.
“Bu Rini!” seru seseorang.
Ibu berhenti sejenak, lalu berbalik. Seorang perempuan setengah baya dengan celemek batik tergesa menghampiri. “Lama nggak kelihatan! Kirain udah pindah kota!”
Ibu tersenyum lebar. “Anak-anak lagi pulang. Sekalian nostalgia ke pasar,” katanya sambil melirikku dan Damar.
“Oh, ini to anak-anakmu? Udah gede, ya Allah!”
Kami hanya senyum-senyum canggung. Tapi hangat. Hangat seperti pelukan yang dikirim lewat mata.
Perjalanan kami menyusuri pasar dimulai dari kios sayur. Ibu selalu punya langganan. Seorang bapak tua dengan wajah keriput tapi senyum lebar, yang tahu cara memilih bayam terbaik tanpa harus ditanya. “Yang ini baru metik subuh tadi,” katanya sambil menyerahkan seikat bayam. “Nggak dikasih plastik ya, Bu Rini, biar nggak lembek.” Di tempat lain, kami beli tempe bungkus daun, tahu goreng hangat, sambal terasi yang bikin mata berkaca-kaca hanya dari aromanya. Dan tentu saja, kue-kue pasar yang berjajar manis seperti sedang saling memikat.
“Masih ada klepon, Bu?” tanya Ibu.
Penjual kue, Mbok Ijah, langsung tersenyum. “Khusus buat Bu Rini, saya sisihin tadi pagi!”
Aku menggeleng takjub. Ibu seperti selebriti di pasar ini. Semua kenal dia. Dan lebih dari itu—semua merindukannya.
Kami berhenti sejenak di pojok pasar, di dekat kios kelontong tua yang dulu sering jadi tempatku ngumpet dari Ibu karena nggak mau pulang.
“Dulu kamu suka ngambek di situ,” kata Ibu tiba-tiba sambil menunjuk kios itu.
Aku tertawa. “Gara-gara nggak dibeliin mainan?”
Ibu mengangguk. “Dan kamu duduk di situ dua jam, sampai akhirnya ketiduran.”
Damar ikut menimpali, “Waktu itu aku pulang sendiri dan bilang ke Ibu, ‘Kakak sudah saya tinggal di bawah rak deterjen.’”
Kami tertawa bersama. Bahkan pemilik kios yang mendengar kami ikut terkekeh. Pasar ini mungkin tak sebersih mal, tak seharum swalayan, atau sepraktis belanja daring, tapi di sinilah semua hal terasa nyata. Di sinilah kita mengingat bagaimana suara tawar-menawar bisa menjadi lagu, bagaimana harga bawang bisa jadi bahan diskusi nasional, dan bagaimana satu pasar bisa menyimpan beribu cerita keluarga. Setelah belanja selesai, kami duduk di warung kecil di ujung pasar. Ibu memesan teh hangat. Damar membeli es cendol. Aku sendiri cukup dengan air putih, karena perut sudah kenyang hanya dari mencium aroma makanan sejak masuk tadi. Seorang anak kecil lewat membawa balon. Aku menatapnya lama.
“Dulu aku juga sering minta balon kayak gitu ya, Bu?” tanyaku.
Ibu mengangguk. “Tiap minggu.”
“Dan Ibu selalu bilang, ‘Kalau kamu jaga balonnya sampai pulang, minggu depan dibeliin lagi.” Ibu tertawa. “Tapi hampir selalu kamu hilangin atau pecahin sebelum sampai rumah.”
Aku menatap meja, terdiam.
“Tapi Ibu tetap beliin minggu depannya...” aku berkata pelan.
Ibu hanya tersenyum. “Karena Ibu tahu, beberapa pelajaran hidup itu butuh diulang-ulang.”
Aku mengangguk. Rasanya kalimat itu bisa disimpan dalam hati untuk seumur hidup.
Saat matahari mulai tinggi, kami berjalan keluar pasar. Trotoar sempit, becek di beberapa tempat, tapi entah kenapa kami semua tak merasa lelah. “Kamu ingat dulu pernah jatuh di sini?” tanya Ibu sambil menunjuk pinggiran jalan.
Aku mengangguk. “Ingat. Aku nangis karena lutut berdarah, bukan karena sakit, tapi karena malu.” “Dan Ayahmu langsung bawa kamu ke tukang es mambo buat nenenin hatimu,” tambah Damar sambil tertawa.
Kami kembali tertawa.
Ya, pasar ini bukan hanya tempat belanja. Ini adalah album keluarga yang tidak tersusun dari foto-foto, melainkan dari bau, suara, dan kejadian-kejadian kecil yang ternyata tak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Sesampainya di rumah, Ibu segera menata hasil belanjaan di dapur. Damar menyalakan radio tua dan lagu lawas pun mengalun lembut dari sudut ruang tamu.
Aku duduk di serambi, membawa sepotong klepon dan secangkir teh. “Pasar Minggu masih seperti dulu,” kataku lirih, pada diriku sendiri. Tiba-tiba Ibu datang membawa bungkusan kecil.
“Ini,” katanya, menyerahkan sebungkus kecil kertas minyak berisi empat butir balon tiup warna-warni.
“Aku lihat di lapak dekat pintu keluar tadi. Ingat ini?”
Aku tersenyum lebar. Air mataku menetes sebelum sempat berkata apa-apa.
“Terima kasih, Bu.” “Kamu nggak harus tiup semua. Tapi... simpan satu buat kenangan,” kata Ibu sambil duduk di sebelahku. Kami diam beberapa saat. Tapi dalam diam itu, hati kami saling bicara, jauh lebih keras dari kata-kata. Hari itu, aku tidak hanya kembali ke Pasar Minggu—aku kembali pada diriku yang dulu. Anak kecil yang mudah menangis karena balonnya pecah. Anak yang selalu dibelikan lagi meski sudah berkali-kali gagal menjaga.
Dan hari itu, aku sadar: pulang tidak selalu soal jarak. Tapi tentang momen-momen kecil seperti ini, yang membawa kita kembali ke siapa diri kita sebenarnya.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_