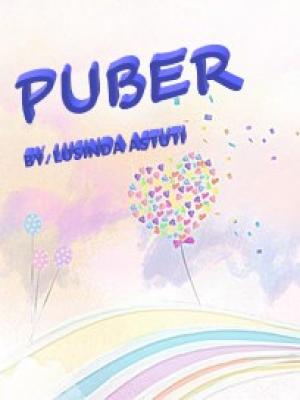“Bang. Oi. Kamu gak ada kelas pagi kah?”
Suara itu terdengar akrab… tapi anehnya seperti datang dari kejauhan. Aku membuka mata perlahan. Plafond Gypsum. Bau sabun cuci piring dari dapur. Tumpukan pakaian di pojok kamar. Kipas angin yang berderit lemah.
Aku langsung duduk. Mataku membelalak.
Ini... kamarku. Bukan. Ini kamar kos. Kamar kosku dan Rizal.
“Bang?” Rizal muncul dari balik pintu, sikat gigi masih nempel di mulutnya “Ngimpi serem ya?”
Aku memegang dada. Deg-degan. “Jal... sekarang tanggal berapa, kita sekarang semester berapa?”
“Lah apaan sih. Emangnya kamu siapa? Doraemon? Hari gini kok nanya tanggal…” Rizal balik lagi ke kamar mandi, suaranya masih bisa kudengar dari dalam, “Semester dua, bang! Baru juga masuk minggu ketiga kuliah!”
Semester dua. Semester dua...
Aku kembali.
Tapi… aku nggak mati. Aku cuma... sujud.
Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna semua ini. Kalau penglihatan masa depanku yang pertama berakhir ketika aku tidur, yang kedua pas aku mati... berarti sekarang?
Aku tersenyum kecil.
Berarti aku bisa kembali tanpa harus mati.
Segala rasa takut dan berat yang menumpuk di dadaku semalam seperti menguap perlahan. Rasa syukur menyesaki dada. Rasanya seperti... diberi kesempatan baru, tapi tanpa harus membayar dengan nyawa.
"Ya Allah..." aku mengusap wajahku. "Makasih. Aku nggak akan sia-siain kali ini."
Rizal muncul lagi, sekarang udah ganti baju. “Eh bang, serius deh. Tadi kamu ngigau apa sih?”
Aku menoleh dengan senyum kecil. “Ngomong-ngomong Jal… kamu pernah kepikiran buat ikut pengajian rutin nggak?”
Rizal langsung pasang muka curiga. “Bang… kamu kerasukan setan tobat kah semalam?”
***
Setelah salat magrib, aku mengajak Rizal pergi ke salah satu masjid yang katanya sering ada pengajian. Informasi dari Rafa, sih. Katanya, “Masjid itu keren banget! Acaranya selalu jalan, ustaznya asik, dan jamaahnya banyak.”
Dan ternyata... benar.
Masjidnya besar. Bersih. Halamannya luas. Suara adzan isya mulai menggema dari menara, bikin suasana jadi tenang banget. Parkiran sudah penuh motor, beberapa orang duduk di serambi depan sambil baca Al-Qur’an atau sekadar ngobrol pelan.
“Ya Allah, bang... aku ada tugas, bang. Laprak!” Rizal mengeluh sambil membuka tasnya, menunjukkan kertas tebal yang sejak tadi dibawanya.
Aku menoleh ke dia. “Selesai dari sini, kamu kerjainnya.”
Rizal memonyongkan bibir, lalu menoleh ke masjid. “Tapi ini... acaranya panjang nggak sih?”
“Paling sejam, setengah dua belas juga kelar,” ucapku sok yakin, padahal aku juga belum pernah datang sebelumnya. Aku hanya nggak ingin kesempatan ini Rizal lewatkan.
“Abang ini ketularan Rapa ya?” tanya Rizal, berjalan di sampingku.
“Ya, begitulah.”
“YUD, JAL!” teriak seseorang dari arah parkiran juga, suaranya jelas banget, itu Rafa.
Aku dan Rizal serempak menoleh, benar saja. Kenapa nih anak ada di sini juga. Hmmm wajar sih, kan dia yang ngasih rekomendasi kesini.
Rafa berlari kecil menghampiri kami, hijab pashminanya rumit namun rapi seperti biasanya, dan tangan kirinya menenteng tote bag gede yang isinya entah apa. Nafasnya sedikit ngos-ngosan, tapi senyum lebarnya nggak ilang-ilang.
“Masya Allah! Aku tuh baru mau WA kalian, eh malah ketemu langsung di sini!” katanya sambil nyengir lebar.
“Loh, kamu sendiri atau sama temenmu?” tanyaku sambil salaman.
“Sendiri lah, temenku pada bilang ngantuk. Emangnya aku bocil apa butuh temen buat ngaji?” jawabnya dengan gaya sok dewasa, yang malah bikin Rizal ketawa ngakak.
“Wah Rafa, kamu jadi panutan banget. Nih, aku aja digeret Yudhis ke sini,” kata Rizal sambil menunjukku.
Rafa melipat tangan di dada dan menaikkan alis. “Alhamdulillah. Berarti doaku dikabulin. Kemarin aku doain kalian cepet-cepet dapet hidayah. Tapi aku kira bakal butuh gempa dulu biar kalian nyadar.”
Aku dan Rizal saling pandang, lalu tertawa bareng.
“Eh, tapi serius, Rap,” kataku sambil jalan menuju pintu masjid bersama mereka, “Thanks ya udah rekomendasiin masjid ini. Tempatnya tenang banget.”
Rafa tersenyum, lalu menatap kami agak lama. “Yud, Jal… aku nggak tahu kalian lagi ada masalah apa. Tapi langkah kecil kayak gini tuh... besar banget.”
“Jadi sebenernya kecil apa besar?” tanya Rizal polos, mengernyit.
“Kuhajar ya kamu, Jal. Maksudku dampaknya yang besar!” Rafa menjitak pelan kepala Rizal. Kami bertiga langsung tertawa.
“Itu di tasmu isinya apaan, Rap?” tanyaku sambil melirik tas Rafa yang kelihatan padat.
“Al-Qur’an. Kalian nggak bawa, ya?” jawabnya sambil mengangkat alis. “Ngaji tuh harusnya bawa, jadi kalau penceramahnya nyebut dalil, kita bisa buka. Kecuali kalian udah hafal semua sih.”
Aku dan Rizal saling pandang, lalu mengangguk pelan.
“Lah, terus isi tas kalian apa?” tanya Rafa curiga.
Rizal membuka tasnya. “Kertas laprak… dan permen kopi.”
Aku membuka tasku, lalu terdiam. “Rokok.”
“YUD! Kamu ini mau ngaji atau mau ngewarkop?!”
Kami tertawa lagi, dan Rafa langsung berkata, “Udahlah, mana HP kalian. Biar kuinstalin aplikasi Qur’an digital sekalian.”
Setelah itu kami berpisah dengan Rafa—dia naik ke lantai dua, sementara aku dan Rizal di bawah. Aku masih menatap sekeliling… dan tiba-tiba mataku menangkap sosok yang tidak asing.
Fajar.
Aku langsung tercekat. Dia di sini? Jadi dia memang sering ke masjid ini?
Atau… jangan-jangan dia cuma mau ketemu Rafa?
Kusapa nggak, ya? Dia kan udah kenal aku dan Rizal juga, gara-gara Rafa - ‘sahabat rasa abang’ katanya.
Tapi entah kenapa, melihatnya sekarang, aku jadi teringat lagi mimpi itu. Masa depan Rafa... masa depan mereka. Kalau diingat-ingat kayak dia datang kesini memang murni untuk memantaskan diri. Beruntung ya Rafa ada yang mau memperjuangkan dirinya segitunya.
Tiga puluh menit kemudian, kami sudah selesai salat Isya, dan akhirnya pengajian dimulai.
“Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…” ucap penceramahnya.
Serempak seluruh jamaah menjawab, tidak terlalu nyaring memang, tapi cukup untuk membuat seluruh masjid ini menggema.
Baru lima menit ceramah berjalan, aku menoleh ke kiri—HAHAHAHA RIZAL UDAH TIDUR. Sialan nih anak… kuat banget setannya pasti.
Lima menit kemudian, giliranku yang mulai goyah. Aku sudah menguap tiga kali, dan mata rasanya berat kayak bawa galon. Akhirnya aku menyerah, “Tidur lima menit aja deh,” pikirku sambil merem sebentar.
Semenit.
Dua menit.
Tiga menit.
Tiba-tiba, satu masjid berseru, “Aamiin!”
Aku tersentak. Refleks langsung angkat tangan mengikuti jamaah lain, begitu juga Rizal yang setengah sadar ikut-ikutan. Kami saling melirik. Hampir saja ketawa. Sepertinya sedang doa bersama.
“…Mohon maaf bila ada salah kata, mari bersama-sama membaca doa kafiratul majelis…” ucap penceramah itu.
LAAHHH! UDAH SELESAI. Perasaan aku tidurnya cuma lima menit! Tiga malah! Aku dan Rizal saling tatap dengan wajah paling polos sedunia. Pengajian pertama kami… sukses kami lewati dalam mimpi.
“Bang, kamu ketiduran ya?” tanya Rizal sambil cekikikan.
“Seenggaknya aku lima menit lebih unggul dari kamu Jal, kamu kan baru salam udah tidur.” Kami berdua tertawa.
“Besok kita datang lagi, tapi tidur dulu sejam sebelumnya,” Ucapku.
“Deal. Tapi jangan duduk dekat kipas angin, bang… dingin-dingin gini, ngantuknya double.”
***
Hari Sabtu pagi, Rafa datang ke kos sambil membawa tas belanjaan di tangannya.
“Nih, kubelikan Qur’an, sama notes khusus buat pengajian,” katanya sambil menyerahkan tas Gramedia ke aku dan Rizal—yang tadi baru saja dia cipratin air saat kami masih tidur.
Oh iya, kalau kalian bingung kenapa dia bisa masuk seenaknya, jawabannya simpel: Rafa juga pegang kunci kos ini. Jangan tanya kenapa, kami juga udah menyerah mempertanyakan hidup.
Setelah menyerahkan tas belanjaan itu, Rafa langsung masuk ke dapur. Nggak lama, dia balik lagi bawa dua piring nasi goreng hangat.
“Nih makan dulu. Baru mandi. Habis itu aku mau kenalin seseorang ke kalian.”
Kami berdua masih belum sepenuhnya sadar, tapi hidung kami sudah lebih dulu bangun—tercium wangi nasi goreng kecap yang menghangatkan pagi.
Setelah sarapan dan mandi, kami diajak Rafa pergi ke salah satu kafe—kafe lagi, kafe lagi. Aku sampai hafal aroma setiap kafe di kota ini. Di sana sudah duduk seorang perempuan—entah siapa, dan satu orang laki-laki yang langsung kukenal. Fajar.
“Tuh, kamu bilang mau ketemu, kan?” celetuk Rafa sambil menatap Fajar dengan ekspresi setengah gemas, setengah ngambek.
Fajar berdiri, lalu mengulurkan tangan dengan sopan. “Bang, saya Fajar,” ucapnya dengan sama sopannya dengan gayanya, padahal kami seumuran.
Aku melirik tangan Fajar sekilas, lalu bersandar ke kursi. “Oh, jadi ini yang katanya serius sama kamu, Rap.” Tangannya tetap menggantung di udara. Nggak kugubris.
Sialnya, Rizal malah menyambut uluran itu. “Saya Rizal,” ucapnya dengan senyum kaku.
Dasar nih anak, pura-pura cool dikit kek. Sekali-sekali pasang poker face gitu loh, Jal.
Yang perempuan tiba-tiba ikut bicara, suaranya lembut. “Saya Vania, temennya Rafa.” Ia menunduk sopan, senyumnya ramah.
“Oh iya, saya Yudhis,” sahutku sambil ikut mengulurkan tangan.
Plak!
Tangan itu langsung kena pukul pakai sendok kopi milik Rafa.
“Begitu cewek aja langsung semangat kamu, Yud,” semprot Rafa dengan alis naik sebelah.
Aku garuk kepala sambil nyengir. “Refleks, Rap.”
“Jadi, Bang... saya mau nanya aja. Kira-kira, yang harus saya siapin buat nikah sama Rafa, apa aja ya, Bang?” tanya Fajar, tanpa basa-basi. Suaranya tenang banget, kayak lagi pesen kopi.
UHUK!
Hampir aja kopiku nyembur ke muka Vania. APA DIA BILANG? NIKAH?!
Aku melirik Rizal. Matanya melebar, mulutnya setengah terbuka. Sama syoknya. Bahkan si Vania sempat berhenti ngaduk minumannya.
Bukannya ini... terlalu cepat? Aku aja masih bingung gimana bales chatnya Susan, dia udah mau nikah? Stress nih anak.
“Heh! Emangnya kamu yakin bisa ngejaga rasa itu selama empat tahun? Itu pun kalau kamu suksesnya cuma segitu—bisa aja lebih lama, kan?” tanyaku, nadaku tegas… walau sebenarnya agak dibuat-buat.
“Insyaallah, Bang. Saya yakin… yang saya butuhkan di masa depan adalah perempuan seperti Rafa,” jawabnya kalem. Pinter ngomong, nih anak.
Memang benar, Rafa gak punya sosok ayah atau saudara laki-laki. Satu-satunya yang tersisa cuma pamannya—itu pun entah sekarang di mana. Ibunya? Seorang PNS yang kerja jauh di Kalimantan. Dan dia… udah menitipkan Rafa ke kami—aku dan Rizal.
Tapi… apa itu cukup jadi alasan buat kami nentuin siapa yang pantas buat dia?
Walaupun… aku tahu, anak ini memang serius. Dan diam-diam, aku berharap—semoga, apa yang kulihat dalam mimpiku terakhir (penglihatan masa depan itu)… benar-benar jadi kenyataan buat Rafa.
“Oke, kalau kamu memang serius, kamu harus buktiin,” kali ini Rizal angkat suara. Suaranya datar, tapi matanya berbinar iseng.
“Gimana, Bang? Caranya?” tanya Fajar, masih dengan ekspresi sopan nan tulus.
“Traktir kita selama satu bulan penuh.”
Mata Fajar langsung membelalak. Sementara aku dan Rizal saling lempar pandang—nyengir puas.
“Oi! Hehe… enggak, enggak, dia bercanda kok, Jar…” potongku buru-buru, soalnya Rafa udah melotot.
“DUA BULAN!” lanjutku dengan muka serius.
Rafa langsung nyubit lengan bajuku.
“HAHAHA!” Kami semua ngakak, kecuali Fajar yang cuma senyum kaku, antara pasrah dan bingung.
“Gak kok, Jar. Kalo kamu memang serius sama nih gorila,” aku menepuk bahu Rafa sambil meliriknya nakal, “Kamu cuma perlu buktiin kalau kamu beneran niat. Soal keuangan, bisa kamu siapin dari sekarang. Terus, banyakin ilmu agama. Masa iya mau nikahin ustadzah, tapi kamu sendiri masih buta arah?” Aku menghela napas, lalu melirik Rizal seolah mau lempar kode. “Dan satu lagi…”
Rizal ikut nyengir.
Aku menunduk sedikit, siap melontarkan syarat pamungkas “Traktir ki—”
BRAK!!
Rafa memukul meja.
Aku dan Rizal langsung duduk tegak, jantung rasanya naik ke tenggorokan. Sementara Vania? Malah cekikikan, pura-pura ngelap pipinya pakai tisu.
“E-eh... maaf, gak sengaja,” ucap Rafa datar, tapi matanya kayak bilang: “Coba ulangin lagi, kutimpuk beneran.”
“Hehehe, becanda Rap…” aku kembali menoleh ke arah Fajar “Intinya gak boleh pacarana.” Rafa mengangguk-angguk pelan.
“Iya, pokoknya aku gak mau sama cowo yang. Pertama merokok, kedua gak solat, ketiga suka mainin cewe.” Sambut Rafa “Iyakan Van.”
“Iya Rap, aku juga gak setuju kalo kamu jadi kayak mantanku Jar, aku bahkan hampir masuk penjara gara-gara dia nitip narkoba.” Sambung Vania, kayaknya dia adalah sahabatnya Rafa di UNS.
Eh? Narkoba? Penjara? Kayaknya pernah dengar. Wajar sih kalo aku serinng dengar, memang lagi marak-maraknya kasus mahasiswa terjerat narkoba dan judi online.
Diskusi soal nikahin Rafa terus berlanjut. Gak lama kok—ya… cuma dua jam aja. Tapi dua jam yang isinya full curhatan dari Rafa dan Vania.
Kami bertiga—aku, Rizal, dan Fajar—cuma bisa jadi pendengar setia, kayak audiens podcast yang nggak bisa skip.
“Vania nih ya, Yud,” kata Rafa semangat, sambil nuding sahabatnya, “waktu itu dia bela-belain pertahanin cowok yang gak jelas itu. Duh, cinta emang bikin buta.”
“Hahaha, iyaa…” Vania nyengir lebar. “Untung kamu sadarin aku, Rap. Nggak kebayang kalau waktu itu kamu nggak ada. Pokoknya sekarang aku udah nggak percaya deh sama cowok yang ngajak pacaran!”
“Iya, aku juga nggak percaya…” Rizal ikut-ikutan, nyengir. “Sama cewek yang mau diajak pacaran!”
“Iyaa, aku juga nggak percaya…” giliranku angkat suara, “Sama cewek yang nggak hijaban!”
Aku senggol Fajar, kasih kode biar ikut nimbrung. “E-eh… iya, aku juga nggak percaya sama cewek yang… hmm… yang punya mantan…” katanya ragu-ragu.
BRAK!
Astaghfirullah! Kaget. Rafa tiba-tiba mendebrak meja. Matanya nyala kayak abis denger pernyataan sesat dari ketua sekte.
“Heh! Jangan nilai orang dari masa lalunya ya!” suaranya meninggi. Tegas. Gawat.
“Hayuk kamu Jar,” Rizal malah makin manas-manasin, ketawa cekikikan.
“Eh, sorry, maksudku bukan Vania kok…”Tapi terlambat. Aku baru sadar wajah Vania udah berubah. Pandangannya kosong, senyumnya menghilang kayak ditebas angin.
“Maksudku, hmmm... nggak papa kalo cewenya sudah tobat,” ucap Fajar lebih yakin.
Pernyataan itu berhasil bikin kita ngakak, termasuk Vania. Suaranya kembali ceria, dan tatapannya ke Fajar... nggak sekeras tadi.
Mungkin Fajar bukan tipe yang pinter merangkai kata, tapi dari semua cowok yang pernah duduk bareng sama Rafa, cuma dia yang berani minta izin buat masa depan.
Dan jujur, di antara kami semua, cuma dia yang bener-bener berani mikir jauh.
***
Malam harinya, kami kembali ke masjid tempat pengajian dilaksanakan. Dan malam saat ini lah kami baru tahu kenapa Rafa membelikan kami Al-Quran dan notes ini. Ini adalah kedua kalinya bagiku dan Rizal, dan seperti pengajian yang pertama, kami hanya tidur selama satu jam penuh tadi. Dan sekarang aku juga tahu kenapa Rafa hanya meminta kami datang tiga kali dalam seminggu, mengikuti jadwal dia.
Setelah mendengarkan ceramah (dalam mimpi), Rafa meminta kami berkumpul di halaman masjid. Dia berdiri bersama Vania.
“Mana notes kalian, aku mau liat.” Rafa mengulurkan tangannya.
Aku dan Rizal saling tatap, senyum kecut. Kami mengambil notes kami yang masih mulus—literally belum tersentuh, dan menyerahkannya.
“Masih ada plastiknya?!” suara Rafa melengking, nyaris histeris. “Ngapain dibawa kalo nggak dipake!”
Dia langsung merobek segelnya, membuka notes A5 yang bentuknya lebih mirip diary lucu daripada catatan pengajian.
“Pokoknya minggu depan ini harus ada isinya. Nggak boleh ngasal. Harus sama kayak punyaku...” lanjutnya sambil menyelipkan notes itu kembali ke tas kami.
“Ayo Van,” katanya lagi, meninggalkan aku dan Rizal yang masih berdiri mematung.
Kami menghela napas bersamaan. Bahkan belum sempat membela diri.
Di pertemuan selanjutnya aku dan Rizal sudah menyiapkan strategi.
“Jal, pokoknya kalo aku mulai ngantuk langsung tempeleng ya Jal!” Rizal mengangguk-angguk, aku juga akan melakukan hal yang sama jika Rizal ngantuk.
Namun percuma kami tetap terbangun saan penceramah mulai berdoa.
“Oi! Kamu kenapa nggak bangunin?!”
“Aku juga ketiduran bang.”
Sekarang kami kembali berkumpul di halaman masjid. Rafa dan Vania sudah sejak tadi duduk menunggu di sana, tangannya bersilang, tatapan mereka waspada kayak guru BK habis nangkep murid bolos.
“Mana?” tanya Rafa singkat.
“Nih.” Rizal menyerahkan bukunya santai banget. Lah kok santai banget nih anak?!
Rafa menyandingkan catatannya dengan milik Rizal, membolak-balik halamannya, lalu mengangguk pelan.
KOK BISA?! Bukannya tadi dia ketiduran bareng aku?!
“Yud?” Giliranku. Aku menghela napas, lalu dengan pasrah menyodorkan buku catatan yang... cuma berisi tanggal. Rizal di sebelahku udah gak kuat nahan tawa. Brengsek. Jadi tadi dia gak tidur beneran!
“Jal,” Rafa menatap Rizal, “kamu jelasin ulang materinya ya.”
Rizal menegakkan badan, siap siaga. Vania hanya bisa tertawa melihat penderitaanku.
“Yud, kamu catat penjelasannya Rizal. Jangan cuma nulis tanggal doang.”
Rizal membersihkan tenggorokannya, lalu mulai menjelaskan seperti sedang jadi ustaz dadakan.
“Jadi begini, Yud... yang tadi disampaikan ustadz tuh, intinya jodoh itu udah ditulis. Gak akan ke mana. Tapi...”
Dia mengangkat jari telunjuk, kayak dosen lagi kasih poin penting.
“...bukan berarti kita cuma nunggu sambil rebahan, nonton anime, dan ngarep calon istri tiba-tiba ngetok pintu sambil bawa martabak.”
Aku mengangguk pelan sambil menulis, mencoba terlihat serius, meski kata martabak tadi hampir bikin aku ngakak.
“Usaha tetap harus ada,” lanjut Rizal, “kayak belajar agama, memperbaiki diri, kerja keras, biar kita pantas untuk orang yang juga baik. Jangan minta jodoh yang shalihah tapi diri kita sendiri jauh dari shalat. Itu namanya pengen iPhone, tapi modalnya pulsa darurat.”
“Astaghfirullah!” Vania tiba-tiba menyela sambil nyengir lebar, “Siapa yang kamu maksud nih? Pengen jodoh hijaban tapi pengajian materinya jodoh malah tidur?”
Nih anak kenapa ikut-ikutan, dah?
Aku dan Rizal langsung menoleh. “Heh, jangan bawa-bawa aku!” seruku, pura-pura tersinggung.
Vania tertawa. “Gak nyebut nama loh, tapi kamu yang marah duluan... hmm mencurigakan!”
Rafa cuma geleng-geleng, tapi senyumnya muncul. “Lanjut Jal.”
Rizal melanjutkan, makin percaya diri. “Intinya, jangan panik soal jodoh. Kalau udah waktunya, dia pasti datang. Tugas kita sekarang tuh bukan cari siapa yang mau sama kita, tapi jadi pribadi yang pantas buat didampingi.”
Vania kali ini menimpali lebih serius, suaranya jadi tenang. “Iya, kayak kata Rafa waktu itu... kita tuh harus jadi jodoh yang baik dulu, baru nanti ketemu yang baik juga. Bukan nunggu diselamatin, tapi siap buat saling menyelamatkan.”
Kami semua diam sebentar. Kata-kata Vania tadi... dalem juga. Aku melirik catatanku. Baru dua kalimat.
Rizal menoleh, “Udah berapa yang kamu tulis, Yud?”
“Eh, kamu jelasinnya nggak bener ya, jadi aku cuma tulis segini…” aku memperlihatkan catatanku yang baru empat baris “kan intinya jodoh nggak akan kemana, kan Rap.” Aku menoleh ke arah Rapa.
Rapa hanya tertawa pelan “Hahahaha, iya iya, jadi mulai besok kita gini terus ya, besok yang ngerangkum materi Yudhis, terus aku, abistu Vania.” Jelasnya
Kami menangguk, sepakat.
“Besok awas kamu tidur lagi, Yud,” celetuk Rafa sambil melirik tajam tapi senyum-senyum.
Aku langsung menoleh ke arah Rizal. “Eh, anak dajjal! Jangan-jangan tadi kamu sengaja biarin aku ketiduran ya?”
Lalu aku menatap Rafa. “Eh, Rap. Tadi tuh sebelum ke sini, kita udah buat strategi. Kalau aku mulai ngantuk, Rizal harus bangunin. Kalau dia yang ngantuk, aku yang bangunin. Tapi eh... si sok pintar ini malah pura-pura tidur. Padahal nyatet!”
“HAHAHA, PARAH BANGET!” Rafa ketawa lepas.
Vania ikut ngakak sambil nutup mulut pakai jilbabnya, dan Rizal? Udah ketawa sambil pegangin perut. Emang dasar licik, tapi lucu.
Setelah semua tawa reda dan kami mulai membenahi sandal untuk bersiap pulang, aku berdiri agak menjauh sebentar. Malam mulai turun, langit mendung, tapi anginnya pelan dan menenangkan.
Rizal masih ribut sendiri sama Vania, Rafa sibuk merapikan notes. Dan aku... Aku malah kepikiran Susan.
Mimpi itu muncul lagi di kepalaku. Mimpi gila. Mimpi buruk.
Aku dan Susan. Hamil duluan. Berantakan.
Dulu aku anggap itu sebagai tanda untuk menjauh. Tapi sekarang… entah kenapa rasanya beda. Bukan lagi soal menjauh. Tapi soal menyiapkan diri.
Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. Mungkin bukan Susan yang salah. Mungkin justru karena dia jodohku, Tuhan kasih penglihatan itu biar aku nggak main-main. Biar aku tahu, jalan menuju dia tuh panjang dan penuh ujian. Dan aku harus berubah, harus siap, sebelum benar-benar bersanding sama dia.
Aku nggak bisa jadi pacarnya. Aku juga nggak bisa terus mikirin dia sambil hidup asal-asalan. Kalau aku mau Susan jadi akhir yang benar, aku harus mulai dari awal yang bener juga.
Dan tiba-tiba, semuanya jadi lebih jelas. Bukan tentang takut mengulang mimpi buruk.
Tapi yakin: kalau aku jaga diriku sekarang, mimpi itu gak akan jadi kenyataan. Karena jodoh nggak akan ke mana, selama aku nggak kemana-mana dari jalan-Nya.
Aku menatap langit. "InsyaAllah, Su... kita ketemu di waktu yang bener, dengan cara yang bener."
Aku senyum sendiri. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena aku tahu: aku nggak lagi lari dari masa depan. Aku lagi jalan ke arahnya—pelan, tapi pasti.
Tapi… emang bener ya jodohku Susan? Kan mimpinya gak nyampe aku nikah?
Entahlah.
Siapapun jodohku nanti, satu hal yang pasti : dia gak boleh ketemu Yudhis versi brengsek.
Kalau Rizal mah udah jelas jodohnya Anti. Aku bahkan sudah pernah ketemu sama Ellena – anak mereka berdua.
Tenang aja, Ti. Mulai sekarang, Rizal kupastikan nggak akan melenceng ke jalan yang salah.
***
Satu minggu kemudian, acara IMM akhirnya dilaksanakan di kampus, nama acaranya ‘Panggung Budaya’. Aku meng-handle sebagian besar persiapannya—mulai dari desain panggung, koordinasi dengan panitia dekorasi, sampai menyusun urutan penampil. Sempat ada perubahan urutan, tapi semuanya masih terkendali.
Saat ini kami sedang briefing panitia. Dipimpin oleh Nabil—ketua angkatan sekaligus ketua panitia. Tapi tetap aku yang menyampaikan detail teknis pelaksanaan. Dan Susan… dia banyak membantuku, sering nanya hal-hal kecil, tapi tetap penting. Misalnya...
“Yud, ini sound dari seni tari FKIP udah dikirim belum?”
“Oh iya… kemarin udah kutanyain sih, tapi belum ada respons.”
Ketika acara dimulai, aku standby di belakang panggung bersama beberapa panitia lainnya. Termasuk Susan—meskipun dia bendahara, hari ini dia bertugas membagikan uang pembinaan ke para penampil.
Acara IMM berjalan lancar... sampai giliran penampilan drama musikal dari prodi Sastra.
“Yud, kamu udah bener kirim file musik mereka ke operator?” tanya Susan panik, saat kami sama-sama ngecek rundown.
“Eeh...” aku celingukan. “Harusnya udah sih, semalem aku kirim via Google Drive—eh tapi itu belum ke-download ya?”
“YUDHIS!”
Dan benar saja, saat rombongan drama sudah naik panggung, musiknya... tidak muncul. Lampu panggung sudah menyala, aktor-aktornya sudah ambil posisi, tapi backsound-nya? Hening.
Semua panitia panik.
“Ada file backup-nya nggak?!” teriak Nabil dari depan.
Aku menoleh ke Rizal, yang dari tadi sibuk di belakang sound system. “Jal, kamu bawa flashdisk aku nggak?”
Rizal dengan tenang menjawab, “Aku kira kamu yang bawa.”
DEG.
Aku langsung lari ke ruang transit, nyari file di laptop, tapi... laptop-nya Susan. Dan Susan nggak bawa kabel USB.
“Udah, improv aja, kasih musik random dulu, yang penting gak kosong!” teriak seseorang.
Dan Rizal? Dengan polosnya memutar lagu dangdut koplo.
Lagu bergema keras di seluruh ruangan, sementara para aktor drama musikal yang mengenakan toga dan jubah era Yunani kuno langsung saling pandang, panik.
Satu di antaranya tetap jalan ke depan dan mulai berakting... dengan ekspresi penuh penderitaan... diiringi musik “Lagi Syantik.”
Penonton? Pecah tawa.
Panitia? Panik setengah mati.
Aktor-aktor? Merasa harga dirinya hancur.
Sampai akhirnya Nabil berdiri di depan panggung, mematikan musik secara paksa, dan minta maaf atas “kesalahan teknis yang tidak bisa dihindari karena... Rizal dan Yudhis.”
Aku dan Rizal disuruh berdiri di atas panggung, disuruh minta maaf. Kami membungkuk, malu-malu tapi ketawa-ketawa.
Rizal berbisik di sampingku, “Yud, ini kayaknya kita masuk blacklist panitia acara selanjutnya.”
Aku mengangguk. “Tapi penontonnya puas hiburan gratis.”
Aku kembali ke belakang panggung dan akhirnya momen itu terjadi… di mana aku duduk berdua dengannya. Di tengah hiruk-pikuk acara, kami sempat punya jeda. Singkat, tapi cukup bikin suasana jadi... berbeda.
“San.”
“Iya, Yud?”
Aku menarik napas. “Mungkin ini terlalu cepat, tapi kamu mau nggak… nunggu aku sukses?”
“Hah?! Maksudnya? Nungguin kamu sukses? Kamu lagi bahas apa, Yud?”
...
...
MALUUU BANGET! KENAPA AKU NGOMONGNYA SEAKAN-AKAN DIA BENERAN SUKA!?
Oke, tenang Yud. Gas aja deh, udah kepalang tanggung!
“E-eh, maksudnya… aku mau ajak kamu nikah.”
Susan tersentak. Tentu saja dia terkejut. Tapi kemudian dia tertawa kecil. “Hahah, Masya Allah. Nggak nyangka kamu seberani ini, Yud. Tapi… sebagai perempuan, aku ragu lho, kamu bisa nahan rasanya.”
DEG!
Di tengah-tengah kebisingan ini, suara Susan tetap terdengar jelas di telingaku. Kata-katanya… persis seperti yang pernah kuucapkan ke Fajar. Iya sih—laki-laki memang terkenal mudah beralih.
Tapi aku menatapnya mantap. “BISA! Tinggal minta ke Allah kan, ya?”
Susan tersenyum. Lama. Lalu ia mengangguk pelan. “Kalau kamu yakin… semoga Allah mampukan.”
Aku tersenyum lebar. “Itu artinya kamu mau, San?”
Susan menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. “Jodoh itu rahasia Allah, Yud. Kita cuma bisa berdoa... bukan dengan menyebut nama, tapi minta yang terbaik. Karena menurut kita baik, belum tentu begitu juga menurut Allah.”
INI SEBENARNYA AKU DITOLAK APA DITERIMA SIH?!
“Tapi—”
“YUD, DIPANGGIL NABIL TUH DI DEPAN!”
Suara Dimas tiba-tiba terdengar dari ruang transit, berusaha mengalahkan dentuman musik yang sedang diputar.
“Oh iya—iya.” Aku segera beranjak.
Sial. Sekarang aku nggak tahu deh... perasaan Susan sebenarnya gimana.
Sampai acara selesai, aku dan Susan sudah tidak pernah membahas hal tersebut, bahkan sampai seterusnya.
Entah karena malu, atau karena kami sama-sama tahu—ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menggantung, daripada dipaksakan mengikat.
Tapi sejak malam itu, aku nggak pernah lagi bercanda soal cinta.
Bukan karena aku patah hati. Tapi karena untuk pertama kalinya… aku merasa, perasaan bisa seserius itu.


 saputera
saputera