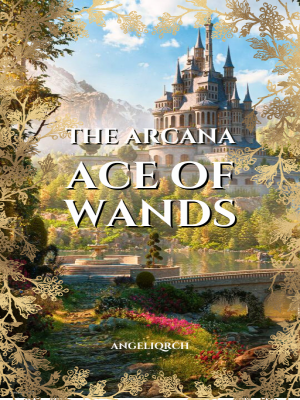Satu minggu berlalu setelah band bubar, dan jujur saja, aku masih merasa aneh. Biasanya, setelah pulang sekolah, aku nongkrong sama anak-anak, ngobrolin hal nggak penting sambil nunggu magrib. Sekarang, rutinitas itu hilang. Aku masih sering bareng Agung—teman sebangkuku—tapi tetap nggak sesering dulu.
Tyas dan Rafli? Kami kayak orang asing sekarang. Kalau nggak sengaja papasan di kantin atau lorong kelas, kami cuma saling melirik sekilas lalu pura-pura sibuk. Nggak ada sapa, nggak ada obrolan. Aneh. Tapi ya, mungkin memang harus begini.
Di tengah semua perubahan ini, ujian pekan depan jadi satu-satunya hal yang bisa kupikirkan. Aku bukan tipe yang rajin belajar, tapi Pak Byan bilang ada satu buku yang bisa ngebantu banget buat ujian sekolah, bahkan buat persiapan masuk perguruan tinggi.
Jujur aja, aku masih nggak yakin mau kuliah atau nggak. Bahkan kalaupun iya, aku belum tahu mau ambil jurusan apa. Tapi entah kenapa, hari ini aku kepikiran buat pergi ke toko buku. Kalau buku itu memang sebagus yang dibilang Pak Byan, mungkin ada gunanya buatku.
Maka dari itu, saat ini aku sedang berdiri di depan toko buku, menatap papan namanya yang elegan. Desainnya modern, luas, dan yang paling penting: ada AC. Sempurna untuk kaum-kaum berdarah tipis yang nggak kuat panas.
Begitu masuk, aku langsung menuju rak akademik, berharap bisa menemukan buku sakti yang direkomendasikan Pak Byan.
Di antara deretan rak tinggi itu, aku melihat seorang cowok berdiri, asyik membaca sambil menopang buku dengan satu tangan. Bajunya biasa aja, tapi auranya... ngeselin.
Lah, kenal nih muka.
Aku melotot, mencoba memastikan. Itu kan Rizal!
Dari semua orang yang bisa kutemui di kota ini, kenapa harus dia? Aku baru aja ngelihat versi dewasanya di ‘penglihatan masa depan’, dan sekarang versi bocahnya ada di sini? Bentar, kalo gitu ITU BUKAN MIMPI DONG!?
Jantungku langsung ngebut. Aku berdiri di sampingnya, berusaha menyapa dengan santai.
"Lagi baca apa, bre?"
Wah, sok asik banget aku barusan. Sumpah, malu sendiri.
Rizal muda tetap membaca tanpa menoleh. Lalu, dengan suara datar tapi penuh penghinaan, dia menjawab:
"Gak punya mata apa gak bisa baca, Bang?"
Anjing, ini bocah kenapa ketus banget!?
Aku menahan diri biar nggak ambil ensiklopedia dan nimpuk kepalanya. Oke, tarik napas. Aku harus tetap ramah.
"Hahahaha, aku liat kok. Lagi persiapan ujian ya?"
"Gak juga," jawabnya, tetap nggak ngelirik.
Astaga, pengen banget aku tabok nih anak pake buku "Matematika Dasar Untuk Pemula" biar dia sadar kalo kesopanannya perlu di-upgrade!
Aku mendekat sedikit. "Sering ke sini?" tanyaku lagi, mencoba menggali informasi.
"Sering," jawabnya pendek, tanpa niat buat ngembangin obrolan.
"Sering beli buku juga?"
Rizal akhirnya menoleh. Dia menatapku lama, lalu tertawa kecil, kayak baru denger lelucon paling goblok di dunia. "Beli? Nggak lah, Bang. Aku mah baca aja di sini, abis itu pulang. Duit dari mana?"
Aku bengong. INI ANAK NGUTANG ILMU!?
"Jadi... kamu baca buku akademik sambil berdiri gini tiap hari?" tanyaku heran.
Rizal mengangguk santai. "Iya. Mau gimana lagi? Pendidikan mahal, Bang. Tapi ilmu gratis asal nggak ketahuan satpam."
Aku hampir tepuk jidat. Ini bocah bukan cuma ngeselin, tapi juga jenius dalam kemiskinan.
Aku mendengus pelan. "Gila, kamu lebih parah dari mahasiswa yang fotokopi buku kuliah tanpa beli. Ini mah mode ultra hemat."
Rizal nyengir bangga. "Hemat pangkal kaya, Bang."
"Ngomong gitu, tapi tetap miskin," timpalku.
Kami bertatapan beberapa detik. Lalu, entah kenapa, malah ketawa bareng.
Kapan pun, di mana pun, Rizal tetaplah Rizal.
“Namaku Yudhis,” ucapku santai. Kali ini, sudah tidak ada kecanggungan di antara kami.
Rizal menyambut uluran tanganku dengan ekspresi setengah malas. “Aku Rizal.”
Aku mengangguk, lalu menatap tumpukan buku di tangannya. Bocah ini beneran serius belajar, ya?
“Jal, ayo ke kafe, bawa aja nih buku. Kubayarin,” tawarku.
Mata Rizal langsung berbinar. "Beneran, Bang?"
Aku pura-pura langsung berbalik badan. "Gak jadi, deh."
"Eh, jadi! Jadi! Baperan amat sih jadi orang!" Rizal buru-buru narik ujung bajuku, ekspresinya panik. Aku nyengir puas.
Sekarang aku sudah berdiri di depan kasir, membayar buku yang sudah kupilih. Dan Rizal...
ANAK SETAN. KENAPA DIA AMBIL EMPAT BUKU SEKALIGUS!?
Kapan dia sempat ngambil buku-buku ini!?
Mbak-mbak kasir mulai menghitung total harga buku. Aku sudah pasrah.
"Semuanya 556 ribu, Kak."
Ya Allah, kemarin-kemarin aku gak pernah ke toko buku. Sekalinya datang, malah ketemu si maniak belajar ini.
Aku melirik Rizal yang tampak santai seolah ini bukan uangku yang melayang. Bocah ini benar-benar berbakat dalam seni menghabiskan uang orang lain.
***
“Bang, ini aku boleh pesan apa aja?” Tanya Rizal sambil melihat-lihat buku menu. Kami sudah sampai di kafe yang tidak terlalu besar, namun desainnya cukup indah dengan tema alam. Meski tanpa AC, dengan diberi banyak bukaan, ruangan ini tetap sejuk, ditambah ada area outdoor yang mengarah ke taman dengan kolam kecil.
Aku melotot. “NGGAK BOLEH! Pesan es teh aja satu.” Enak aja dia mau pesan apa aja. Uangku sudah hampir habis sekarang gara-gara beli buku yang sedang ada di tas ransel si kutu buku ini. Jadilah kami hanya memesan dua es Teh.
“Yaelah bang, kafe bagus-bagus gini cuma minum es teh.”
“Uangku udah sekarat ini.”
“Berrr!... itu suara perutku bang.” Ucap Rizal setelah menciptakan suara itu dengan bibirnya sendiri, dia kira aku anak TK apa?
Aku mengangkat buku menu kemudian berkata, “Kamu mau kuhantam buku menu apa gimana?”
“HAHAHA, becanda bang.”
“Eh Jal, panggil aku pake nama aja napa, kita kan seumuran.”
“Beda bang, kita memang sama-sama kelas 3 SMA, tapi aku kelahiran 2007.”
“Lho, kok bisa?”
“Kecepetan sekolah.”
Aku terdiam sejenak, menatap ngeri Rizal. “Jadi kamu bocil ya.”
“Beda setahun doang bang, gak usah sok tua gitu deh. Cukup muka yang tua.”
Mau Rizal yang sudah tua ataupun Rizal yang masih muda, kebiasaannya tidak berubah. Setelah itu kami mengobrol banyak tentang dirinya Rizal, dan ternyata memang persis seperti yang Rizal Tua ceritakan padaku saat itu.
Saat ini Rizal sedang terpisah dari Ibunya, dia tinggal di kos yang murah agar tidak jauh dari sekolah, karena di kampungnya belum ada SMA, jadilah dia pergi ke Balikpapan untuk bersekolah, sekolahnya ternyata tidak jauh dari sekolahku. Dia tidak memiliki keluarga di sini.
Cita-cita Rizal cukup sederhana, ia ingin punya kerjaan bagus kemudian membantu ibunya. Beberapa minggu terakhir ia bahkan tidak pernah bolos pergi ke toko buku tadi hanya untuk membaca di sana. Dan ternyata mba-mba cantik tadi juga sudah sangat mengenalnya.
Tujuan hidup Rizal cukup jelas. Terus kenapa dia bisa terjerumus ke lingkungan yang buruk gitu, ya? Harus ku tes nih anak.
“Jal, kamu merokok gak?”
“Gak bang, masih suci aku.”
“Halaah, lebay amat lu, nih rokok. Cobain.” Aku menyodorkan sebatang rokok ke arahnya.
Rizal hanya melirik sekilas. “Gak mau bang.” Kemudian lanjut membaca buku yang sudah ia baca sejak 5 menit lalu.
“Kalo kukasih 10 ribu buat nyobain ini, kamu mau?”
“Mau abang kasih berapapun tetap kutolak bang.”
“Seratus Ri…”
“MAU!”
Astaga, tanpa pikir panjang. Pantesan mudah terjerumus, sekarang aku tahu bahwa Rizal adalah orang yang imannya lemah alias tidak punya pendirian. “Buset, gitu doang dah terpengaruh kamu, Jal, Jal. Nih, dengerin abangmu ngomong…” Aku menepuk pundaknya sok bijak. “Cowok itu harus punya pendirian. Kalo dari awal nggak mau, ya sampai akhir pun nggak mau!”
Rizal mengangguk-angguk seolah tercerahkan.
“Tapi Bang...” Dia menyipitkan mata. “Bukannya Abang juga gitu?”
Aku langsung terdiam. Astaga. Aku sendiri kan nggak punya pendirian.
Setelah itu, kami ngobrol santai sampai es teh kami habis, bersamaan dengan topik yang ikut menguap. Kami pun memutuskan untuk meninggalkan kafe itu.
Di perjalanan pulang, aku masih mikir—apa hanya dengan ini Rizal bisa benar-benar terhindar dari lingkungan buruk nantinya?
Rizal berjalan di sampingku, sesekali masih membaca buku yang tadi kubelikan.
“Bang, makasih ya. Akhirnya bisa baca sambil tiduran di kos. Nggak perlu pegal berdiri di toko buku lagi.”
Aku tertawa kecil. “Baguslah. Tapi inget, buku nggak bikin sukses kalau cuma dibaca doang, Jal.”
“Tenang aja, Bang. Aku nggak cuma baca, aku serap sampai ke tulang.”
Aku menggeleng, senyum tipis. “Sombong amat.”
Kami berhenti di perempatan kecil. Kos Rizal ada di gang kanan, rumahku lurus ke depan.
“Yaudah, Bang. Aku duluan. Besok kita ketemu lagi, kan?”
Aku angkat tangan santai. “Tergantung, kalau kamu nggak berubah jadi kriminal duluan.”
Rizal ngakak, lalu melambaikan tangan dan belok ke gang. Aku memerhatikannya sebentar sebelum jalan lagi.
Mungkin ini awal yang baik. Tapi tetap saja... apa ini cukup?
***
Keesokan Harinya
Aku ngajak Rizal belajar di rumah. Biar dia nggak masuk lingkungan toxic, sekalian aku manfaatin otaknya buat ngajarin pelajaran yang aku sendiri nggak kuasai. Win-win solution, kan?
Kami duduk di ruang tengah. Buku-buku berantakan di meja. Aku mencoba baca buku biologi, tapi otakku kayak menolak keras.
Aku melirik halaman dengan judul besar, lalu nyeletuk:
“Osteoporosis itu bukannya hubungan saling menguntungkan itu, Jal?”
Rizal langsung noleh, ekspresinya kayak habis denger hal paling bodoh sealam semesta.
“Itu simbiosis mutualisme, BANG!”
Biasa aja kali, nggak usah pakai bentakan! Ingin rasanya teriak ke telinganya, tapi kuurungkan. Sayang banget kehilangan guru privat gratis.
“Oh iya iya,” ujarku pura-pura paham.
Rizal menghela napas dan kembali baca. Sementara itu, perutku mulai protes.
“Bang, ambil air di mana ya?” tanyanya tiba-tiba.
Aku langsung berdiri dan teriak ke arah dapur, “MAAAK! RIJAL LAPAR, MAK!”
Rizal melotot, ekspresinya antara panik dan emosi. “Eh, sialan kamu, Bang! Aku cuma nanya air, bukan minta makan!”
Aku cengengesan. “Udah terlanjur. Liat aja gimana reaksi emak.”
Langkah kaki terdengar dari dapur. Mamak muncul, bingung.
“Nah, itu dia,” bisikku.
Mamak mengusap tangan dengan celemek. “Siapa yang lapar?”
Rizal buru-buru angkat tangan. “Saya nggak lapar, Tante. Sumpah. Ini Yudhis bohong.”
Mamak melirikku. “Kamu iseng lagi, Yud?”
Aku tertawa, tapi tiba-tiba perutku bunyi keras. Mamak mendengus. “Yaudah, tunggu. Mamak lagi goreng tahu.”
Aku menoleh ke Rizal dengan kemenangan. “Tuh, kan. Dapet makanan.”
Rizal menarik napas panjang. “Kenapa aku mau-mau aja belajar di sini, ya?”
Kami lanjut belajar sampai malam. Tapi ya, tetap diselingi drama.
“Tunggu, tunggu...” Rizal memijat pelipis. “Bang, kamu baru tahu kalau gravitasi itu ditemukan Newton?”
Aku mengangguk polos. “Iya, kirain dari dulu udah ada.”
Dia menatap langit-langit, putus asa. “Astaga... aku kira abang cuma malas, ternyata abang juga...”
“Ternyata aku apa?”
“Nggak, nggak jadi.”
Tapi waktu sampai ke matematika, ekspresinya berubah.Dia periksa pekerjaanku, menyipitkan mata. “Weiss, kok bener semua? Nyontek Google ya?”
“Enak aja! Aku tuh jenius, cuma malas.”
Rizal mendengus. “Iya deh, percaya...”
Saat kami masih belajar, Mamak datang dengan daster andalan. Langsung duduk di samping Rizal.
“Kenapa kamu nggak datang dari dulu, Jal? Baru kali ini Tante lihat dia belajar,” katanya sambil melirikku.
Astaga, kenapa emak segampang itu membuka aib anaknya?!
Rizal menahan tawa.
“Mak, ini bukan pertama kalinya aku belajar,” protesku.
“Iya, iya. Waktu SD juga pernah, pas ujian naik kelas.”
Rizal langsung ngakak.
TOK TOK!
“Assalamualaikum, wuih, rame amat,” suara Bapak.
“Waalaikumsalam. Ini temennya Yudhis belajar,” jawab Mamak, lalu menambahkan, “Tumben kan, Pak? Biasanya cuma nyanyi-nyanyi nggak jelas.”
Aku sudah pasrah. Biarlah Rizal tahu kebiasaan rumah ini memang menjatuhkan harga diriku secara kolektif.
Bapak ikut nimbrung. “Wahaha, jangan gitu, De. Yudhis dari dulu rajin belajar, kok. Dia...”
Aku terharu, akhirnya dibela!
“...belajar main game, belajar merokok, belajar kabur dari rumah.”
Lupakan.
Rizal sampai batuk nahan tawa. Aku hanya bisa memandang jendela dan berpikir: Ya Allah, kapan aku diangkat jadi anak raja?
“Udah ah, jangan ganggu. Aku mau fokus belajar,” ujarku, sok ngambek.
Mamak tertawa. “Yee, gitu doang ngambek. Nih, Mamak masak, sekalian nunggu Bapak tadi.”
Rizal menyipitkan mata, curiga.
Aku melirik. “Kenapa liat aku gitu?”
“Bang... cara ngomong abang sama Tante mirip banget, ya?”
Bapak langsung nyeletuk, “Hahaha, ya iyalah. Anak mamaknya dia.”
Jokes bapak-bapak detected.
***
10 menit kemudian, kami duduk di meja makan. Aroma sayur lodeh dan ayam goreng memenuhi ruangan.
“Wih, masakan Tante enak banget,” komentar Rizal sambil nyendok nasi.
“Ya iyalah. Makanya sering-sering mampir,” jawab Mamak bangga.
“Waduh, nanti aku diangkat jadi anak beneran nih,” katanya sambil nyengir.
Aku ikut nyengir. “Nggak apa-apa, biar aku ada temennya. Dari dulu aku minta adik, tapi Mamak nggak mau.”
Bapak menimpali, “Itu bukan nggak mau, tapi takut adiknya kayak kamu juga.”
Rizal hampir keselek gara-gara ketawa sambil makan. Aku mendengus. “Nggak ada yang belain aku di rumah ini.”
Mamak tertawa sambil ambil lauk buatku. “Yud, Yud, becanda aja. Lagian, yakin bisa akur kalau punya adik?”
Aku angkat bahu. “Minimal rumahnya lebih rame.”
Aku melirik Rizal yang masih asik makan. Rasanya aneh ada orang lain makan bareng di rumah ini. Tapi anehnya... hangat.
Mungkin ini pertama kalinya aku merasa punya saudara.
***
Hari Ujian
Hari pertama ujian akhir. Meja ujian sudah disusun supaya susah nyontek. Tanganku dingin. Tapi aku percaya diri—Rizal udah ngajarin banyak.
Mata ujian pertama: Bahasa Indonesia. Aku yakin. HAHAHA. Akan kutunjukkan pada Bu Yani siapa Yudhis yang sebenarnya.
Pengawas bagikan soal. Aku berdoa, lalu baca soal pertama...
LAAAH, EMANG ADA MATERI PUISI?!
Aku mengedip-ngedip. Salah baca? Nggak. Ini beneran. Ya Allah, baru juga mulai ujian, aku udah pengen pulang.
Aku cuma fokus ke teks berita. Puisi? Enggak tahu sama sekali.
Kulirik Agung. Dia santai, elus dagu kayak dosen. Sementara aku? Senyumku udah mirip orang putus asa.
Ya Allah, kalau ini ujian kesabaran, hamba udah lulus duluan.
***
Seminggu Berlalu
Ujian... lancar. Mungkin.
Rizal? Santai banget. Kayak baru tes kepribadian, bukan ujian sekolah. Besok ujian terakhir.
Aku lagi ketuk-ketuk pensil waktu pintu kebuka. Rizal nyelonong masuk.
“Bang, aku udah hafal semua rumus Fisika nih!”
“Oke, bocah jenius. Rumus Archimedes apa?”
“Yah, yang gitu doang. Tanya yang susah napa.”
Anak ini makin betah di rumah. Mamak pun sekarang selalu masak lebih banyak kalau tau dia mau datang.
Setelah makan malam, Rizal pamit.
“Makasih ya, Jal, udah mau ngajarin,” ucapku, tulus. Rizal pasang muka serius. “Abang juga bilang ke Tante ya... aku mau kok jadi anak angkatnya.”
Aku mendesah. “Sialan kamu, Jal.” Dia hanya ketawa puas. “Aku pulang dulu ya, Bang.”
***
Malam Itu
Besok ujian terakhir. Setelah itu, aku harus mikirin... kuliah.
Aku berbaring di kasur. Lampu diredupkan. Kipas angin berdetak pelan. HP berkedip malas.
Akhir-akhir ini aku mulai yakin mau kuliah. Tapi... jurusannya apa? Teknik nuklir? Ilmu roket? Kebanyakan nonton anime, kayaknya.
Aku menatap meja belajar yang berantakan. Gelas kopi tadi sore masih di sana. Sebenarnya, aku nggak punya passion khusus.
Toh, ujung-ujungnya jadi karyawan juga, kan?
Suara jangkrik dari luar bercampur dengan deru motor. Malam ini tenang. Tapi pikiranku rame.
Kayaknya aku pilih asal aja deh. Yang penting: kuliah.
Malam itu aku tidur damai. Tanpa tahu, hal besar akan terjadi... lagi.


 saputera
saputera