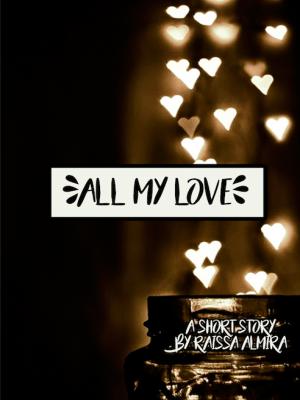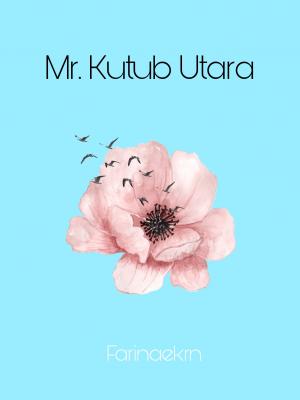Aku membuka mata perlahan, lalu langsung menyipit karena cahaya redup yang menembus jendela. Kepalaku terasa berat, seolah habis dihantam palu godam. Napasku memburu, dada naik-turun dengan ritme yang nggak biasa.
Langit-langit di atasku bukan putih bersih seperti yang kuingat—melainkan penuh retakan seperti guratan peta. Dinding sekelilingku kusam, bercak-bercak hitam tersebar di beberapa sudut. Bau lembap dan debu menusuk hidung.
Aku meraba kasur di bawahku—keras, kasar, dan lebih mirip papan daripada tempat tidur. Ini bukan kamarku. Aku bukan di rumah.
"Apa-apaan ini?" Suaraku serak, nyaris nggak terdengar. Aku mengusap wajah, mencoba mengusir sisa kantuk. Sesuatu terasa sangat salah.
Aku mengedarkan pandangan, mencoba mengenali tempat ini. Kamar ini sempit, asing, tapi anehnya terasa familiar. Kertas bekas berserakan di lantai, kipas tua di sudut ruangan berdecit pelan, seolah udah lelah muter sejak lama. Aku menggerakkan tubuh, tapi nyeri menjalar di punggung, seperti udah bertahun-tahun tidur di tempat yang salah.
Jantungku mulai berdetak kencang. Oke, tenang. Pikir. Apa hal terakhir yang kuingat?
Latihan band. Pulang larut. Tidur.
Lalu sekarang... ini?
Tanganku meraba-raba nyari HP. Masih ada. Layarnya menyala dengan redup, menampilkan wajah yang... bukan wajahku.
ASTAGFIRULLAH!!! KENAPA MUKAKU JADI TUA BANGET?!
Aku hampir melempar HP-ku sendiri. Wajahku tampak lebih tua! Kulit lebih kasar, ada kerutan di dahi. Aku meraih layar dengan panik, nyari penjelasan. Tanggal di sudut atas bikin napasku tercekat.
2036.
Lima belas tahun dari hari terakhir yang kuingat.
***
Anehnya, tubuhku mulai bergerak seolah udah tahu apa yang harus dilakukan. Aku langsung mandi di kamar mandi umum di luar. Aneh, aku tahu persis lokasinya, padahal ini bukan memoriku. Seolah tubuh ini udah terbiasa, walau pikiranku nggak ingat apa-apa.
Apa aku koma? Nggak mungkin lah, Yudhis. Kalo koma, bangunnya pasti di rumah sakit. Atau... aku diculik? Banyak banget pertanyaan muncul, dan nggak ada satu pun yang bisa dijawab.
Setelah mandi, aku pakai kaos dan celana pendek yang—anehnya—udah tertata rapi. Aku langsung ngelirik atas lemari dan... ya ampun, di sana ada gitar. Lagi-lagi: kenapa aku tahu itu di sana?
Tubuhku bergerak kayak autopilot. Nggak pakai mikir.
20 menit kemudian, aku udah ada di lampu merah, lengkap dengan sound system, nyanyi sambil main gitar. Di sebelahku ada seseorang—entah siapa—yang bertugas ngambilin uang dari para pengendara.
Ternyata... aku jadi penyanyi profesional. Di pinggir jalan.
Sudah hampir dua jam aku bernyanyi, duduk saat lampu hijau, berdiri pas lampu merah. Rutinitas yang entah kenapa terasa akrab.
Orang asing di sebelahku tiba-tiba ngajak sarapan.
"Bang, ayo cari makan dulu," ucapnya santai. Aku hanya mengikutinya diam-diam. Orang ini kelihatan udah lewat umur 30-an, pakai tas pinggang coklat usang dan topi hitam lusuh.
"Abang lagi sakit ya? Dari tadi pagi diam mulu," tanyanya.
"E-eh, nggak kok. Aku sehat," jawabku canggung.
"Biasanya abang udah marah-marah kalau uang cuma segini," katanya sambil nunjukin uang dua ribuan yang totalnya mungkin nggak sampai 20 ribu.
Kami tiba di warmindo. Aneh, tapi aku ngerasa udah sering banget makan di sini.
"Bang, seperti biasa… indomie telur dua," katanya lantang. Langsung duduk di meja dekat kasir. Aku ikut duduk.
"Oke, Jal," jawab si penjual. Sekarang aku tahu nama panggilannya: Jal.
Aku menatapnya. "Jal..."
"Iya, Bang, kenapa?"
"Kita sering makan di sini ya?"
Dia melongo. "Astagfirullah. Abang sakit kah? Di sini langganan kita, Bang. Apalagi pas hari-hari sial. Kalo nggak punya uang pun, Bang Arib tetap kasih makan. Baik banget dia."
Aku menarik napas. "Jal, kalo kubilang aku hilang ingatan... kamu percaya?"
"HAH?!" teriaknya kencang. Dia langsung minta maaf karena bikin kegaduhan.
"Kenapa Jal, masih pagi udah teriak-teriak?" tanya Bang Arib.
"Bang Yudhis hilang ingatan katanya."
"HAH! HILANG INGATAN?!" Balasan Bang Arib lebih nyaring lagi.
"Serius kamu, Yud?" tanya Bang Arib sambil balik mengaduk telur. Aku cuma mengangguk pelan.
"Dari tadi pagi anak ini emang agak aneh, Bang," kata Jal. "Diam mulu. Kayak lagi peringati Hari Hening Internasional."
Dan dimulailah sesi ghibah massal. Mereka mulai cerita soal keburukan-keburukanku, di hadapanku.
Tapi aku jadi tahu: nama asli Jal adalah Rizal Marzuki.
"Bang Yudhis pernah tuh, saking keselnya, nyanyi Bintang Kecil. Eh, malah dapat uang banyak."
"Terus waktu pertama kali ke sini, pesen banyak tapi nggak punya uang. Bilang bakal ngelakuin apa aja sebagai bayaran. Aku suruh dia minta nomor HP mbak-mbak langganan yang aku naksir. Sebulan kemudian tuh mbak jadi istriku. Dia kukasih makan gratis sebulan penuh, hahaha."
Kalau benar aku sudah di sini hampir 10 tahun, aku cuma bisa berharap... ini semua mimpi.
“Eits, bentar dulu. Kalau mau lewat, kamu harus bayar 30 ribu.”
Preman itu menahan badanku saat aku baru mau jalan. Tangannya yang besar mencengkeram bahuku. Tekanan dari genggamannya langsung bikin aku sadar: aku nggak bakal menang kalau ini lanjut jadi berantem.
“Kita udah capek dari pagi sampai sore buat ngumpulin 30 ribu, terus kamu seenak jidat mau ambil? Belum pernah cium lutut apa gimana?” sergahku lantang. Rizal sejak tadi diam, nggak berani ngapa-ngapain. Aku tahu aku ngomong gede, tapi kalau nggak ada yang ngelawan, preman macam ini bakal makin jadi.
BUK!
Satu pukulan keras mendarat di wajahku. Pandanganku goyang. Panas menjalar di pipi, dan rasa besi dari darah mulai terasa di sudut bibir.
Refleks, aku balas mukul. Tanganku melayang ke wajahnya.
BUK!
Sial. Bukan dia yang kena. Malah perutku yang dihantam lututnya. Entah gimana itu bisa terjadi, tapi sebelum sempat berpikir, aku sudah rebahan di jalanan. Napas tercekat. Dunia rasanya berputar.
Aku bisa melihat bayangan si preman mendekati Rizal.
Rizal mundur setengah langkah, tangan gemetar. “B-bang, udah, ambil aja duitnya,” katanya lirih.
Tapi aku nggak bisa tinggal diam.
Perlahan aku bangkit. Tanganku meraba tanah dan—nah! Ada batu ukuran sedang. Aku genggam erat. Ini kesempatan. Dia nggak lihat aku.
Hahaha, mampus kau, preman pasar!
Aku angkat batu tinggi-tinggi, siap melempar ke kepalanya.
BUK!
BUKAN! Itu BUK dari dia! Tangan si preman menghantam wajahku TANPA MELIHAT!
DIA MUKUL TANPA LIHAT?!
Aku jatuh lagi. Oke, fix. Saatnya menyerah.
Rizal menatapku horor. Sebelum sempat bertindak, preman itu merampas uang dari tangannya.
“Lumayan buat beli rokok,” katanya santai. Lalu, BUK!—dia pukul Rizal.
Rizal jatuh terduduk. Napas memburu. Tetap nggak melawan.
Dua pengamen dikalahkan satu preman. Keras banget hidup di jalan.
Kami terdiam. Lampu jalan berkedip pelan, menciptakan bayangan preman yang makin memanjang sebelum dia benar-benar pergi.
Langkah sepatunya menjauh. Bersama suara itu, harga diriku juga ikut terkikis.
Kami lanjut jalan. Aku masih ngomel ke Rizal, si penakut ini. Kakiku berat, entah karena luka atau karena harga diri yang babak belur.
Aku melirik Rizal yang masih ngusap pipinya. Matanya sipit, ekspresinya kayak orang baru sadar hidup itu penderitaan.
Aku meringis, megang pipiku. “Jal, kenapa kamu tadi cuma diam?! Kalau kita lawan bareng, mungkin nggak separah ini!”
Rizal menghela napas. “Bang... lawan satu orang aja udah kayak gini. Kalau aku ikut, paling cuma nambah korban.”
Aku diam. "... Iya juga, ya."
Rizal menatapku. “Bang, walaupun abang hilang ingatan, tapi soal beginian nggak berubah.”
“Maksudnya?”
“Abang selalu berani lawan preman...” Rizal elus pipinya yang bengkak. “...tapi selalu kalah juga, sih.”
“Yeee, aku mah mending, Jal! Masih berani lawan!” Aku membela diri.
Tapi aku mikir. “Eh, emang bener ya, dari dulu aku selalu berani lawan preman?” tanyaku sambil meliriknya curiga.
Rizal mengangguk mantap. “Iya, Bang. Dari dulu abang jago bikin masalah...” Dia menatapku dalam. “...tapi tetap spesialis kalah.”
Bangke emang.
Aku menghela napas. Ya Allah, ternyata aku ditakdirkan jadi petarung sejati... yang nggak pernah menang.
Perutku yang kena lutut barusan masih nyeri. Rasanya kayak hamil 12 bulan. Sakit banget. Bentar lagi brojol nih anak.
Rizal menatapku ngeri. “Bang, jangan brojol di sini ya. Aku nggak siap jadi bidan.”
Aku melotot. “ASTAGA, Jal! Kamu bisa baca pikiran ya?!”
Rizal mundur sedikit, ekspresinya panik. “Bukan, Bang, tapi wajah abang barusan kayak ibu-ibu sinetron pas mau lahiran!”
Aku nepuk jidat. “Jal, plis, aku lagi sak—TUNGGU, SINETRON APAAN YANG KAMU TONTON?!”
Dia angkat bahu. “Ya pokoknya yang ada efek zoom tiga kali terus suara ‘JENG JENG JENG!’ gitu, Bang.”
Aku menatap langit. Bukan cuma harga diri kami yang hancur, mungkin akal sehat kami juga.
***
Tiga puluh menit kemudian, kami duduk di depan kos. Menatap bintang. Malam itu rame banget di atas, kayak lagi ada bagi-bagi sembako.
Kami sudah bersih, minum kopi, ngerokok. Walau uang hari ini diambil si tringgiling itu, kami masih punya tabungan untuk... ya, kesehatan paru-paru.
“Jal, aku pernah cerita tentang diriku ke kamu, nggak?” tanyaku sambil menatap langit.
“Sering, Bang. Mau kuceritain lagi?”
“Iya, Jal. Aku mau tahu kenapa aku bisa jadi pengamen Jogja tingkat atas begini.”
“Walau lupa ingatan, masih tetap bego ya, Bang.”
“HAHAHA, emang dulu aku bego, Jal?”
“Nggak sih, lebih ke tolol. Hahaha.”
“Udah, udah. Buru cerita tentang Yudhistira Wijaya si pengamen kelas dunia.”
Aku baru kenal Rizal hari ini, tapi hati ini kayak udah kenal dia lama. Otakku mungkin lupa, tapi hatiku nggak.
“Dengerin ya, Bang. Dulu abang cerita, abang punya mimpi jadi penyanyi terkenal. Waktu SMA, abang nggak mau kuliah, mau fokus sama band. Tapi setelah dua tahun, band abang cuma bisa tampil di kafe-kafe kecil. Pendapatan dikit, dibagi-bagi makin dikit. Lama-lama, teman-teman abang keluar. Pilih kuliah. Abang sendiri, nyanyi sendiri, lamar kerja pakai ijazah SMA nggak ada yang nerima. Akhirnya abang ke Jogja. Nyewa kos ini, murah banget, soalnya...”
Aku mengernyit. “Soalnya apa?”
“Abang berhasil nego ke Bapak Kos. Katanya kos ini nggak perlu bayar listrik.”
“Hah? Kok bisa?”
“Entah dari mana skill itu abang dapet, tapi abang berhasil sambungin kabel kos ke kabel jalan. Jadi listrik kita nyolong.”
Aku melongo. “Hah?”
Rizal ngisep rokok, diem. Hela napas. Diam lagi.
Lama banget.
Aku mulai gelisah. Jangan-jangan ini momen refleksi hidup. Atau dia sadar selama ini salah jalan.
Nunggu beberapa detik. Masih diem.
“Oi! Lanjut, bujang!” Aku nepuk pundaknya.
Rizal kaget. Lirik aku malas. “Bang, sabar dikit napa. Cerita ini butuh feel.”
Aku mendelik. “Kamu butuh feel atau kehabisan akal?!”
Rizal nyengir. “Aku lupa, Bang. Hehehe.”
Sialan nih anak. Kirain klimaks, ternyata ngambang.
“Bentar amat ceritanya,” protesku.
Yang kuingat sekarang cuma satu: aku tidur setelah latihan band, di Kalimantan.
Tiba-tiba bangun... di Jogja. Tahun 2036.
Hah?!
Biarpun hilang ingatan, kenapa aku masih inget jelas kalau aku tidur? Kenapa malah itu satu-satunya yang otakku pertahankan?! Atau ini normal ya? Entahlah. Aku bukan anak kedokteran.
Terlalu banyak yang harus kupikirkan.
Kenapa Tuhan membiarkanku mengalami ini?
Aku udah coba segala cara balikin ingatan. Sebagian besar solusi melibatkan dokter. Tapi aku nggak punya uang.
Jadi aku pakai cara sendiri: ngetok kepala ke dinding sekeras mungkin.
Hasilnya? ZONK.
Kupikir setelah dengar cerita Rizal, ingatan bakal balik. Tapi tetap nggak ada apa-apa yang muncul.
Tapi... waktu Rizal cerita soal teman-teman band pergi dan milih kuliah, ada sesuatu yang terasa di dadaku. Sesak.
Hanya sesaat.
Kepalaku memang lupa segalanya. Tapi hatiku...
Rasanya nggak pernah benar-benar lupa.
Aku bahkan nggak yakin pernah mengalami semua yang dia ceritakan.
Tapi aku percaya.
Aku percaya sama semua yang Rizal bilang.


 saputera
saputera