***
Yogyakarta, Indonesia.
Pilah-memilah, masuk-keluarkan, maju-mundur pula keputusan Kaur yang tak selesai-selesai mengemasi barang bawaannya selama satu jam terakhir.
Bagaimana dengan satu-dua benang rajut? Oh, tidak-tidak. Mungkin beberapa pensil dan buku sketsa lagi? Siapa yang tahu kapan mereka akan patah dan hilang, kan? Kertas origami satu pack sepertinya juga butuh? Dan tambahan lotion? Satu botol antiseptik lain? Sisir cetarku jangan lupa!
Kaur mengusap dagu penuh bimbang—memerah otak begitu keras, sampai-sampai selapis keringat dingin terbentuk di dahi mulusnya. Buru-buru ia tap-tap dengan tisu kering, khawatir bila biang keringat bermunculan dan merusak seluruh usahanya merawat diri selama ini.
“Kan tidak mungkin orang lain mengataiku biang keringatan ....” Kaur menarik napas kesal dan mendadak menggeleng kuat—sebab lagi-lagi begitu mudah terdistraksi, cepolan poninya yang mulai memanjang juga ikut bergoyang-goyang persis balon dancer promosi di depan toko.
Masalahnya, sang Ayah sudah mewanti untuk membawa satu koper saja. Hapal mati kebiasaan Kaur yang menganggap semua barang begitu penting.
Kaur berdecak, memandangi jejeran barang di atas kasur. Dua puluh kaus dengan tingkat saturasi dari tua ke muda dilipat rapi tanpa sehelai kusut, sepuluh celana berbahan serupa di sisi, satu set alat mandi yang sudah ditakar hati-hati isinya agar pas untuk 30 hari ke depan. Terlihat rapi—tetapi tidak cukup baginya.
Bagaimana dengan totebag manis yang cocok untuk hari cerah? Lalu, apa jadinya kalau tiba-tiba butuh lilin aroma terapi sebagai moodbooster? Pasti di sana stres banget, sih. Masa iya harus ngandelin pengharum ruangan yang jangan-jangan beraroma stella jeruk kolaborasi apek angkot? Bah, yang benar saja!
“Bisa gila aku.” Kaur mendengus. Detik berikutnya, gedoran keras menggetarkan pintu kamar. Sebelum sempat sang Ayah meludahkan berbagai jenis belati dari mulut, Kaur gegas menekan isi koper bergantian dengan lutut dan bokongnya—kendati percuma saja, gespernya tetap tidak mau tertutup.
Meraih gegabah totebag bercorak abstrak favorit yang dilengkapi bordiran bunga kantil di tepi, Kaur memasukkan seluruh barang tak berguna lainnya.
“Halah, peduli amat dengan aturan satu koper. Kalau mendadak mati di sana, setidaknya aku bisa dievakuasi dalam keadaan wangi dan tampan. Tidak seperti ....” bibir Kaur lantas terkatup rapat, tak melanjutkan kalimatnya. Luapan sesak di dada justru membuat tangannya cekatan membersihkan segala kekacauan di muka, alih-alih badai di kepalanya.
“Kaur!”
“Iya, sebentar!”
“Tidak perlu lagi kamu catok rambutmu itu! Jangan bawa seisi rumah!”
“Iya!”
“Jangan iya-iya saja! Keluar kamu! Entah didikan apa yang ibumu itu terapkan sampai kamu jadi manusia lelet dan repetitif seperti ini.”
Brakk!
Hentak pintu kamar terbuka kencang, memaksa ayahnya bungkam seketika. Kaur menjulang di ambang pintu dengan napas putus-putus, keringat mengaliri kembali dahinya, sedang buku-buku jari memutih mencengkram erat pegangan koper. Sorot mata Kaur menghunus dingin, merah-mendidih air mukanya seperti menahan berak tatkala berkata, “Jangan bawa-bawa ibuku.”
Kaur tersinggung. Jelas.
“Ayah pikir aku tidak capek cemas seperti ini? Memperhitungkan segala sesuatunya seperti orang konyol ....” Kaur menarik napas gemetar, melempar pandangan ke arah plafon guna menahan tanggul yang hampir jebol di pelupuknya. Sesaat yang cukup sebelum Kaur meluruskan kepala, sebab melihat seekor cicak nangkring tepat di atasnya. Jujur saja, ia tiba-tiba takut diberaki.
“Kamu memang konyol, Kaur,” tukas sang Ayah menambah tusukan.
Eh, apalah ini? Bukannya seharusnya dia merasa bersalah?
“Apa yang ada di kepalamu? Kamu mau pergi ke asrama dengan penampilan seperti ini?” Ayahnya merujuk pada cepolan anti badai Kaur yang lupa dilepas, mirip tali pocong tanpa kain kafan. Kaur segera sadar dan melepaskan karet di rambutnya, lalu berjalan melewati pria itu tanpa patah kata. Selalu begitu, mengalihkan pembicaraan. Menjengkelkan.
Lincah menuruni anak tangga yang naasnya ganjil. Sehingga Kaur harus berulang-ulang turun-naik agar jumlahnya genap. Barulah ia lega.
***
Di sepanjang mobil membelah lautan kendaraan jalanan Yogyakarta, hanya ada dengung mesin dan hentak geluduk ban tiap kali menghantam permukaan tak rata aspal. Matahari perlahan larut dalam belitan jingga, sementara pepohonan dan bangunan-bangunan berlari mundur dalam kecepatan stabil—persis seperti kesabaran Kaur yang semakin menipis per-detiknya.
Lucunya, masih sempat-sempat Kaur menghitungi jumlah bangunan yang terlewati, atau mengamati bagaimana kaca helm ojol yang melaju bersisian dengan mobil sang Ayah terdengar terkikik sekitar 33 kali ditampar deru angin karena bautnya tak lagi kencang—nyaris lepas. Bah, apalah itu? Ingin sekali aku turun dan melepas kacanya sekalian, batin Kaur mengerang gatal.
Seolah belum cukup memantik rasa gemasnaik ke ubun-ubun, satu motor tepat di sebelah si Ojol dengan muatan roti lapis empat: Ayah, Ibu, dan dua anak perempuan. Si bungsu berkepala mirip Adudu—begitu persepsi Kaur, yang lututnya bertumpu di besi bagasi motor paling depan, terlihat cengengesan ke arahnya. Angka sebelas berwarna kuning-kehijauan bertengger manis di kedua lubang hidung, mulai tercecer diendus angin.
Kaur mereguk ludah. Rasa pedas di pangkal tenggorokan menjadi bukti jikalau asam lambungnya mendadak naik drastis!
Buru-buru membuang pandangan dan menaikkan kaca jendela mobil. Sejurus kemudian, mulutnya komat-kamit tanpa suara.
Es kopi susu ... es kopi susu dengan tambahan gula ekstra! Agh!
“Kenapa lagi kamu?” teguran ayahnya menyentil habis kegelian Kaur perkara anak tadi. Ia hanya menoleh sekilas pada pria yang masih fokus memegang kemudi itu, lalu menggeleng singkat. Bukan karena takut, melainkan malas. Setiap obrolan selalu berakhir layaknya permainan bola bisbol; ayahnya sebagai pemain, dan Kaur berperan bak bola yang dilempar-pukul hingga memar.
Bukannya ia tidak ingat bagaimana dulu semua terasa begitu mudah, meski tak benar-benar ingat kapan terakhir kali.
Jauh sebelum kebiasaan saling mendiamkan ini terjadi, Kaur pernah duduk gembira di pundak ayahnya sewaktu kecil. Berceloteh banyak hal selagi mereka bertiga keliling kebun binatang, kemudian ibunya akan menyodorkan dua potong es kado yang sontak jadi bahan rebutan, karena Kaur bersikeras bahwa bagian es yang lebih panjang adalah hak miliknya.
Sekarang? Lupakan. Ia dan ayahnya bahkan tidak bisa duduk bersebelahan lebih dari sepuluh menit tanpa ada yang mendesah jengah atau mengetukkan jari di setir dengan irama pasif-agresif.
Ban mobil meringkik tatkala berbelok tajam ke dalam sebuah lorong sempit yang dipenuhi pepohonan rimbun. Kaur jadi teringat alasan ia telat mengemasi barang-barangnya hari ini. Itu dikarenakan ia sibuk menelusuri informasi mengenai profil juga lokasi kursus yang anehnya tidak ada di gmaps. Mengutak-atik untuk mencari lulusan kursus dan testimoni mereka. Tetap saja, tidak ada petunjuk sama sekali.
Ia skeptis, skeptis dengan sistem kursus dan mengapa ayahnya mau-mau saja percaya pada kegilaan serta ketidakpastian yang disuguhkan.
“Baik-baik di asrama. Akan ada yang jemput setelah kursus selesai, karena Ayah mungkin masih di luar kota,” ujar sang Ayah memecah hening, ketika akhirnya mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar yang tampak terlalu serius untuk disebut “kursus”.
Ayahnya turun lebih dulu, membuka bagasi, lalu mengangkat koper kuning cerah milik Kaur yang dilengkapi ikatan syal bermotif bunga. Tatkala hendak mengambil, mata Kaur sekilas menangkap koper lain di dalam bagasi—hijau lumut, agak bulukan, dengan bekas sobekan di salah satu sisinya.
Ia mendengus.
Peduli amat.
Tanpa banyak basa-basi, ayahnya kembali masuk ke mobil dan pergi begitu saja. Meninggalkan Kaur sendirian di depan gerbang dengan plang besar bertuliskan semboyan kursus.
KURSUS KILAT JADI ORANG DEWASA
“Mewujudkan Generasi Anti Menye-Menye”
Kaur melongo.
Alamak. Kenapa seperti bootcamp militer?
***


 rupa🎭
rupa🎭







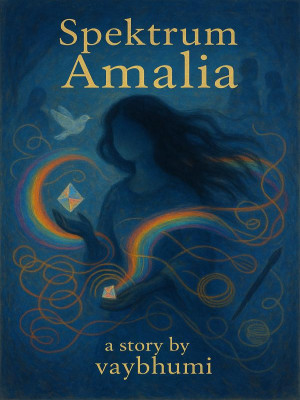



Semangat kak Rupa!
Comment on chapter 00 - Prolog