Dalam keheningan yang tak terucap, kami mulai bertaut—dua jiwa yang menemukan simpul baru di tengah perjalanan panjang yang penuh liku. Bukan sekadar pertemuan, tapi ikatan yang mengikat tanpa perlu banyak kata.
**
Sudah seminggu pameran berlangsung, dan semuanya akan berpuncak di malam ini. Lapangan belakang fakultas berubah jadi lautan kabel, rigging, lampu sorot, dan suara cek-cek mic yang tiada henti. Tenda logistik didirikan di sudut, dipenuhi kardus minuman, kotak konsumsi kru, dan berkas rundown yang mulai kusut karena berpindah tangan terus. Di mana-mana ada orang berlari, ada yang bawa HT, ada yang bawain properti, ada yang cuma teriak:
“Powerbank! Siapa punya powerbank?!”; “MC cadangan mana?! Ini udah jam lima!”; “Kabel ini nyambung ke mixer yang mana sih, kok malah feedback?!”
Semangat itu terasa. Tegang, panas, berkeringat, tapi juga hidup. Ini bukan lagi cuma kerja panitia. Ini misi.
Aku berdiri di pinggir panggung, headset di telinga, satu tangan memegang HT, satu lagi memegang rundown. Di sekelilingku, kru teknis sibuk menarik kabel, pasang properti, dan panitia lain berlarian menyelesaikan printilan terakhir sebelum sound check.
“Lighting kiri, siap?” tanyaku ke HT.
“Siap,” jawab suara dari ujung sana.
Aku mengangguk, lalu berjalan ke sisi panggung sambil menyapu pandang ke layout mic dan properti. Di tengah langkah, mataku menangkap kabel monitor yang melintir ke jalur kru. Aku menunduk sebentar, meluruskannya. Bukan hal besar, tapi cukup bikin pikiranku gatal kalau dibiarkan.
Di dekat tepi panggung, ada satu kotak kecil berisi HT yang posisinya terlalu mepet. Sambil berlalu, aku geser dua jengkal ke dalam. Langkahku belum berhenti saat melihat mic MC di atas meja yang tampak miring. Sekilas, aku raih untuk meluruskan tanpa sadar, semua itu kulakukan sambil terus bergerak.
“Nara!” seru seseorang dari belakang. “MC-nya udah datang!”
“Lima menit, suruh dia standby di belakang stage,” jawabku cepat.
Langkahku berbelok ke sisi kanan panggung. Di sana, posisi speaker kecil terlalu miring dari arah audiens. Aku jongkok, memutarnya sedikit, lalu berdiri lagi. Mataku terus bergerak, mencari celah yang belum sempurna.
Keringat mulai merembes di punggungku. Rambutku lengket di pelipis. Tapi aku masih terus bergerak. Di meja kontrol kecil di dekat layar LED, ada dua botol air mineral yang sudah kosong. Aku hampir mengambilnya, tapi mataku lebih dulu tertumbuk pada banner sponsor yang sedikit miring di panggung belakang. Langkahku berputar balik. Tangan kiriku otomatis menarik sisi banner, mencoba meluruskannya. Masih tampak agak miring. Aku luruskan lagi. Masih belum pas. Sekali lagi. Tiga kali. Baru setelah itu aku kembali menatap botol air tadi.
Lalu aku menyadari: aku belum makan dan minum apa pun dari pagi. Tapi tanganku masih sibuk. Masih ada satu properti kecil di tengah panggung, sebuah miniatur replika gedung yang tampaknya terlalu jauh ke sisi kiri. Aku melangkah ke sana, membungkuk, menggesernya dua jengkal ke tengah. Lebih rapi. Lebih tenang.
Aku baru saja turun dari panggung ketika seseorang menyorongkan botol minuman dingin ke tanganku.
“Minum dulu,” katanya
Aku menoleh, sedikit terkejut. Nata datang dari arah stage dengan dua botol di tangan, satu untukku, satu untuk dirinya sendiri. Wajahnya basah oleh keringat, rambutnya sedikit acak, telinganya masih terlihat menggunakan headset panitia, tapi senyumnya tetap tenang seperti biasa.
“Belum sempat minum dari tadi, kan?” lanjutnya sambil duduk di sebelahku, di atas boks properti.
Aku membuka botol itu, meneguknya sedikit, lalu mengangguk. “Makasih.”
Nata menyodorkan plastik kecil berisi roti dan vitamin. “Makan dulu yang ringan. Kamu udah kayak robot. Takutnya nanti jatuh.”
Aku nyaris bilang “aku nggak lapar”, tapi menahan diri. Karena entah kenapa, meski tak ada rasa, aku tahu tubuhku butuh itu.
“Barusan aku lihat kamu ngulang tiga kali mindahin posisi banner sponsor,” ucapnya setengah bercanda. “Emang mata kamu penggaris?”
Aku menarik napas. “Enggak cocok aja. Miring lima derajat.”
Aku tersenyum tipis, merasa sedikit lega ada yang memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya cuma aku pedulikan sendiri.
Nata tertawa pelan. “Kalau gitu, aku siap jadi penggaris cadangan kamu.”
Aku menatapnya, sedikit geli. “Duh jangan bilang begitu, malah bikin aku tambah deg-degan.”
Dia mengangkat bahu santai. “Ya, namanya juga kerja tim. Harus saling bantu kan?,”
“Tim yang agak aneh,” kataku sambil mengunyah roti. “Aku biasanya bisa fokus sendiri, tapi ini... terlalu banyak yang harus diurus.”
Nata mengangguk mengerti. “Aku lihat kamu udah berusaha banget. Jangan lupa juga jaga diri, ya. Biar kamu nggak kelelahan.”
Aku menatap botol air di tanganku, lalu menoleh ke Nata. “Kamu nggak capek bantuin aku?”
Dia mengangkat botolnya, tersenyum lebar. “Capek sih iya, tapi kalau bantuin kamu, capeknya malah jadi seneng.”
Kami diam beberapa saat, saling bertukar pandang dalam keheningan yang terasa hangat di tengah riuhnya persiapan konser.
Aku menarik napas dalam-dalam. “Makasih ya.”
“Anytime, Ra.” Nata tersenyum tulus. “Apapun yang bisa buat kamu seneng, buat kamu gak ngerasa capek, bakal aku usahain itu” Lanjutnya dengan tatapan hangat.
Tiba-tiba HT di tangan Nata berbunyi. Suara panitia lain menyebutkan masalah di area venue. Nata buru-buru berdiri.
“Aku harus backup ke depan panggung,” katanya cepat, lalu berdiri. “Kamu di belakang aja, bantu rundown performer, ya?” Katanya sambil tersenyum ringan.
Aku mengangguk pelan, tapi anehnya dadaku terasa sesak.
“Nata...” aku memanggilnya, tapi dia sudah berjalan meninggalkan tenda logistik. Dan rasanya aku merasa tidak rela melihatnya pergi ke tempat lain.
Suara langkahnya menjauh dan hiruk-pikuk persiapan makin menggema di sekelilingku. Aku berdiri di tempat itu, dikelilingi oleh kerumunan orang yang sibuk, tapi anehnya, aku merasa sendirian. Aku menatap botol air di tanganku, perlahan meneguk sedikit, tapi rasanya jauh lebih hambar dari biasanya.
Senyuman Nata, tatapan hangatnya, dan suara lembutnya yang selalu bisa menenangkan, tiba-tiba terasa begitu jauh. Aku merasakan sesuatu yang aneh dan baru di dada, sejenis kekosongan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Seolah-olah, tanpa Nata di samping, semua keramaian ini berubah menjadi bisu.
Aku mencoba mengalihkan perhatian, membuka rundown di tanganku, membaca ulang jadwal performer. Tapi pikiranku terus melayang ke sosok yang baru saja pergi. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi suara konser yang mulai dipersiapkan dari kejauhan malah semakin membuat jantungku berdebar.
Tak terasa, langit mulai menggelap, semburat jingga dan ungu memudar pelan digantikan kelamnya malam. Lampu-lampu sorot di panggung utama mulai dinyalakan, memotong kegelapan dengan semburan warna yang berkilauan. Suara cek-sound-check menggema dan bercampur dengan obrolan panitia yang tak kunjung surut. Angin malam membawa sisa debu dan aroma kayu dari panggung yang dipasang terburu-buru.
Aku berdiri di sisi panggung, mataku menatap rundown yang mulai kusam di tangan. Tubuhku sedikit membungkuk, kedua lengan melingkar di depan dada seolah mencoba menghangatkan diri dari dinginnya udara malam.
Dari kejauhan, Nata melangkah mendekat dengan tenang. Dia sudah memperhatikan aku yang sesekali menggosok lengan sendiri. Tanpa kata, ia mengulurkan jaketnya dan menyampirkannya ke pundakku.
“Nih,” katanya singkat. “Kamu udah terlalu banyak mikir, jangan sampai masuk angin juga.”
Aku sempat terkejut dan langsung merespon “Terus kamu pakai apa?.”
“Aku gerah malah. Udah, pake aja.” Jawabnya sambil tersenyum.
Aku ingin menolak, tapi jaket itu sudah terlanjur menyelimuti lengan dan pundakku. Hangatnya tak benar-benar sampai ke hati, tapi menenangkan. Dan anehnya, aku tak punya dorongan untuk melepaskan, padahal biasanya aku risih memakai barang orang lain, apalagi dengan bekas keringat dan bau yang pasti melekat. Tapi malam ini berbeda. Rasanya seperti pelukan dari udara dingin yang mulai menusuk tulang. Mungkin karena ini adalah Nata.
Lampu panggung menyala penuh warna, memantulkan kilauan gemerlap ke arah kerumunan yang makin memadati lapangan. Suara dentuman bass dan irama drum mulai menggema, mengisi malam dengan gelombang musik yang kuat, membangun energi yang sulit diabaikan.
Nata berdiri di sampingku, matanya berbinar menikmati setiap hentakan musik. Dia sesekali mengangguk, tersenyum, bahkan ikut menggerakkan kepala mengikuti irama. Aku memperhatikannya dengan pandangan yang berbeda, sementara dia tenggelam dalam semangat konser. Aku malah merasa kosong, seolah ada jarak tak terlihat memisahkan diriku dari keramaian.
Suara band memenuhi udara, mengaburkan percakapan di antara kami. Tiba-tiba Nata menoleh padaku, wajahnya serius. Dia mencondongkan badan sedikit, berusaha berbicara di atas dentuman musik yang menggema.
“Nara, aku suka kamu...” ucapnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara gitar yang menggelegar.
Aku menoleh cepat, mencoba menangkap kata-katanya. “Apa?”
Dia hanya tersenyum, menggelengkan kepala, lalu berkata lirih, “Nanti aja.”
Kami berdua tertawa kecil. Suasana malam itu terasa aneh dan hangat sekaligus, seolah dunia berhenti sejenak hanya untuk kami. Meski begitu, dalam hati, aku tetap merasa hampa. Musik yang menggelegar, sorak sorai penonton, dan energi Nata yang membara, semua terasa jauh dan tak sampai ke dalamku. Aku berdiri di sana, terbungkus jaketnya, menyaksikan dunia yang berputar tanpa bisa aku ikuti sepenuhnya.
Setelah konser berakhir dan kerumunan mulai berangsur bubar, Nata mengantarku pulang. Malam itu, jalanan terasa sepi, hanya ada lampu jalan yang temaram dan suara mesin yang berdengung pelan. Di dalam kabin yang hangat, kami membahas hal-hal kecil yang terasa ringan. Tentang acara, tentang bagaimana kru bekerja, dan siapa saja yang paling capek. Tapi perlahan, suasana berubah menjadi lebih sunyi, lebih dalam.
Di tengah perjalanan, Nata menepikan mobil di ruas yang sepi. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas tapi lembut,
“Aku suka kamu, Nara. Aku udah lama ngerasain ini, dan aku nggak mau terus diem aja. Aku pengen kamu tahu perasaanku.”
Aku menatap wajahnya yang serius, sorot matanya yang hangat tapi penuh ketulusan membuat dadaku berdebar. Suara mesin mobil yang berdengung pelan seolah jadi latar musik untuk momen ini.
“Kalau kamu butuh waktu, aku bisa tunggu,” ucap Nata pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Tangannya sedikit menggenggam ujung setir, seperti berusaha menahan rasa gugup.
Aku ingin berkata sesuatu, tapi lidahku terasa kelu. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan, mencoba meresapi keberanian yang ia tunjukkan. Ada kehangatan yang menyelinap perlahan ke dalam hati yang selama ini dingin dan kosong.
Nata mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh, lalu membiarkannya turun perlahan. Tapi dari tatapannya saja, aku tahu—aku tidak sendiri.
“Nggak harus dijawab sekarang kok,” katanya, “Aku cuma pengen kamu tahu, kalau aku di sini. Dan kapan pun kamu siap, aku akan selalu ada.”
Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan perasaan itu meresap dalam-dalam. Rasanya asing, tapi tidak menakutkan. Seolah ada cahaya kecil yang akhirnya kembali menyala di ujung lorong.
Mobil kembali melaju pelan ke jalan raya, lampu-lampu kota membias di kaca depan. Hening menyelimuti kabin, tapi bukan hening yang canggung, melainkan tenang, hangat, dan penuh sesuatu yang belum selesai diucapkan. Nata sesekali melirikku, tapi tak memaksakan apa-apa. Aku hanya menatap ke luar jendela, membiarkan pikiranku menari di antara kata-katanya tadi.
Mobil akhirnya berhenti di depan rumahku. Mesin dimatikan, tapi kami berdua masih diam di dalam, seolah belum siap mengakhiri malam ini.
Aku membuka suara pelan, nyaris seperti gumaman, “Nata... makasih.”
Dia tersenyum, pandangannya tetap lembut. “Aku yang makasih. Udah ngebolehin nganter kamu pulang malam ini.”
Aku mengangguk, membuka pintu mobil dengan gerakan ragu. Tapi sebelum turun, aku menoleh sebentar. “Hati-hati di jalan, ya.”
“Hati-hati juga... di dalam pikiran kamu,” katanya sambil tersenyum tipis.
Hatiku terenyuh. Aku menutup pintu dan melangkah masuk ke rumah, membawa serta degup yang belum selesai kutafsirkan.
Langkahku pelan menaiki tangga, melewati ruang tamu yang sunyi, dan masuk ke kamar yang sejak tadi menunggu dalam gelap. Aku membersihkan diri, mengganti pakaian, lalu membaringkan tubuh di ranjang. Tapi mata ini menolak terpejam.
Di luar, malam terus berjalan. Namun di dalam kepalaku, kata-kata Nata berputar tanpa henti “Kalau kamu siap, aku akan selalu ada.”
Aku menghela napas panjang, membenamkan wajah ke bantal. Tapi keheningan ini justru memperjelas semua yang tadi terasa kabur. Ada sesuatu yang menekan dada, bukan sakit… tapi juga bukan nyaman.
Malam makin larut. Kamar tetap gelap, hanya ada cahaya ponsel yang menerangi wajahku. Jemariku ragu-ragu menekan ikon kontak. Nama “Nata” terpampang jelas di layar, dan sebelum sempat berpikir dua kali, aku menekan tombol call.
Suara dering pertama membuat jantungku berdebar. Dering kedua membuatku ingin membatalkan. Tapi dering ketiga, suara itu menjawab.
“Halo? Kamu belum tidur?”” Suara Nata terdengar agak serak, tapi tetap hangat.
Aku menatap ke arah kursi di pojok kamar. Jaket Nata masih terlipat rapi di sana, jaket yang tadi dia sampirkan ke pundakku tanpa banyak bicara. Aromanya masih samar tercium, seperti sisa kehadirannya yang belum sepenuhnya pergi.
“Nggak bisa tidur,” jawabku pelan.
Sejenak hening. Aku menarik napas panjang, menahan segala rasa yang berkecamuk, lalu berkata:
“Nata.. Aku mau coba. Tapi... Aku nggak bisa janji bisa ngejalanin hubungan ini kayak orang lain. Kadang, aku bahkan bingung sama perasaanku sendiri. Kayak... nggak ada rasa, tapi juga nggak benar-benar kosong.”
Dari ujung telepon, Nata tak langsung menjawab. Ada keheningan, lalu Nata tertawa, lega.
“Ra.. kamu tahu gak? Rasanya udah lama aku nunggu kata-kata itu dari kamu. Kamu nggak harus ngerti semuanya sekarang. Kamu nggak perlu jadi kayak orang lain. Kamu juga nggak perlu janji apa-apa. Cukup kamu tetap jadi kamu. Sisanya… biar aku yang jaga.”
Aku tersenyum, meski dia tak bisa melihatnya.
“Makasih udah sabar ya Nat.” Kataku akhirnya.
“Makasih juga udah percaya sama aku, Ra.” Jawab Nata dengan suara lembut, penuh harap. “Kita mulai dari sini, ya. Bersama.” Lanjutnya.
Aku memejamkan mata. Di luar jendela, suara sisa konser masih samar—gema drum yang perlahan meredup di kejauhan. Tapi yang tertinggal di dadaku bukan lagi bunyi bising, melainkan jeda yang tenang. Sebuah ruang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan setelah sekian lama, aku merasa... mungkin aku tidak harus sembuh sendirian.


 bunca_piyong
bunca_piyong








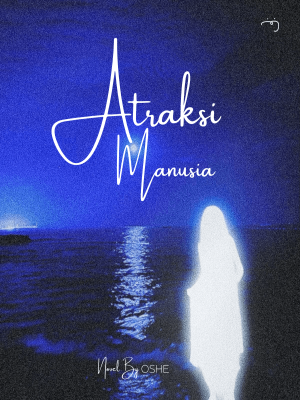



ga ada typo, bahasanya puitis tapi ringan, setiap bab yang di baca dengan mudah membawa masuk ke cerita. ceritannya juga unik, jarang banget orang mengedukasi tentang KESEHATAN MENTAL berbalut romance. dari bab awal sampe bab yang udah di unggah banyak kejutannya (tadinya nebak gini taunya gini). ini cerita bagus. penulisnya pintar. pintar bawa masuk pembaca ke suasananya. pintar ngemas cerita dengan sebaik mungkin. pintar memilih kata dan majas. kayaknya ini bukan penulis yang penuh pengalaman...
Comment on chapter PROLOG