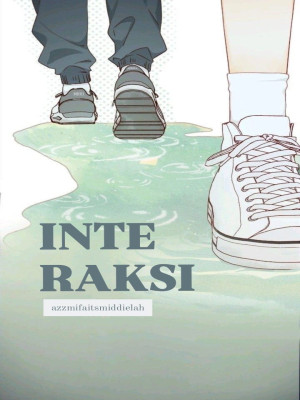Aku benar-benar tidak menemukan Nube sepanjang perjalanan pulang. Yang ada justru Noah—diam-diam seperti penjaga bayangan—terus berada di sampingku.
Padahal aku sudah berkali-kali memintanya untuk pulang saja. Aku bukan anak kecil yang butuh diantar, apalagi malam itu jalanan masih cukup ramai, banyak orang keluar dari stadion yang baru selesai digunakan.
Tapi dia tetap di situ. Tidak bergeming. Tidak mundur sejengkal pun. Bahkan saat aku mempercepat langkah, dia seperti magnet yang otomatis ikut merapat.
Jujur saja, aku mulai kesal.
Sepanjang jalan aku mendesah, berharap dia sadar diri dan berhenti mengikutiku. Tapi sepertinya ia tak peka-pela juga. Dan seolah belum cukup, suara gemuruh di langit mulai terdengar.
“Noah...” gumamku pelan, hampir seperti ingin mengusir awan. Aku begitu ragu menyebut namanya yang terkesan asing.
“Sepertinya tugas pawang hujan sudah selesai,” katanya santai sambil menatap langit yang mulai meneteskan rintik.
Aku menoleh tajam. “Kau dengar kan? Pulang saja. Aku tidak ingin repot menahanmu kalau tiba-tiba... hu—”
Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, langit seolah menepuk pundakku keras-keras. Hujan turun. Deras. Tiba-tiba. Seolah membalas ucapanku sendiri.
Butiran hujannya besar-besar, seperti memukul wajahku tanpa ampun. Wajahku terasa perih, dan mataku kabur oleh air.
Kami segera berlari mencari tempat berteduh. Jalan ke rumahku masih cukup jauh. Gelap mulai menelan gang-gang kecil. Lampu jalan yang temaram oranye pun tak banyak membantu. Beberapa kali aku hampir terperosok ke lubang kecil yang tertutup genangan. Pergelangan kakiku mulai terasa nyeri.
Sementara Noah masih berada di dekatku, diam-diam mengamati langkah kakiku yang mulai pincang. Tapi tetap saja, aku tidak tahu kenapa dia masih mengikuti.
Aku muak. Tapi... juga bingung. Aku lelah. Dan jujur saja, kacau.
Tiba-tiba dia menarik tanganku. Tanpa banyak bicara, dia membawaku ke sebuah halte kecil di pinggir jalan. Atapnya reyot dan penuh lubang. Sama sekali bukan tempat yang ideal untuk berteduh, tapi setidaknya bisa menahan sebagian hujan.
Kami duduk berdempetan dalam diam. Jarak kering dari tempias hanya beberapa jengkal.
“Astaga, kakimu kenapa?” katanya tiba-tiba, matanya menatap kaki kananku yang kuangkat sedikit.
Aku menggigit bibir, berusaha mengalihkan rasa sakit. “Entahlah. Mungkin terkilir.”
Dia langsung melepas kemeja biru muda yang tadi dipakainya. Tenang saja, dia masih memakai kaus oblong di dalamnya. Kaos itu bertuliskan The Beatles yang sudah agak pudar.
“Kemeja ini basah, nggak banyak membantu,” katanya sambil menyodorkannya. “Tapi mungkin bisa sedikit mengurangi rasa sakit dari hujan yang mukul kepalamu.”
Aku memandangi kemeja itu. “Enggak usah. Sama aja, tetap basah.”
Tapi dia tidak peduli. Dia tetap menaruhnya di atas kepalaku, membentangkannya seperti tenda kecil. Kemeja itu menutupi wajahku sebagian. Hangatnya bukan dari bahan kainnya, tapi dari sikap yang janggal tapi tulus.
“Ayo pulang,” katanya sambil jongkok di sampingku.
Aku mengernyit. Dia bilang pulang, tapi kenapa malah jongkok?
“Naiklah.” Nada suaranya tenang. Tidak memaksa, tapi tegas.
Aku mematung. Baru kusadari, dia sedang menawarkan punggungnya. Untuk menggendongku?
“Serius?” desisku. “Hei! jangan aneh-aneh. Aku masih bisa jalan sendiri. Lagipula aku nggak minta bantuan!”
Dia tetap diam. Lalu, perlahan berdiri. Menatapku—bukan dengan wajah lucu seperti biasanya. Tatapannya tenang, jernih, dan serius.
“Kalau keras kepala jadi nama tengahmu, ya sudah. Tapi jangan salahkan aku kalau kau tambah parah nanti.”
Lalu dia berjalan. Tidak menoleh. Tidak menunggu.
Aku terpaku. Ada jeda. Lalu aku berdiri, berjalan tertatih di belakangnya, sambil tetap menahan hujan yang memukul wajahku dari sela-sela kemeja yang menempel di kepala.
Malam itu, aku berjalan di belakangnya. Hujan masih deras. Dia tidak bicara sepatah kata pun. Tapi entah kenapa, aku merasa dia sedang menahan sesuatu.
Apakah dia kecewa?
Marah?
Atau hanya lelah seperti aku?
Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, langkahnya cepat sekali. Sampai-sampai aku kehilangan bayangannya di tikungan terakhir.
Dan ya. Dia menghilang. Tidak menunggu. Tidak menemaniku sampai depan rumah.
Tapi aku bersyukur. Aku sampai di rumah dengan selamat. Meskipun kakiku sakit luar biasa.
Sesampainya di rumah, lampu teras masih menyala. Tapi tidak ada tanda-tanda ayah sudah pulang. Sepertinya beliau lembur atau mungkin sedang dalam perjalanan.
Aku membuka ponsel. Basah kuyup, tapi untungnya masih bisa menyala. Ada beberapa SMS dari Ayah, bilang bahwa dia pulang terlambat.
Satu pesan lainnya dari Brian. Katanya dia sudah menemukan ide untuk tugas kesenian.
Aku tersenyum kecil. Lucu sekali. Di tengah semua kekacauan ini, hal kecil seperti itu bisa membuatku tenang.
Aku masuk kamar. Tanpa pikir panjang, aku mandi air hangat, lalu merebahkan tubuhku di kasur.
Sambil menarik selimut, aku menutup mata dan berdoa dalam hati:
Semoga besok tidak sesakit hari ini. Dan kalaupun sakit, semoga aku punya cukup tenang untuk menerimanya.
***
Aku terbangun karena nyeri hebat di pergelangan kaki kananku. Rasanya seperti disayat—tajam dan berulang-ulang.
Begitu membuka mata, aku menatap kakiku yang membengkak seperti ditampar kenyataan.
Sungguh... pagi macam apa ini?
Belum sempat aku bangkit, suara ketukan pelan di pintu kamar terdengar.
"Tiara, bangun. Sudah hampir subuh," suara ayah dari luar.
Aku melirik jam. 04.45 pagi.
Rasanya baru lima menit aku terlelap.
Dengan berat hati aku bangkit dan menyeret tubuhku ke kamar mandi.
Di sana, aku hanya duduk di pinggiran bak, merendam kakiku ke dalam air hangat. Harapanku sederhana—nyeri ini menguap, meski hanya sebentar.
Dan benar saja. Nyeri itu reda. Tapi hanya sebentar. Begitu kakiku kuangkat, rasa itu datang lagi, lebih dalam. Lebih menusuk.
Aku menyerah. Tapi tetap berdiri. Tetap melanjutkan rutinitas seolah tidak terjadi apa-apa.
***
Di meja makan, aku duduk dengan wajah datar. Ayah sedang menyeduh kopi.
“Ayah, aku ikut bus ayah aja hari ini ya?”
“Boleh.”
Dia tak bertanya lebih jauh. Mungkin karena tahu, atau mungkin memang sedang terlalu sibuk untuk peduli.
Akhirnya, kami berangkat pagi-pagi sekali.
Setibanya di sekolah, pintu gerbang baru saja dibuka. Beberapa siswa tampak baru datang.
Tapi bagiku, perjuangan sebenarnya baru dimulai: menaiki puluhan anak tangga ke lantai tiga.
Setiap langkah terasa seperti ujian sabar. Kakiku mulai berdenyut hebat, tapi aku terus memaksakan naik.
Hingga akhirnya... di pertengahan tangga, aku menyerah.
Aku terduduk di anak tangga, menunduk, menahan napas panjang. Bukan hanya karena sakit. Tapi juga karena malu. Takut ada yang melihatku dalam keadaan begini.
Ketika aku mendongak untuk mengecek apakah ada yang melihat, aku justru menangkap tatapan... Kenan.
Dia berdiri di ujung tangga. Diam. Tidak berekspresi. Tapi... aku tahu dia memperhatikanku.
Aku segera berdiri. Menyembunyikan luka di pergelangan kakiku sebaik mungkin dan melanjutkan naik, pura-pura tidak terjadi apa-apa.
Kami berpapasan. Tidak ada sapa. Tidak ada salam. Hanya keheningan yang menggantung.
Tapi tiba-tiba—dia menarik lenganku. Tanpa sepatah kata.
Aku refleks terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Rasa nyeri mencuat lagi, membuatku menggertakkan gigi.
Dia mau apa? pikirku bingung. Aku ingin marah, tapi juga takut bicara. Otakku seperti sedang rapat darurat: harus bertanya dulu? Menolak? Atau... terima saja?
Dia membawaku menjauh dari arah kelas. Lalu membuka pintu sebuah ruangan.
Ruangan putih. Ada tempat tidur. Aroma antiseptik. Dan tulisan yang terbaca terbalik dari balik kaca:
UKS.
Aku menoleh cepat. “Kenapa kau bawa aku ke sini?” pikirku, tapi tak sempat terucap. Dia sudah memberi isyarat agar aku duduk di ranjang.
Aku bingung. Ragu. Tapi akhirnya menuruti.
Kenan berjalan ke sisi ruangan, membuka kotak bening di atas meja, lalu kembali menghampiriku dengan beberapa perlengkapan di tangan.
Aku masih berdiri, kaku.
“Kenapa masih berdiri?” tanyanya datar.
Dia meletakkan alat-alat di ranjang, lalu menarik kursi ke sisiku.
“Buka sepatumu,” lanjutnya.
“Eh... apa?” aku mengerutkan alis.
Dia menirukan ekspresiku. “Nggak ngerti?”
“Aku nyuruhmu duduk dan buka sepatumu,” ulangnya.
“Buat apa?”
Dia menghela napas panjang, menahan diri agar tidak kesal. “Turuti aja dulu. Nanti juga ngerti.”
Dengan canggung, aku duduk dan membuka sepatuku perlahan. Dia mengambil selimut tipis dan menaruhnya di pangkuanku.
Lalu, ia berjongkok di depan tempat tidur, menyuruhku membuka kaos kaki. Tangannya sigap menyiapkan perban dan kompres dingin.
“Sampai bengkak begini?” gumamnya lirih.
“Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau tahu—”
Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, dia mengangkat kakiku dengan hati-hati, lalu membalutnya dengan perban elastis. Sentuhannya cepat, efisien, tidak kasar, tapi juga tidak lembek.
“Masih nyeri?” tanyanya singkat.
Aku mengangguk.
Tanpa komentar tambahan, dia bangkit, berjalan ke kotak di dinding dan mengambil satu tablet obat.
“Ini direkomendasikan pembimbing dari rumah sakit. Lumayan untuk pereda nyeri ringan. Tapi kalau nyerinya bertahan lebih dari dua hari, lebih baik periksa ke klinik.”
Lalu, ia membereskan alat-alat yang tadi ia keluarkan. Rapi. Hening.
Sebelum keluar ruangan, dia berkata lagi, “Kalau keseleo, jangan langsung air hangat atau koyo. Harusnya kompres dingin dulu. Dan pakai ini.”
Dia menyodorkan tongkat jalan. “Gunakan ini selama beberapa hari. Jangan dipaksakan.”
Kemudian ia pergi. Tanpa pamit. Tanpa menunggu jawaban.
Aku hanya bisa duduk terpaku.
Kenapa dia seperti tahu semua ini? pikirku.
Aku turun dari ranjang perlahan, mengambil tongkat itu. Dan sebelum keluar dari UKS, mataku menangkap sesuatu di dinding: struktur organisasi sekolah.
Mataku membidik satu nama dan foto. Di sana, tertulis:
Kenan – Divisi Kesehatan, PMR.
Ah...
Pantas saja.


 tavxoc
tavxoc