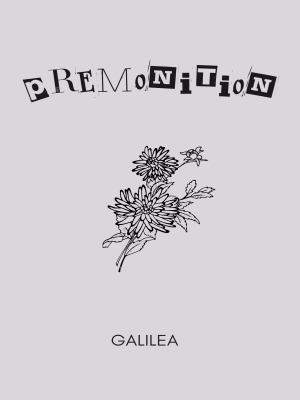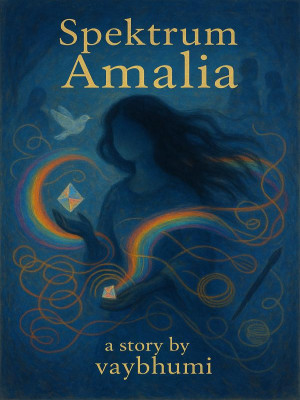Badanku hampir remuk. Ayah tidak membiarkanku istirahat sejenak. Sesampainya di rumah, dia langsung menyuruhku membersihkan rumah: menyedot debu, menaruh baju di lemari, membantu memasak makan malam, bahkan menyiram tanamannya yang jumlahnya luar biasa banyak—dan sialnya, hujan turun, membuat semuanya sia-sia. Ayah memang tidak suka aku bermalas-malasan. Katanya, “Istirahat itu kalau semua pekerjaan sudah selesai.” Baginya, tidak ada kata menunda pekerjaan dalam kamus hidupnya. Padahal aku masih mabuk laut dan jet-lag.
Setelah semua pekerjaan selesai, bukannya mengantuk, aku malah terjaga sepanjang hari. Menunggu—aku bahkan tidak tahu apa yang kutunggu. Malam pun terasa lambat. Jam baru menunjukkan pukul tujuh. Hujan turun deras. Aku duduk bersila di depan jendela ruang tamu, secangkir matcha di tangan, melamun. Lampu taman berwarna oranye menyala, dan aku melihat anak itu... dia masih di sana. Duduk, diam, dengan pakaian yang sudah basah kuyup. Yang terlihat hanyalah punggungnya. Aku tidak tahu apa yang sedang ia nanti. Ia bahkan mengabaikan tubuhnya yang basah.
Seharian aku tidak membuka pintu depan dan tidak memastikan apakah dia masih di sana, tapi nyatanya—dia masih ada. Aku tidak tahu apa misinya. Sosok misterius itu... kurasa dia arwah anak yang jatuh di dermaga. Mungkin dia mengikutiku karena aku melihatnya saat jatuh. Karena mayatnya belum ditemukan, ia terus menempel padaku, mungkin ingin kuselesaikan urusannya. Tapi... bukankah dia tidak nyata? Aku bingung.
Apa dia hanya halusinasi? Boom? Ya, aku bahkan memberinya nama. Tapi mengapa ia begitu nyata, padahal hanya hasil halusinasi? Apakah karena aku kesepian lalu menciptakannya? Tapi kenapa sosoknya tak sesuai dengan imajinasiku? Laki-laki, berseragam sekolah, bersepeda, dan menunggu... Aku tidak pernah menggambarkan sosok seperti itu sebelumnya. Atas dasar apa dia hadir dalam hidupku?
“Tidak tidur?” tanya Ayah saat lewat menuju kamar bawah tanahnya.
“Belum ngantuk,” jawabku.
Dia hanya mengangguk, tangannya masuk ke kantong celana training. Kacamata tanpa bingkainya melorot di hidungnya yang kurus. “Besok kamu mulai masuk sekolah. Ayah antar sekalian berangkat kerja.”
“Tidak bisa aku libur dulu beberapa hari?” Pintaku dengan wajah memelas. Tapi dia hanya tersenyum, tanda tidak setuju.
“Kamu sudah tingkat akhir. Terlalu banyak libur itu tidak baik.” Suaranya tenang tapi tegas. Namun ada kehangatan yang kurindukan.
Aku mendengus, memasang wajah kecewa, tapi tetap tak meluluhkan hatinya. “Bus ayah datang jam enam. Siap sebelum itu.”
“Jam enam? Jangkrik saja belum pulang.”
“Ayah tak bisa antar lebih dari jam itu. Kamu bisa sendiri di hari pertama?”
Aku menggeleng. “Bahkan aku tidak tahu kapan hari pertama. Bisa besok, lusa, minggu depan...”
Dia menggeleng tegas. “Tidak ada libur. Banyak anak ingin sekolah dan harus berjalan jauh untuk bisa sekolah.”
“Baiklah-baiklah,” kataku buru-buru sebelum ceramahnya jadi panjang. “Kalau begitu aku tidur, supaya bisa bangun pagi.” Kuteguk habis matcha-ku dan berdiri.
“Sebelum jam enam kita jalan, oke?” tegasnya.
Begitulah bincanganku dengan ayah. Tak banyak yang bisa kami habiskan bersama. Kami selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah berpisah di ruang tamu, aku kembali ke kamar dan melamun.
Malam ini begitu suntuk. Aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar yang memantulkan bayangan tetes hujan dari cahaya lampu jalan. Kamarku gelap, hanya ada pantulan cahaya yang tak kusukai. Aku lebih suka gelap daripada sedikit cahaya—seolah suasana ini mencerminkan isi jiwaku.
Aku bangun, berjalan ke jendela besar, lalu membukanya. Kamarku berada di lantai dua. Hanya kamarku dan gudang yang ada di atas, sedangkan ayah tinggal di lantai satu. Lantai dua membuatku merasa nyaman—jauh dari gangguan.
Aku menaikkan kaki kanan, menekuknya di dada. Dari sini, aku bisa melihat laut tanpa harus ke pantai. Bisa mengamati orang-orang tanpa perlu menyapa. Bus malam lewat, bukan bus umum, melainkan bus penjemput pekerja tambang. Meski malam, orang masih bekerja di pulau kecil ini.
Jam sembilan malam, aktivitas sudah mati. Semua menutup pintu, jendela, dan gorden rapat-rapat. Tak ada hiburan, bahkan pasar malam pun tidak. Tidak ada minimarket. Kebutuhan seadanya. Mayoritas penduduknya petani, nelayan, dan pekerja tambang. Kulit mereka legam terbakar matahari, bahasa mereka logat daerah yang berbeda-beda.
Asing.
Aku berdiri, lalu berjalan ke meja belajar. Seperti biasa, kutulis kejadian hari ini. 13 September 2014 kutulis sebagai awal di buku harianku. Hari yang sulit dilupakan. Aku merasa semakin gila. Hari pertama di pulau ini malah menyisakan tragedi.
Seorang anak laki-laki, yang kusebut Boom, muncul dalam imajinasi. Ia jatuh dari jembatan dermaga bersama sepedanya. Tak tertangkap kamera. Lalu dia datang ke rumah, duduk di bawah hujan berjam-jam. Dia... siapa sebenarnya? Yang hanya kulihat, tapi tak terlihat oleh orang lain. Aku menutup buku, buru-buru naik ke tempat tidur. Badanku merinding. Kuselimuti tubuhku. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba merasa takut.
Bayangan pohon masuk ke kamar, seperti sesuatu datang tanpa izin. Padahal aku tahu itu hanya bayangan. Ranting mengetuk dinding kayu. Ini bukan suasana yang kuinginkan, terutama di hari pertama kembali ke rumah ini setelah sekian lama.
Kau tahu mitos itu—rumah yang lama tak ditinggali akan punya penghuni lain. Tak kasat mata. Ayah tinggal sendiri. Tentu saja, kamar ini pasti pernah dihuni sebelumnya. Jika benar... aku tak ingin tahu. Lagipula, aku tidak percaya hantu atau sejenisnya.
Pulau ini punya sejarah, meski tak tertulis di buku. Saat masa penjajahan, tempat ini jadi persinggahan tentara Belanda. Tadi siang aku melihat rumah bundar—kata ayah, peninggalan Belanda.
Dan malam di sini sangat gelap. Lampu jalan berjauhan. Jarak antar rumah juga jauh. Sekelilingnya hutan. Nuansa mistis menyelimuti saat kau pertama kali mengenal pulau kecil ini. Seperti titik di peta, dikelilingi laut.
Aku menghubungkan semua itu dengan suasana kamarku yang mencekam. Angin dan hujan seolah ingin menerobos jendela. Aku takut.
Jendela bergetar. Aku turun dari tempat tidur, mengikat handle jendela dengan tali ke tiang ranjang. Lebih baik begitu daripada mendengar getaran semalaman.
Saat aku selesai, kusandarkan badan. Petir menyambar, kilat menyinari halaman.
Dia berdiri di sana.
Boom?
Aku pun heran kenapa menamainya begitu. Apakah dia benar dari dimensi lain? Dia selalu datang tiba-tiba. Aku bingung, mana kenyataan.
Apakah dia anak yang meninggal pagi tadi? Atau arwah yang lebih lama?
Pikiran-pikiran itu menyesak. Dia menghantuiku tanpa ampun. Seolah ada urusan denganku di masa lalunya. Balas dendam? Permintaan tolong?
Dia menatapku dari bawah, matanya teduh. Pakaian sekolahnya basah. Tatapannya seakan mengharap sesuatu... tapi apa?
Aku mundur. Ingin menghindar. Kenapa harus kuladeni? Mungkin dia cuma halusinasi.
Bruak!
Tumitku tersandung. Badanku terjerembab jatuh. Kupikir tali... tapi posisinya tidak mungkin. Apa ada sesuatu yang sengaja menjatuhkanku?
Bau karat berubah menjadi bau anyir darah. Hujan menghantam wajahku. Langit-langit—adegan familiar terulang. Aku sadar aku tak di kamar.
Aku terbaring di jalan. Genangan darah. Langit siang mendung menatapku.
Aku mengerti.
Kepalaku membentur lantai kamar membuatku kembali ke titik—titik yang paling kutakuti. Lalu lintas kacau di depan sana. Teriakan orang-orang. Tiba-tiba aku berusia lima belas lagi.
Walkmanku terlempar. Tapi lagu di dalamnya masih terdengar.
Beberapa menit sebelumnya, rencana perjalanan ini tak seharusnya berakhir di sini.
Aku tak tahu berapa lama terbaring. Tak melihat Ayah atau Ibu. Hanya mataku yang bisa bergerak.
Tuts piano. Senyuman. Perjalanan ke hutan...
Hutan?
Aku menyusuri jalan setapak, dikelilingi pepohonan. Hijau berubah emas saat senja. Damai.
Gambaran liburan musim dinginku beberapa bulan lalu. Saat itu aku semangat, meski dingin dan lembap. Tapi kini—semangat itu hilang. Tak ada tenaga untuk berdiri.
Sebelum aku terlelap, jika ini akhir...
Ada satu hal yang ingin kukatakan.
Jika aku tak bangun lagi...
Hal terakhir yang kupikirkan...
Aku melihat sekeliling.
Hanya satu sosok terlihat samar. Terbaring tak bergerak, tak jauh dariku.
Dan yang terakhir kupikirkan...
...Adalah kau.


 tavxoc
tavxoc