Namanya Sastra.
Ia mengampu mata pelajaran Sastra Indonesia di jurusan Bahasa juga, tapi tampaknya ia tak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri.
“Sama sekali nggak ada murid baru yang daftar ke ekskul teater, Pak.” Sekali lagi, Ibu Kepala Sekolah mengoyak pisau yang tertancap di dada Sastra. “Jumlah peserta dari kelas sebelas dan kelas dua belas berapa, ya?”
Sastra menengadah. Tatapannya nanar memandang langit-langit ruang yang tinggi, kipas angin kuno peninggalan dua puluhan tahun lalu—masa saat ia masih menjadi murid di sini—dan sarang laba-laba yang membungkus pucuk ukiran lis dinding yang rumit.
Lisnya menguning, mengingatkan Sastra bahwa waktu telah berlalu begitu cepat, dan ....
Tak bisa terulang lagi.
“Tiga.” Suaranya serak.
“Tiga.” Ibu Kepala Sekolah mengulang dengan iba.
“Nggak ada peserta dari kelas dua belas karena mereka harus fokus belajar, Bu.”
“Benar sekali, Pak. Tapi benar-benar hanya ... tiga?”
“Apa benar-benar nggak ada murid kelas sepuluh yang daftar?”
Ketika pertanyaannya dibalas gelengan, Sastra ingin menangis. Jikalau ia memang bisa menangis. Ia bisa menangis di panggung, tetapi tidak di kuburan dan sewaktu diumumkan bahwa ekstrakurikuler yang diampunya sedang krisis.
“Begini, Pak. Seperti hasil rapat tahun ajaran baru kemarin ... kita kena dampak efisiensi anggaran dari yayasan.” Wanita di hadapannya menghela napas saat membolak-balik catatan. “Ekskul-ekskul yang sudah nggak aktif lagi, atau sedang di ambang batas, akan ditutup tahun ini. Pihak yayasan ingin mengalokasikan anggarannya untuk program-program baru menyesuaikan imbauan Pak Menteri.”
Sastra masih memandang laba-laba yang merangkak di sarangnya.
“Saya ... saya mengerti perasaan Pak Sastra.” Ibu Kepala Sekolah berbisik, nadanya melembut dan sedikit personal. “Teater Layar Surya memang pernah berjaya dua puluhan tahun lalu. Malah itu yang bikin SMA Surya Cendekia jadi terkenal di mana-mana. Tapi zaman udah berubah, benar? Minat anak-anak lebih terarah ke ekskul bahasa asing dan, yah ... yang tetap berfungsi sehari-hari seperti PMR.”
Sastra menutup mata. Diingatkan seperti itu rasanya pedih. Seolah-olah teater tak lebih dari sekadar tontonan sinetron di televisi yang bisa diganti kanalnya kapan saja.
Teater Layar Surya lebih dari sekadar kejayaan di masa mudanya. Itu hidup Sastra. Alasan ia tetap bernapas hingga saat ini. Teater Layar Surya menyembuhkannya lebih ampuh daripada gabungan dukun, psikiater, dan rumah sakit jiwa mana pun.
Namun, ia tahu curhatan hati takkan membuat anggaran yayasan tetap mengalir.
“Apa yang bisa saya lakukan, Bu?”
“Minimal ada prestasi baru, Pak.” Jawabannya diplomatis. “Ikut lomba, tapi pastikan Layar Surya jadi finalis dan dapat piala. Bukan sekadar jadi peserta saja. Untuk anggotanya menyesuaikan. Minimal lima ... enam ... yang penting kepengurusannya berjalan.”
Pria di awal empat puluhan itu membuka mata. Tatapannya terarah lurus kepada sang kepala sekolah dan, bersama duka serta kenangan yang terbakar di dalam hatinya, ia mengangguk.
“Saya usahakan, tapi ... tolong,” ujarnya lirih. “Beri saya waktu.”
Selama sesaat, tak ada suara di ruangan itu selain detak dari lemari jam kayu tua di pojok. Lalu, dengan anggukan pasrah, Ibu Kepala Sekolah berkata, “Sebelum semester genap dimulai, saya ingin ada perkembangan besar.”


 andywylan
andywylan

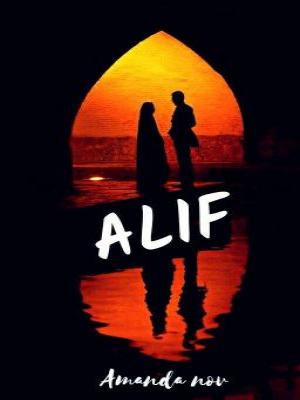








Haruskah kita bertemu lagi dengan efis---
Comment on chapter Prolog: Ambang Batas