Sophia melangkah masuk ke kelas dengan gerakan canggung seperti biasa. Pagi itu, anak-anak X-E tampak sibuk menyalin PR Matematika sebelum Pak Erhan datang. Suara gesekan pensil dan desahan terburu-buru mengisi udara.
Ia berjalan menuju kursinya, namun langkahnya melambat saat melewati meja Bella. Sekilas, matanya menangkap isi buku tulis yang terbuka di atas meja itu.
Jawabannya salah, pikir Sophia.
Ia sampai di bangkunya, tapi tidak langsung duduk. Tubuhnya membeku sejenak. Tangannya mengepal tanpa sadar di sisi tubuhnya. Ia tahu risikonya. Bella dan gengnya bukan tipe yang bisa menerima kritik. Tapi membiarkan orang lain menyalin jawaban yang salah… terasa lebih kejam daripada rasa takut yang kini mencengkeram tenggorokannya.
Dengan napas pelan dan langkah ragu, ia berbalik. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh bahu Bella.
Bella menoleh. Wajahnya tampak tidak ramah.
“Jawabannya ada yang salah,” bisik Sophia, nyaris tak terdengar.
Bella mengerutkan alis. “Kalau gitu, sini gue lihat PR lo.”
Sophia cepat-cepat menggeleng. “Gue enggak bisa kasih contekan… tapi gue bisa ajarin caranya.”
Bella mendengus sinis. Ia berdiri, tubuhnya kini menghadap langsung ke Sophia.
“Kenapa? Kenapa lo enggak mau ngasih?” Nadanya mulai meninggi.
Sophia mundur selangkah. “So—soalnya… nanti lo jadi enggak belajar...”
Tawa dingin meluncur dari mulut Bella. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Beberapa teman dari geng-nya ikut berdiri dari kursi mereka, membentuk barisan tak ramah di belakang Bella.
“Heh, Sophia. Waktu SMP, gue nganggep lo temen, ya. Tapi apa balesan lo? Waktu ulangan gue minta tolong, lo malah nyuekin gue. Pura-pura enggak denger. Lo tau enggak, gara-gara itu gue harus ngulang?!”
Sophia menelan ludah. “Gu-gue waktu itu udah ngajakin belajar bareng sebelum ulangan… tapi lo enggak mau. Katanya sibuk ekskul...”
“JADI MAKSUD LO GUE YANG SALAH?!” bentak Bella, suaranya menggema di seluruh ruangan.
Suasana kelas mendadak senyap. Semua kepala menoleh ke arah mereka.
Lalu… pintu kelas berderit terbuka.
Bumi masuk.
Wajahnya datar seperti biasa. Tangannya terlipat di dada. Ia berjalan perlahan, melintasi kerumunan itu tanpa mengucap sepatah kata pun, ia menaruh tasnya di meja, lalu duduk di kursinya. Ia menyandarkan punggung dan menatap langit-langit seolah sedang menikmati pagi yang damai.
“Kalian enggak punya kerjaan lain?” ucapnya tenang.
Suaranya pelan, tapi cukup tajam untuk membuat semua orang mendengarnya.
Anak-anak yang tadinya menonton drama itu mulai berpaling. Beberapa langsung membungkuk kembali ke buku mereka. Suasana kelas kembali seperti semula.
Bella mendelik tajam ke arah Sophia untuk terakhir kalinya, lalu kembali ke tempat duduknya.
Sophia perlahan duduk. Wajahnya muram. Ia membuka bukunya dan menatap halaman kosong di hadapannya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya.
***
Pelajaran Matematika hari itu, Pak Erhan masuk ke kelas dengan aura gelap seperti biasa. Langkahnya berat, dan begitu ia meletakkan buku di atas meja, pandangannya langsung menyapu ruangan, tajam dan mengintimidasi.
Tatapannya berhenti pada salah satu meja di tengah kelas—dua siswa tampak tengah berbagi satu buku paket.
“Hei, kalian.” Suaranya menggema, tajam. “Siapa yang enggak bawa buku?”
Kedua anak itu saling berpandangan, gugup. Salah satu dari mereka, Agus, akhirnya mengangkat tangan perlahan.
“Sa-saya, Pak...”
“Ke mana buku kamu?” tanya Pak Erhan, nadanya meninggi.
“Belum beli, Pak...” jawab Agus pelan, menunduk dalam.
Pak Erhan mendengus kasar. “Kalau miskin, enggak usah sekolah sekalian. Keluar kamu!”
Kelas terdiam. Bumi mengangkat alis, rahangnya menegang. Tapi ia menelan amarahnya, menarik napas dalam-dalam. Menahan diri.
Wajah Agus memerah. Dengan kepala tertunduk, ia bangkit dan melangkah keluar kelas. Suara pintu yang menutup terdengar lebih nyaring dari biasanya—seperti menyegel rasa malu yang tertinggal di ruangan.
Tanpa menoleh, Pak Erhan mengambil kapur dan mulai menulis di papan. Ia menjelaskan tentang penerapan persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah. Suaranya monoton, tak ada yang benar-benar mendengarkan.
Sementara itu, di bangkunya, Sophia tampak gelisah. Jari-jarinya mengetuk buku, bibirnya digigit, dan matanya terus berpindah dari buku ke papan, lalu kembali lagi.
Bumi, yang duduk di sebelahnya, melirik sekilas. Ia mengerti.
“Ngomong aja,” gumamnya pelan tanpa menoleh.
Sophia tersentak kecil. Ia menoleh cepat ke Bumi, menatapnya dengan wajah terkejut.
“Jangan takut,” gumam Bumi lagi.
Sophia diam sejenak. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa nyali dalam dirinya. Lalu, dengan sedikit ragu tapi mantap, tangannya terangkat.
Seisi kelas membeku. Semua kepala menoleh.
Pak Erhan menghentikan gerak tangannya, menoleh. Alisnya terangkat. “Apa?”
“Maaf, Pak,” ucap Sophia. “Tadi ada yang salah… seharusnya...”
Kali ini Sophia tidak memberi pertanyaan, ia menguraikan. Runut, sistematis, dan jelas. Beberapa anak yang semula hanya menunduk mulai mengangkat wajah, mendengarkan. Bahkan ada yang mencatat, karena penjelasan Sophia terasa jauh lebih mudah dipahami.
Namun wajah Pak Erhan mengeras. Belum selesai Sophia berbicara, ia melangkah cepat ke arahnya—dan PLAK! buku paket tebal menghantam kepala Sophia.
Seisi kelas terkesiap.
Sophia terhenyak, menunduk dalam. Napasnya memburu, dadanya naik-turun cepat.
Bahkan Bella yang tadi pagi dipenuhi kemarahan terhadap Sophia, wajahnya kini terlibat iba memandangnya.
Di bangkunya, tangan Bumi yang terlipat kini mengepal, buku-bukunya memutih. Matanya menatap lurus ke depan. Dalam diamnya, amarah menggelegak.
“Kalau kamu ngerasa lebih pintar dari saya, kamu aja yang ngajar di depan,” kata Pak Erhan, dingin.
Bumi memejamkan mata. Jangan bikin masalah… jangan bikin masalah, Bumi… bisiknya dalam hati. Tapi saat ia membuka mata, yang dilihatnya adalah punggung Sophia yang gemetar halus, tangan yang mencengkeram rok erat-erat, dan mata... basah.
Persetan.
“Mungkin memang seharusnya Sophia yang ngajar di depan, bukan Bapak.”
Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Bumi. Tenang... tapi tajam seperti pisau.
Pak Erhan, yang sudah berbalik untuk bergerak ke mejanya, menoleh perlahan. Alisnya terangkat tinggi, rahangnya mengeras.
“Apa kata kamu tadi?” tanyanya, suaranya menantang.
Bumi menyandarkan tubuh santai ke sandaran kursi. “Simpel, Pak. Kalau penjelasan Sophia tadi salah, Bapak tinggal kasih yang benar…”
Ia menoleh, menatap langsung ke mata Pak Erhan. Senyum tipis muncul di wajahnya, datar dan dingin.
“Bapak enggak bisa bantah ya? Makanya Bapak harus mukul?”
PLAK!
Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bumi. Kelas kembali terkesiap. Beberapa siswa menutup mulut mereka, ngeri.
Pak Erhan tampak gemetar, wajahnya merah karena marah… atau takut.
Sementara Bumi? Pipinya memang memerah, tapi matanya tidak gentar. Tatapannya tetap tajam, tenang, kokoh. Seperti gunung yang menolak tunduk pada badai.
Lalu ia menyeringai. Dingin. Mengerikan.
Seringai yang sontak membuat bulu kuduk Pak Erhan meremang dan tangannya gemetar.
“Kenapa, Pak? Enggak bisa bantah saya juga?” kata Bumi dengan nada lembut tapi menusuk.
“Ka-kamu… kurang ajar kamu! Keluar kamu sekarang juga!!” bentaknya. Tapi suaranya goyah.
Bumi menatapnya lama. Lalu ia mendengus dan tiba-tiba bangkit berdiri. Suara kursinya yang terseret keras mengoyak keheningan kelas.
Pak Erhan tersentak.
Dengan langkah santai, tanpa terburu-buru, Bumi melangkah keluar. Di belakangnya, puluhan pasang mata mengiringi kepergiannya dengan takjub, ngeri, dan... kagum.
***
Kabar tentang Bumi yang melawan Pak Erhan menyebar cepat ke seluruh sekolah. Di kantin, kelas, hingga perpustakaan, namanya disebut-sebut dalam bisikan kagum dan penasaran.
“Pas dia ngelawan Pak Erhan, suaranya santai banget... tapi matanya, bro!” seru Geri dari kelas X-E.
“Cara dia ngelihat tuh... serem,” tambah Nino sambil menirukan senyum miring Bumi.
“Kayak psikopat.”
Anak-anak yang mendengar saling pandang. Takut, tapi juga terpesona.
Bumi bukan lagi sekadar murid baru. Ia mulai jadi legenda hidup.
Tapi efeknya tak berhenti di sana.
Keberanian Bumi membangkitkan semangat di antara murid-murid yang selama ini diam. Anak-anak seperti Sophia mulai berani angkat tangan di kelas Pak Erhan—bertanya, menyanggah, bahkan mengajak diskusi.
Murid-murid lain pun mendukung dengan mengeluarkan celetukan kecil seperti, “Harusnya emang lo aja yang ngajar,” disusul tawa-tawa tertahan.
Suasana kelas pun berubah. Bukan karena Pak Erhan jadi lebih lunak—justru sebaliknya. Tapi kini murid-murid tak lagi takut.
Meski dikeluarkan dari kelas, mereka tidak lagi tunduk. Mereka tertawa ringan.
Dan Pak Erhan? Ia semakin keras. Setiap pertanyaan yang tak bisa dijawab dibalas dengan gertakan. Sampai akhirnya... ia memukul anak yang salah.
Rafi dari kelas X-C. Pendiam, penurut, tak pernah melawan.
Tapi ayahnya pengurus POMG. Ibunya pengelola koperasi sekolah.
Malam itu, telepon kepala sekolah nyaris tak berhenti berdering.
Orang tua murka. Desakan datang dari mana-mana.
Akhirnya, Pak Erhan dimutasi.
Hari terakhirnya di sekolah sepi. Tanpa perpisahan. Tanpa ucapan terima kasih. Ia berjalan melewati lorong dengan wajah gelap, membawa barang-barangnya sendiri. Tatapan murid-murid yang ia lewati dingin. Bukan sedih, tapi lega. Bahkan puas.
Dan Bumi?
Siang itu, ia berdiri di atas pembatas rooftop. Tangan terlipat.
Seperti raja di menara, menyaksikan musuhnya jatuh.
Saat Pak Erhan menoleh sekali lagi, pandangannya bertemu dengan Bumi.
Anak itu tersenyum.
Tipis. Tenang. Penuh kemenangan.


 dwyne
dwyne





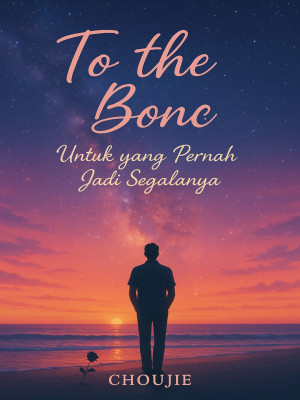
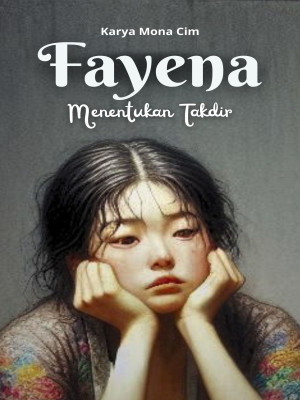




suka dengan bagaimana kamu ngebangun ketegangan di awal, adegan di toilet itu intens, tapi tetap terasa realistis. Dialog antar karakter juga hidup dan natural, terutama interaksi geng cewek yang penuh nostalgia masa SMA; kaset AADC dan obrolan ringan itu ngena banget.
Comment on chapter Pandangan Pertama