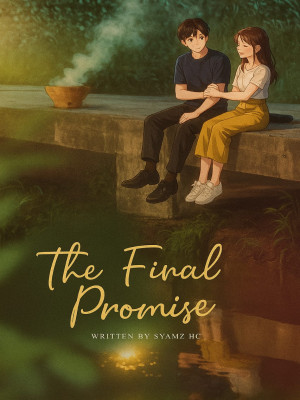Semesta memberiku nama, artinya 'Penguasa', tapi tangan-takdir mengikat pergelanganku erat, menjadikanku tawanan dalam kisah yang terus menginginkanku sebagai tokoh yang seharusnya tidak ada.
__Arsya Abiseka G
_____________________________________________________________________________________________________
Detik jam dinding berdetak seperti hitungan mundur menuju kematian. Nohan menatap sosok di balik kaca—ketidakberdayaan tubuh itu hanyalah kamuflase. Sebab identitasnya adalah bom waktu bagi Pak Nohan.
Arsya. Nama yang terpampang di pintu itu menikam benaknya, memanggil karma lama yang ia kira telah berhasil disembunyikan, terkubur di balik dinding-dinding hati nurani.
"Kenapa?" tanya Nohan dalam hati. "Aku sudah menitipkannya... Aku yakin, tempat itu aman. Laporan terakhir bilang semua baik-baik saja. Tapi kenapa dia justru di sini? Kenapa dia bisa sampai ke rumah sakit ini?"
Pandangan Nohan menelusuri wajah pucat di balik selimut rumah sakit. Itu memang dia. Arsya. Dan kebetulan Pak Aswan memintanya menyelidikinya, karena anak ini meyeretnya ke masalah.
Tiba-tiba, dingin menjalar di tengkuk Nohan, seolah jari-jari tak kasat mata menyentuhnya. Ini bukan kebetulan. Bagaimana mungkin dari sekian banyak pasien, Arsya justru berada di sini, di bawah pengawasannya? Hanya ada dua kemungkinan: Pertama : Takdir yang menuntunnya. Kedua : Jebakan.
Apakah Aswan sedang menguji kesetiaannya, menarik jaring laba-laba untuk melihat apakah Nohan akan terjerat dalam dosa lamanya?
Jika Aswan tahu anak ini masih bernapas—tak ada yang selamat. Tidak Arsya. Tidak juga Nohan. Bahkan Dokter Nata yang terlalu banyak tahu.
Lutut Pak Nohan lemas mendadak, seolah jiwanya ditarik paksa dari tubuh. Jantungnya bergemuruh di dalam dada. Ia menekan permukaan kaca, berharap kekuatannya tak sepenuhnya pergi, menundukkan kepala begitu lama hingga sapaan seseorang menariknya kembali dari pusaran pikirannya.
"Permisi, Pak..."
Suara itu datang dari Dokter Nata, yang kini berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kemeja putih bersihnya terlihat rapi, jubah dokter tersampir di lengannya, memancarkan aura tenang namun berwibawa.
Pak Nohan tersentak. Ia tidak menyadari bahwa Dokter Nata sudah berdiri di sampingnya. Pikirannya justru kembali kepada Arsya.
"Anak ini bisa mengguncang segalanya, membuka kembali luka lama yang selama ini kami tutupi."
Tapi apa yang bisa dia lakukan? Menghilangkan anak ini dari rumah sakit mungkin satu-satunya cara untuk melindungi semuanya. Meski bagian kecil dari dirinya tahu bahwa itu salah.
"Apa kamu punya kepentingan dengan pasien saya? Maksud saya, Arsya—anak yang sedang berbaring di sana," ujar Dokter Nata lagi.
Pak Nohan menarik napas panjang, mencoba mengendalikan kecemasannya. "Saya hanya datang untuk memeriksa keadaan anak ini, atas permintaan Pak Aswan." Nada suaranya terdengar tenang, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang meluap.
Dokter Nata menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Saya masih menjalankan tugas sesuai permintaan beliau. Anak ini masih membutuhkan perawatan. Kami tidak akan menerima intervensi apapun yang membahayakan kesembuhannya."
Pak Nohan terdiam setelah penegasan Dokter Nata. Sementara itu, Dokter Nata sendiri berhasil menyimpulkan identitas pria yang sudah cukup lama menatap ke dalam ruangan Arsya.
"Orang ini... aku tahu dia tidak asing. Ternyata benar. Dia berhubungan langsung dengan Pak Aswan."
"Sebelumnya, perkenalkan. Saya Nata. Dokter yang bertanggung jawab selama Arsya dirawat di sini, atas permintaan Pak Aswan."
Nama itu meluncur dari bibir Dokter Nata dengan nada yang dipertegas, sebuah taruhan kecil untuk melihat seberapa jauh pria di depannya akan terperangkap. Ini adalah ujian pertama setelah kesepakatan mereka.
"Maaf sebelumnya. Saya Nohan, utusan dari Pak Aswan. Setahu saya, Bapak Aswan meminta Anda memindahkannya? Kenapa dia masih di sini? Dia harusnya sudah tidak ada di sini," sanggah Pak Nohan.
Dokter Nata membaca ketakutan yang terukir jelas di manik mata Pak Nohan. "Itu bukan kesepakatan kami. Arsya akan berada di sini sampai dia benar-benar sembuh."
"Sepertinya ada kesalahan dalam pemahaman Anda. Saya akan bertindak sesuai perintah." Pak Nohan mengeluarkan ponselnya, siap menghubungi seseorang. "Datanglah ke ruang VIP rumah sakit—"
Belum sempat Pak Nohan menyelesaikan kalimatnya, tangan Dokter Nata dengan cepat menyambar ponsel itu, menekan tombol merah di layar, memutus sambungan itu tanpa suara.
Tatapan tajam tak terbantahkan kini tertuju pada Pak Nohan. "Apa peringatan saya kurang jelas?" Dokter Nata sengaja menjeda kalimatnya. "Saya tidak akan mengizinkan intervensi yang membahayakan pasien saya, Pak Nohan."
Di benaknya, gambaran Pak Aswan muncul—sang dermawan penyelamat yang kelak mungkin akan diwawancarai media. Drama itu hampir membuatnya melupakan sumpah dokter. Tapi kini, dengan Arsya yang bangun dalam kurang dari 48 jam, dia kemudian melayangkan tawaran: biarkan anak ini sembuh, dan citra pahlawan Pak Aswan akan terus bergaung. Apalagi dengan amnesia Arsya, cerita bisa diatur. Rajendra, perawat yang menyaksikan semuanya, bisa menjadi bukti kesepakatan ini. Ini kesempatan untuk menang tanpa mengorbankan pasien.
Proses tawar-menawar itu berhasil, tapi pria di hadapannya—Nohan—justru bersikeras mencabut Arsya. Pasti pria ini punya agenda lain.
Di tempat tidurnya, Arsya yang semula tertidur atas permintaan perawat mulai terusik oleh suara-suara di sekitarnya.
Pak Nohan mencoba menerobos ruangan dengan langkah terburu-buru. Ponselnya masih digenggam Dokter Nata. Matanya langsung tertuju pada sosok kecil di ranjang, sebelum akhirnya beralih ke Dokter Nata yang berdiri di sisinya, menggenggam gagang pintu, menghalangi jalannya.
"Dokter, saya ulangi—Pak Aswan ingin anak ini dipindahkan hari ini juga. Ke panti asuhan," katanya tegas, tanpa basa-basi.
Dokter Nata tidak langsung menjawab. Dia melangkah ke depan, menghentikan pergerakan Pak Nohan tepat di ambang pintu. Matanya juga menajam, menelanjangi pria itu dengan sorot penuh perhitungan.
"Permintaan... atau ancaman?" suaranya datar, tapi ada ketegasan yang sulit diabaikan. "Karena sebagai dokter, saya hanya tunduk pada kondisi medis."
Pak Nohan mengalihkan pandangan, menghindari tatapan langsung. "Bukan urusan Anda," ujarnya pendek. "Saya hanya menjalankan tugas. Pindahkan dia. Sekarang."
Dokter Nata mendekat, suaranya melirih, namun setiap kata mengandung beban ancaman yang jelas. "Urusan saya adalah nyawa pasien. "
Dia menoleh sekilas ke arah Arsya yang masih tertidur atas perintah Rajendra. Luka-lukanya masih segar, setiap tarikan napas terasa sebagai perjuangan. "Arsya belum stabil. Pendarahan di kepala dan amnesia masih menjadi ancaman. Satu gerakan salah, nyawanya yang jadi bayaran. Apa Anda mau mengambil risiko itu?"
"Dia harusnya sudah tidak ada di sini," desak Pak Nohan lagi.
Arsya mulai merasa kebingungan. Siapa mereka? Mengapa mereka membicarakan dirinya? Apa maksud mereka dengan "dia harusnya sudah tidak ada di sini?"
"Dokter... saya tahu Anda peduli padanya," dagu Pak Nohan menunjuk Arsya. "Bos saya punya cara sendiri menghadapi kejutan, Dokter. Kalau kau tetap di jalur ini... aku harap kau tidak keberatan jadi bagian dari langkah pembersihan berikutnya." Ucap Pak Nohan dengan senyum meremehkan.
Dalam hati, dia melanjutkan: "Dia akan dilenyapkan. Dan kita semua yang berhubungan dengan anak ini juga akan dimakamkan dalam kuburan yang sama."
Kata-kata Pak Nohan membuat bulu kuduk Arsya berdiri. Melenyapkan? pikirnya.
"Seperti kalau salah menulis, lalu dihapus? Tapi... kalau manusia... berarti dibuat hilang? Dibuat mati?"
"Enggak... itu enggak mungkin..." batin Arsya menolak. napas Arsya mendadak tercekat di kerongkongan, dan dadanya terasa seperti dihimpit batu besar.
Di antara denting jam dan bisikan napas mereka, Arsya mendengar—bukan dengan telinga, tapi dari dalam kepalanya—suara-suara orang dewasa yang seharusnya tetap menjadi rahasia, membuat tubuh kecilnya menggigil.
Kehidupannya akan jadi ancaman.
Lebih baik dia dipindahkan.
Tapi ke mana?
Suara itu menyelinap masuk, menembus batas antara kenyataan dan pikirannya sendiri.
Apa lagi kali ini? Pak Aswan berniat menyingkirkan seseorang? Yang dimaksud Arsya? Atau bahkan aku?
Suara-suara itu menyerbu, menghancurkan ketenangan di batinnya. Jantungnya bergemuruh, tangannya gemetar hebat di balik selimut. Arsya tak bisa lagi menahan badai dalam dirinya. Tubuhnya bergerak resah, tak terkendali.
Dokter Nata melihatnya. "Sst... diam dulu," bisiknya pada Pak Nohan, matanya tajam ke arah Arsya.
Pak Nohan tampak ingin membantah, tapi memilih diam.
Dokter Nata lalu membungkuk, nadanya berubah lembut.
"Arsya... kamu sudah bangun?"
Perlahan, mata Arsya terbuka. Sorot matanya kabur, namun pertanyaannya tajam.
"Apakah aku... seharusnya mati?"
Suaranya lirih, tapi getir di dalamnya terasa mengiris hati.
Pertanyaan itu membuat Dokter Nata terdiam sejenak, wajahnya mengeras.
Dia mendengarnya... semuanya...
"Ah, seharusnya aku bicara dengan Nohan di luar, aku membuat kesalahan di depan pasien." lanjutnya.
Penyesalan dokter Nata terdengar oleh Arsya. Membuatnya semakin yakin, bahwa kalimat 'melenyapkan' itu memang ditujukan padanya. "Apa aku nggak boleh hidup?" ulang Arsya, dengan suara serak menahan air mata.
Dokter Nata cepat-cepat memutar otak, mencari cara untuk menenangkan bocah itu tanpa harus menjelaskan langsung—terlalu berisiko. "Arsya, kamu dulu anak nakal, ya?" canda Dokter Nata dengan senyum kecil yang berusaha mencairkan suasana. Usahanya berhasil membuat wajah Arsya berubah menjadi kebingungan sejenak.
"Anak kecil tidak boleh ikut campur urusan orang dewasa," lanjutnya sambil tersenyum kikuk.
"Bukan begitu..." jawab Arsya dengan suara bergetar. "Kalian... berbicara di sampingku."
Dokter Nata menunduk sejenak, lalu mengubah nadanya menjadi lebih lembut. "Arsya, dengar Pak Dokter, ya? Kami di sini hanya ingin membuatmu nyaman dan cepat pulih. Lagipula, Pak Nohan—dia tidak mengatakan itu untukmu. Dia mengatakan itu untuk..."
Arsya tahu Dokter Nata sedang berusaha menenangkannya, dia sengaja berbohong agar Arsya tidak lagi ketakutan, namun tetap saja dibohongi itu menyakitkan. "Bohong!" teriak Arsya tiba-tiba. "Dokter berbohong!"
Arsya mencoba bangkit, tetapi rasa sakit menjalar dari perutnya. Dia mengerang dan kembali berbaring, lemas. "Aku... aku harus mati, kan?" suaranya serak. "Aku nggak boleh ada lagi? Mereka mau aku hilang, mati?" tangisannya semakin keras.
Dokter Nata menatap Pak Nohan dengan tatapan penuh amarah. "Pak Nohan, tolong keluar sebentar, aku ingin berbincang dengan pasienku." nada suaranya tegas dan tidak terbantahkan.
"Tapi..." Pak Nohan tampak ragu, mencoba membela diri.
"Keluar," ulang Dokter Nata lebih keras. "Aku ingin bicara dengan pasienku."
Mau tak mau, Pak Nohan menurut. Ia melangkah keluar, punggungnya tegak tapi sorot matanya kosong. Sebelum pintu menutup sepenuhnya, ia menatap sekali lagi ke dalam ruangan.
"Kalau kau tetap di sini, kau akan lenyap... Andai dokter itu tahu, cara terbaik membantumu... adalah membiarkanmu pergi."
Di balik selimut, Arsya mendengarnya. Tidak kata demi kata, tapi maksudnya.
Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi tubuhnya mengerti: dia tidak boleh di sini. Harus segera pergi—meski belum sembuh.
Jadi... membantunya itu artinya menyuruhnya pergi? Atau menyuruhnya berhenti sembuh?
Mungkin maksud mereka, kalau aku tetap di sini dan sembuh... aku akan dilenyapkan. Tapi kalau aku pergi, walau masih sakit... aku bisa selamat? Tapi... bukankah aku harus sembuh dulu? Bukankah itu tujuannya?
Arsya memeluk dirinya lebih erat.
Kalau pergi artinya selamat, dan sembuh justru membuatku hilang... Maka barangkali... cara terbaik agar tidak menyusahkan siapa pun,
...adalah tidak usah sembuh sama sekali.


 notesbyfaeza
notesbyfaeza