Tidak ada peluit kemenangan yang berbunyi setelah UTS selesai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada bunga ucapan, tidak ada pelukan lega dari siapa pun. Tapi bagi Atha, duduk di bangku kelas yang kini tak lagi dikelilingi dua nama paling penting dalam hidupnya, napas yang bisa ia embuskan utuh tanpa rasa tercekat adalah bentuk selebrasi kecil yang cukup.
Sudah terlalu lama ia hidup dalam mode bertahan. Kini, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa hidup dalam mode berjalan.
Hasil ujian belum keluar, dan Atha tahu betul nilainya mungkin tidak akan segemilang dulu. Tapi bukan itu yang paling ia pikirkan sekarang. Yang jauh lebih penting adalah kenyataan bahwa ia bisa menyelesaikannya—bisa duduk di ruang ujian dengan pikiran yang utuh, bukan kepala yang retak, bisa menatap lembar soal tanpa keinginan untuk kabur dari segalanya. Dan di meja yang sama, proyek bimbingan konselingnya pelan-pelan mulai tumbuh dari sekadar kumpulan kutipan menjadi konsep utuh.
Ia bahkan sudah punya daftar bab, draf pendahuluan, dan beberapa halaman yang diam-diam disisipkan oleh perasaan—bukan teori, bukan motivasi instan, tapi sesuatu yang jujur dan mentah. Pak Surya dan Bu Indri sudah membaca sedikit dan memberi lampu hijau. Bahkan Pak Narya sempat berkomentar pendek, “Kayaknya ini proyek pertama dari anak kelas tiga belas yang bakal beneran jadi buku.” Atha hanya tersenyum. Ia tak yakin, tapi ia juga tak lagi menyangkal kemungkinan.
Namun di balik semua kemajuan itu, ada satu ruang yang masih gelap. Satu bab yang tidak bisa ia tulis hanya dengan pena dan kertas.
Niko dan Dero.
Nama itu masih bergema di sela-sela jeda pikirannya. Kadang hadir dalam suara kaset rusak yang terputar ulang, kadang hanya muncul dalam siluet diam ketika ia mengingat kembali momen terakhir mereka bertatapan—yang bahkan bukan benar-benar tatapan, tapi lebih seperti benturan dua dunia yang sama-sama ingin menghindar. Dan sejak saat itu, tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada kunjungan.
Atha sempat berpikir untuk membiarkannya. Mungkin ini memang akhir dari persahabatan mereka. Tapi semakin ia menulis, semakin ia menyelami dirinya sendiri lewat halaman demi halaman yang ia susun untuk proyek itu, semakin ia sadar: kalau ada luka yang paling membekas, maka itu bukan kegagalan di rapor. Bukan juga fitnah yang dilemparkan orang. Tapi diamnya Dero.
Dan hari itu, setelah selesai mengedit satu bagian bab ‘Diem’, Atha menutup laptopnya dan berdiri. Ia tahu langkah selanjutnya bukan menulis. Bukan membaca. Tapi menemui.
Ia pakai hoodie hitam yang agak longgar dan celana jins yang belum sempat disetrika. Rambutnya acak-acakan, dan ia tidak peduli. Ia ambil helm, kunci motor, lalu pamit sebentar pada ibunya yang hanya bertanya, “Mau ke mana?” dengan nada netral.
Atha menjawab singkat, “Ketemu teman.”
Motor melaju pelan menuju salah satu gang kecil di selatan kota—tempat rumah Dero berada. Jalanan tidak terlalu ramai. Suasana sore yang mendung memperlambat waktu, seolah memberi Atha ruang untuk berpikir ulang. Tapi ia tak menginjak rem. Ia terus maju. Ini bukan soal keberanian, tapi soal menyelesaikan sesuatu yang belum selesai.
Begitu sampai di depan rumah bercat abu tua itu, Atha mematikan mesin. Ia diam sejenak di atas motor, memandang pagar besi yang tertutup, jendela-jendela yang tak menyala, dan pintu yang tak bergeming. Ia turun, mengetuk dua kali.
“Dero…” suaranya pelan, hampir tertelan udara sore. Tidak ada jawaban.
Ia coba ketuk lagi, lebih keras kali ini. Tetap sunyi.
Tak ada suara TV. Tak ada suara langkah kaki. Hanya suara burung gereja di kabel listrik dan gesekan daun mangga di halaman. Atha menghela napas. Ia tidak tahu apakah Dero sedang pergi, atau memang tidak ingin ditemui. Tapi ia juga tidak ingin pulang dengan tangan kosong.
Lalu ia ingat sesuatu.
Minimarket.
Atha baru ingat, kalau sore-sore biasanya dia dapat shift jaga di minimarket dekat SMA mereka. Tempat yang sering mereka lewati sepulang sekolah dulu—sebelum segalanya meledak. Dan tanpa berpikir dua kali, Atha kembali naik ke atas motornya. Mesin dinyalakan lagi. Ia tahu benar arah tempat itu.
Ia tidak akan menyerah hari ini.
Motor Atha kembali melaju, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih keras, bukan karena kecepatan, tapi karena ketidakpastian. Angin sore yang dingin menampar wajahnya, dan jalanan sempit mulai berganti dengan deretan ruko dan lampu toko yang baru menyala. Suasana menjelang magrib selalu punya warna yang aneh—tidak benar-benar gelap, tapi juga tidak terang. Seperti perasaan Atha saat ini.
Ia tiba di minimarket itu dalam waktu kurang dari setengah jam. Dari kejauhan, lampu putih terang minimarket tampak kontras dengan langit yang mulai meredup. Beberapa orang masuk keluar membawa kantong plastik. Ada suara notifikasi mesin kasir dari dalam. Atha memarkir motornya di sisi kiri, tepat di bawah pohon kecil.
Begitu turun dari motor, Atha diam sebentar. Matanya menatap pintu kaca otomatis yang bergeser setiap kali pelanggan lewat. Ada keraguan yang sempat mampir lagi di benaknya. Mungkin Dero nggak pengin ketemu. Mungkin kehadirannya malah bikin suasana tambah canggung. Tapi kemudian ia ingat alasan kenapa ia datang sejauh ini. Ia sudah memilih untuk nggak lari lagi. Kalau hari ini ia mundur, bisa-bisa gak ada hari lain yang cukup tepat.
Ia melangkah masuk. Pintu kaca bergeser dengan suara mendesing pelan. Udara dingin dari AC menyambutnya begitu ia menginjakkan kaki ke dalam. Suara musik pop lokal mengalun samar dari speaker di langit-langit, dan deretan rak penuh snack serta sabun mandi membentang di depan mata. Tapi Atha nggak butuh waktu lama untuk menemukan yang ia cari.
Di balik meja kasir, berdiri mengenakan seragam merah dengan name tag kecil bertuliskan ‘Dero Hutahaean.’. Tangannya tengah sibuk memindai barcode barang bawaan pelanggan, sementara pandangannya tertuju ke layar monitor. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Wajahnya tampak lelah, dan rambutnya agak berantakan, seperti belum sempat disisir rapi. Tapi itu memang Dero. Dan Dero nyata di depan mata.
Atha berdiri di dekat pintu, sempat ragu melangkah. Tapi begitu si pelanggan terakhir selesai membayar dan keluar dari pintu otomatis, ia langsung berjalan ke arah meja kasir.
“Eh, hai,” katanya sambil mengangkat satu tangan kecil. Senyum yang muncul di bibirnya bukan dibuat-buat. Ia memang senang akhirnya bisa ketemu Dero langsung.
Dero menoleh cepat. Matanya membulat sebentar, seperti baru lihat hantu. Wajahnya kaget, tapi tidak panik—lebih ke arah bingung harus ngapain. “Atha?” gumamnya nyaris tak terdengar, seolah dia masih butuh waktu untuk memastikan bahwa yang berdiri di depannya bukan ilusi.
Atha mengangguk pelan. “Iya, gue,” katanya, suara tetap ringan, tenang, seolah tidak ada apa-apa di antara mereka. Padahal… ya, ada banyak hal. Terlalu banyak, mungkin.
Dero langsung menunduk, lalu pura-pura sibuk membenahi beberapa bungkus permen karet di rak kecil samping kasir. Tangannya agak gemetar, dan Atha bisa lihat itu jelas. Gerakannya seperti orang yang baru ketahuan menyembunyikan sesuatu.
“Lu… kerja hari ini, ya?” Atha coba mulai obrolan, berusaha tetap ramah. Yah, basa-basi busuk sebenarnya.
Dero tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, tanpa menatap. Lalu berpura-pura mencatat sesuatu di buku kecil yang tergeletak di bawah meja.
Hening sesaat.
Atha berdiri di ujung kasir, memandangnya dari sisi. Suara musik di dalam ruangan seperti mengecil, digantikan oleh keheningan di antara mereka berdua. Atha bisa rasakan jarak itu. Jarak yang dulu nggak ada waktu mereka masih sering ketawa bareng di kelas, atau ngobrolin hal-hal random sepulang sekolah.
Tapi sekarang bahkan menyapa saja terasa seperti usaha besar.
Atha mengambil napas, mencoba lagi. “Gue tadinya nyari lu di rumah… sepi banget. Kirain lagi pergi.”
Dero tidak menjawab. Kali ini bahkan tidak mengangguk.
Dan untuk pertama kalinya sejak datang, Atha merasa sedih bukan karena ditolak, tapi karena kehilangan versi Dero yang dulu: yang selalu punya komentar nyeleneh, yang kadang nyebelin tapi tetap perhatian, yang pernah bilang, “Kalau lu ilang dari sekolah kayak si Niko, gue yang bakal protes duluan.” Tapi sekarang Dero bahkan nggak bisa bilang satu kalimat penuh buat nyambut dia.
Tapi Atha tidak menyerah.
Ia geser sedikit tubuhnya, mendekat, dan berkata dengan suara pelan tapi jelas, “Gue cuma mau nanya… kabar lu gimana?”
Dero diam.
Masih.
Masih tidak ada jawaban.
Hanya tangan yang sibuk membereskan barang yang sebenarnya sudah rapi dari tadi. Wajahnya tertunduk, seperti nggak sanggup menatap Atha sama sekali.
Dan di saat itu, Atha sadar. Mungkin Dero memang belum siap. Mungkin Dero masih menyimpan sesuatu yang lebih berat dari yang bisa ia lihat. Tapi ia juga tahu, pertemuan ini nggak akan selesai dengan basa-basi. Sesuatu di dalam dirinya mulai mendorong lebih keras. Ada satu hal yang sejak tadi ia tahan. Sesuatu yang tidak lagi bisa disimpan sendiri.
Dan pada momen itu—ketika minimarket jadi saksi diam antara dua orang yang pernah saling percaya sepenuhnya—Atha memutuskan untuk berhenti bermain aman.
Beberapa detik berlalu sejak Atha menyapa dan menanyakan kabar, tapi Dero tetap sibuk dengan rak kecil di samping kasir yang dari tadi sebenarnya sudah rapi. Tangannya bergerak pelan, menyusun ulang bungkus permen yang jelas-jelas tidak butuh disusun ulang. Tidak ada balasan, bahkan seucap “baik” pun tidak keluar dari mulutnya.
Atha berdiri canggung, menatap punggung Dero yang membungkuk sedikit, seakan sedang menyembunyikan seluruh ekspresi dari dunia. Jarak mereka hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti berdiri di ujung yang berbeda dari planet yang sama.
Atha mencoba bertahan. Ia menunduk sebentar, menarik napas pelan, lalu memaksakan senyum kecil—senyum yang barangkali juga sudah letih karena terlalu sering dipakai buat pura-pura kuat. “Lu kenapa enggak masuk sekolah?” tanyanya lagi. Suaranya tetap tenang, tidak ada nada menuntut, tidak ada tekanan. Ia hanya ingin tahu. Bukan karena kepo. Tapi karena peduli.
Masih tidak ada reaksi.
Dero seperti batu yang keras kepala.
Seperti tembok besar yang sudah lama dibangun dan gak niat buat dihancurin.
Atha menelan ludah. Suasana di minimarket itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Bukan karena AC-nya, tapi karena sepi dan sunyi yang aneh. Suara kasir otomatis, suara plastik berkeresek dari pelanggan lain di ujung ruangan, bahkan suara lagu di speaker—semua itu tidak bisa menutupi kenyataan bahwa Dero belum siap bicara. Atau mungkin tidak mau.
Tapi Atha sudah terlalu jauh buat mundur sekarang.
Ia mencoba lagi.
“Di sekolah Pak Surya ngasih tugas proyek besar untuk masing-masing kelompok, di mata pelajaran BK. Katanya sih buat syarat kelulusan juga, lu sama niko enggak masuk, jadi akhirnya gue ngerjain sendiri. Tapi, nama lu sama Niko gue cantumin, sih,” ujarnya sambil sedikit menoleh ke arah tumpukan katalog promosi di meja kasir, berusaha terdengar santai. “Gue rencananya bikin buku. Buku self-improvement gitu. Judulnya ‘XIII-A’. Isinya tentang kita bertiga juga… ya, semacam pencarian jati diri. Gue masukin banyak hal di situ.”
Masih tidak ada tanggapan.
Dero bahkan tidak mengangguk. Ia hanya bergerak sedikit, lalu membuka laci kasir dengan alasan memeriksa kembalian. Padahal jelas-jelas tidak ada pelanggan di depannya. Atha tahu, semua itu cuma cara Dero buat menghindar. Buat menunda. Atau menolak, mungkin. Tapi bukan itu yang bikin Atha pengin nyerah—bukan diamnya, tapi rasa sepi yang menyusup ke dalam dirinya pelan-pelan, menyiksa dalam cara yang gak kelihatan. Rasanya seperti ngomong sama tembok.
Atha melirik lantai. Tatapannya kosong sebentar. Lalu, pelan-pelan, ia mengangkat pandangannya lagi. “Gue enggak nyalahin lu, Der,” ucapnya lirih. “Kalau lu emang yang ngirim email itu… gue enggak marah.”
Dero reflek menoleh cepat, tapi hanya satu detik. Lalu langsung kembali berpura-pura merapikan bon kertas yang jatuh—padahal tidak ada apa pun yang jatuh. Reaksi itu kecil, tapi cukup buat Atha tahu: ada sesuatu di sana. Dan mungkin dugaannya benar.
Namun, ia juga sadar, saat ini bukan tentang benar atau salah. Bukan tentang konfrontasi atau pembelaan. Ini tentang dua orang yang dulu saling kenal, tapi sekarang berdiri dalam ruang yang sama tanpa bisa bicara jujur. Dan satu-satunya yang berusaha menyambung itu cuma Atha.
Ia memejamkan mata sebentar, menahan perasaan yang mulai menumpuk di dadanya. Rasa kecewa, rasa kehilangan, rasa hampa yang pelan-pelan membeku jadi sesuatu yang pahit.
Tapi ia tetap tidak marah.
Karena ia tahu, Dero bukan tembok. Ia hanya lagi berdiri di balik tembok yang ia bangun sendiri. Dan Atha masih belum tahu cara menjebolnya.
Atha tidak tahu kenapa tiba-tiba tenggorokannya terasa sesak. Mungkin karena dia terlalu lama berdiri di hadapan seseorang yang bahkan tidak mau menatap matanya. Mungkin karena setiap kata yang dia ucapkan jatuh ke lantai begitu saja tanpa pernah sampai. Mungkin karena hatinya terlalu capek terus-terusan jadi pihak yang memahami, yang mengalah, yang berusaha. Dan yang paling bikin nyesek: ia tetap tidak tahu harus marah atau sedih.
Dia memutar-mutar helm di tangannya, jari-jarinya gelisah. Satu bagian dari dirinya bilang untuk pulang saja, berhenti maksa, biar waktu yang menyembuhkan semuanya. Tapi bagian lainnya—bagian yang sejak dulu nggak pernah bisa benar-benar menyerah pada orang-orang yang dia sayang—malah ingin bertahan lebih lama di tempat itu. Menunggu meski gak dipersilakan. Bertahan meski gak diharapkan. Dan akhirnya, di tengah campur aduk semua rasa itu, satu kalimat meluncur begitu saja dari mulutnya. Tidak keras. Tapi cukup jelas. Dan fatal.
“Gue udah terima email itu. Gue udah terima email pengakuan lu, Dero.”
Sekali ucap, dunia langsung berhenti bergerak.
Atha langsung refleks menutup mulutnya sendiri. Matanya membelalak. Ia seperti baru saja menjatuhkan gelas di tengah ruangan yang sepi—dan bunyinya menggema ke mana-mana. Matanya panik, bibirnya gemetar. Ia bahkan tidak sadar bahwa napasnya memburu, jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Kalimat itu seharusnya belum keluar sekarang. Belum waktunya. Atau mungkin memang tidak pernah akan ada waktu yang tepat untuk mengatakannya.
Dero tidak langsung menoleh. Tapi seluruh tubuhnya seketika membeku, seperti seseorang yang barusan mendengar suara yang seharusnya tidak pernah didengar. Tangannya menggenggam meja kasir erat-erat. Tidak bergerak. Tidak bicara. Bahkan tidak bernapas, mungkin. Detik-detik hening yang menyusul terasa seperti jeda yang dipaksakan oleh dunia agar semuanya bisa memproses apa yang baru saja terjadi.
Lalu perlahan—sangat perlahan—Dero menoleh.
Matanya lebar. Sorotnya bukan marah. Bukan juga kesal. Tapi bingung. Kaget. Seolah semua lapisan pertahanannya baru saja runtuh oleh satu kalimat pendek. Ia menatap Atha lama, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali… Dero benar-benar melihat ke arahnya. Menatap langsung, tanpa topeng, tanpa alasan buat kabur.
Dan dari bibirnya yang kaku, kalimat itu akhirnya keluar. Pelan. Penuh ketidakpercayaan.
“Serius lu?”


 harrisradcliffe
harrisradcliffe






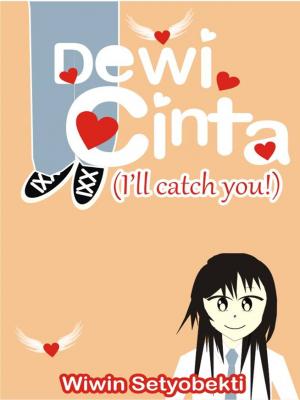



arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN