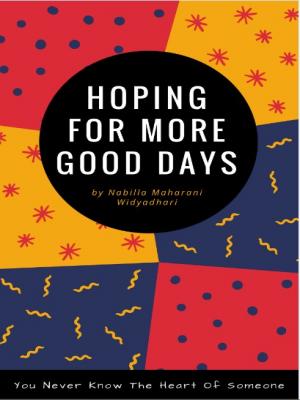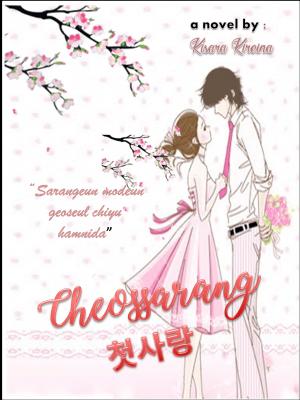Jurnalku hari ini isinya hanya mengeluh saja.
Perihal perasaan malu yang membuatku berdoa agar besok demam saja. Menghindar untuk bersitatap dengan orang beraroma buku lama. Payah dalam menghadapi masalah adalah aku. Memikirkan apa yang terjadi hari ini hanya membuatku menghela napas panjang sambil bersandar pada kursi kayu. Aku segera mencatat sesuatu saat terbesit ucapan wali kelasku.
“Hadapi masalah. Jangan melarikan diri.”
Tulisan itu berhuruf tebal berwarna merah pada sticky note berwarna kuning. Aku menempelkannya pada dinding meja belajar yang memiliki berbagai catatan tempel berwarna-warni dengan tinta tipis. Meja belajarku yang bisa dihitung beberapa jengkal ukurannya ini dipenuhi setumpuk buku sekolah yang hanya dibaca saat hari ujian mendatang.
“Jadilah berani. Mulai dengan mengatakan tidak.”
Aku kembali menempelkan sticky note serupa dengan tulisan berbeda. Kupikir, aku perlu melakukannya sebagai pengingat bahwa aku harus melancarkan tujuanku. Kedua hal itu layaknya tantangan. Dalam lubuk hati terdalam, aku meragukan bisa menjalankan hal tersebut.
“Harus yakin bisa,” gumamku berasumsi positif. Sedetik kemudian, aku mengembuskan napas dan bersandar santai pada punggung kursi kayu yang bantalannya kian tipis seiring waktu. Kupikir, aku harus menggantinya demi kenyamanan berlama-lama di depan meja belajar berlampu kuning hangat seraya menulis jurnal.
Itu menyenangkan, setidaknya membosankan bagi kakakku yang sedaritadi berceloteh dengan ponselnya yang menyeruakan suara seorang pria.
“Have a good night, babe,” ucapnya disertai kecup ringan. Aku bergidik dan melayangkan tatapan mengejek yang dipahami kakakku. Ia langsung terbahak dan malah mengatakan, “Nanti lo juga paham kalau punya pacar.”
Kupikir, aku tak ingin tahu.
“Btw, lo punya cepek?” cengirnya. “Pinjem, dong. Gue mau potong rambut. Lo mau bareng? Kata temen gue sih kalau berdua dapat potongan harga yang lumayan.”
Aku tak ingin memotong rambutku. Yah, gaya rambut lurus monoton selama tiga tahun ini tak membuatku berpikir untuk memotongnya dalam waktu dekat. Lagipula, aku selalu memotongnya sendiri daripada pergi ke salon seperti tawaran saudariku.
“Cepek itu berapa?”
Kenapa pertanyaanku mendapatkan tawa kencang sebagai jawaban. Jujur saja, istilah gaul seperti itu masih membuatku bingung.
。。。
“Lewat kelas IPS aja ya,” pintaku dengan ekspresi yang dibuat semelas mungkin. Aku yakin wajahku jelek sekali sampai April Lia yang mengajak ke kantin menahan tawa. “Ketawa aja sebelum ketawa dilarang, April.”
Dan ya, teman sebangku yang rambutnya agak bergelombang ini tertawa di sepanjang koridor saat mengambil jalan memutar menuju kantin. Menyinggung soal kejadian hari kemarin, April kian terbahak sampai menyita beberapa pasang mata yang kami lewati. Aku hanya menunduk malu.
Jujur saja, melewati kelas IPA 5 dengan tiga anak tangga itu terasa seperti aib jika kulewati. Jadi, aku sama sekali tak mengikuti sticky note yang memintaku untuk tak menghindari masalah. Namun, dipikir-pikir aku dan cowok beraroma woody itu tak memiliki masalah. Jadi, apa yang bermasalah adalah aku?
Iyalah, rasa malu bikin lo nggak mau ketemu dia.
Isi kepalaku berteriak demikian. Aku mengangguk setuju. Aku harus mengoreksi diriku dan kalimat pada stiky notekemarin malam lebih cocok jika seperti ini, “Harus berani lewat IPA 5.”
Aku kembali mengangguk-anggukan kepala sampai April menyimpan atensi padaku di antara ramainya kantin. Aku hanya menggelengkan kepala. Kurasa konyol jika menjawab, “Lagi ngomong sama diri sendiri.”
“Makan di sini aja deh. Muter jalan ‘kan lama.” April memberi usul. Sejujurnya, aku tak terlalu suka karena ramainya orang-orang. Hanya saja aku tak ingin merepotkan April lebih dari memutari jalan kembali ke kelas. Mungkin, beberapa waktu akan kami lakukan hal merepotkan itu.
Bakmi pesananku telah tersimpan di nampan sekaligus bakso milik April, lantas kami duduk bersisian di tempat kosong saat di hadapan kami ada pelajar lain. Aku mengangguk ringan sebagai sapa saat mata orang beratribut angka dua belas dalam bahasa romawi melirik.
“Kalian kelas sepuluh, ‘kan? Udah gabung eskul apa? Eits, biar gue tebak.” Senior di hadapan April itu mengerutkan kening berpikir dengan tangan mengusap dagu. Saat memandangiku, dia menebak, “Muka lo kayak orang pinter yang doyan buku, kayaknya ikut kumpulan khusus olimpiade atau eskul sastra.”
Apa wajahku memang semembosankan itu? Stereotip seperti itu sedikit membuatku kecewa sekaligus mengulum senyum bangga diam-diam. Sedikit sombong, di antara nilai biasaku memanglah pelajaran bahasa yang selalu unggul setiap ujian.
“Dia ikut basket, Bang.”
Sebelum aku mengoreksi, seseorang menempati bangku kosong di hadapanku. Aku spontan mengusap leher dan sok sibuk dengan bakmi setelah dia melambai disertai senyum lebar. Dia malah bercakap dengan senior seolah saling mengenal bahkan menertawakannya bersama.
Kuperhatikan, rambutnya memamerkan sebelah kening yang memiliki dua tahi lalat kecil di atas alis. Kerah seragamnya tak memiliki dasi abu yang menjuntai. Dan, yang menyita perhatianku adalah liontin berwarna ruby yang menyembul keluar.
“Diliat-liat, cakep juga, ya.” April berbisik, setelah kutanya siapa malah cengegesan, “Dia lah. Yang lo peluk kemarin.”
Wajahku merona. Tolong, jauhkan topik itu.
“Kalian tertarik gabung band, nggak? Eits, gue setengah maksa, nih. Butuh anggota baru buat lanjutin bandgenerasi selanjutnya. Nggak masalah kalau nggak bisa alat musik, karena soal itu bisa belajar bareng nanti,” jelas senior itu.
Aku tak pernah terpikirkan untuk bergabung band meski bisa memainkan alat musik petik bernama gitar akustik.
“Band kumpulnya setiap Kamis ‘kan, Kak?” April bertanya, lalu menolak ajakan dengan sopan setelah diiyakan, “Gue nggak bisa gabung, Kak. Soalnya ikut marching band.”
Aku baru tahu April mengikuti perkumpulan orang-orang yang mengenakan baju seiras saat penyambutan siswa ajaran baru. Menurutku, April akan cocok dengan rambut bergelombangnya yang alami.
“Kalau lo?” Pertanyaan itu diajukan untukku. Lantas, aku menjawab, “Biar gue pikirin, ya, Kak.”
“Ohh, bagus. Biar lo yakin, hari ini kumpulannya. Lo boleh gabung buat liat-liat sebelum gue kasih formulir pendaftaran. Gue tetap sedikit maksa biar lo join, haha.”
Aku mengulas senyum.
“Gue diundang buat liat-liat nggak nih, bang? Soalnya gue pernah les piano pas kecil.” Cowok di hadapanku memamerkan deretan gigi rapinya. Senior itu lebih riang menerima tanpa embel-embel kata memaksa lalu pamit entah ke mana meninggalkan kami bertiga.
Kulirik April yang memerhatikan orang di hadapanku dengan senyum terukir. Apa dia menyukai orang aneh yang memandangiku dengan senyum mencurigakan?
“Lo anak kelas IPA 5?” April memulai dialog, ditanggapi anggukan oleh orang yang diberi pertanyaan. Mereka berkenalan saat aku berperan sebagai pelengkap dunia yang mendengarkan lelucon garing cowok di depanku. Sungguh April terbahak karenanya?
“Nggak sopan kalau kenalan cuma sama satu cewek cantik aja. Jadi, nama lo siapa?”
Dia mengulurkan tangan dan aku menggapainya. Hangat seperti waktu itu. Aku menggeleng untuk mengenyahkan memori kenangan berupa aib tersebut. Eh? Lepasin tangan gue, hei.
“Gue Anbi Sakardja,”katanya. Pandangan matanya seolah mengejekku. “Lo bisa panggil gue Bi, Iffaa.”
Eh? Apa? Apa dia bilang?
Aku berpendapat lain dan berharap ekspresiku tak terlihat menghakimi, “Gue pikir An lebih bagus.”
“Tolong, lepasin tangan gue, Anbi Sakardja,”jeritku dalam kalbu. Kulirik April yang memandangi kami dengan alis tertaut dan entah mengapa sorot matanya seakan tak suka.


 azzmifaitsmiddielah
azzmifaitsmiddielah