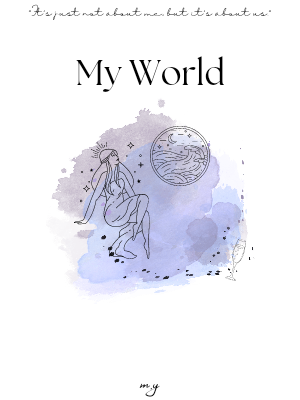“Bahkan luka di masa lalu tidak cukup untuk menghentikan kegilaannya.” -Amerta
Tubuh Amerta terhempas ke lantai. Dinding rumah megah yang seharusnya menjadi perlindungan justru menjadi saksi kebengisan yang terbungkus rapi dalam status sosial dan jabatan sang ayah. Napasnya tercekat. Luka di betis yang terhantam sisi meja masih menyisakan nyeri yang menusuk. Namun, bukan rasa sakit itu yang membuatnya menggigil, melainkan suara itu, teriakan yang menelanjangi setiap batas rasa aman.
"RASAKAN INI! INI HUKUMAN UNTUK ANAK YANG SUDAH BERANI MENANTANG PAPA!" Penggaris panjang dari baja ringan di tangan lelaki itu mendarat tanpa ampun ke kaki Amerta tanpa ampun. Benar saja, Amerta diamuk oleh sang papa hanya karena dirinya kemarin berada di taman tanpa izin.
“Papa… ampun, pa… ampun…” Isaknya pecah, tubuhnya menggeliat tak berdaya.
Namun teriakannya justru menambah deretan cambukan. Lantai dingin seperti menyerap air matanya, menghapus jejak ketakutannya, seolah dunia ingin berpura-pura bahwa tragedi ini tak pernah terjadi.
Laki-laki paruh baya itu berhenti. Napasnya memburu layaknya binatang buas yang baru saja melukai mangsanya. "Bangun! KEMBALI KE KAMARMU! SEKARANG JUGA!"
Amerta merangkak. Kedua kakinya gemetar seperti tanah setelah gempa. Saat ia mencoba berdiri, tangan mungilnya tak sengaja menyentuh serpihan bingkai foto yang jatuh. Goresan di telapak tangannya tak seberapa dibanding goresan dalam jiwanya. Luka yang tak bersuara, tapi menggema dalam jiwa.
Ia tertatih meninggalkan laki-laki paruh baya yang begitu kejam, ia tak habis pikir laki-laki yang berstatus sebagai papanya begitu keji kelakuannya.
“Non... ayo, Bibi bantu,” suara lembut itu datang seperti embun di tengah gurun. Seorang wanita paruh baya menghampiri, menyelimuti Amerta dengan pelukan hangat yang sudah terlalu sering menjadi perisai bagi luka yang tak terlihat. Saat ini hanya tersisa sang bibi yang begitu menyayangi Amerta.
Air mata Amerta menetes di bahu wanita itu. “Bi... Memangnya luka di masa lalu tidak cukup menghentikan kegilaan papa?”
Kalimat itu begitu mengoyak. Sang Bibi memeluknya lebih erat, meraba luka-luka di kaki dan tangan Amerta yang masih mengeluarkan darah.
“Non, sabar ya. Nanti ada saatnya kebahagiaan yang non harapkan hadir.”
Dengan suara gemetar, Amerta menjawab, “Dan aku akan selalu sabar. Selalu.”
~
Di tempat berbeda, Harsa berdiri di atas balkon dengan tatapan kosong yang menusuk cakrawala. Angin menusuk jasnya, tapi pikirannya lebih dingin dari apapun yang bisa disentuh cuaca.
“Cliff,” panggil Harsa pada robot cerewetnya itu.
“Ya, Harsa?”
“Cari semua data tentang gadis bernama Amerta. Lokasi, identitas, catatan pendidikan. Semuanya,” perintah Harsa tanpa memandang pada robotnya itu.
Cliff terdiam sejenak, lalu menjawab, “Maaf, Harsa. Semua data terkunci. Bahkan aku tak bisa menembusnya.”
Harsa menyipitkan mata. “Terkunci?”
“Ya. Identitasnya tersembunyi dalam sistem proteksi tingkat tinggi. Seolah dia adalah seseorang yang sangat penting atau sedang dilindungi oleh negara.”
“Ini semakin aneh.” Harsa mengepalkan tangan. “Aku ingin tahu siapa yang melindunginya, Cliff. Bahkan jika aku harus mengacak-acak sistem pusat sekalipun. Atau mungkin ini semua karena ulah papanya?”
“Bisa jadi, aku juga berpikir seperti itu,” balas Cliff.
~
Sementara itu, di kamar berwarna putih susu yang sepi, Amerta terbangun dari mimpi buruk. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya terbuka lebar, lalu mulutnya mengucapkan satu kata yang membuat udara di ruangan itu membeku.
“Bunda…”
Ia menggigil, tubuhnya gemetar. Suara-suara masa lalu kembali bergaung di kepalanya. Teriakan, isak tangis. Suara retakan kaca dan jeritan terakhir yang membuat dunia gelap seketika. Bayangan tentang kepergian ibundanya oleh tangan yang seharusnya menjadi pelindung mereka, tapi sayangnya malah menghancurkan mereka.
Ia menyeka air matanya, netranya sibuk mencari-cari sesuatu. Ia melihat tablet usang yang ia temukan di gudang rumah, tablet itu masih tergeletak di meja. Dengan cepat, ia kunci pintu, lalu mengaktifkannya. Berharap tak ada yang memergokinya.
Jari-jarinya gemetar saat mencari satu nama: Harsa. Satu-satunya kebahagiaannya saat ini. Sambungan mulai tersambung. Degup jantungnya terdengar lebih keras dari suara apa pun di ruangan itu.
“Ayo… angkat, tolong…” lirih Amerta merasa gelisih.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, layar menyala. Wajah Harsa muncul, dengan rambut acak-acakan dan mata yang masih merah. Amerta berpikir jika Harsa baru saja terbangun dari tidurnya dan sejujurnya Amerta sedikit terpana oleh ketampanan Harsa.
“Amerta?” suara Harsa terdengar cemas.
“Hai, Harsa. Maaf aku telepon larut malam,” ungkap Amerta tak enak mengganggu waktu tidur Harsa, tetapi hanya cara inilah yang membuatnya terasa sedikit lega.
Harsa mengamati wajah Amerta yang pucat, matanya yang sembab. “Kamu menangis?”
Amerta hanya menggeleng, tapi air matanya mengkhianati usahanya.
“Aku ingin bicara. Tapi tidak bisa lama,” kata Amerta.
“Bicara saja,” balas Harsa, suaranya terdengar berat. Laki-laki muda itu mengubah posisinya, dari berbaring menjadi duduk, seolah siap untuk mendengar cerita baru yang dibawakan oleh gadis di layar hologramnya itu.
Setelah beberapa tarikan napas, Amerta berkata, “Aku ingin bertemu. Minggu depan. Taman Nirashvara. Jam empat sore.”
“Taman Nirashvara?” beo Harsa.
“Iya, apakah kamu keberatan?” tanya Amerta memastikan.
Harsa menggeleng cepat. “Tentu saja tidak, memangnya kamu sudah mendapat izin dari kedua orang tuamu? Mengingat kamu terlihat seperti anak baru gede,” tanya Harsa pada lawan bicaranya.
“Perlu kamu ingat, aku sudah berumur 19 tahun. Aku tidak harus mendapat izin dari orang tuaku hanya untuk ke taman saja,” ungkap Amerta tak terima dikatakan sebagai anak baru gede.
Harsa tertawa, “Oh begitu ya? Berarti kamu perlu memanggil aku dengan sebutan ‘kak’ sebab umurku terpaut empat tahun lebih tua darimu.”
Amerta membelalakan matanya tak percaya, “Kamu terlihat lebih muda dari usiamu, tapi sepertinya aku tidak bisa memanggilmu dengan embel-embel ‘kak’ sebab aku terlanjur nyaman memanggilmu Harsa,” ungkap Amerta dengan jujur.
“Oke, tidak masalah. Kembali ke topik, apakah kamu sudah mendapat izin?” tanya Harsa memastikan.
“Sepertinya tidak akan, sebab laki-laki kejam itu tak akan memperbolehkanku keluar dari rumahnya, lebih tepatnya rumah jeruji untukku,” ujar Amerta, dilubuk hatinya ada rasa takut jika rencananya ini diketahui oleh sang papa.
Lagi-lagi Harsa dibuat bingung oleh Amerta, “Lalu, bagaimana caramu untuk dapat ke taman Nirashvara? Dan siapa laki-laki kejam itu?”
“Tenang saja, aku pastikan aku datang untuk menemuimu, sebab aku ingin sekali bertemu dengan mu, Harsa.” balas Amerta, “Dan mengenai laki-laki kejam itu adalah papa kandungku.”
Hening sejenak, hingga Harsa memulai dengan pertanyaan, “Dia kasar padamu?”
Amerta tertunduk. “Lebih dari itu. Dia menyimpan sesuatu, Harsa. Sesuatu yang selama ini aku nggak tahu. Sejak kepergian Bunda, dia semakin berubah. Dia bukan manusia yang sama.” ujarnya dengan suara pelan.
“Kenapa kamu tidak memilih kabur?”
“Karena aku dikurung. Semua akses keluar rumah ini dikendalikan. Bahkan untuk bicara denganmu saja, aku harus menyelinap,” terang Amerta dengan perasaan khawatir.
“Itu berarti kamu dalam bahaya,” ujar Harsa yang semakin dibuat bingung oleh kehidupan Amerta.
“Aku tidak ingin kamu ikut terluka.” Mata Amerta menatap lurus ke layar, “Aku cuma ingin kamu datang minggu depan. Tolong...” pinta Amerta berharap Harsa menepati janjinya.
“Oke. Aku janji aku datang.”
Sambungan terputus. Harsa masih menatap layar gelap itu, perasaannya bergejolak. Ada sesuatu yang sangat salah dan dia tahu, waktunya tak banyak. Gadis itu banyak menyimpan sesuatu yang membuat Harsa tertarik untuk menyelam lebih dalam.
~


 iniijee_
iniijee_