Jakarta sore itu tak begitu bersahabat. Asap motor berbaur dengan udara panas yang melekat di kulit, namun entah kenapa, langkah Lara terasa lebih ringan dari biasanya.
Baru saja ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, ia berdiri menghadapi Zea dan teman-temannya. Meski tangan gemetar dan air mata sempat jatuh, ada bagian dari dirinya yang merasa bangga.
Sera berjalan di sampingnya, mengayunkan tas kecil dengan santai. “Eh tadi aku liat mall, mumpung kita pulang cepet, ke sana yuk, deket kan? Kita jalan aja, sekalian cari angin.”
Lara terdiam sejenak. Dalam kepalanya, ia terpikirkan apa akibat jika ia tak langsung pulang ke rumah, namun Lara... ingin mengambil langkah lain sekali ini saja.
“Boleh…” jawab Lara pelan, tapi mantap. “Sekali-sekali, gak apa-apa.”
Mereka menyusuri trotoar sempit, sesekali berhenti karena lalu lintas pejalan kaki. Di dekat lampu merah, sebuah keramaian kecil menarik perhatian mereka. Beberapa stan berjajar di bawah tenda putih, dengan spanduk warna-warni bergelantung di antara tiang.
“Eh, bazar!” seru Sera, matanya berbinar. “Yuk liat-liat dulu.”
Di antara aroma kopi dingin dan poster-poster komunitas seni, ada satu brosur yang membuat Lara terhenti. Warna pastel dan gambar anak-anak panti dengan tulisan besar di atasnya:
DIBUTUHKAN RELAWAN SENI UNTUK KEGIATAN DI PANTI ASUHAN MAHARDIKA.
Aktivitas: melukis, mendongeng, bermain musik dan puisi.
Sera langsung menoleh, menangkap tatapan Lara yang tak berkedip. "Kita daftar yuk!"
Lara menatap poster itu lama. Rasanya seperti dunia memberinya isyarat—tentang tempat yang mungkin bisa membuatnya merasa berarti. “Aku... mau,” katanya cepat, bahkan sebelum sempat berpikir soal izin orangtua.
Perjalanan mereka lanjutkan ke mall dengan langkah yang lebih ringan. Begitu sampai, mereka langsung menuju lantai paling atas, di mana photobooth berdiri mencolok dengan latar warna pastel dan rak aksesoris lucu.
Lara mengenakan bando kelinci dan memberikan kacamata besar berbentuk hati ke Sera. Mereka tertawa, saling dorong, berpose macam-macam—dari duck face sampai gaya drama Korea. Setiap jepretan menghasilkan tawa baru.
Setelahnya, mereka berjalan melewati deretan toko. Lara berhenti di depan gerai kosmetik yang terang dengan deretan warna lipstik menggoda.
“Masuk yuk, coba-coba makeup,” ajak Lara.
Sera langsung geleng-geleng. “Ih, gak mau ah, gak pede.”
Lara menarik tangannya. “Ayo dong, kamu harus lihat kalau kamu itu cantik, Sera.”
Sera tak punya pilihan lain selain mengangguk. Mereka mencoba berbagai produk. Lara mengambil lipstik warna coral dan dengan hati-hati mengaplikasikannya ke bibir Sera secara perlahan.
“Nah, liat deh,” kata Lara, mendorong Sera pelan ke arah cermin.
Sera menatap bayangannya. Ragu. Tapi perlahan, senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. “Aku... nggak kelihatan aneh?”
“Kamu cantik, Sera,” kata Lara tulus. “Serius deh.”
Sera menoleh, matanya berkaca-kaca. “Makasih, Lara.”
Mereka pun keluar dari gerai kosmetik dengan tawa yang masih tersisa di ujung bibir. Pipi Sera masih bersemu, dan lipstik lembut warna peach membingkai senyumnya.
“Ya ampun, aku keliatan jelek gak sih?” tanya Sera gugup, melirik pantulan dirinya di kaca etalase.
Lara tergelak. “Gak sumpah! Malah pretty banget kayak idol korea!”
Sera memukul pelan lengan Lara. “Apasi ah! Jadi malu...”
Mereka berjalan pelan, langkah ringan diiringi canda. Tapi ketika mereka membelok ke lorong utama mall, suasana mendadak berubah.
Dari arah berlawanan, seorang wanita keluar dari sebuah butik, membawa dua kantong belanja berisi dress pesta. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya elegan tapi tegas. Di sebelahnya, Luna, adiknya, mengenakan bando baru, terlihat sedang asyik mengunyah permen.
Langkah Lara terhenti. Jantungnya mencelos.
Lusi.
Ibunya.
Mata Lusi hanya butuh dua detik untuk mengenali Lara. Kepalanya sedikit miring, ekspresinya datar—terlalu datar. Tapi matanya bicara banyak, rautnya kecewa, marah, dan tersinggung.
“Lara?” suara itu pelan tapi tajam. “Kamu ngapain di sini?”
Lara menelan ludah. Tubuhnya gemetar halus. “Aku… aku habis dari sekolah. Cuma… sebentar, Bu…”
Lusi menyipit. Pandangannya turun menyapu seragam yang masih dikenakan Lara, lalu naik ke wajahnya—dan berhenti tepat di bibir Lara yang masih berlapis warna peach lembut.
Lusi melipat tangan. “Dan kamu ke mall pakai lipstik? sama siapa?” Nadanya dingin. Sangat dingin.
Sera yang berdiri di samping Lara menegakkan bahu. “Saya, Tante. Kami tadi cuma—”
“Saya gak nanya kamu,” potong Lusi tanpa menoleh ke Sera. Matanya tetap tertuju ke anaknya sendiri.
Luna menyeringai kecil. “Tuh kan, udah aku bilang. Tadi aku lihat Kak Lara ke mall habis sekolah. Gak bilang-bilang lagi.”
Lusi menghela napas panjang, kemudian memandang Lara seperti menilai barang yang rusak.
“Kamu tahu betul kamu harus langsung pulang. Dan sekarang kamu jalan-jalan, dandan, bahkan ikut-ikut… ini?” Lusi melambaikan tangan ke arah Sera, entah bermaksud menunjuk apa—teman barunya atau keberanian Lara yang mendadak tumbuh.
“Bu, Lara cuma mau main bentar. Aku gak ke mana-mana ataupun aneh-aneh kok. Aku cuma—”
“Cuma bikin malu,” kata Lusi, pelan tapi menusuk. “Kamu gak diajari begitu, Lara.”
Lara terdiam. Tenggorokannya tercekat. Kata-kata ibunya jauh lebih menyakitkan dari teriakan. Suasana yang tadi hangat seketika menjadi dingin, membekukan.
Sera menarik napas, maju setengah langkah. “Tante, saya yang ajak Lara. Ini bukan salah dia sepenuhnya.”
Lusi menatap Sera—dingin, penuh penilaian. Tapi dia tidak membalas. Hanya berbalik pada Lara dan berkata, “Pulang sekarang. Kita akan bicara di rumah.”
Kemudian ia berjalan pergi bersama Luna, langkahnya cepat, tumit sepatunya berderak di lantai ubin mengilap mall.
Lara berdiri di sana. Tak bergerak. Matanya berkaca.
Sera memegang tangannya, lembut. “Kamu gak papa?”
Lara menggeleng pelan. “Enggak kok. Aku pulang dulu ya!”
Dia menatap ke arah Ibunya yang menghilang, lalu kembali pada Sera, mencoba tersenyum meski matanya masih basah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lara merasa itu layak.
*****
Langit Jakarta malam itu tampak berat. Awan mendung menggantung tanpa hujan, seolah ikut menyimpan kemarahan yang belum sempat jatuh. Di dalam sebuah rumah berlantai dua di kawasan Cipinang, suasana lebih sunyi dari biasanya.
Pintu dibanting. Suaranya menggema sampai ke lantai atas.
Lara menunduk, berdiri tepat di depan rak sepatu, masih dengan sepatu sekolah yang belum sempat ia lepas. Sera sudah pulang lebih dulu, setelah Lara memaksa agar ia naik taksi online sendiri. Lara tahu, badai sedang menunggunya di rumah.
Langkah sepatu berhak menghentak lantai marmer.
"Lara."
Suaranya datar, tapi lebih menakutkan daripada bentakan. Suara yang penuh tekanan.
Lara menoleh pelan, matanya bertemu dengan tatapan Lusi yang dingin. Ibunya berdiri dengan tangan terlipat, masih memakai atasan satin dan celana putih mahal yang sama seperti di mall tadi. Luna ada di belakang, hanya diam dengan senyum mengejek.
"Baru pulang dari sekolah?" Lusi memulai dengan nada yang menggigit. "Terus ke toko kosmetik?"
Lara terdiam, menahan napas, berharap ini hanya sebuah mimpi. Namun, suara ibunya yang tajam itu semakin nyata.
"Sama temen? Kamu yakin itu temen?" Lusi bertanya lagi, dengan nada semakin tinggi. "Dandan-dandan, pakai lipstik segala?"
Lusi melangkah mendekat, tangannya meraih dagu Lara, memaksa untuk menatapnya langsung. Mata Lusi mengintip dengan tatapan penuh penilaian—dingin dan menghakimi.
"Kamu pikir wajahmu itu cocok dipoles, Lara? Sudah tahu kamu itu nggak secantik Luna," katanya dengan nada mencemooh.
Lara menggigit bibir bawahnya, merasakan panas di dadanya. Dulu, kata-kata seperti itu akan menghancurkannya. Sekarang, ia mencoba untuk menahan air mata yang mengancam. Sesaat, ia merasa hampa. Namun, sebuah kenangan terngiang di benaknya. Tawa Sera yang ceria, suara mereka berdua di photobooth tadi—hal yang tak pernah ia rasakan di rumah ini.
"Aku... cuma pengen main bentar, Bu" bisik Lara, suara penuh gemetar.
Lusi terdiam, matanya menyipit. "Apa? Udah berani jawab? Kemarin nolak Luna, sekarang main? Terus bantah Ibu kamu? Kamu mau jadi nakal, Lar?" dia mendekat lebih dekat, seperti ingin memastikan kalau dia benar-benar mendengar kata-kata itu.
"Maafin Lara, Bu. Tapi... emang salah ya kalau Lara juga pengen main bebas kayak Luna? Lara juga pengen bahagia, Bu." Lara menatap Ibunya dengan mata yang berani, untuk pertama kalinya. Mata itu yang selama ini ia sembunyikan di balik rasa takut.
Lusi menghembuskan nafas kasar. "Salah! Bahagia itu cuman untuk anak yang tahu diri." Lusi kemudian berbalik pergi seakan sudah malas menatap anak sulungnya itu.
Luna mendekat pelan, tanpa empati. Matanya menatap Lara dengan tatapan dingin dan sedikit menyeringai. "Drama banget sih. Nggak cocok lho jadi rebel. Mending lo balik ke kamar, belajar. Biar Ibu gak malu."
Luna meninggalkan Lara begitu saja, tanpa menunggu jawaban. Suasana di ruang tamu kini terasa mencekam—sepi dan berat.
Lara berdiri di sana, menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menahan segala perasaan yang ingin meledak. Ada rasa sakit, tentunya. Tapi ada juga sebuah bara yang mulai tumbuh. Sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Sesuatu yang lebih kuat.
Dengan napas yang berat, Lara melepaskan sepatu sekolahnya. Langkahnya terasa lebih pasti ketika ia mulai naik ke kamarnya, meskipun perlahan. Tapi ada keteguhan baru dalam dirinya—tidak lagi ingin menyerah.
*****
Di kamar, Lara duduk di pinggir ranjang, menatap jendela yang sedikit terbuka. Angin malam menyapu tirai, membawa sedikit kesegaran yang sangat dibutuhkan. Namun, pikirannya tetap berputar. Kata-kata Lusi masih terdengar jelas di telinganya, seperti sebuah dering yang tak kunjung berhenti.
"Bahagia itu buat anak yang tahu diri..."
Lara memejamkan mata sejenak. Pikirannya kembali mengingatkan pada Sera. Betapa hari itu terasa berbeda. Betapa tawa mereka di photobooth terasa begitu nyata dan menghangatkan hati. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan di rumah.
Lara menarik napas panjang, lalu meraih buku catatan kecil yang ada di meja belajar. Ia membuka halaman pertama dan memegang pulpen, ujungnya menyentuh kertas. Ketenangan malam itu seperti memberikan ruang bagi Lara untuk melepaskan semua rasa yang selama ini tertahan. Tanpa sadar, jari-jarinya mulai bergerak, menulis kata-kata yang datang begitu saja, seperti suara hatinya yang ingin terdengar.
Di bawah langit yang berat, aku berdiri,
Di tengah kecemasan yang tak pernah berakhir,
Lalu ada tawa, ada bahagia—seperti kebebasan yang aku rasa,
Yang baru pertama kali kutemukan,
Dan aku ingin,
Hanya untuk satu hari,
Menjadi aku.
Lara terdiam, menatap tulisan itu. Kata-kata itu tidak sempurna, tetapi terasa begitu tepat. Begitu sesuai dengan apa yang ia rasakan sekarang—perasaan yang sering disembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri.
Ia menghapus sejenak tulisan yang belum selesai itu, lalu menulis lagi dengan lebih hati-hati, seolah ingin menyusun kata-kata dengan cermat, mencoba menuntaskan kalimat yang baru saja dimulai.
Aku selalu bertanya-tanya,
Apakah ada ruang untuk bahagia dalam hidupku?
Atau akankah aku terus dibebani oleh harapan yang tak pernah cukup,
Dari mereka yang tak mengerti siapa aku sebenarnya?
Hari ini, aku ingin berhenti bertanya,
Hari ini, aku hanya ingin merasa cukup.


 yourassiee
yourassiee










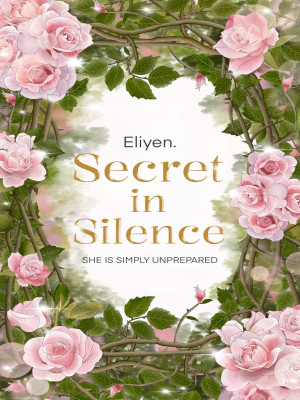







@pacarmingyuu, ahaha, maaf aku sensi, abisnya komennya menjerumus banget, aku kepikiran punya salah apa, dikomen juga aku jelasin, aku harap aku salah, kalau beneran aku salah, aku minta maaf ya😔😔🙏🩷
Comment on chapter 3 - Aku ingin berubahthank you udah berkenan komen juga, have a great day🩷🙏