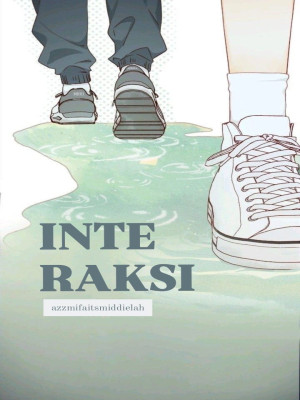Bun, hidup berjalan seperti bajingan
Seperti landak yang tak punya teman
Ia menggonggong bak suara hujan
Dan kau pangeranku, mengambil peran
Bun, kalau saat hancur aku disayang
Apalagi saat aku jadi juara
Saat tak tahu arah kau di sana
Menjadi gagah saat aku tak bisa
Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu
Agar seisi dunia tahu
Keras kepala sama kamu
Caraku marah, caraku tersenyum
Seperti detak jantung yang bertaut
Nyawaku nyala karena kamu
Aku masih ada di sini
Melihatmu kuat setengah mati
Seperti detak jantung yang bertaut
Nyawaku nyala karena kamu
Bun, aku masih belum mengerti banyak hal
Semuanya berenang di kepala
Dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya
Menjadi jawab saat saya bertanya
Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu
Agar seisi dunia tahu
Keras kepala sama kamu
Caraku marah, caraku tersenyum
Seperti detak jantung yang bertaut
Nyawaku nyala karena kamu
Aku masih ada di sini
Melihatmu kuat setengah mati
Seperti detak jantung yang bertaut
Nyawaku nyala karena kamu
Semoga lama hidupmu di sini
Melihatku berjuang sampai akhir
Seperti detak jantung yang bertaut
Nyawaku nyala karena kamu...
————
Suara petikan gitar terakhir menghilang bersama dengungan terakhir dari nadaku. Lagu Bertaut milik Nadin Amizah telah selesai aku nyanyikan, dan untuk beberapa detik, keheningan menggantung di udara. Aku menarik napas dalam—lega, namun juga menyesakkan dada. Rasanya seperti baru saja membongkar seluruh isi hatiku di depan orang-orang asing.
Mata-mata itu tertuju padaku. Puluhan pasang mata, yang sebelumnya tak kukenal, kini menatapku seolah mereka tahu siapa aku. Bukan dengan sorotan menghakimi, tapi dengan tatapan hangat yang entah mengapa terasa seperti pelukan diam-diam. Mereka tidak mengenalku, namun mereka menerima aku—dengan caraku, dengan suaraku, dengan lukaku yang kutitipkan lewat lagu.
Tepuk tangan meriah pecah, membuyarkan lamunanku. Rasanya begitu nyata, begitu hidup. Aku tersenyum kecil, masih tak percaya. Dengan hati yang berdetak cepat, aku turun dari kursi. Ada rasa bangga yang tumbuh diam-diam di dada—perasaan yang lama tak kurasakan.
Ternyata, dunia luar tidak semenakutkan yang selama ini kubayangkan. Ternyata, ada ruang di luar kepalaku yang bisa menerima kehadiranku, tanpa harus tahu cerita lengkap di baliknya.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa... mungkin aku bisa bertahan.
Dari sisi lain, Beni, teman dekatku sejak dunia terasa terlalu bising, berdiri di antara kerumunan. Ia tak berusaha meneriakiku seperti yang lain. Ia hanya menatap—dengan mata yang paham, bukan mata yang penasaran. Ia tahu semua tentangku. Tentang malam-malam panjang yang kuhabiskan menangis dalam diam. Tentang hari-hari ketika aku pura-pura kuat padahal dalam hati aku rapuh seperti kaca yang sudah retak sebelum dijatuhkan.
Dengannya, aku tidak perlu berpura-pura. Aku bisa menjadi aku yang paling jujur—tanpa topeng, tanpa alibi. Ia tahu kapan harus bicara, dan lebih sering, tahu kapan harus diam dan memelukku sampai aku merasa sedikit lebih baik.
Saat aku turun dari panggung, ia menghampiriku. Senyumnya lebar, hangat, dan penuh apresiasi. Tangannya terulur untuk menepuk bahuku, seperti berkata, “aku melihat usahamu, dan aku bangga.”
"Aku gak nyangka kamu bakal nyanyi lagu itu," katanya pelan, nyaris hanya untuk kami berdua.
Aku tertawa kecil. “Aku juga nggak nyangka bakal selesai tanpa nangis.”
"Nyaris sih," godanya sambil mengerling. "Aku lihat matamu berair waktu bagian ‘semoga lama hidupmu di sini’." Katanya sambil menyanyikan bagian tersebut.
Aku mengangguk pelan. “Itu bagian paling dalam. Kayak… aku nyanyi buat semua orang yang pernah jadi pelindungku.”
Beni mendesah, lalu menyenderkan tubuhnya di tiang dekat panggung. "Kamu tahu nggak, kamu keren banget tadi. Semua orang diem, dengerin. Seolah-olah kamu nyanyi buat mereka masing-masing."
Aku menggigit bibir, menahan senyum. “Aku takut banget sebelum naik. Takut ditolak. Takut diketawain.”
“Tapi kamu tetap naik,” jawabnya cepat. “Dan itu… lebih berani dari semua orang di sini.”
Aku menatapnya. “Terima kasih ya, Ben. Udah percaya sama aku, bahkan waktu aku nggak percaya sama diri sendiri.”
Dia mengangkat bahu, seperti biasa—seolah semua kebaikannya tak perlu dibesar-besarkan.
“Ya iya lah,” katanya santai, “aku kan Beni, manusia yang paling sabar ngadepin kamu yang dramanya melebihi drama China, Korea, Thailand dan terakhir Indosiar.”
Seketika kami tertawa. Untuk pertama kalinya malam ini, tawaku lepas. Tidak ragu. Tidak takut. Karena pada akhirnya, aku menemukan satu titik di dunia ini—dimana aku diterima, dilihat, dan tidak dihakimi.
Dan mungkin, dari titik ini, aku bisa mulai berjalan… pelan-pelan saja, tapi dengan kepala yang sedikit lebih tegak.


 asa_rina
asa_rina